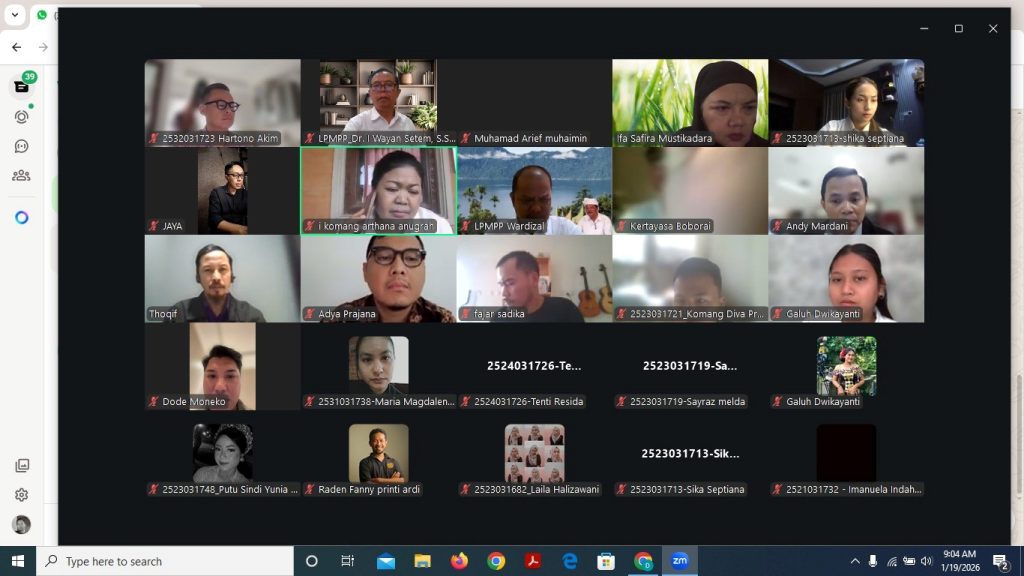Merayakan 100 Tahun Pramoedya Ananta Toer Lewat Tafsir Visual Lintas Medium

Denpasar, 29 Juli 2025 — Sebuah peristiwa budaya yang melampaui sekadar perayaan estetika tengah berlangsung di Nata-Citta Art Space (N-CAS), Institut Seni Indonesia (ISI) Bali. Bertajuk Pram–Bhuwana–Patra: Earth and Humanity, pameran internasional seni rupa dan desain ini menghadirkan 63 perupa dari Indonesia dan mancanegara, dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran sastrawan besar Indonesia, Pramoedya Ananta Toer (1925–2006).
Diselenggarakan pada 29 Juli hingga 7 Agustus 2025, dan menjadi bagian dari Festival Bali Padma Bhuwana V, pameran ini lahir dari kolaborasi antara ISI Bali, Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), dan Korea-Indonesia Centre (KIC). Lebih dari sekadar mengenang, Pram–Bhuwana–Patra menghadirkan ruang tafsir atas pemikiran dan semangat Pramoedya melalui karya-karya seni yang membentang lintas medium: dari lukisan, fotografi, kriya, busana, keramik, hingga instalasi dan media baru.
“Karya Pram sepatutnya tidak hanya dikenang lewat teks, tetapi harus dibaca ulang melalui bahasa rupa, dalam konteks zaman yang terus bergerak,” ujar Prof. Dr. I Wayan Kun Adnyana, Rektor ISI Bali sekaligus kurator pameran.
Dari Kata ke Rupa: Membaca Kemanusiaan Hari Ini
Mengangkat tema Earth and Humanity (Bumi dan Manusia), pameran ini tidak hanya menampilkan tokoh-tokoh legendaris dari novel Bumi Manusia seperti Nyai Ontosoroh, Annelies, atau Minke. Melainkan, ia mengolah kembali warisan pemikiran Pram sebagai lensa kritis untuk menyoroti isu-isu kontemporer: krisis lingkungan, ketimpangan sosial, patriarki yang tak kunjung padam, serta trauma sejarah yang masih menganga.
Alih medium dari sastra ke seni rupa menjadi proses interpretasi yang kaya: negosiasi antara teks dan konteks, antara narasi historis dan refleksi kekinian. Sosok-sosok perempuan dalam karya Pram, misalnya, dihidupkan kembali bukan sebagai figur pasif, melainkan sebagai simbol agensi, luka, dan kekuatan.
Dalam karya Arka Nyai (Ni Luh Ayu Pradnyani Utami), Sekar Kolonial (Tjokorda Gde Abinanda Sukawati), dan Kala Rau dan Indrayudha (A.A. Anom Mayun Tenaya), karakter Nyai Ontosoroh menjelma dalam desain busana yang merepresentasikan keteguhan, kecerdasan, dan martabat perempuan di tengah ketidakadilan.
Di sisi lain, karya Sisa Tubuh, Sisa Tanah (Aprililia) dan Trinity (Nyoman Sani) menyoroti sisi rapuh sosok Annelies, sebagai metafora generasi yang tercerabut dari akar dan ruang pulang—potret batin manusia yang kehilangan pijakan di tengah zaman yang gaduh.
Kesadaran Ekologi dan Lintas Generasi
Seni tak hanya berbicara tentang masa lalu. Ia juga menyuarakan kegelisahan hari ini. Lewat medium tiga dimensi, para seniman menyampaikan kritik atas eksploitasi alam dan hilangnya nilai-nilai spiritual. Dalam karya Paradoks Seribu Bunga (Nyoman Suardina), tubuh manusia dihiasi bunga artifisial sebagai metafora keindahan palsu dalam budaya citra. Sementara Menatap Luka Bumi (Ida Ayu Gede Artayani) menggambarkan penderitaan ekologis lewat wajah-wajah yang saling tatap di atas ranting mati.
Dalam fashion art, seniman seperti Dewa Ayu Putu Leliana Sari dan Tiartini Mudarahayu merajut narasi perempuan dalam bentuk kebaya, kain bordir, dan instalasi partisipatif yang menyentuh tema trauma keluarga dan penghapusan identitas.
Fotografi sebagai Arsip dan Memori Kolektif
Bagian paling menggugah dari pameran ini hadir dalam karya-karya fotografi yang melampaui fungsi dokumenter. Mereka menjadi ruang ekspresi atas luka sejarah dan kekerasan sistemik.
Karya The Day After–Without Us oleh fotografer Korea Joo Yong-seong menyoroti nasib perempuan “camptown” pasca-Perang Korea yang menjadi korban industri seks militer. Sementara Rustling Whisper of the Wind oleh Sung Namhun menghadirkan lanskap bekas pembantaian Jeju 4.3 yang ditangkap lewat teknik Polaroid memburam—simbol trauma yang tak terhapus.
“Fotografi tak hanya menyimpan citra, ia juga menyimpan luka. Melalui cahaya dan kontras, para fotografer menyuarakan kembali sejarah yang dibungkam,” ujar Jeon Dongsu, kurator asal Korea yang terlibat dalam pameran ini.
Tidak hanya seniman Indonesia, pameran ini juga menghadirkan perupa internasional seperti Ted van Der Hulst (Belanda), Aimery Joessel (Perancis), dan Paul Trinidad (Australia).
Dalam Colonial Threads, Van Der Hulst menyoroti tubuh albino Indonesia dalam balutan kolonial, mengangkat isu representasi visual dan warisan kuasa. Joessel menampilkan potret humanistik atas Ibu Hindun, petani lokal yang mengolah tanah dengan keteguhan senyap. Adapun Trinidad menelusuri relasi manusia dan alam melalui instalasi lintas budaya yang menyandingkan gurun Australia, tari Toraja, dan filosofi dualitas Bali.
Peristiwa Budaya, Bukan Sekadar Pameran
Pameran ini juga menayangkan video wawancara langka antara Pramoedya dan Prof. Koh Young Hun, Indonesianis asal Korea. Dalam kutipan rekaman tersebut, Pram berkata, “Duniaku bumi manusia dengan persoalannya.” Sebuah pernyataan yang kini menemukan gaung baru melalui seni rupa.
“Digagas oleh Prof. Koh Young Hun, Indonesianis terkemuka, penelaah karya dan sosok Pram, bersama kami kurator, simposium dan pameran ini membentang sebagai ruang interaksi pemikiran berikut capaian seni visual. Salah satu penanda penting dalam pameran ini adalah petikan video wawancara Prof. Koh dengan Pramoedya, buah pertemuan puluhan tahun, “ ujar Warih Wisatsana, penyair dan salah satu kurator.
Pameran Bali Bhuwana Rupa dan Simposium Internasional ini menghadirkan juga tokoh-tokoh pemikir dan seniman mumpuni dari berbagai negara. Salah satunya adalah Happy Salma yang bertimbang renungan pengalamannya saat memerankan Nyai Ontosoroh pada berbagai panggung di tanah air, termasuk Blora, tanah kelahiran Pram. Sebuah napas panjang yang menghidupkan kembali tokoh perempuan yang melampaui zaman.
Peristiwa ini mempertemukan pemikiran Pram dengan gaung kemanusiaan yang melampaui batas geografis. Han Kang, sastrawan Korea Selatan peraih Nobel Sastra tahun 2024, menggemakan tentang cinta pada sesama manusia serta keyakinan akan masa lalu yang bisa menyelamatkan masa kini. Pandangan ini senapas dengan semangat Pram yang menempatkan manusia sebagai pusat perjuangan sejarah. Kepedulian Han Kang pun sejalan dengan karya-karya para fotografer Korea dalam pameran ini, yang mengabadikan jejak kekerasan dan tragedi kemanusiaan sebagai peringatan dan renungan lintas generasi.
Melalui benang merah pemikiran Pramoedya, Han Kang, dan para seniman lintas disiplin, pameran ini menegaskan bahwa sastra, seni, dan sejarah bukan sekadar artefak masa lalu, melainkan medan keberanian untuk menyuarakan keadilan, dan martabat kemanusiaan.
Sebagai ajang lintas generasi dan lintas disiplin, Pram–Bhuwana–Patra menunjukkan bahwa seni—seperti juga sastra—adalah ruang untuk menyimak jiwa zaman. Ia bisa menyembuhkan, menggugat, dan menyuarakan kembali apa yang nyaris luput dari ingatan kolektif.