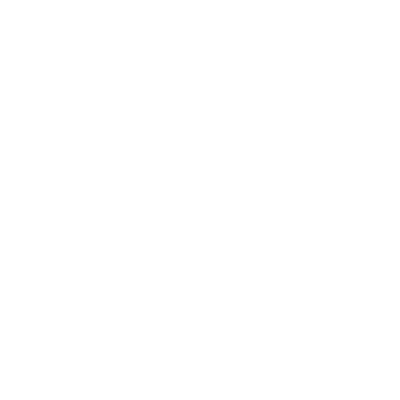by admin | May 20, 2011 | Berita
 Denpasar – “Guk-guk”, sebuah garapan infotainment Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Denpasar lolos pra seleksi dewan juri RRI pusat Jakarta, untuk selanjutnya diikutsertakan dalam kompetisi tahunan Organisasi Lembaga Penyiaran se-Asia Pasifik.
Denpasar – “Guk-guk”, sebuah garapan infotainment Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Denpasar lolos pra seleksi dewan juri RRI pusat Jakarta, untuk selanjutnya diikutsertakan dalam kompetisi tahunan Organisasi Lembaga Penyiaran se-Asia Pasifik.
“Garapan karya seni itu selanjutnya akan dinilai dalam Kompetisi Kompetisi Asia Pasific Broadcasting Union (ABU)
Prizes 2011 bersama produksi katagori lainnya,” kata Kepala Bidang Programa Siaran RRI Stasiun Denpasar Bagus Ngurah Rai, S.H, M.M di Denpasar, Kamis.
Bagus Ngurah Rai yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali itu menjelaskan, garapan Guk-Guk juga dinilai bersama naskah drama anak dan remaja serta berita.
Garapan infotaiment itu ditulis oleh Ir Made Suartini yang disiarkan pada acara Dagang Gantal RRI Stasiun Denpasar yang menceritakan tentang Rabies.
Ariadi Putra, S.H selaku Supervisi garapan tersebut menjelaskan, gagasan cerita `Guk-guk` dalam Katagori Infotainment ini terinspirasi saat PWI Bali menggelar Sarasehan Penanggulangan Rabies di Bali pada peringatan Hari Pers 2011, pertengahan Maret lalu.
Bahaya penyakit rabies yang ditampilkan dalam acara Dagang Gantal merupakan acara unggulan RRI Denpasar yang digelar sejak 1992 atau 19 tahun yang silam.
Siaran Dagang Gantal menurut Bagus Ngurah Rai mendapat respon positif dari para pendengar di Pulau Dewata, terbukti melalui saluran telepon (phone in programe) ikut berperanserta menyemarakkan acara siaran Dagang Gantal tersebut.
“Masyarakat tidak hanya ingin tahu, namun juga sebagai upaya antisipasi penanggulangani penyakit rabies yang semakin meluas di Bali,” tutur Bagus Ngurah Rai.
Ia menambahkan, untuk pra seleksi kompetisi ABU Prizes 2011, RRI Denpasar Bidang Programa Siaran mengirimkan katagori drama, anak & remaja serta Infotainment.
Sementara bidang pemberitaan mengirimkan katagori “news dan documentary.” kata Bagus Ngurah Rai yang juga Plh Kepala Stasiun RRI Denpasar.
Kegiatan tersebut merupakan kompetisi tahunan dari Organisasi Lembaga Penyiaran se Asia Pasifik. RRI Stasiun Denpasar 2010 berhasil meraih juara I untuk Katagori The Best Musical Show Promoting The Musical Heritage dalam AIBD Prizes (Asia – Pasific Instute For Broadcasting Development ).
Karya yang berhasil meraih prestasi gemilang tingkat internasional itu berjudul `Jes Eksotik` hasil garapan kerja sama RRI Denpasar, PWI Bali dengan A.A Ngurah Kusuma Wardana dari Sanggar tari Penggak Men Mersi Puri Kesiman Denpasar.
Berkat prestasi tersebut RRI Stasiun meraih tropi yang diserahkan di Macau China 26 Juli 2010, tutur Bagus Ngurah Rai yang berharap prestasi tersebut bisa diraih kembali dalam tahun 2011.
Sumber: antaranews.com

by admin | May 19, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Wardizal Ssen., Msi., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar.
Kiriman: Wardizal Ssen., Msi., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar.
Didalam pertunjukan dendang, materi atau teks nyanyian pada umumnya berbentuk pantun, berwujud baris atau lirik (curahan perasaan) yang dikelompokkan menjadi bait, untaian atau kuplet. Berkaitan dengan pengertian pantun, Navis dalam bukunya Alam Terkembang Jadi Guru mengatakan:
Pantun, sama maknanya dengan umpama. Sepantun sama dengan seumpama, seperti yang ditemukan pula dalam bahasa Melayu yang sering menyebut kami sepantun anak itik, kasih ayam maka menjadi atau tuan sepantun kilat cermin dibalik gunung tampak jua (1984:233).
Zuber Usman dalam suatu diskusi pada seminar kesenian Minangkabau di Batusangkar (1970) mengatakan bahwa, pantun berasal dari kata petuntun (pa- tuntun = penuntun) yang artinya sama dengan umpama atau perumpamaan. Perubahan bunyi patuntun menjadi pantun adalah hal yang lazim dalam bahasa Minangkabau. Poerwodarminto dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan:
Pentun 1. sb. Sajak pendek, tiap-tiap kuplet biasanya empat baris (ab, ab) dan dua baris yang dahulu biasanya untuk tumpuan saja; 2. pribahasa sindiran; 3. jawab (pd. tuduhan) dan sebagainya; berpantun (pantunan): menyanyikan (membawakan) pantun bersahut-sahutan; memantuni; menyindir dengan pantun; memantunkan: mengarang pantun; mengatakan dan sebagainya dengan pantun; pemantun: pengarang pantun (1984:710).
Pantun terdiri dari beberapa baris dalam jumlah yang genap, dari dua baris sampai dua belas baris; separoh jumlah baris permulaan disebut sampiran, separoh berikutnya adalah isi pantun yang sesungguhnya. Fungsi sampiran adalah sebagai pengantar pada isi, bunyi, dan iramanya. Pantun yang sempurna adalah apabila sampirannya mengandung unsur tersebut.
Di samping berbentuk pantun, didapati juga teks nyanyian yang berbentuk talibun, yaitu karya puisi yang juga berwujud baris: enam, delapan, sepuluh dan seterusnya; biasanya dalam jumlah yang genap. Dapat dikatakan bersajak ab-ab untuk pantun yang berjumlah empat baris, abc-abc untuk yang enam baris dan abcd-abcd untuk pentun yang berjumlah delapan baris.
Ditinjau dari segi isinya, isi pantun dendang dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu: pantun nasehat, pantun muda, pantun gembira, pantun kiasan, pantun adat, pantun bebas, pantun jenaka, dendang kaba, pantun tua, pantun duka dan pantun suka. Pantun nasehat adalah jenis pantun yang lebih banyak berisikan nasehat orang tua kepada anaknya, mamak kepada kemenakannya atau nasehat untuk anak-anak muda. Pantun nasib ditandai dengan isi pantun yang menyatakan kesulitan hidup, kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan dan sebagainya. Pantun muda adalah pantun yang isinya menggambarkan masalah-masalah hubungan muda-mudi, percintaan, kerinduan terhadap kekasih dan semacamnya. Pantun gembira adalah suatu bentuk pantun yang menggambarkan rasa suka cita terhadap sesuatu. Pantun kiasan adalah jenis pantun yang isinya lebih banyak berupa kiasan. Pantun adat adalah pantun yang baik sampiran maupun isinya terdiri dari pepatah- petitih atau kata-kata adat yang dijadikan pegangan hidup masyarakat Minangkabau. Pantun bebas adalah jenis pantun dimana sampiran dan isi pantun dibuat secara bebas, tergantung pada suasana dimana pantun itu di dendangkan; sampiran dan isi pantun keluar secara spontan. Walaupun bebas, tetapi pantun tersebut mempunyai sampiran dan isi sebagaimana kaidah sebuah pantun. Pantun jenaka adalah jenis pantun yang lebih banyak digunakan untuk berolok-olok atau mempermainkan seseorang melalui kata-kata. Biasanya isi pantun tidak terjadi sebagaimana digambarkan dalam pantun tersebut.
Berdasarkan kesan yang ditimbulkan dan kegunaannya dalam masyarakat, musik vokal yang berkembang di Minangkabau dapat dikelompokan atas lima bentuk, yaitu: dendang ratok, dendang kaba, dendang gembira, salawat/dikie dan baindang (Syarif, 1983:7). Dendang ratok adalah pembagian jenis dendang di Minangkabau yang didasarkan atas melodi dendang tersebut yang terdengar sedih dan isi pantunnya berhiba-hiba, menyadari nasib yang malang, kesengsaraan hidup dan sebagainya. Dendang kaba adalah jenis dendang yang digunakan untuk menceritakan kaba (cerita rakyat Minangkabau masa dahulu). Dendang gembira adalah jenis dendang yang sifatnya gembira. Salawat talam adalah salah satu musik vokal yang berkembang di Minangkabau dimana pada masa dahulunya digunakan untuk syiar agama Islam. Lagu-lagu yang dibawakan pada umumnya berbahasa Arab. Dalam perkembanganya sekarang lebih banyak difungsikan untuk keperluan hiburan dengan menggunakan bahasa daerah. Instrumen musik yang digunakan untuk keperluan salawat talam ini adalah Dikie atau rebana dan ada juga yang menggunakan Talam. Jenis musik ini sering juga disebut Badikie. Baindang (berindang) adalah berdendang bersahut-sahutan antara dua orang penyanyi yang berasal dari dua kelompok pemain Indang. Pertunjukan indang ini biasanya diiringi dengan instrumen musik yang dinamakan Rapa’i.
Pantun Sebagai Teks Nyanyian di Minangkabau, selengkapnya

by admin | May 19, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman I Putu Juliartha, Mahasiswa PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman I Putu Juliartha, Mahasiswa PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Ngemoncolin pada dasarnya adalah melakukan pembentukan muka trompong yang menitik beratkan pada pembentukan moncol, perataan, merapikan, membuat garis lingkaran, dan membuat sudut pada bangun trompong. Proses ngemoncolin membutuhkan waktu lebih lama daripada proses penguadan dan dalam melakukan pemanasan cobekan di dalam tungku perapian dilakukan lebih hati-hati dibanding pemanasan laklakan pada tahap penguadan. Hal ini disebabkan karena permukaan cobekan lebih tipis dari laklakan sehingga diperlukan panas yang merata pada semua bagian permukaan untuk menghindari adanya sobekan atau pecah akibat terlalu panasnya api dalam pembakaran.
Tahapan-tahapan pada proses ngemoncolin adalah sebagai berikut :
a) Ngincep atau merapikan lambe, terlebih dahulu diratakan bagian sudut yang berada pada basang cobekan yang mana sudut tersebut nantinya akan menjadi pejungut. Kemudian dipukul menggunakan palu yang terbuat dari kayu atau seseh bertujuan untuk mendapatkan sudut yang rata sebagai batas tinggi lambe. Kemudian cobekan ditaruh di atas landesan pengenjuh dengan memasukkan basang cobekan pada ujung landesan. Landesan berfungsi sebagai alas yang membantu pembentukan lambe menjadi incep. Ngincep dilakukan dengan melakukan pemukulan pada bagian lambe yang dimulai pada bagian tengah lambe menggunakan palu pengincep sambil memutar cobekan, dan selanjutnya diarahkan pukulan agak kebawah yang berakhir pada batas bawah lambe. Palu pengincep yang tadi digunakan diganti dengan palu penabdab dengan pemukulan diarahkan pada batas bawah lambe, kemudian di ulang lagi dari bagian atas menggunakan palu pengincep dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Kekuatan pukulan pada proses ini tidak keras tetapi pukulan agak ditekan dengan agak menarik ke bawah, mengingat pukulan ini bertujuan untuk meratakan dan menata halus semua permukaan lambe, membuat agak miring atau melengkung ke dalam atau kebasang trompong yang disebut dengan incep, yang sebelumnya lambe kelihatan tegak antara muka cobekan dengan lambe membentuk sudut 100% dibuat miring dengan perkiraan sudut yang di bentuk sekitar 70 sampai 80%, sehingga ukuran lambe bagian atas yang nantinya menjadi pejungut lebih lebar dengan batas bawah lambe yang akan menjadi pengilat. Pengincepan dilakukan hingga di dapat bentuk lambe sesuai dengan yang dikehendaki. Prosesnya dilakukan berulang-ulang 3-4 kali pengulangan dengan perhitungan naik turun dari landesan ke jalikan prapen untuk dipanaskan terlebih dahulu, dan diperkirakan pemanasan dilakukan sebanyak 25 kali dalam proses pengincepan ini.
b) Ngeracap dilakukan apabila bentuk lambe cobekan dianggap sudah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ngeracap dilakukan di luar prapen dengan keadaan cobekan tidak dalam keadaan panas, karena sebelumnya sudah dimasukkan atau disepuh kedalam bak air ( penyeeban). Selanjutnya dipapar atau dirapikan menggunakan kikir, dan pengikiran dilakukan pada ujung lambe yang disebut dengan pengilat. Ngeracap bertujuan untuk mendapatkan pengilat yang rapi dan rata sehingga memiliki ketinggian yang sama pada semua sisi lambe yang membentuk sebuah lingkaran.
c) Mesuang moncol adalah sebuah proses yang diawali perataan pada bagian user cobekan yang terletak pada tengah-tengah basang cobekan yang dipukul dengan menggunakan palu besi yang beratnya 3kg. Cobekan diletakkan di atas landesan penguadan untuk dipukul bertujuan untuk mendapat ketebalan yang merata pada user cobekan yang nantinya akan dibangun menjadi moncol. Proses ini disebut ngeplak dan hanya dilakukan sekali saja dalam 1 kali pemanasan atau abarakan. Tahap selanjutnya barulah dimulai pemoncolan dengan cara user cobekan yang telah digeplak kembali dipukul menggunakan palu pemoncolan dengan memakai alas batu pemoncolan. Batu ini berisi lubang dipergunakan sebagai tempat yang menimbulkan moncol saat dipukul-pukul dengan palu, lubang batu ini berukuran sesuai dengan ukuran maksimal sebuah moncol yaitu dalamnya 8cm dan lebar 6cm. Membangun moncol dilakukan hanya tiga kali pemanasan atau tiga kali naik turun ke api/telung barakan.
Membangun Moncol Dalam Pembuatan Gamelan, selengkapnya

by admin | May 19, 2011 | Berita
 Makassar – Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia saat ini memprioritaskan revitalisasi kesenian tradisional di seluruh daerah.
Makassar – Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia saat ini memprioritaskan revitalisasi kesenian tradisional di seluruh daerah.
“Kesenian tradisional merupakan ekspresi yang sangat mendalam dan menunjukkan indentitas suatu daerah,” kata Direktur Kesenian Kemenbudpar, Sulistyo Tirtokusumo, di Makassar.
Karena itu, kata dia, kesenian daerah ini perlu kembali dihidupkan, mengingat saat ini kesenian tradisional sudah cukup banyak ditinggalkan, khususnya oleh generasi muda.
“Revitalisasi ini juga merupakan bentuk apresiasi bagi para pelaku seni yang selama ini masih terus menggiatkan kegiatan-kegiatan seni tradisional yang mulai tergerus oleh budaya-budaya luar,” kata dia.
Hal ini, lanjutnya, juga sekaligus menjadi tantangan besar bagi para pelaku serta apresiator kesenian tradisional untuk bisa terus berkarya dan bisa menjadikan kesenian tradisional semakin kreatif.
Ia mengatakan, pentingnya revitalisasi kesenian tradisional juga dilakukan mengingat rata-rata kesenian tradisonal merupakan seni tradisi lokal yang memberikan pengakuan terhadap yang Maha Kuasa.
“Karena itulah, seni tradisional banyak mencerminkan nilai-nilai sosial yang sangat penting untuk kembali diangkat di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.
Pada tahun ini, Kemenbudpar melakukan revitalisasi kesenian tradisional Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tari Pakkarena, dan juga revitalisasi untuk kesenian Kraton Cirebon yang dinilai mulai redup.
Menurutnya, Tari Pakkarena merupakan tari tradisional yang tidak lagi dikenal secara lokal di Sulsel, melainkan juga secara nasional, sehingga harus kembali dihidupkan dan menjadi kekayaan budaya bangsa Indonesia.
Sumber: antaranews.com

by admin | May 18, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: I Wayan Sudirana, PhD Candidate
Kiriman: I Wayan Sudirana, PhD Candidate
Para seniman dan pecinta seni budaya Indonesia yang datang dari Amerika Serikat, Inggris, Indonesia dan berbagai kota di Kanada telah menjalin kolaborasi dan berpartisipasi pada acara Gong! The Gamelan Festival yang diselenggarakan di Simon Fraser University, Vancouver, Kanada, pada 15-17 April 2011. Pertunjukan gamelan dalam format festival ini diadakan menandai 25 tahun keberadaan gamelan Indonesia di Vancouver, Kanada.
Kelompok gamelan Bali “Gita Asmara”, yang dipimpin oleh Prof. Michael Tenzer dan I Wayan Sudirana dari University of British Columbia (UBC), Vancouver tampil pada hari pertama dengan membawakan komposisi tembang Bali, Sembur Tangi (Purple Fountain) karya Wayan Sudirana dan Sekar Gendot. Gerakan Tari Sekar Jagat, Topeng Arsawijaya, Legong Keraton Condong dan Tari Oleg Tamulilingan yang kompleks dan eksotik dibawakan dengan indah sekali oleh para seniman Bali, Kanada, Thailand dan Jepang, terlebih dengan iringan gamelan “Gita Asmara” yang begitu rancak dan dinamis. Penampilan I Wayan Sudirana, kandidat doktor di UBC, menambah suasana semakin memikat penonton yang memadati gedung pertunjukan yang berkapasitas 400 kursi, dengan memperkenalkan suara berbagai alat gamelan dan cara memainkannya serta memberikan kesempatan tanya jawab dengan para penonton.
Pada hari kedua, acara diisi dengan pagelaran wayang kulit “Anoman the Envoy” yang dilakonkan dengan baik oleh dalang Dr. Matthew Cohen, seorang pengajar di University of London yang pernah belajar seni pedalangan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Kelompok gamelan Jawa “Madu Sari” dari Simon Fraser University, Vancouver, pimpinan seniman Sutrisno Hartono, kandidat doktor di University of Victoria, British Columbia, mengiringi penampilan dalang Ki Matthew Cohen, yang dengan kepiawaian dan kejenakaannya membuat hadirin bertahan sampai selesainya pertunjukan hingga larut malam.
Hari terakhir festival menampilkan kelompok gamelan Sunda “Si Pawit” dari Vancouver Community College oleh Jon Siddall menampilkan beberapa komposisi tembang Sunda, antara lain Mypongan yang mengambil beberapa bagian dari musik Jaipongan, dan diperkuat oleh seniman kecapi dan suling Sunda, Andrew Timar dan Bill Parsons dari Toronto. Cengkok Jessika Kenney, pesinden Jawa dan Sunda dari Amerika Serikat, dalam mengalunkan tembang Anjeun, Kalangkang, Warung Pojok dan Asmarandana Kandhil telah memikat hadirin.
Di sela-sela festival, untuk merespon minat warga Kanada yang ingin lebih mendalami budaya Indonesia, telah diselenggarakan workshop dan demo cara memainkan peralatan gamelan serta penyebarluasan informasi seni budaya dan pariwisata Indonesia melalui stan batik, cindera mata, buku promosi pariwisata dan sajian aneka kuliner Indonesia.
Untuk lebih melengkapi promosi seni budaya Indonesia di wilayah barat Kanada ini, panitia penyelenggara telah pula menjalin kerja sama dengan Vancouver International Film Festival untuk menayangkan film “Opera Jawa” karya Garin Nugroho di Vancouver pada tanggal 11 April dan 17 April 2011. Banyak pengunjung menyatakan terkesan dan mengungkapkan penghargaan terhadap karya sutradara Indonesia tersebut.
Selain didukung oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, rangkaian acara Gong! The Gamelan Festival dan pemutaran film “Opera Jawa” tersebut terselenggara berkat adanya kerja sama dengan Caravan World Rhythms dan Simon Fraser University serta dukungan dari Pemerintah Kota Vancouver yang tengah merayakan 125 tahun berdirinya Vancouver.

by admin | May 17, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman Kadek Suartaya, SSKar., MSi., Dosen PS. Seni Karawitan ISI Denpasar.
Kiriman Kadek Suartaya, SSKar., MSi., Dosen PS. Seni Karawitan ISI Denpasar.
Bhinneka Tunggal Ika adalah sasanti negara Indonesia yang telah menyalakan api kesadaran masyarakatnya sebagai sebuah bangsa yang dirajut dari keberagaman. Sejak cikal bakal negeri yang disatukan dalam bentangan jambrut khatulistiwa ini bertumbuh, benih-benih perbedaan itu telah dikelola secara bijaksana. Perbedaan bukan dipandang dan ditakuti akan melahirkan perpecahan, namun sebaliknya menjadi dorongan yang bertenaga untuk bertemu, mengenal dan saling menerima. Namun, masih menyejukkankah rekatan Bhineka Tunggal Ika itu di tengah kecenderungan prilaku kekerasan yang mengusik kemajemukan masyarakat Indonesia belakangan ini?
Sebuah karya seni pertunjukan mencoba menggugah masyarakat Indonesia tentang pentingnya makna sloka bhineka tunggal ika yang terpampang di kaki Garuda Pancasila lambang negara kita. Sebuah sendratari atau oratorium yang kisahnya diangkat dari zaman keemasan Majapahit disajikan di Jakarta pada Senin (21/3) malam lalu berkaitan dengan Dharma Santhi Nasional perayaan hari raya Nyepi tahun Saka 1933. Bertempat di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar didaulat menyuguhkan seni pentas bertajuk “Purusadsantha”. Undangan kehormatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Budiono, beberapa menteri, Ketua MPR Taupik Keimas, para duta besar, dan para tokoh agama tampak menyimak dengan tekun gelar seni yang berdurasi sekitar 45 menit itu. Demikian pula ribuan umat Hindu yang datang dari seluruh penjuru Jakarta menunjukkan antusiasisme sarat gairah menikmati dari menit ke menit sendratari yang menggunakan narasi bahasa Indonesia itu.
Oratorium “Purusadasantha” berkisah tentang keangkaramurkaan raksasa Purusada yang berhasil disadarkan atau diinsafkan (santha) oleh ketulusan budi dan kasih damai penegak keberanan tanpa kekerasan, Sutasoma. Sutasoma adalah Putra Raja Hastina, Sri Mahaketu, yang tidak mau hidup dalam gelimang kemewahan keraton melainkan memilih menjadi pertapa di hutan untuk mencari kehidupan sejati. Sementara itu, Purusada, seorang raja raksasa, memburu Sutasoma untuk dipersembahkan sebagai tumbal kaulnya kepada Betara Kala. Sutasoma berserah diri untuk dimangsa Batara Kala tetapi dengan permohonan 100 raja yang ditawan Purusada agar dibebaskan. Batara Kala dan purusada terharu dengan keiklasan Sutasoma. Napsu Batara Kala untuk menelan Sutasoma sirna. Keangkaramurkaan Purusada pun padam dan kemudian bertobat.
Dibawakan oleh lebih dari 100 orang pelaku seni. Tuturan kearifan dan kebeningan nurani Sutasoma itu merupakan cuplikan lontar “Purusadha” gubahan Mpu Tantular, pujangga keraton Maajapahit. Lontar yang ditulis pada abad ke-14 zaman pemerintahan Rajasanegara atau lebih dikenal dengan nama kecil Hayam Huruk ini, di tengah masyarakat Bali lebih populer dengan sebutan kakawin Sutasoma yang sejatinya memang disusun dalam bentuk puisi lirik. Dari kakawin Sutasoma, pupuh 139 bait 5, sasanti bhinneka tungga ika pada awal larik tan hana dharma mangrwa, kemudian disyukuri oleh Raja Hayam Wuruk sebagai pemersatu keberagaman Nusantara sebagai buah dari Sumpah Amukti Palapa Patih Gajah Mada.
Seperti dikisahkan pada awal oratorium “Purusadasantha” itu, sebelum munculnya susastra Sutasoma, Hayam Wuruk resah akan keberagaman Nusantara yang ditenun lewat penaklukan. Raja Hayam Wuruk menyadari api dalam sekam mengancam kesatuan Nusantara. Disadarinya bahwa, kemajemukan suku, agama, golongan dan budaya Nusantara memerlukan perekat yang menyejukkan. Hadirlah kemudian Mpu Tantular, memercikkan tirta kearifan lewat karya sastra yang menonjolkan figur Sutasoma yang teguh dan bijaksana menghadapi kebatilan serta rela berkorban untuk kepentingan rakyat. Larik bhinneka tungga ika tan hana dharma mangrwa dalam kakawin itu menjadi penyejuk Nusantara di bawah panji-panji Majapahit.
Ajaran kasih Sutasoma terasa kontekstual dalam pluralisme bangsa kita. Adegan saat Sutasoma memberikan ajaran kasih kepada Purusada disambut haru penonton. Ujar Sutasoma, “Semailah selalu kasih damai, di hati dan di bumi. Kasih kepada Hyang Widhi, kasih kepada bumi pertiwi dan kasih kepada sesama insan kehidupan. Mari, mari bersama menyucikan nurani memajukan bangsa. Mari berkasih damai menegakkan kebenaran tanpa amuk kekerasan. Mari berkasih mesyukuri keindahan pelangi keberagaman kita,” penonton bertepuk tangan berkali-kali menyambut pesan-pesan kasih damai Sutasoma.
Pelangi Seni Budaya Di Tengah Badai Kekerasan, selengkapnya

 Denpasar – “Guk-guk”, sebuah garapan infotainment Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Denpasar lolos pra seleksi dewan juri RRI pusat Jakarta, untuk selanjutnya diikutsertakan dalam kompetisi tahunan Organisasi Lembaga Penyiaran se-Asia Pasifik.
Denpasar – “Guk-guk”, sebuah garapan infotainment Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Denpasar lolos pra seleksi dewan juri RRI pusat Jakarta, untuk selanjutnya diikutsertakan dalam kompetisi tahunan Organisasi Lembaga Penyiaran se-Asia Pasifik.