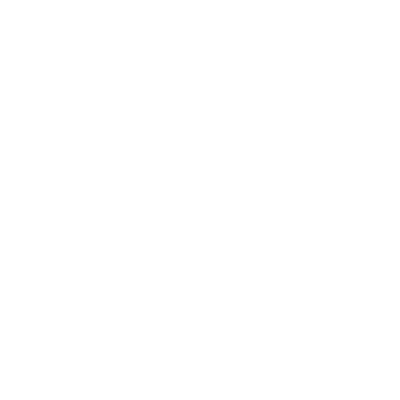by dwigunawati | Jun 7, 2011 | Berita, pengumuman
 Jakarta – Pembangunan bangsa tidak hanya berupa fisik dan ekonomi semata, namun bisa dilakukan dengan pembangunan karakter melalui pendidikan budi pekerti. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) melalui Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, menghimbau para seniman untuk memasukkan unsur budi pekerti di setiap karyanya.
Jakarta – Pembangunan bangsa tidak hanya berupa fisik dan ekonomi semata, namun bisa dilakukan dengan pembangunan karakter melalui pendidikan budi pekerti. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) melalui Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, menghimbau para seniman untuk memasukkan unsur budi pekerti di setiap karyanya.
Konten budi pekerti dalam setiap karya seni harus dikedepankan. Kesadaran ini menjadi gerakan nasional yang dilakukan bersama,” ujar Ukus Kuswara, Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Kemenbudpar, di sela seminar Pendidikan Budi Pekerti Akar Jati Diri bagi Pertahanan & Persatuan Bangsa di Era Globalisasi, di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (1/6).
Generasi muda, lanjut Ukus, menjadi target utama dari pendidikan budi pekerti. Media pembelajaran seperti museum, perpusatakaan, film, galeri, dan sanggar seni, dapat dijadikan alat untuk memupuk pendidikan budi pekerti, tegasnya. Namun, pendidikan demikian harus dimulai dari unit sosial terkecil, yaitu lingkup keluarga, lingkungan masyarakat, dan pendidikan formal.
Mewakili Menbudpar Jero Wacik, Ukus menyampaikan, ada 7 komponen pokok pendidikan budi pekerti berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang dapat diteladani guna memecahkan masalah Indonesia dewasa ini. Yakni: mengembangkan religiositas dan toleransi; rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional; persatuan dan gotong royong; cinta damai dan anti kekerasan; kedisiplinan, ketertiban, dan ketaatan hukum; daya juang; dan berpikir positif.
Ukus berharap, untuk mencapai 7 komponen pokok tersebut, seluruh elemen bangsa tetap mengindahkan pendekatan humanism dan multikulturalisme.
Menurutnya, Bangsa Indonesia dewasa ini memiliki kecenderungan memudarnya rasa toleransi atas perbedaan, menurunnya penghargaan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya, meningkatnya budaya kekerasan, menurunnya penghargaan atas etika dan moral, rasa minder terhadap bangsa lain, dan kecenderungan menurunnya capaian prestasi di sejumlah bidang.
Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menyampaikan, pentingnya mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pendidikan Karakter Bangsa. Pancasila harus dijadikan dasar, agar kekerasan dan radikalisme bisa ditangkis. Pendidikan karakter bangsa ini tumbuhnya dari masyarakat, dari bawah ke atas (bottom up), sehingga bisa menjadi gerakan nasional bersama, ujarnya seraya mengatakan keberhasilan pendidikan budi pekerti adalah makin tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap budaya bangsa.
Sementara itu Diah Harianti yang mewakili Wakil Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, salah satu komponen penting dalam pendidikan budi pekerti adalah media massa. Media perlu menyuguhkan sajian yang bisa menumbuhkan pikiran positif dalam diri bangsa, ujarnya. Diah menegaskan, menurunnya moral bangsa disebabkan banyaknya praktisi pendidikan yang terlalu mengutamakan komponen kognitif sehingga mengabaikan komponen afektif (moral dan budi pekerti).
Seminar yang digagas oleh Alumni Perguruan Cikini (ALPERCIK) ini diikuti sekitar 300 peserta dari kalangan praktisi dan pengamat pendidikan. Hadir pula dalam seminar tersebut, Akbar Tandjung sebagai Ketua Akbar Tandjung Institut dan Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Rully Chairulazwar.
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Ka. Pusformas Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Sumber : antaranews.com
by admin | Jun 7, 2011 | Berita, pengumuman
Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Denpasar mengadakan pameran karya tugas akhir mahasiswa pada :
Tanggal : 7 – 15 Juni 2011
Tempat : Bentara Budaya Bali, Jl. Raya Prof. Ida Bagus Mantra 88 A
Pembukaan : 7 Juni 2011, Pukul 18.00 wita
Ujian tugas akhir dilaksanakan di kampus ISI Denpasar pada tanggal 8 – 17 Juni 2011, jadual dapat didownload disini.
Denpasar, 7 Juni 2011
Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
TTD
I Ketut Suwitra, SE

by admin | Jun 6, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Kadek Suartaya, S.Skar., Msi., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman: Kadek Suartaya, S.Skar., Msi., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Garuda nan gagah perkasa. Telah sekian masa merajut kesatuan negeri tercinta ini. Susastra Hindu menuturkan, begitu menetas dari telurnya, Garuda mengguncang jagat semesta, terbang membelah angkasa, menyapu mega-mega. Diceritakan, pada suatu hari, kepakan sayap putra Bagawan Kasyapa ini menerjang Sorgaloka. Para dewa tak kuasa menghadapi amukan dahsyat Garuda yang menginginkan tirta amerta untuk diberikan kepada Naga Kadru sebagai balasan hutang ibunya. Dewa Wisnu menganugrahkan air kehidupan abadi itu dengan syarat Garuda bersedia menjadi wahananya, bersama-sama menumpas kebatilan serta menjaga keharmonisan, kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kisah keluhuran budhi dan kepahlawanan Sang Garuda itulah yang menggugah para pendiri bangsa ini mengukuhkan Garuda sebagai lambang Negara Indonesia.
Masyarakat Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang mensyukuri rahmat hidup Hyang Widhi ini, juga mengusung Garuda sebagai maskot dan spirit warganya, ditandai dengan sebuah patung Garuda yang terbuat dari beton setinggi lima meter bertengger persis di tengah-tengah desa setempat. Syahdan pada tahun 1970-an, ketika dunia kepariwisataan Bali mulai bangkit, para perajin atau seniman Desa Guwang mendapat berkah dari membuat seni ukir patung kayu yang banyak diminati oleh kalangan wisatawan. Ada pun bentuk atau figur yang seakan serentak dibuat oleh masyarakat setempat saat itu adalah patung Garuda yang dikendarai Dewa Wisnu.
Kekaguman dan rasa takzim masyarakat Desa Guwang terhadap Sang Garuda tetap bergelora hingga kini. Tengokkan Sabtu (16/4) sore lalu di panggung terbuka Balai Budaya Gianyar. Lewat ungkapan seni pertunjukan kolosal, para pelaku seni Banjar Buluh Guwang menyajikan kisah burung agung Garuda, disaksikan ribuan penonton yang menyesaki Lapangan Astina Gianyar. Garapan seni bertajuk “Garuda Sang Pangayu Jagat” ini ditampilkan dalam Pawai Budaya berkaitan dengan hari jadi ke-240 Kota Gianyar.
Mitologi tentang burung Garuda sangat lekat dengan kebudayaan Hindu. Di tengah masyarakat Bali masa kini, Garuda dalam berbagai ekspresi seni, patung dan lukisan misalnya, tidak hanya memiliki nilai komersial kepariwisataan namun dimuliakan penuh respek sebagai raja diraja burung yang berkepala, paruh, sayap dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Patung Garuda ditempatkan sebagai penyangga bale gede pada bangunan arsitektur tradisional. Di Bali, bahkan, Garuda bukan hanya melayang-layang dalam kisahan dan dongeng tetapi “hidup“ menerjang lincah dalam seni tontonan, jadi ikon pahlawan pembela kebenaran dalam puspa warna seni pertunjukan seperti tampak pada Wayang Kulit, Calonarang, Wayang Wong, dan Sendratari.
Internalisasi tokoh Garuda yang begitu kokoh di tengah masyarakat Bali mengalir dari masa kejayaan kerajaan Hindu di Jawa. Pada masa keemasan Majapahit misalnya, Sang Garuda diusung sebagai lambang kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wisnu, Garuda juga memiliki sifat pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Penghormatan terhadap Garuda sebagai wahana Wisnu dapat dijumpai dalam berbagai candi kuna peninggalan Hindu Jawa seperti pada candi Pranbanan, Mendut, Penataran, Belahan, Sukuh dan Cetho dalam bentuk relief atau arca. Sebuah arca menggambarkan Airlangga sebagai Wisnu tengah mengendarai Garuda yang ditemukan di candi Belahan, merupakan arca Garuda Jawa Kuna paling terkenal yang kini disimpan di Museum Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.
Ratusan tahun, dari zaman ke zaman Sang Garuda mengepak-ngepak dalam imajinasi generasi terdahulu. Maka, ketika bangsa Indonesia memerlukan lambang negara, burung mitologi Hindu ini seakan meluncur dari langit khatulistiwa dan hinggap menjadi penanda keindonesiaan kita. Garuda sebagai lambang negara, dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Pada tanggal 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut dengan menambahkan “jambul” pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita. Disain Garuda lambang negara itu tak berubah hingga kini. Pekik “Garuda di dadaku” kini menjadi api semangat dan kebanggaan bangsa Indonesia.
Garuda Di Dadaku Dalam Debur Pentas Seni, selengkapnya
by admin | Jun 6, 2011 | Berita, pengumuman
PENGUMUMAN
Nomor: 1270/IT5.5.1/DT/2011
PERUBAHAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2011
Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Denpasar tahun 2011 yang sedianya dilakukan tanggal 6 – 22 Juni 2011 diundur menjadi tanggal 1 – 14 Juli 2011 setiap hari kerja.
Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal sebagai berikut:
1. Pengambilan formulir dari tanggal 6 – 22 Juni 2011
2. Pembayaran pendaftaran dilakukan melalui Bank BRI ke Rekening No:
0368-01. 000687.30.7 atas nama Bendahara Penerimaan ISI Denpasar
Pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dengan melampirkan tanda bukti setoran pembayaran
Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan
Terimakasih
6 Juni 2011
a.n. Rektor
Pembantu Rektor I
ttd
Drs. I Ketut Murdana, M.Sn.
NIP. 195712311985031009

by admin | Jun 6, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman I Gede Yudarta, SSKar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman I Gede Yudarta, SSKar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Orang Bali, dimanapun keberadaan mereka baik secara individu maupun berkelompok akan senantiasa hidup sebagaimana di daerah asalnya yaitu Bali. Bagi yang hidup secara berkelompok atau tinggal pada suatu kawasan tertentu di luar Bali, akan senantiasa hidup dengan sistem yang telah melekat dari diwarisi oleh para leluhur mereka. Menyimak kehidupan masyarakat Bali di Mataram, dilihat dari sistem sosial yang dianut, mereka masih tetap mewarisi dan melaksanakan sistem sosial sebagaimana layaknya di Bali, bahkan dalam menjalankannya mereka lebih ketat, taat dan disiplin dari pada di daerah asalnya.
Dalam kehidupan berorganisasi, masyarakat Bali di Mataram masih melaksa-nakan sistem organisasi sebagaimana layaknya di Bali. Sebagaimana dikatakan Suyadnya (2006:6), komunitas Bali di Lombok mengorganisasikan diri dalam bentuk banjar-banjar, organisasi tradisional ala Bali. Banjar adalah organisasi kemasyara-katan tradisional yang merupakan kesatuan sosial atas dasar ikatan wilayah. Namun demikian, ada sedikit perbedaan antara banjar yang ada di Mataram dengan bajar yang ada di Bali. Apabila di Bali keberadaan banjar sebagai bagian organisasi sosial yang lebih kecil dari desa, atau kelurahan serta memiliki fungsi secara adat dan kedinasan. Di Mataram banjar tidak memiliki afiliasi ke desa adat karena tidak ada orgaisasi desa adat. Sebagaimana dikatakan lebih lanjut oleh Suyadnya, ada tiga jenis banjar di Mataram yakni banjar rojong, banjar suka duka dan banjar karya. Banjar rojong biasanya terdapat di kampong-kampung tua yang ada di Mataram. Dikatakan banjar rojong karena kramanya memiliki hubungan sidikara atau setingkat rojong (warisan/keturunan) yang diwarisi oleh para leluhur mereka. Selanjutnya banjar suka duka adalah organisasi sosial yang dibentuk berdasarkan kebutuhan suka duka. Anggotanya adalah mereka yang tidak menjadi anggota banjar rojong dan mereka pada umumnya adalah pendatang baru atau anggota banjar rojong yang kesepekang oleh rojongnya. Sama halnya dengan banjar suka duka, banjar karya adalah organisasi sosial yang anggotanya tidak atas dasar hubungan sidikara.
Selain banjar, organisasi tradisional yang sama dengan di Bali adalah sekaa, yaitu suatu perkumpulan atau kesatuan sosial yang mempunyai tujuan-tujuan khusus tertentu (Rivai Abu. ed. 1980/1981:56). Adapun sekaa–sekaa yang ada diantaranya: sekaa truna, sekaa angklung, sekaa gong, sekaa pesantian, sekaa jogged dan berbagai jenis lainnya sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Bali, merebaknya kembali persoalan soroh (klen), di Mataram saat ini juga muncul organisasi sejenis seperti maha semaya warga pande, pasemetonan pasek sapta rsi, arya kenceng dan berbagai soroh lainnya. Di samping organisasi tradisional sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula berbagai organisasi yang bersifat modern diantaranya: Paradah, Pemuda Hindu, Parisada dan organisasi lainnya yang merupakan himpunan dari masyarakat Bali.
Bentuk kehidupan sosial lain yang dilakoni oleh masyarakat Bali di Mataram adalah dalam pelaksanaan berbagai upacara adat seperti sebagaimana tercakup dalam Panca Yadnya, dimana masyarakat Bali senantiasa melaksanakan upacara tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka warisi dari para leluhur mereka. Sikap gotong royong, kebersamaan dan saling menghargai satu sama lainnya masih tampak dalam kehidupan masyarakat di Kota Mataram. Seperti tradisi megibung (makan bersama), yang merupakan tradisi masyarakat dari daerah Karangasem (Bali) pada saat pelaksanaan upacara ngaben, pernikahan dan upacara lainnya masih tetap dilestarikan dan dilakukan oleh masyarakat Bali di Kota Mataram. Tradisi ini sudah ada sejak tahun 1614 Caka (1692 Masehi) ketika salah satu Raja Karangasem, I Gusti Anglurah Ktut Karangasem, berperang menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sasak (Lombok). Di kala para prajurit istirahat makan, beliau membuat aturan makan bersama yang disebut megibung yang sarat akan tata nilai dan aturan yang khas.
Kehidupan Sosial masyarakat kota mataram, Selengkapnya

by admin | Jun 5, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman Ida Bagus Surya Peradantha, S.Sn.
Kiriman Ida Bagus Surya Peradantha, S.Sn.
Dramatari Arja, merupakan kesenian tradisional Bali yang terkenal. Setiap kabupaten di Bali, sejak jaman dahulu telah memiliki Dramatari Arja dengan berbagai style atau gayanya masing-masing. Pada tahun 1920-an sampai 1960-an, kesenian ini menemukan kejayaannya, dimana setiap pementasannya selalu dipadati penonton. Durasi yang panjang, yaitu sekitar 5-6 jam ini tidak menyurutkan niat penonton untuk menyaksikan jalannya cerita hingga penghujung. Wajar saja Dramatari Arja pada jaman itu menjadi tontonan sekaligus hiburan utama masyarakat, mengingat pola hidup masyarakat serta kebiasaan yang dianut tidaklah seperti sekarang. Setelah masa kejayaannya berakhir, eksistensi Dramatari Arja perlahan tapi pasti mengalami kemunduran. Bahkan tidak jarang, setelah ditinggalkan oleh para generasi emasnya, sangat sulit ditemukan seniman yang memiliki bakat sekaligus niat untuk melanjutkannya.
Etimologi kata Arja menurut I Made Bandem dalam bukunya Ensiklopedi Tari Bali diduga berasal dari kata “ Reja “ yang mendapat awalan “A” sehingga menjadi kata Areja. Oleh karena kasus pembentukan kata, istilah Areja berubah menjadi Arja yang berarti “sesuatu hal yang mengandung keindahan”. Dewasa ini kata Arja dipergunakan untuk menamakan satu jenis kesenian Bali yang berunsurkan tari, drama dan nyanyian.
Melihat perkembangan teater belakangan ini, maka teater dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, masing-masing :
- 1. Literary Music Form ( Bentuk literer, Drama )
- 2. Musical Form ( Seni Drama yang mempergunakan seni suara sebagai pengungkap cerita, juga dapat disebut opera )
- 3. Audio Visual Form ( Televisi dan Film )
Setelah kita mengetahui penggolongan jenis teater tersebut, maka dapatlah kita menggolongkan Dramatari Arja ini ke dalam Musical Form, dimana musik ( Tembang dan Instrumental ) menjadi bagian yang paling dominan dan penting. Karena, setiap pengungkapan dramatisasi pasti menggunakan tembang dan istrumen.
Jika diperhatikan ke belakang, di saat derasnya pengaruh globalisasi, kebutuhan manusia akan sebuah hiburan sungguh merupakan sesuatu yang mutlak. Hal ini dikarenakan begitu padatnya volume aktivitas yang mereka jalani tiap harinya. Maka dari itu, waktu luang yang ada merupakan hal yang harus dimanfaatkan secara efisien untuk menyegarkan kembali pikiran yang lelah. Salah satu cara misalnya adalah dengan menyaksikan televisi yang sarat hiburan berbagai genre. Namun di sisi lain, justru hal inilah yang menjadi salah satu penyebab pudarnya kilau Dramatari Arja yang dahulu merupakan hiburan yang ditunggu-tunggu.
Sebagai seorang seniman muda, saya mencoba untuk peka terhadap isu yang terjadi pada apa yang dihadapi oleh Dramatari Arja. Kebetulan, saya mempunyai seorang nenek yang merupakan penari Arja terkenal pada zamannya. Beliau bercerita bahwa membawakan kesenian Arja merupakan sesuatu yang sangat sulit. Kita dituntut harus bisa berakting, berdialog verbal, berdialog dengan tembang tradisional Bali, menari dan bahkan mengarang syair tembang secara spontan di atas panggung. Di samping itu, seorang penari juga dituntut untuk mengetahui beberapa cerita yang bersumber dari legenda, babad, epos, dan sejarah. Secara tidak langsung hal ini menuntut seorang penari harus menguasai bidang sastra daerah secara cukup dalam.
Kompleksitas dari Dramatari Arja inilah yang ternyata menjadi salah satu isu penting dari memudarnya pamor kesenian ini di mata seniman muda dan menyebabkan perlunya proses ekstra panjang untuk melakukan regenerasi. Di samping itu, pengaruh televisi yang menyajikan jenis hiburan lebih beragam, menarik, mudah dan murah, serta praktis, juga turut memberikan andil sepinya penonton untuk menyaksikan hiburan tradisional seperti Dramatari Arja. Maka dari itu, kesenian ini pun menyesuaikan diri dengan memadatkan cerita dan durasi pementasan menjadi maksimal dua jam yang semula sangat panjang hingga enam jam. Cukupkah itu untuk kembali menarik minat masyarakat menyaksikan Dramatari Arja tradisional? Sayang sekali, hal itu belumlah memberikan hasil maksimal untuk menyegarkan kesenian ini.
Untungnya, seniman di Bali tidak begitu saja melupakan dan meninggalkan warisan kesenian adiluhung ini. Sebagai bukti, untuk menyelamatkan keberadaan Dramatari Arja, banyak usaha yang dilakukan, seperti misalnya pembinaan sejak usia dini, dibukanya kesempatan tiap sanggar untuk menampilkan kesenian Arja pada event-event tertentu seperti PKB kali ini, hingga revitalisasi dan inovasi keberadaan Dramatari Arja. Usaha terakhir ini patut mendapat perhatian lebih, sebab memungkinkan seorang seniman untuk membawa sebuah misi pembaruan dalam usahanya mempertahankan eksistensi kesenian ini.
Revitalisasi dan Inovasi Dramatari Arja: Sebuah Harapan Baru, selengkapnya

 Jakarta – Pembangunan bangsa tidak hanya berupa fisik dan ekonomi semata, namun bisa dilakukan dengan pembangunan karakter melalui pendidikan budi pekerti. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) melalui Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, menghimbau para seniman untuk memasukkan unsur budi pekerti di setiap karyanya.
Jakarta – Pembangunan bangsa tidak hanya berupa fisik dan ekonomi semata, namun bisa dilakukan dengan pembangunan karakter melalui pendidikan budi pekerti. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) melalui Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, menghimbau para seniman untuk memasukkan unsur budi pekerti di setiap karyanya.