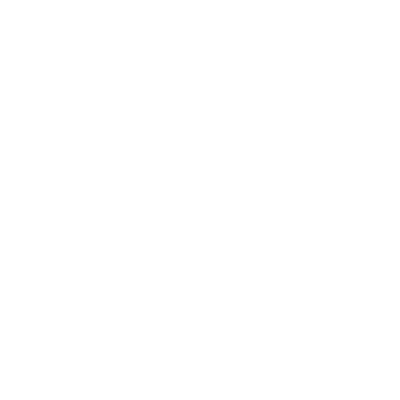by admin | Apr 22, 2010 | Artikel, Berita
Peranan Bakat Kinestetik dalam meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar
Oleh: Drs. I Nengah Sarwa
Abstrak Penelitian Dosen Muda/Kajian Wanita
 Pada era globalisasi dewasa ini, intelegensi (IQ) bukanlah segala-galanya. Gardner menyatakan manusia memiliki Kecerdasan Jamak (Multiple Intelligences) yaitu Kecerdasan Matematis-Logis (Logical Mathematical Intelligence), Kecerdasan Linguistik/verbal (Linguistic/verbal = Word Smart), Kecerdasan Ruang Visual (Visual Spatial Intelligence), Kecerdasan Gerakan Fisik (Bodily-kinesthetic Intelligence), Kecerdasan Musik (Musical Intelligence), Kecerdasan Hubungan Sosial (Interpesonal Intelligence), Kecerdasan Diri (Intrapersonal Intelligence), Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence), dan Kecerdasan Natural (Existence Intellegence). Goleman menambahkan satu lagi yaitu Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence). Dalam hal inilah dunia pendidikan ditantang untuk mengembangkan kecerdasan yang dimiliki anak didik, agar dapat menghasilkan manusia-manusia yang memiliki keterampilan hidup (life skill), mempunyai kompetensi pada bidangnya, sehingga dapat sukses menjalani kehidupan di masyarakat.
Pada era globalisasi dewasa ini, intelegensi (IQ) bukanlah segala-galanya. Gardner menyatakan manusia memiliki Kecerdasan Jamak (Multiple Intelligences) yaitu Kecerdasan Matematis-Logis (Logical Mathematical Intelligence), Kecerdasan Linguistik/verbal (Linguistic/verbal = Word Smart), Kecerdasan Ruang Visual (Visual Spatial Intelligence), Kecerdasan Gerakan Fisik (Bodily-kinesthetic Intelligence), Kecerdasan Musik (Musical Intelligence), Kecerdasan Hubungan Sosial (Interpesonal Intelligence), Kecerdasan Diri (Intrapersonal Intelligence), Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence), dan Kecerdasan Natural (Existence Intellegence). Goleman menambahkan satu lagi yaitu Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence). Dalam hal inilah dunia pendidikan ditantang untuk mengembangkan kecerdasan yang dimiliki anak didik, agar dapat menghasilkan manusia-manusia yang memiliki keterampilan hidup (life skill), mempunyai kompetensi pada bidangnya, sehingga dapat sukses menjalani kehidupan di masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi korelasi dan besarnya kontribusi: antara Bakat Kinestetik terhadap Prestasi Belajar, sehingga dapat diketahui seberapa jauh peranan Bakat Kinestetik di dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif Expost Fakto. Sebagai populasi adalah semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan baik teori maupun praktek program S1 Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar pada semester genap tahun 2008/2009. Sampel diambil secara purposive sampling, sebanyak 35 mahasiswa yang berada pada jurusan/program studi Karawitan Semester 4. Kegiatan penelitian dilakukan dengan langkah-langkah (1) penyusunan instrumen penelitian yang divalidasi, sesuai dengan jenis data yang digali, (2) menggali data dari sumber data yang terdiri dari mahasiswa dengan menggunakan instrumen yang telah disusun, dan (3) melakukan tabulasi, deskripsi, analisis data, dan pemaknaan hasil analisis data, dengan menggunakan Metode Statistik “Uji Korelasi Product Moment Pearson”.
Adapun data yang dikorelasikan adalah skor Bakat Kinestetik dengan skor Prestasi Belajar mahasiswa pada mata kuliah Karawitan, dan hasil analisis data membuktikan bahwa:
(1) Terdapat hubungan yang linear positif dan signifikan antara Bakat Kinestetik dengan Prestasi Belajar mahasiswa, dengan kontribusi 44 %,
(2) Dalam upaya meningkatkan Prestasi Belajar mahasiswa, bakat kinestetik ternyata mempunyai peranan sebesar 44 % dan sisanya 56 % disebabkan oleh faktor yang lain.
Dengan hasil yang diperoleh tentang peranan Bakat Kinestetik dalam pembelajaran, maka diharapkan dalam penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dapat dijadikan pertimbangan dalam; tes penerimaan mahasiswa baru, maupun dalam pembinaan mahasiswa untuk memilih minat kajian atau minat penciptaan, sehingga pencapaian prestasi belajar mahasiswa dapat diupayakan secara maksimal.
Kata kunci: Pembelajaran, Bakat Kinestetik, Gerak dan Prestasi Belajar

by admin | Apr 22, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: I Ketut Kodi, SSP. M.Si
Ringkasan Hasil Penciptaan Dana DIPA 2009
 Wayang Betel adalah sebuah garapan pewayangan yang ter inspirasi dari Wayang Lemah/Wayang Gedog, garapan ini tecipta karena penggarap melihat kehidupan wayang lemah pada masyarakat Bali hanya dikaitkan dengan upacara keagamaan. Penanggap pertunjukkan ini kurang memperhatikan baik tempat pentas maupun sarana-sarana pendukung lainnya. Hal ini membuat para dalang malas untuk menggarap bagian artistiknya, hiburan dan konteksnya. Wayang Lemah yang berfungsi ritual menjadi kemasan baru berbentuk hiburan seni yang segar, sehat dan bermutu.
Wayang Betel adalah sebuah garapan pewayangan yang ter inspirasi dari Wayang Lemah/Wayang Gedog, garapan ini tecipta karena penggarap melihat kehidupan wayang lemah pada masyarakat Bali hanya dikaitkan dengan upacara keagamaan. Penanggap pertunjukkan ini kurang memperhatikan baik tempat pentas maupun sarana-sarana pendukung lainnya. Hal ini membuat para dalang malas untuk menggarap bagian artistiknya, hiburan dan konteksnya. Wayang Lemah yang berfungsi ritual menjadi kemasan baru berbentuk hiburan seni yang segar, sehat dan bermutu.
Dalam masalah ini akan dicoba menyiasati agar seniman Dalang dan musisinya tidak hanya duduk sebagaimana pagelaran wayang lemah biasa, melainkan juga berinteraksi aktif membangun suasana dramatik. Jelasnya, dalang yang biasanya hanya duduk memainkan wayang kini ditampilkan dengan berakting di atas panggung didukung oleh penataan lampu dan musik pengiring inovatif berintikan Gender Rambat.
Beberapa wayang kiranya perlu dibuat dengan ukuran yang lebih besar sehingga suasana wayang lemah yang semula hanya ritus akan dikembangkan menjadi suatu bentuk hiburan/entertainmen yang mengintegrasikan kritik dan komentar sosial sesuai dengan perkebangan Zaman Kaliyuga dewasa ini. Sesuai dengan namanya, Betel berarti tembus pandang. Garapan wayang Betel ini berbentuk Wayang Lemah sehingga dapat dilihat tembus betel oleh penonton tanpa terhalang kelir/screen putih. Musik iringan yang berintikan instrumen Gender Rambat juga akan diintegrasikan sedemikian rupa sehingga garapan wayang ini juga menyajikan komponen musikal teater atau teater musik. Dalam garapan “Wayang Betel” ini penggarap akan menggunakan konsep menimalis dengan tidak mengerungangi keunggulan – keunggulan yang telah ada. Karena berkesenian itu tidak harus selalu mewah, seni pun bisa muncul dari sesuatu yang sederhana.Garapan ini merupakan bagian dari epos Mahabharata yakni kehidupan Pandawa di hutan setelah lepas dari bencana kebakaran Gua gala-gala sampai gugurnya Detya Adimba.
Kata Kunci : Wayang Betel, Gender Rambat, Mahabharata

by admin | Apr 22, 2010 | Artikel, Berita
Oleh I Wayan Suharta Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
 Palegongan merupakan salah satu barungan klasik yang mampu bertahan dan masih terpelihara sampai sekarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “klasik” diartikan mempunyai nilai atau posisi yang diakui dan tidak diragukan, yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur, bersifat sederhana, serasi dan tidak berlebihan (Tim Penyusun Kamus, 1988 : 445).
Palegongan merupakan salah satu barungan klasik yang mampu bertahan dan masih terpelihara sampai sekarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “klasik” diartikan mempunyai nilai atau posisi yang diakui dan tidak diragukan, yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur, bersifat sederhana, serasi dan tidak berlebihan (Tim Penyusun Kamus, 1988 : 445).
Istilah klasik tidak sekedar menggolongkan sekelompok bentuk seni menurut tempat atau kelompok orang, akan tetapi sebagai sebutan bentuk kesenian yang mengandung konotasi penting tentang sifat bentuk-bentuk kesenian karena keindahan dan standarnya yang tinggi, dipeliharan sampai ke anak cucu, mengacu kepada suatu gaya dari suatu masa khusus, suatu gaya karena ciri-ciri bentuk yang dapat digambarkan secara jelas. Lebih lanjut istilah klasik menunjukan sifat antik atau tua, sifat mapan dari bentuk-bentuk kesenian yang sudah mencapai suatu keadaan ideal (Jennifer Lindsay, 1989 : 50).
Berbicara tentang Palegongan sebagai bentuk kesenian yang tergolong klasik punya konotasi yang sama dengan kerumitan, bentuk dan standar yang tinggi. Bagaimanapun juga, istilah klasik masih mempunyai hubungan etimologis khusus, jika digunakan utnuk menggambarkan kesenian tradisional. istilah klasik tidak mempunyai petunjuk acuan yang dapat dibandingkan dengan perkembangan selanjutnya. Jika istilah tersebut dipakai untuk mengacu kepada salah satu kesenian yang mencapai puncaknya, sehingga berkaitan dengan gagasan tentang identitas, masa lalu, dan suatu pandangan tentang bentuk yang ideal atau yang optimal, maka istilah klasik selalu menunjuk kepada bentuk terbaru yang dicapai pada masa sebelumnya.
Suatu gagasan bahwa tahap perkembangan yang dicapai oleh Palegongan sebagai kesenian klasik, merupakan tahap yang ideal atau “puncak” dan bukan tahap menengah atau paling rendah, menunjukkan bahwa artistik masa lalu itu sendiri sekarang lebih dihargai. Tetapi implikasi pandangan semacam itu adalah bahwa bentuk kesenian klasik yang telah mencapai puncaknya tidak dapat dikembangkan lebih lanjut, kecuali dilepaskan dari keadaan optimum tersebut, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa setiap perubahan dan bentuk yang ideal dapat berarti kemunduran atau penurunan.
Dalam pendekatan klasik kesenian merupakan pernyataan dari pada idealisme intelektual, didasari oleh seperangkat sistem perlambangan yang menetap, yang dapat berbeda-beda menurut kemampuan setiap seniman dalam cara menyatakan dan cara menyajikannya, serta identitas penghayatannya (Jennifer Lindsay, 1989: 52).
Melalui acuannya kepada sifat mapan dari kesenian klasik, dan gagasan tentang suatu puncak yang telah dicapai, berarti bahwa bentuk-bentuk kesenian yang telah mencapai puncaknya harus dapat dikenali, dan bahwa bentuk puncak juga harus tidak hanya dapat dikenali, tetapi paling tidak dalam teori harus dapat direproduksi. Menekankan identifikasi batasan-batasan formal sebagai ciri pokok kesenian klasik punya implikasi penting bagi cara bagaimana bentuk-bentuk kesenian semacam itu dihargai, dan bagi keputusan-keputusan yang dibuat sebagai usaha mempertahankan bahkan menyelamatkan bentuk-bentuk kesenian tersebut.

by admin | Apr 21, 2010 | Artikel, Berita
Oleh Bendi Yudha
Pengantar Karya seni Lukis
Bahan Akrilik pada Kanvas
Ukuran: 100 X 100 Cm
 Fenomena yang terjadi sekarang ini bahwa dunia materi mengungguli dan bahkan menguasai dunia spiritual, sehingga carut marutnya tatanan kehidupan ini muncul di mana-mana. Nampaknya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan ini sudah mulai luntur yang mendasari pikiran dan prilaku manusia, sehingga segala sesuatunya selalu diukur berdasar atas materi, membuat manusia terninabobokan olehnya bahkan ia menjadi bingung serta lupa akan jati dirinya sebagai manusia. Di sinilah manusia harus menyadari bahwa kunci dari kebingungan tersebut adalah; ia hendaknya insaf serta kembali ke jalan yang benar yaitu menghayati nilai-nilai sastra yang mengajarkan kebenaran untuk menuju jalan keabadian.
Fenomena yang terjadi sekarang ini bahwa dunia materi mengungguli dan bahkan menguasai dunia spiritual, sehingga carut marutnya tatanan kehidupan ini muncul di mana-mana. Nampaknya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan ini sudah mulai luntur yang mendasari pikiran dan prilaku manusia, sehingga segala sesuatunya selalu diukur berdasar atas materi, membuat manusia terninabobokan olehnya bahkan ia menjadi bingung serta lupa akan jati dirinya sebagai manusia. Di sinilah manusia harus menyadari bahwa kunci dari kebingungan tersebut adalah; ia hendaknya insaf serta kembali ke jalan yang benar yaitu menghayati nilai-nilai sastra yang mengajarkan kebenaran untuk menuju jalan keabadian.
Hal tersebut di atas divisualisasikan lewat bentuk uang kepeng dengan ukuran besar sebagai simbol akan besarnya pengaruh kekuatan duniawi terhadap kehidupan manusia, yang seyogyanya harus diimbangi dengan ajaran ajaran spiritual sebagai penyucian diri yang bersumber dari sastra aji merupakan kunci agar tidak terjerumus ke lembah nista. Dalam konteks ini hal tersebut disimbolkan dengan berbagai bentuk dan jenis lontar serta bentuk kunci beralaskan kain putih pada sudut kanan yang mengandung arti bahwa hanya nilai-nilai kesucianlah yang mampu mengantarkan manusia ke alam keabadian.

by admin | Apr 21, 2010 | Artikel, Berita
Oleh I Wayan Gulendra
Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Denpasar
Ringkasan Penelitian
 Seni merupakan ekspresi gejolak jiwa pengalaman imajinatif atas pengamatan dan perenungan terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian dengan kemampuan inteleksi dan intuisi mengintepretasi fenomena artistic yang diekspresikan ke dalam bahasa visual seni rupa. Seni akan mencerminkan latar belakang kebudayaan dan lingkungannya dimana ia diciptakan.
Seni merupakan ekspresi gejolak jiwa pengalaman imajinatif atas pengamatan dan perenungan terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian dengan kemampuan inteleksi dan intuisi mengintepretasi fenomena artistic yang diekspresikan ke dalam bahasa visual seni rupa. Seni akan mencerminkan latar belakang kebudayaan dan lingkungannya dimana ia diciptakan.
Pencipta sebagai bagian dari komunitas masyarakat Bali, dalam berkesenian ternyata fenomena-fenomena social, agama serta pesona keindahan alam lingkungan Bali telah menggetarkan batin dan memberikan rangsangan imajinatif. Hal tersebut memprovokasi aktivitas intuisi , membangun potensi kreatif untuk dicurahkan di atas kanvas. Berangkat dari aktivitas intepretasi terhadap perbedaan sebagai suatu realita keindahan, ketika perbedaan-perbedaan dipahami secara filosofis dari hakekat kehidupan semesta. Perbedaan sesuatu yang hakiki bagi setiap bentuk kehidupan di dunia ini, ketika disusun, dikelola secara harmonis maka terbentuk suatu kehidupan yang dinamis, saling membutuhkan, dan saling menghargai. Fenomena-fenomena tersebut dieksplorasi, diamati, direnungkan sehingga memperolrh gagasan-gagasan kreatif untuk diujudkan kedalam karya seni lukis.
Tujuan penciptaan adalah mengintepretasi fenomena kehidupan masyarakat tentang perbedaan yang sering dijadikan ajang konflik demi kepentingan tertentu, hal tersebut diartikulasikan ke dalam bahasa rupa yang lebih bersifat pribadi.
Untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan penciptaan, maka pencipta menggunakan pendekatan eksploratif secara eksternal maupun internal, artinya setiap fenomena yang diamati secara nyata, kemudian direnungkan, dihayati sehingga memperoreh imajinasi tentang konsep ide, bentuk maupun warna.
Perwujudan ide-ide dalam tataran konsep bentuk dan cara ungkap lebih mengutamakan makna-makna simbolik. Motif-motif yang hadir merupakan perpaduan teknik dan respon tekstur, namun sumber gagasan masih terbaca. Baik dari unsur bentuknya maupun unsur warnanya.
Kata kunci: Beda dalam keselarasan adalah keindahan

by admin | Apr 20, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: Wardizal dan Hendra Santosa
Abstrak Penelitian
 Penelitian ini mencoba mengkaji secara kritis ilmiah tentang fenomena resistensi dan kompromitas, terhadap keterlibatan wanita dalam aktivitas berkesenian di Minangkabau. Secara mendasar, penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran fakta atau informasi tentang adanya anggapan, bahwa melibatkan diri dalam aktivitas berkesenian bagi wanita di Minangkabau merupakan perbuatan ’sumbang’ atau perilaku ’menyimpang’ yang dapat memberi malu pada kaum kerabat pesukuan. Resistensi terutama dari pihak mamak (saudara ibu yang laki-laki), sebagai figur yang berkuasa dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh suku bangsa Minangkabau. Pada sisi lain, fakta empiris menunjukan munculnya beberapa seniman wanita yang kemudian melegenda di tengah masyarakat. Untuk mendapatkan jawaban atas fenomena tersebut, ada tiga masalah penelitian yang relevan diajukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) mengapa terjadi resistensi terhadap keterlibatan wanita dalam aktifitas berkesenian di Minangkabau, terutama dari pihak mamak, (2) Apakah keterlibatan wanita dalam aktifitas berkesenian di Minangkabau merupakan bagian dari proses kompromitas, dan (3) Sejauh mana kontribusi wanita dalam pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional di Minangkabau. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti studi kepustakaan, untuk mendapatkan berbagai informasi dari sumber tertulis. Observasi, untuk mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat. Wawancara dengan informan, nara sumber terpilih dan tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat.
Penelitian ini mencoba mengkaji secara kritis ilmiah tentang fenomena resistensi dan kompromitas, terhadap keterlibatan wanita dalam aktivitas berkesenian di Minangkabau. Secara mendasar, penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran fakta atau informasi tentang adanya anggapan, bahwa melibatkan diri dalam aktivitas berkesenian bagi wanita di Minangkabau merupakan perbuatan ’sumbang’ atau perilaku ’menyimpang’ yang dapat memberi malu pada kaum kerabat pesukuan. Resistensi terutama dari pihak mamak (saudara ibu yang laki-laki), sebagai figur yang berkuasa dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh suku bangsa Minangkabau. Pada sisi lain, fakta empiris menunjukan munculnya beberapa seniman wanita yang kemudian melegenda di tengah masyarakat. Untuk mendapatkan jawaban atas fenomena tersebut, ada tiga masalah penelitian yang relevan diajukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) mengapa terjadi resistensi terhadap keterlibatan wanita dalam aktifitas berkesenian di Minangkabau, terutama dari pihak mamak, (2) Apakah keterlibatan wanita dalam aktifitas berkesenian di Minangkabau merupakan bagian dari proses kompromitas, dan (3) Sejauh mana kontribusi wanita dalam pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional di Minangkabau. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti studi kepustakaan, untuk mendapatkan berbagai informasi dari sumber tertulis. Observasi, untuk mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat. Wawancara dengan informan, nara sumber terpilih dan tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukkan, terjadinya resistensi terhadap keterlibatan wanita dalam aktifitas berkesenian di Minangkabau merupakan suatu proses rekontrukasi sosial. Pemahaman atau wacana yang berkembang di tengah masyakarakat mengidentikkan kehidupan berkesenian dengan dunia laki-laki. Faktor moralias dan etik-kulutural yang didasarkan kepada norma adat dan ajaran agama Islam, memberikan rambu-rambu yang sangat ketat menyangkut tata pergaulan antara wanita dan laki-laki. Dalam konteks berkesenian, ditenggarai tidak terbebas dari eksploitasi seksual yang sangat berpotensi bagi wanita untuk berbuat salah atau sumbang. Secara etik, adat Minangkabau melarang seseorang tidak saja untuk berbuat salah, karena akan membuat malu keluarga melainkan juga mencegahnya sejak awal dalam bentuk perilaku yang dapat menggiring keperbuatan salah itu, yaitu sumbang.
Trauma sejarah terkait dengan fungsi kesenian di masa lalu ikut menjadi pemicu antipati masyarakat terhadap dunia berkesenian. Beberapa bentuk seni pertunjukan rakyat sangat erat kaitanya dengan dunia mistik, magig dan difungsikan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Saluang Sirompak misalnya, pada masa dahulu difungsikan untuk mengguna-gunai seorang gadis akibat cinta seorang pemuda yang ditolak. Wanita yang terkena sirompak biasanya sulit disembuhkan dan tidak jarang menjadi gila. Demikian juga halnya dengan pendukung kesenian di masa lalu yang disebut dengan parewa. Pada dasarnya masyarakat anti kepada sikap dan tingkah laku parewa. Kehadiran mereka menimbulkan konflik psykologis di tengah masyarakat. Golongan adat kurang mempedulikan sikap parewa, sementara golongan alim ulama sangat enggan dan benci kepada parewa, karena semua tingkah laku dan perbuatan mereka bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kesenian yang dikembangkan dan dimainkan oleh parewa juga ikut dibenci oleh golongan alim ulama. Bahkan sampai sekarang, masih terdapat ulama ortodok di Minangkabau yang tetap menganggap kesenian sebagai pekerjaan yang hukumnya haram.
Pada masa sekarang telah terjadi proses demokratisasi proses berkesenian di tengah kehidupan sosio-kulural masyarakat Minangkabau. Wanita telah memainkan peran pada setiap genre kesenian yang ada. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu dan pemacunya, yaitu: (1) Perubahan kebudayaan di tengah masyarakat, yaitu melemahnya peranan keluarga luas (exented family) dan menguatnya peranan keluarga batih (nucleus family). Tangung jawab rumah tangga lebih banyak ke atas pundak suami (ayah) dari pada mamak. Kedekatan hubungan bathin antara seorang anak dengan bapak (ayah) tampaknya lebih banyak menghasilkan proses kompromi dari pada konflik. (2) Berdirinya Lembaga Pendidikan Tinggi Kesenian STSI Padang Panjang (3) Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (4) Perkembangan Industri Pariwisata, dan (5) Tuntutan Kesetaraan Gender.
Kontribusi wanita terhdap perkembangan dan pelestarian kesnian tradisonal Minangkabau, secara kualitatif telah melahirkan beberapa seniman yang melegenda di tengah masyarakat. Dua orang diantara seniman wanita tersebut adalah (1) Syamsimar, tukang dendang dan (2) Gusmiati Suid, penata tari yang cukup punya nama di tingkat Nasional maupun Internasional.

 Pada era globalisasi dewasa ini, intelegensi (IQ) bukanlah segala-galanya. Gardner menyatakan manusia memiliki Kecerdasan Jamak (Multiple Intelligences) yaitu Kecerdasan Matematis-Logis (Logical Mathematical Intelligence), Kecerdasan Linguistik/verbal (Linguistic/verbal = Word Smart), Kecerdasan Ruang Visual (Visual Spatial Intelligence), Kecerdasan Gerakan Fisik (Bodily-kinesthetic Intelligence), Kecerdasan Musik (Musical Intelligence), Kecerdasan Hubungan Sosial (Interpesonal Intelligence), Kecerdasan Diri (Intrapersonal Intelligence), Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence), dan Kecerdasan Natural (Existence Intellegence). Goleman menambahkan satu lagi yaitu Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence). Dalam hal inilah dunia pendidikan ditantang untuk mengembangkan kecerdasan yang dimiliki anak didik, agar dapat menghasilkan manusia-manusia yang memiliki keterampilan hidup (life skill), mempunyai kompetensi pada bidangnya, sehingga dapat sukses menjalani kehidupan di masyarakat.
Pada era globalisasi dewasa ini, intelegensi (IQ) bukanlah segala-galanya. Gardner menyatakan manusia memiliki Kecerdasan Jamak (Multiple Intelligences) yaitu Kecerdasan Matematis-Logis (Logical Mathematical Intelligence), Kecerdasan Linguistik/verbal (Linguistic/verbal = Word Smart), Kecerdasan Ruang Visual (Visual Spatial Intelligence), Kecerdasan Gerakan Fisik (Bodily-kinesthetic Intelligence), Kecerdasan Musik (Musical Intelligence), Kecerdasan Hubungan Sosial (Interpesonal Intelligence), Kecerdasan Diri (Intrapersonal Intelligence), Kecerdasan Spiritual (Spiritual Intelligence), dan Kecerdasan Natural (Existence Intellegence). Goleman menambahkan satu lagi yaitu Kecerdasan Emosional (Emotional Intelligence). Dalam hal inilah dunia pendidikan ditantang untuk mengembangkan kecerdasan yang dimiliki anak didik, agar dapat menghasilkan manusia-manusia yang memiliki keterampilan hidup (life skill), mempunyai kompetensi pada bidangnya, sehingga dapat sukses menjalani kehidupan di masyarakat.