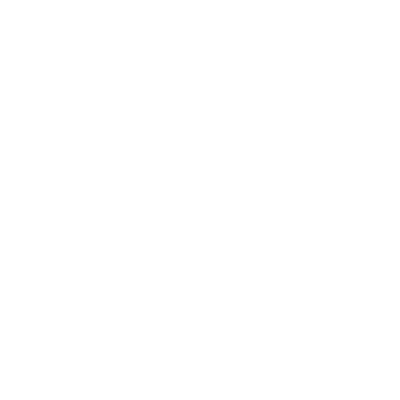by admin | May 18, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: I Wayan Budiarsa Dosen PS Seni Tari
 Salah satu sarana untuk mempertebal keyakinan dan menghubungkan diri dengan Ida Sanghyang Widi Wasa ( Tuhan Yang Maha Esa) adalah dengan cara berkesenian. Tari Rejang Sutri pada umumnya mempunyai fungsi sebagai sarana upacara dalam rangkaian suatu upacara piodalan ( Dewa Yadnya). Karena agama Hindu dalam menghubungkan diri dengan Tuhan lebih banyak dengan menggunakan simbul-simbul, seperti halnya dengan sarana tulisan aksara suci, upakara/ banten, berkesenian ( tari ) dan lain sebagainya. Berbagai jenis tarian Bali menampakan adanya hubungan yang erat dengan aktivitas keagamaan dan juga berkembang menjadi tari-tarian yang dipentaskan di atas panggung. Baik seni pertunjukan sebagai sarana upacara atau ritual, sebagai hiburan maupun sebatas penyajian estetis semata. Masyarakat Hindu di Bali dalam berkesenian akan dilengkapi pula pelaksanaan ritual dengan upacara sesajen ( banten) sesuai dengan adat daerahnya masing-masing, dimana upacara tersebut akan berpedoman pada filsafat konsep Tri Kona yaitu Desa (tempat), Kala (waktu) dan Patra (kondisi/ keadaan). Seusai pertunjukan diharapkan mendatangkan kedamaian di dunia ini secara lahir bathin, makanya saat-saat tertentu dapat kita jumpai adanya pementasan tari Sanghyang, Rejang, Topeng, Barong, Baris Gede, Barong Ketingkling dan sebagainya.
Salah satu sarana untuk mempertebal keyakinan dan menghubungkan diri dengan Ida Sanghyang Widi Wasa ( Tuhan Yang Maha Esa) adalah dengan cara berkesenian. Tari Rejang Sutri pada umumnya mempunyai fungsi sebagai sarana upacara dalam rangkaian suatu upacara piodalan ( Dewa Yadnya). Karena agama Hindu dalam menghubungkan diri dengan Tuhan lebih banyak dengan menggunakan simbul-simbul, seperti halnya dengan sarana tulisan aksara suci, upakara/ banten, berkesenian ( tari ) dan lain sebagainya. Berbagai jenis tarian Bali menampakan adanya hubungan yang erat dengan aktivitas keagamaan dan juga berkembang menjadi tari-tarian yang dipentaskan di atas panggung. Baik seni pertunjukan sebagai sarana upacara atau ritual, sebagai hiburan maupun sebatas penyajian estetis semata. Masyarakat Hindu di Bali dalam berkesenian akan dilengkapi pula pelaksanaan ritual dengan upacara sesajen ( banten) sesuai dengan adat daerahnya masing-masing, dimana upacara tersebut akan berpedoman pada filsafat konsep Tri Kona yaitu Desa (tempat), Kala (waktu) dan Patra (kondisi/ keadaan). Seusai pertunjukan diharapkan mendatangkan kedamaian di dunia ini secara lahir bathin, makanya saat-saat tertentu dapat kita jumpai adanya pementasan tari Sanghyang, Rejang, Topeng, Barong, Baris Gede, Barong Ketingkling dan sebagainya.
Di Desa Pakraman Batuan tari Rejang Sutri mempunyai fungsi sebagai tari upacara ( ritual ), pada saat sasih kelima ( bulan Nopember ) sampai sasih kesanga ( bulan Maret ) tahun berikutnya yang di barengi dengan upacara Bhuta Yadnya. Kalau dilihat fungsi dari Rejang Sutri dapat dikategorikan sebagai tari sacral atau wali, tinjauan yang lain yaitu sebagai tari tolak bala dirunut dari saat dilaksanakan sampai prosesi upacara/ upakara yang gunakan. Rentetan upacara saat Rejang Sutri dilaksanakan adalah pertama mengadakan upacara Dewa Yadnya yaitu melaksanakan upacara persembahyangan di Pura Desa dan Puseh, Ratu Ngurah Agung, Ratu Saung, Ratu Pase Leb ( matur piuning ) yang diantar oleh pemangku desa Batuan dengan sarana upakara pejati jangkep, canang sari, petabuh dan sebagainya. Sedangkan untuk masing-masing keluarga menghaturkan upakara pejati jangkep ke Pura Desa/ Puseh selanjutnya di upacarai oleh pemangku selanjutnya dibawa pulang untuk di tempatkan di pura keluarga ( sanggah,merajan) di sanggah kemulan. Setiap harinya menghaturkan upakara canang dan di lebar saat Rejang Sutri usai ( nyineb ). Kedua, mengadakan atau melaksanakan upacara mecaru ( bhuta yadnya) yang dilaksanakan di Pura Desa dan Puseh pada siang hari sebelum nanti malamnya dilaksanakan Rejang Sutri, mecaru di tapal batas Desa Batuan yaitu di ujung banjar Dentiyis batas utara, di ujung banjar Jeleka batas barat, di ujung banjar Puaya simbul batas selatan, di ujung banjar Peninjoan sebagai simbul batas timur. Mecaru di masing-masing tapal batas desa Batuan diantaranya menggunakan sarana boki diisi tapak dara, wastra poleng, kayu sakti ( carang dadap ) jeroan babi sebagai symbol pengamer-amer. Dilanjutkan mecaru di masing-masing banjar, kemudian di muka rumah masing-masing anggota masyarakat atau depan pintu masuk ( angkul-angkul) saat senja ( sandikala ), dan pada malam harinya di laksanakan tari Rejang Sutri, yang sebelumnya diawali dengan menghaturkan sesajen berupa Pejati yang dihaturkan di Pura Desa dan di tempat pertunjukan. Pejati yang di haturkan di tempat pertunjukan yaitu di Sanggar Tawang wantilan Pura Desa di sudut timur laut ( Ersanya) yang dilakukan oleh Pemangku Desa. Sanggar Tawang tersebut merupakan tempat upakara sesaji/ banten, untuk setiap harinya sudah ada yang bertugas menghaturkan upacara, tempat berstananya Widyadara-widyadari, Bethara-Bethari, tempat pemujaan masyarakat Batuan saat Rejang Sutri dilaksanakan.
Fungsi Wali Tari Rejang Sutri selengkapnya

by admin | May 17, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: Wardizal (dosen PS Seni Karawitan)
 Minangkabau, sering dikenal sebagai bentuk kebudayaan dari pada sebagai bentuk negara yang perah ada dalam sejarah (Navis, 1984:1). Secara umum, perkataan Minangkabau mempunyai dua pengertian, pertama Minangkabau sebagai tempat berdirinya kerajaan Pagaruyung. Kedua, Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah tersebut (Mansoer, 1970:58). Kerajaan Pagaruyung yang pada masa dahulu pernah menguasai daerah budaya Minangkabau, tampaknya tidak banyak memberikan atau meninggalkan pengaruh yang nyata terhadap budaya rakyat Minangkabau sampai sekarang. Dewasa ini, kharisma kerajaan Pagaruyung telah terlupakan begitu saja oleh masyarakat Minangkabau. Istilah Minangkabau tidak lagi mempunyai konotasi sebuah daerah kerajaan, akan tetapi lebih mengandung pengertian sebuah kelompok etnis atau kebudayaan yang didukung oleh suku bangsa Minangkabau (Hajizar, 1988:31).
Minangkabau, sering dikenal sebagai bentuk kebudayaan dari pada sebagai bentuk negara yang perah ada dalam sejarah (Navis, 1984:1). Secara umum, perkataan Minangkabau mempunyai dua pengertian, pertama Minangkabau sebagai tempat berdirinya kerajaan Pagaruyung. Kedua, Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis yang mendiami daerah tersebut (Mansoer, 1970:58). Kerajaan Pagaruyung yang pada masa dahulu pernah menguasai daerah budaya Minangkabau, tampaknya tidak banyak memberikan atau meninggalkan pengaruh yang nyata terhadap budaya rakyat Minangkabau sampai sekarang. Dewasa ini, kharisma kerajaan Pagaruyung telah terlupakan begitu saja oleh masyarakat Minangkabau. Istilah Minangkabau tidak lagi mempunyai konotasi sebuah daerah kerajaan, akan tetapi lebih mengandung pengertian sebuah kelompok etnis atau kebudayaan yang didukung oleh suku bangsa Minangkabau (Hajizar, 1988:31).
Realias yang berkembang di tengah masyarakat (terutama orang luar Minangkabau), kata Minangkabau sering diidentikkan dengan kata Sumatera Barat pada hal secara subtantif keduanya mempunyai makna yang berbeda. Perkembangan sejarah menunjukkan, bahwa daerah geografis Minangkabau tidak merupakan bagian daerah propinsi Sumatera Barat (Mansoer, 1970:1). Sumatera Barat adalah salah satu propinsi menurut administratif pemerintahan RI, sedangkan Minangkabau adalah teritorial menurut kultur Minangkabau yang daerahnya jauh lebih luas dari Sumatra Barat sebagai salah satu propinsi (Hakimy, 1994:18).
Secara administratif, propinsi Sumetara Barat mempunyai 14 daerah tingkat II, terdiri dari 8 daerah tingkat II yang tercakup dalam kapupaten, dan 6 daerah yang tercakup dalam Kota Madya. Delapan (8) kabupaten terdiri dari kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Solok, Pariaman, Sawah Lunto Sijunjung, 50 Kota, dan Padang Pariaman. Enam (6) Kota Madya terdiri dari Kota Madya Padang, Solok, Sawah Lunto, Payakumbuh, Padang Panjang dan Bukittinggi. Batas-batas propinsi yang berbatasan dengan Sumatera Barat Adalah: sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia; bahagian utara berbatasan dengan Sumatera Utara; sebelah selatan berbatasan dengan propinsi Bengkulu dan propinsi Jambi; dan sebelah timur berbatasan dengan propinsi Riau.
Minangkabau dalam pengertian sosial budaya merupakan suatu daerah kelompok etnis yang mendiami daerah Sumatera Barat sekarang, ditambah dengan daerah kawasan pengaruh kebudayaan Minangkabau seperti: daerah utara dan timur Sumatera Barat, yaitu Riau daratan, Negeri Sembilan Malaysia; daerah selatan dan timur yaitu; daerah pedalaman Jambi, daerah pesisir pantai sampai ke Bengkulu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia (Couto dalam Arisman, 2001:56). Tidak ada yang dinamakan suku bangsa Sumatera Barat atau kebudayaan Sumatera Barat. Namun secara praktis pemerintah Daerah Tingkat I propinsi Sumatera Barat-lah yang menggerakkan kebudayaan Minangkabau. Boestanoel Arifin Adam mengatakan:
Pengertian Minangkabau selengkapnya

by admin | May 17, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: Ida Ayu Gede Artayani, S.Sn, M.Sn., Dosen PS Kriya Seni
 Usaha kerajina gerabah di Desa Binoh merupakan usaha industri rumah tangga yang sifatnya sudah turun-temurun. Pembuatan kerajinan ini merupakan mata pencaharian yang cukup mendapat perhatian dari para kaum wanita di desa ini. Usaha kerajinan ini ditekuni oleh mereka yang sudah berumah tangga, maupun yang masih lajang. Sesuai dengan hasil surve yang diperoleh dilapangan, ada beberapa faktor pendorong dari kaum wanita untuk bekerja pada usaha kerajinan gerabah antara lain:
Usaha kerajina gerabah di Desa Binoh merupakan usaha industri rumah tangga yang sifatnya sudah turun-temurun. Pembuatan kerajinan ini merupakan mata pencaharian yang cukup mendapat perhatian dari para kaum wanita di desa ini. Usaha kerajinan ini ditekuni oleh mereka yang sudah berumah tangga, maupun yang masih lajang. Sesuai dengan hasil surve yang diperoleh dilapangan, ada beberapa faktor pendorong dari kaum wanita untuk bekerja pada usaha kerajinan gerabah antara lain:
- Faktor Ekonomi
Pembangunan pertanian di Indonesia mampu meningkatkan pendapatan petani khususnya dan penduduk pedesaan pada umumnya. Ini terbukti dengan semakin kecilnya jumlah penduduk miskin di pedesaan. Disamping itu perlu diperhatikan masih banyaknya penduduk yang memusatkan bekerja di sektor pertanian.
Hal ini menyebabkan tambahan tenaga kerja disektor pertanian lebih besar dari kepemilikan lahan.
Lahan pertanian yang kian hari semakin sempit tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga petani yang bersangkutan. Hal ini berarti rumah tangga petani harus meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan diluar sektor pertanian.
Pekerjaan-pekerjaan di luar sektor pertanian, seperti misalnya pekerjaan dalam industri rumah tangga atau industri kecil, sudah dikenal di daerah pedesaan sejak lama. Keberadaan pekerjaan di luar sektor pertanian ini penting artinya bagi rumah tangga petani. Hal ini berkaitan dengan sifat musim kegiatan di bidang pertanian. Pada umumnya keluarga petani membutuhkan pekerjaan di luar sektor pertanian untuk menambah penghasialannya. ( Mubyanto, 1985: 45).
Demikian pula halnya keadaan penduduk di Desa Binoh, kepemilikan lahan pertanian semakin sempit, berubah menjadi kawasan perumahan. Kepemilikan lahan rata-rata 0,16 Ha per kepala keluarga. Melihat kenyataan yang demikian, pendapatan dari sektor pertanian tidak memungkinkan lagi sebagai penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu bukan saja kaum laki-lakinya, kaum wanitanya pun dituntut untuk mencari nafkah di sektor lain. Menurut informasi yang diterima, kerajinan gerabah yang ada di desa ini sudah ada sejak dulu, mereka tidak bisa menyebutkan angka dan tahunnya, karena mereka mewarisi kerajinan ini sejak lahir. Hal ini memungkinkan para wanita di desa ini tidak banyak terlibat dalam pekerjaan pertanian sehingga mereka banyak mempunyai waktu luang setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Hanya saja waktu itu pekerjaan mereka bersifat kecil-kecilan. Peralatan yang dipergunakan dalam pembuatan gerabah masih sangat sederhana, begitu pula bentuk-bentuk barang yang dibuat tidak banyak variasi dan pemasaarannya masih bersifat lokal.
Faktor – faktor Yang Mendorong Wanita Bekerja pada Usaha Kerajinan Gerabah Di Desa Binoh Kelurahan Ubung Kaja Denpasar selengkapnya

by admin | May 16, 2010 | Artikel, Berita
Oleh Hendra Santosa, Dosen PS Seni Karawitan
Hasil wawancara dengan Wardizal dan Kadek Wahyu dengan I Wayan Sinti, MA, pada Hari Sabtu, 27 Oktober 2007
 Secara mendasar, proses penciptaan gamelan Siwa Nada bertitik tolak dari gamelan Manika Santi. Pada barungan gamelan Manika Santi, hanya bisa dimainkan gendhing-gendhing gamelan Bali. Gamelan Manika Santi tidak bisa digunakan untuk memainkan musik-musik dari negara lain seperti musik Barat, China, India, Jepang, dan lain-lain karena masalah interval. Oleh karena itu, nada-nada yang terdapat dalam barungan gamelan Manika Santi tersebut dicoba ditata kembali, baik jumlah nada maupun interval. Karena secara prinsip musik Barat sudah mempunyai standar tuning, berbeda dengan musik tradisi pada umumnya. Melalui percobaan-percobaan yang tidak mengenal lelah, akhirnya terwujudlah satu bentuk barungan gamelan baru yang disebut Siwa Nada dengan harapan bisa dijadikan sebagai Ensiklopedi Musik Dunia. Dengan perkataan lain, sebuah bentuk/jenis gamelan yang bisa difungsikan untuk memainkan repertoar dari berbagai jenis musik dunia.
Secara mendasar, proses penciptaan gamelan Siwa Nada bertitik tolak dari gamelan Manika Santi. Pada barungan gamelan Manika Santi, hanya bisa dimainkan gendhing-gendhing gamelan Bali. Gamelan Manika Santi tidak bisa digunakan untuk memainkan musik-musik dari negara lain seperti musik Barat, China, India, Jepang, dan lain-lain karena masalah interval. Oleh karena itu, nada-nada yang terdapat dalam barungan gamelan Manika Santi tersebut dicoba ditata kembali, baik jumlah nada maupun interval. Karena secara prinsip musik Barat sudah mempunyai standar tuning, berbeda dengan musik tradisi pada umumnya. Melalui percobaan-percobaan yang tidak mengenal lelah, akhirnya terwujudlah satu bentuk barungan gamelan baru yang disebut Siwa Nada dengan harapan bisa dijadikan sebagai Ensiklopedi Musik Dunia. Dengan perkataan lain, sebuah bentuk/jenis gamelan yang bisa difungsikan untuk memainkan repertoar dari berbagai jenis musik dunia.
Secara filosofis, pemberian nama Siwa Nada pada barungan gamelan ini didasarkan atas keyakinan umat hindu di Bali bahwa Siwa adalah sebagai Dewa (pencipta). Gamelan Siwa Nada dapat diartikan sebagai gamelan yang mepergunakan nada-nada ciptaan Dewa Siwa. Secara spsifik, pemberian nama Siwa Nada lebih bersifat praktis dan pragmatis dimana, Si merupakan singkatan dari Sinti; Wa berarti Nawa (sembilan) atau Washington. Dengan demikian, Siwa nada dapat diartikan gamelan sembilan nada ciptaan Sinti di Washington. Ide penciptaan gamelan ini sudah pernah diekspos di koran Bali pada tahun 1998 untuk menciptakan tangga nada baru 9 atau 12, khususnya 9. Dalam perkembanganya kemudian, proses penciptaanya dilakukan Sinti ketika berada di Amerika (Washington). Proses penciptaan dilakukan pada tahun 2004 dan selesai (diupacarai) tepat purnama 17 Oktober 2005, lebih kurang 1 tahun 49 hari.
Secara umum instrumen gamelan Siwa Nada berbentuk bilah, kalau berbentuk pencon akan memakan waktu dan lebih rumit. Oleh karena di Amerika sulit mendapatkan kerawang, maka dipergunakan baja. Di samping itu, di Amaerika sulit mendapatkan bambu yang bagus, maka dipakai kayu (kayu padok) yang dibeli dari Ghana, Afrika. Setelah Sinti pulang ke Bali, kemudian dibuatkan istrumen dari kerawang. Dengan demikian, instrumen-instrumen yang terdapat dalam gamelan Siwa Nada merupakan kombinasi antara kerawang dan bambu. Barungan gamelan Siwa Nada sengaja dibuat dalam jumlah yang kecil, untuk dikombinasikan dengan vokal. Kalau barungannya lebih besar, akan bisa mengakibatkan vokal tenggelam. Jenis vokal yang dimaksud khususnya “Wirama”, dimana intervalnya sangat pendek-pendek. Kalaupun ada gamelan lain seperti gender wayang atau gong, hanya sebagai ilustrasi. Hal yang diinginkan adalah interlocking antara gamelan dan vokal.
Gamelan Siwa Nada selengkapnya

by admin | May 15, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: Drs. I Made Mertanadi, M.Si (Dosen PS Kriya Seni)
Ringkasan Penelitian
 Masyarakat Hindu di Bali melaksanakan begitu banyak jenis kegiatan upacara yadnya, baik dalam rutin atau acara tertentu. Dalam setiap pelaksanaan upacara memakai sarana berbagai jenis banten. Akan tetapi dalam pelaksanaan yadnya ini masyarakat belum memahami sepenuhnya maksud dari upacara tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan perilaku keagamaan tidak sepenuhnya dimengerti dan dipahami. Masyarakat Hindu di Bali pada umumnya menaruh perhatian yang sangat besar pada masalah yadnya, Mereka melaksanakan yadnya dengan penuh kesadaran dan beraktivitas sesuai dengan adat budaya setempat. Pemakaian jenis-jenis sarana serangkaian pelaksanaan yadnya disebut upakara. Adapun jenis sarana dalam upacara yadnya yaitu air dan api. Pengunaan air dan api sebagai sarana dalam suatau upacara yadnya memerlukan suatu tempat atau wadah yang disebut gerabah.
Masyarakat Hindu di Bali melaksanakan begitu banyak jenis kegiatan upacara yadnya, baik dalam rutin atau acara tertentu. Dalam setiap pelaksanaan upacara memakai sarana berbagai jenis banten. Akan tetapi dalam pelaksanaan yadnya ini masyarakat belum memahami sepenuhnya maksud dari upacara tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan perilaku keagamaan tidak sepenuhnya dimengerti dan dipahami. Masyarakat Hindu di Bali pada umumnya menaruh perhatian yang sangat besar pada masalah yadnya, Mereka melaksanakan yadnya dengan penuh kesadaran dan beraktivitas sesuai dengan adat budaya setempat. Pemakaian jenis-jenis sarana serangkaian pelaksanaan yadnya disebut upakara. Adapun jenis sarana dalam upacara yadnya yaitu air dan api. Pengunaan air dan api sebagai sarana dalam suatau upacara yadnya memerlukan suatu tempat atau wadah yang disebut gerabah.
Penelitian ini pada prinsipnya hendak mengetahui dan mendiskripsikan gerabah dalam upacara yadnya pada masyarakat Hindu di Bali dari dimensi bentuk, fungsi, dan makna. Teori yang digunakan, yakni untuk mengungkap bentuk digunakan teori Estetika, mengungkap fungsi digunakan teori Fungsionalisme Struktural, dan untuk mengungkap makna digunakan teori Simbol. Metode yang digunakan adalah (1) Pengumpulan data dengan Habermes, observasi, wawancara, dan analisis dokumen (2) Analisis data (3) Pengecekan dan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.
Penelitian ini menemukan bahwa dalam upacara yadnya pada masyarakat Hindu di Bali, bentuk gerabah yang digunakan antara lain coblong, caratan, pasepan, dandang, paso (pane), payuk pere (jun pere), payuk Siwa Budha, puluk-puluk ari-ari, puluk-puluk pedagingan (pendeman), sesenden, gentong, eteh-eteh pedudusan, dan kumbecarat. Fungsi gerabah adalah sebagai wadah air, api, bunga, biji-bijian, buah, dan daun. Makna gerabah terdiri dari makna relegi dan makna filosofis. Makna relegi yaitu sebagai simbol kumunikasi religius antara manusia dengan Tuhan, yang pada hakikatnya manusia dalam bertindak melaksanakan yadnya selalu memikirkan Tuhan. Makna filosofis yaitu bentuk gerabah dalam upacara yadnya bundar adalah simbol bumi (bhuana agung) dan segala bentuk isinya adalah simbol bhuana alit. Makna yang terkandung adalah sebagai simbol penyatuan wadah dengan isinya, yaitu penyatuan antara bhuana agung (alam makrokosmos) dan bhuana alit (alam mikrokosmos).

by admin | May 15, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: I Wayan Budiarsa
Dibiayai DIPA ISI Denpasar tahun 2009
 Rejang Sutri adalah nama tarian yang yang terdapat di daerah Gianyar tepatnya di Desa Pakraman Batuan, Sukawati, Gianyar yang oleh masyarakat Batuan sangat di sakralkan keberadaanya. Rejang Sutri ditarikan oleh penari perempuan baik dari usia anak-anak, muda maupun tua. Dari sekian banyak tari rejang sakral yang ada di Bali, Rejang Sutri di desa Batuan memiliki keunikan atau gaya tersendiri yaitu mulai di tarikan/ ngawit masolah menurut sasih penanggalan kalender Bali yaitu sasih / bulan kelima ( lima) dengan mencari hari/rerahinan kliwon, kajeng kliwon, purnama ataupun tilem sesuai pawisik yang diterima oleh pemangku Desa Batuan, dengan mempersembahkan beberapa sarana upacara dan upakara. Kalau diperkirakan mulai sekitar bulan Nopember sampai bulan Maret (tahun berikutnya ), dan berakhir atau nyineb/ngeluhur pada saat sasih kasanga bertepatan dengan upacara malam Ngembak Geni sehari setelah Hari Raya Nyepi yang merupakan hari perayaan tahun baru Saka Agama Hindu. Jadi sekitar empat bulan kalender masehi, ini dilaksanakan setiap hari dengan cara bergiliran dari delapan banjar pangempon yaitu Banjar Puaya, Banjar Jeleka, Banjar Tengah, Banjar Pekandelan, Banjar Dentiyis, Banjar Delodtunon, Banjar Peninjoan, Banjar Jungut dan satu tempekan/ kelompok Tri Wangsa. Sebagai tarian Rejang yang disakralkan sudah barang tentu terkandung makna filosofis yang sangat kental. Untuk mengetahui sejarah timbulnya tari Rejang Sutri di desa Batuan sangatlah sulit, karena tidak adanya catatan-catatan, literatur, buku-buku yang menyebutkan tentang tari Rejang Sutri ini. Hanya keterangan secara lisan yang secara turun temurun telah dipercaya oleh masyarakat Batuan. Keterangan itu adalah berawal dari kekalahan Ratu Gede Mecaling (menguasai ilmu hitam ) atas I Dewa Babi mengakibatkan terciptanya tarian Rejang Sutri tersebut. Kejadian tersebut kira-kira terjadi pada abad ke 17 (1658 Masehi), saat kerajaan Sukawati dipegang oleh Ida Sri Aji Maha Sirikan yang bergelar I Dewa Agung Anom dan nama lainnya Sri Wijaya Tanu. Masyarakat Batuan percaya dengan keberadaan Ratu I Gede Mecaling dari Nusa Penida yang sekiranya sewaktu-waktu akan mengganggu ketentraman masyarakat desa Batuan. Dimana legenda/ mitos, kepercayaan ini telah dipercaya secara turun temurun dan telah berakar di hati masyarakat Batuan umumnya. Kepercayaan terhadap seorang tokoh I Gede Mecaling yang sangat sakti, tinggal di tegallinggah banjar Jungut Batuan melawan I Dewa Babi, kekalahan itu mengakibatkan I Gede Mecaling terusir dari Batuan dan akhirnya tinggal di Jungut Batu Nusa Penida Kabupataen Klungkung. Kekalahan tersebut membuat beliau murka dan ingin membalas dendam kepada keturunan I Dewa Babi, masyarakat Batuan serta siapa saja yang berani datang ke Nusa Penida akan mendapatkan celaka. Untuk mengalihkan kemarahan Gede Mecaling beserta pengikutnya akhirnya terciptalah tarian Rejang Sutri tersebut. Namun pada masa sekarang ini beberapa orang masyarakat batuan sudah sering melakukan persembahyangan ke Pura Dalem Peed Nusa Penida tempat berstananya Ratu Gede Mecaling, tetapi tidak terjadi apa-apa, dan mudah-mudahan beliau melupakan kejadian masa lalu dan memberikan keselamatan kepada kehidupan kita. Bahkan suatu kepercayaan bahwa pada mulai sasih kelima ( sekitar bulan Nopember) sampai sasih kesanga ( bulan Maret) tahun berikutnya dikenal masa berjangkitnya bermacam-macam penyakit ( wabah) dan dirasakan sebagai saat-saat sangat genting, kepercayaan masyarakat Desa Batuan saat inilah I Gede Mecaling sedang berkelana di Bali untuk mencari labaan ( tumbal ) dan menyebar gering/ penyakit. Maka, khususnya di Batuan menggelar pertunjukan Rejang Sutri untuk meminimalisir pengaruh negatif saat bulan-bulan tersebut.
Rejang Sutri adalah nama tarian yang yang terdapat di daerah Gianyar tepatnya di Desa Pakraman Batuan, Sukawati, Gianyar yang oleh masyarakat Batuan sangat di sakralkan keberadaanya. Rejang Sutri ditarikan oleh penari perempuan baik dari usia anak-anak, muda maupun tua. Dari sekian banyak tari rejang sakral yang ada di Bali, Rejang Sutri di desa Batuan memiliki keunikan atau gaya tersendiri yaitu mulai di tarikan/ ngawit masolah menurut sasih penanggalan kalender Bali yaitu sasih / bulan kelima ( lima) dengan mencari hari/rerahinan kliwon, kajeng kliwon, purnama ataupun tilem sesuai pawisik yang diterima oleh pemangku Desa Batuan, dengan mempersembahkan beberapa sarana upacara dan upakara. Kalau diperkirakan mulai sekitar bulan Nopember sampai bulan Maret (tahun berikutnya ), dan berakhir atau nyineb/ngeluhur pada saat sasih kasanga bertepatan dengan upacara malam Ngembak Geni sehari setelah Hari Raya Nyepi yang merupakan hari perayaan tahun baru Saka Agama Hindu. Jadi sekitar empat bulan kalender masehi, ini dilaksanakan setiap hari dengan cara bergiliran dari delapan banjar pangempon yaitu Banjar Puaya, Banjar Jeleka, Banjar Tengah, Banjar Pekandelan, Banjar Dentiyis, Banjar Delodtunon, Banjar Peninjoan, Banjar Jungut dan satu tempekan/ kelompok Tri Wangsa. Sebagai tarian Rejang yang disakralkan sudah barang tentu terkandung makna filosofis yang sangat kental. Untuk mengetahui sejarah timbulnya tari Rejang Sutri di desa Batuan sangatlah sulit, karena tidak adanya catatan-catatan, literatur, buku-buku yang menyebutkan tentang tari Rejang Sutri ini. Hanya keterangan secara lisan yang secara turun temurun telah dipercaya oleh masyarakat Batuan. Keterangan itu adalah berawal dari kekalahan Ratu Gede Mecaling (menguasai ilmu hitam ) atas I Dewa Babi mengakibatkan terciptanya tarian Rejang Sutri tersebut. Kejadian tersebut kira-kira terjadi pada abad ke 17 (1658 Masehi), saat kerajaan Sukawati dipegang oleh Ida Sri Aji Maha Sirikan yang bergelar I Dewa Agung Anom dan nama lainnya Sri Wijaya Tanu. Masyarakat Batuan percaya dengan keberadaan Ratu I Gede Mecaling dari Nusa Penida yang sekiranya sewaktu-waktu akan mengganggu ketentraman masyarakat desa Batuan. Dimana legenda/ mitos, kepercayaan ini telah dipercaya secara turun temurun dan telah berakar di hati masyarakat Batuan umumnya. Kepercayaan terhadap seorang tokoh I Gede Mecaling yang sangat sakti, tinggal di tegallinggah banjar Jungut Batuan melawan I Dewa Babi, kekalahan itu mengakibatkan I Gede Mecaling terusir dari Batuan dan akhirnya tinggal di Jungut Batu Nusa Penida Kabupataen Klungkung. Kekalahan tersebut membuat beliau murka dan ingin membalas dendam kepada keturunan I Dewa Babi, masyarakat Batuan serta siapa saja yang berani datang ke Nusa Penida akan mendapatkan celaka. Untuk mengalihkan kemarahan Gede Mecaling beserta pengikutnya akhirnya terciptalah tarian Rejang Sutri tersebut. Namun pada masa sekarang ini beberapa orang masyarakat batuan sudah sering melakukan persembahyangan ke Pura Dalem Peed Nusa Penida tempat berstananya Ratu Gede Mecaling, tetapi tidak terjadi apa-apa, dan mudah-mudahan beliau melupakan kejadian masa lalu dan memberikan keselamatan kepada kehidupan kita. Bahkan suatu kepercayaan bahwa pada mulai sasih kelima ( sekitar bulan Nopember) sampai sasih kesanga ( bulan Maret) tahun berikutnya dikenal masa berjangkitnya bermacam-macam penyakit ( wabah) dan dirasakan sebagai saat-saat sangat genting, kepercayaan masyarakat Desa Batuan saat inilah I Gede Mecaling sedang berkelana di Bali untuk mencari labaan ( tumbal ) dan menyebar gering/ penyakit. Maka, khususnya di Batuan menggelar pertunjukan Rejang Sutri untuk meminimalisir pengaruh negatif saat bulan-bulan tersebut.

 Salah satu sarana untuk mempertebal keyakinan dan menghubungkan diri dengan Ida Sanghyang Widi Wasa ( Tuhan Yang Maha Esa) adalah dengan cara berkesenian. Tari Rejang Sutri pada umumnya mempunyai fungsi sebagai sarana upacara dalam rangkaian suatu upacara piodalan ( Dewa Yadnya). Karena agama Hindu dalam menghubungkan diri dengan Tuhan lebih banyak dengan menggunakan simbul-simbul, seperti halnya dengan sarana tulisan aksara suci, upakara/ banten, berkesenian ( tari ) dan lain sebagainya. Berbagai jenis tarian Bali menampakan adanya hubungan yang erat dengan aktivitas keagamaan dan juga berkembang menjadi tari-tarian yang dipentaskan di atas panggung. Baik seni pertunjukan sebagai sarana upacara atau ritual, sebagai hiburan maupun sebatas penyajian estetis semata. Masyarakat Hindu di Bali dalam berkesenian akan dilengkapi pula pelaksanaan ritual dengan upacara sesajen ( banten) sesuai dengan adat daerahnya masing-masing, dimana upacara tersebut akan berpedoman pada filsafat konsep Tri Kona yaitu Desa (tempat), Kala (waktu) dan Patra (kondisi/ keadaan). Seusai pertunjukan diharapkan mendatangkan kedamaian di dunia ini secara lahir bathin, makanya saat-saat tertentu dapat kita jumpai adanya pementasan tari Sanghyang, Rejang, Topeng, Barong, Baris Gede, Barong Ketingkling dan sebagainya.
Salah satu sarana untuk mempertebal keyakinan dan menghubungkan diri dengan Ida Sanghyang Widi Wasa ( Tuhan Yang Maha Esa) adalah dengan cara berkesenian. Tari Rejang Sutri pada umumnya mempunyai fungsi sebagai sarana upacara dalam rangkaian suatu upacara piodalan ( Dewa Yadnya). Karena agama Hindu dalam menghubungkan diri dengan Tuhan lebih banyak dengan menggunakan simbul-simbul, seperti halnya dengan sarana tulisan aksara suci, upakara/ banten, berkesenian ( tari ) dan lain sebagainya. Berbagai jenis tarian Bali menampakan adanya hubungan yang erat dengan aktivitas keagamaan dan juga berkembang menjadi tari-tarian yang dipentaskan di atas panggung. Baik seni pertunjukan sebagai sarana upacara atau ritual, sebagai hiburan maupun sebatas penyajian estetis semata. Masyarakat Hindu di Bali dalam berkesenian akan dilengkapi pula pelaksanaan ritual dengan upacara sesajen ( banten) sesuai dengan adat daerahnya masing-masing, dimana upacara tersebut akan berpedoman pada filsafat konsep Tri Kona yaitu Desa (tempat), Kala (waktu) dan Patra (kondisi/ keadaan). Seusai pertunjukan diharapkan mendatangkan kedamaian di dunia ini secara lahir bathin, makanya saat-saat tertentu dapat kita jumpai adanya pementasan tari Sanghyang, Rejang, Topeng, Barong, Baris Gede, Barong Ketingkling dan sebagainya.