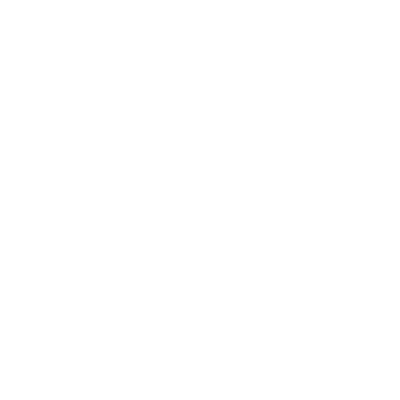by admin | May 28, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: I Made Suparta, Dosen PS Kriya Seni
 Kecamatan Manggis yang memiliki luas wilayah 69,83 km2 dengan jumlah penduduk 47.202 jiwa berada dibagian Selatan Kabupaten Karangasem dengan jarak tempuh 9 KM dari kota Karangasem. Kecamatan yang sarat dengan mitos, adat dan tradisi megeret pandan ternyata memiliki berbagai potensi profesi yang cukup beragam. Lebih membanggakan lagi, berbagai jenis seni , budaya, adat dan kerajinan sampai saat ini masih tetap berlanjut. Tenganan yang identik dengan kain klasik pegringsingan dan megeret pandan juga memiliki potensi dibidang pembuatan prasi. Secara visual bentuk dan teknik tampilan prasi yang berkembang di Desa Tenganan ada perbedaan dengan yang di Sidemen. Bentuk penampilan tokoh yang ada dalam lembaran sebuah daun rontal dihiasi dengan beberapa tokoh atau setiap adegan/babak digambar beberapa tokoh. Untuk sebuah ceritera seperti memerlukan beberapa lembar daun rontal. Tampilan wujud visual dibuat dengan merangkai lembaran-lembaran daun rontal yang menggunakan seutas benang. Untuk merangkai lembaran-lembaran daun rontal tersebut dengan cara melobangi kedua sisi dan bagian tengah rontal. Dari beberapa sumber tertulis maupun nara sumber mengatakan, Tenganan adalah desa tua yang tergolong Bali Age atau pegunungan.
Kecamatan Manggis yang memiliki luas wilayah 69,83 km2 dengan jumlah penduduk 47.202 jiwa berada dibagian Selatan Kabupaten Karangasem dengan jarak tempuh 9 KM dari kota Karangasem. Kecamatan yang sarat dengan mitos, adat dan tradisi megeret pandan ternyata memiliki berbagai potensi profesi yang cukup beragam. Lebih membanggakan lagi, berbagai jenis seni , budaya, adat dan kerajinan sampai saat ini masih tetap berlanjut. Tenganan yang identik dengan kain klasik pegringsingan dan megeret pandan juga memiliki potensi dibidang pembuatan prasi. Secara visual bentuk dan teknik tampilan prasi yang berkembang di Desa Tenganan ada perbedaan dengan yang di Sidemen. Bentuk penampilan tokoh yang ada dalam lembaran sebuah daun rontal dihiasi dengan beberapa tokoh atau setiap adegan/babak digambar beberapa tokoh. Untuk sebuah ceritera seperti memerlukan beberapa lembar daun rontal. Tampilan wujud visual dibuat dengan merangkai lembaran-lembaran daun rontal yang menggunakan seutas benang. Untuk merangkai lembaran-lembaran daun rontal tersebut dengan cara melobangi kedua sisi dan bagian tengah rontal. Dari beberapa sumber tertulis maupun nara sumber mengatakan, Tenganan adalah desa tua yang tergolong Bali Age atau pegunungan.
Keberadaan kain tenun gringsing Tenganan dapat eksis sampai sekarang juga tidak lepas dari kepercayaan masyarakat terhadap Dewa Indra dan asal-usul leluhurnya. Perlu diketahui, walaupun masyarakat Tenganan beragama Hindu Dharma namun hanya percaya hanya pada satu Dewa yaitu Dewa Indra, dan tidak pada Tri Murti yaitu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kain tenun bagi mereka adalah salah satu bagian yang tidak perpisahkan dari kesehariannya baik sebagai busana maupun keperluan upacara. Jenis kain serta warnanya adalah simbol untuk membedakan status dan jenis upacara yang dilakukan.. Jenis kain blebet ini digunakan hampir pada semua umur baik laki-laki maupn perempuan. Khusus bagi ibu ibu kain tenun jenis blebet yang digunakan berwarna putih dengan pola garis kotak-kotak/segi empat. Kegiatan membuat prasi dilakukan sebagai pekerjaan pokok untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Kerajinan membuat prasi yang berkembang di Tenganan lahirnya lebih belakang dibandingkan yang berkembang di Sidemen. Mudita yang merupakan pioner pembuat prasi di Tenganan pada suatu hari mengatakan, kegiatan ini awalnya dilakukan untuk melengkapi naskah dalam menulis rontal yang terkait dengan ceritera yang ada.
Kerajinan di Kecamatan Manggis karangasem selengkapnya

by admin | May 25, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: Hendra Santosa (Dosen PS Seni Karawitan)
Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian Hibah bersaing yang berjudul Nawa Swara: Gamelan sistem 9 nada dalam satu gembyang.
 RC.Hardjosoebroto telah membuat skema laras. Dalam paparannya tersebut terkandung bahwa: Laras salendro Padantara terjadi karena pergeseran kwint Musik dengan kempyung Pelog. Dengan pembuktian seperti dibawah ini :
RC.Hardjosoebroto telah membuat skema laras. Dalam paparannya tersebut terkandung bahwa: Laras salendro Padantara terjadi karena pergeseran kwint Musik dengan kempyung Pelog. Dengan pembuktian seperti dibawah ini :
Sebelum membuktikan diatas, kita harus mencari rumus kempyung atau kwint dulu, dengan jalan mengadakan suara perbandingan antara interval kecil kita umpamakan X dan interval besar adalah Y dari pad interval-interval yang terdapat pada pelog sapta nada.
B o . s G P . U L B
X Y X X Y X X
Rumus : Gembyang = 5 x + 2y = 1200 cent
Kempyung = 3x + y
Dengan diketahui kempyungnya , kita akan dapat mencari x dan y dari pad surupan. Misalnya diketahui besar kempyungnya hádala 680 cent , hitung x dan y itu.
Rumus : Gembyang = 5x + 2y = 1200
Kempyung = 3x + y = 680 x 2
5x + 2y = 1200
6x + 2y = 1360 –
-x = -160
X = 160
3x + y = 680
3 (160)+ y = 680
480 + y = 680
Y = 680 – 480
Y = 200
Maka interval-interval dari surupan yang berkempyung tersebut adalah
B O . S G P . U L B
160 200 160 160 200 160 160
Skema laras RC. Hardjosoebroto selengkapnya

by admin | May 24, 2010 | Artikel, Berita
 Oleh:
Oleh:
Nama : I Gusti Ngurah Nurada
Nim : 200602019
Program Studi : Seni Karawitan
Penelitian ini adalah sebuah kajian seni karawitan yang bertujuan untuk mengetahui seluk beluk gamelan Angklung Sidan, Gianyar yang dilihat dari berbagai aspek-aspek yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Sebagai acuan dalam penelitian ini akan difokuskan pada “Gamelan Angklung Sidan, Gianyar : Kajian Musikalitas dan Eksistensi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah instrumentasi dan karakteristik tehnik permainan, tehnik tetekep dalam menabuh gamelan Angklung Sidan pada saat prosesi upacara Pitra Yadnya, dan eksistensi gamelan Angklung Sidan sampai sekarang.
Sebagai alat bedah untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, akan digunakan tiga buah teori, yaitu Teori Estetika yang digunakan untuk mengungkapkan identitas gamelan Angklung Sidan yang menyangkut keindahan, baik dari aspek ensamble, musikalitas, tata penyajian maupun simbol-simbol notasi. Teori Semiotika digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ungkapan emosional dari pelaku seni yang diwujudkan dalam gamelan Angklung dengan mengungkap bahasa musik dan perkembangan makna. Teori Perubahan mengungkap eksistensi gamelan Angklung Sidan.
Data-data yang sudah dikumpulkan adalah hasil dari observasi, wawancara, studi dokumen, dan telaah kepustakaan. Data-data yang diperoleh di lapangan akan diolah dan dianalisis serta disusun sedemikian rupa sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penulisan ilmiah.
Kata Kunci : Angklung, Instrumentasi, Tehnik Permainan, Tehnik Tetekep,Dan Eksistensi

by admin | May 23, 2010 | Artikel, Berita
 Oleh:
Oleh:
Nama : I Wayan Sucipta
Nim : 200602002
Program Studi : Seni Karawitan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Eksistensi Kesenian Gambuh di Desa Kedisan, 2) Bentuk Musikalitas serta lakon cerita Gambuh Kedisan, dan
3) Fungsi Kesenian Gambuh Kedisan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, sejarah terbentuknya Kesenian Gambuh Kaga Wana Giri yang terdapat di Desa Kedisan, sejalan dengan terbentuknya Desa Kedisan. Datangnya I Gusti Kacang Dawa ke Desa Kedisan pada tahun Isaka Windhu Wisaya Warihing Prabu,(Windhu=0, Wisaya=5, Warih=4 dan Prabu=1) Isaka 1450 atau tahun 1528 Masehi. Kedatangan beliau di iringi dengan putra dari Ki Pasek Gelgel Aan yang bernama Ki Pasek Katrangan. Dimana dibekali Gelungan Panji (hiasan kepala), sebagai tanda kesaktian. Gelungan tersebut sampai sekarang ini masih di simpan dan disakralkan oleh warga Aan di Desa Kedisan. Karena I Gusti Kacang Dawa dan iringannya merasa aman berada di tempat itu akhirnya memutuskan untuk menetap. Sejarah Gambuh ini hanya di singgung dalam lontar Candarasangkala.
Gambuh Kedisan lebih banyak mengalami perubahan dari pada perkembangan. Anggota sekaa Gambuh Kedisan banyak ikut transmigrasi, yang mengakibatkan berkurangnya peran tari dalam pertunjukan. Sulitnya mencari generasi pengganti untuk penari dan penabuh Gambuh mengakibatkan mengalami kendala terhadap perkembangannya. Jumlah anggota yang tersisa dan aktif hanya 25 orang termasuk penari dan penabuh. Instrumentasi Gambuh Kedisan terdiri dari: 4 buah suling, sepasang kendang krumpungan, satu buah rebab, satu buah kajar, satu buah ceng-ceng ricik, satu buah klenang, satu buah Gumanak, satu buah gentorag, satu buah kenyur, dan satu buah gong. Tidak ada instrument kangsi dalam barungan ini. Tetekep yang di pergunakan memainkan suling terdiri dari Lebeng, Matah dan Lebeng Matah. Gending Gambuh hanyal tinggal 13 yaitu 2 gending petegak dan 10 iringan tari.
Fungsi Kesenian Gambuh Kedisan adalah untuk upacara yaitu: Dewa Yadnya, Manusa Yadnya, Pitra Yadnya dan Bhuta Yadnya. Untuk hiburan yaitu: secara tidak langsung sebagai bali-balihan, dan pariwisata.
Kata Kunci: Gambuh Kedisan, Eksistensi, Musikalitas dan Fungsi.

by admin | May 20, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: I Gede Yudarta, Sskar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan
I. Pendahuluan
 Berbagai upaya telah dilakukan oleh para seniman untuk menambah serta memperkaya khasanah seni karawitan Bali. Salah satunya adalah dengan memunculkan terminology “baru” bentuk komposisi karawitan yang saat ini popular dengan Tabuh Kreasi Pepanggulan. Dalam judul tulisan ini sengaja diberikan tanda kutip pada kata “baru”, yang mana dimaksudkan bahwa tabuh kreasi ini terkesan baru karena semenjak dimunculkan sebagai salah satu materi dalam FGK, banyak yang mengaku tidak mengerti akan maksud yang terkandung di dalamnya.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh para seniman untuk menambah serta memperkaya khasanah seni karawitan Bali. Salah satunya adalah dengan memunculkan terminology “baru” bentuk komposisi karawitan yang saat ini popular dengan Tabuh Kreasi Pepanggulan. Dalam judul tulisan ini sengaja diberikan tanda kutip pada kata “baru”, yang mana dimaksudkan bahwa tabuh kreasi ini terkesan baru karena semenjak dimunculkan sebagai salah satu materi dalam FGK, banyak yang mengaku tidak mengerti akan maksud yang terkandung di dalamnya.
Materi ini mulai ditetapkan pada penyelenggaran Pesta Kesenian Bali (PKB) XXIV tahun 2002 untuk menggantikan materi tabuh Lelambatan yang telah menjadi tradisi dari tahun–ketahun dalam kegiatan Festival Gong Kebyar (FGK) yang mana sebelumnya repertoar yang dipergunakan berupa tabuh Pisan, Tabuh Telu, tabuh Pat, Tabuh Nem maupun Tabuh Kutus. Tidak banyak yang mengetahui secara pasti mengapa materi ini dimunculkan kepermukaan. Apakah sudah bosan dengan pola Tabuh Lelambatan sebagai mana biasanya dipilih dari pola lelambatan klasik yang terkesan monoton atau menginginkan adanya suasana baru dalam mata sajian FGK pada saat itu.
Tabuh Kreasi Pepanggulan Bentuk Komposisi “Baru“ Dalam Seni Karawitan Gong Kebyar Selengkapnya

by admin | May 19, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: I Made Berata (dosen PS Skriya Seni)
 Menyimak kata ”Pis Bolong” terasa aneh bagi kebanyakan orang, oleh karena ”pis bolong” adalah sebutan lain dari uang kepeng Cina dalam bahasa Bali. Pis berarti ”uang” dan ”Bolong” adalah lubang; maksudnya uang kepeng yang memiliki lobang segi empat. Uang kepeng ini merupakan pengaruh kebudayaan Cina, yang menjadi petanda hubungan Cina dengan Bali pada zaman kekuasaan dinasti Ming dan dinasti Tang. Dalam kebudayaan Hindu uang kepeng Cina ini digunakan sebagai sarana upacara keagamaan, seperti arca yang merupakan pengejawantahan dewa Khayangan, wakul, pelengkap sesaji yang disebut sarin canang, dekorasi dan sebagainya.
Menyimak kata ”Pis Bolong” terasa aneh bagi kebanyakan orang, oleh karena ”pis bolong” adalah sebutan lain dari uang kepeng Cina dalam bahasa Bali. Pis berarti ”uang” dan ”Bolong” adalah lubang; maksudnya uang kepeng yang memiliki lobang segi empat. Uang kepeng ini merupakan pengaruh kebudayaan Cina, yang menjadi petanda hubungan Cina dengan Bali pada zaman kekuasaan dinasti Ming dan dinasti Tang. Dalam kebudayaan Hindu uang kepeng Cina ini digunakan sebagai sarana upacara keagamaan, seperti arca yang merupakan pengejawantahan dewa Khayangan, wakul, pelengkap sesaji yang disebut sarin canang, dekorasi dan sebagainya.
Bermacam bentuk dekorasi dan arca sarana upacara keagamaan tersebut di atas, mengilhami inspirasi beberapa perajin di banjar Pande desa Kamasan mengembangkan seni kerajinan pis bolong. Seni kerajinan pis bolong atau uang kepeng adalah seni kerajinan yang menggunakan material uang kepeng sebagai bahan dasarnya.
Penggunaan Pis Bolong sebagai material seni kerajinan merupakan salah satu upaya konservasi dan pengembangan budaya Bali, serta mengantisipasi pis bolong asli (pis bolong dari Cina), yang keberadaannya semakin langka. Khususnya di Bali, pis bolong sangat diperlukan oleh masyarakat hindu untuk kepentingan upacara yadnya, karena hampir disetiap upakara mempergunakan pis bolong yang menurut keyakinan masyarakat Hindu mengandung signifikansi simbolis.
Menurut tokoh agamawan/sulinggih Ida Pedanda Sidemen menjelaskan, pada masa kedatangan Majapahit di Bali beredar pis bolong asli dari Cina, yang
dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah (uang kartal) dan digunakan untuk sarana upakara dalam pemujaan oleh umat Hindu. Ketika Belanda mulai menguasai Bali yang ditandai dengan jatuhnya kerajaan Buleleng pis bolong tidak diberlakukannya lagi sebagai uang kartal, namun pis bolong ini tidak ditarik dari peredarannya, karena masyarakat hindu masih menggunakan sebagai sarana upakara (Sidemen, 2006: 51).
Perkembangan berikutnya, pis bolong ini digunakan untuk material seni kerajinan, bahkan setelah tahun 1970 an ketika meroketnya kunjungan wisatawan manca negara ke Bali, serta diperhatikannya sektor kerajinan oleh pemerintah (Michel Picard, 2006: 31), penggunaan pis bolong sebagai material seni kerajinan semakin meningkat pula. Dengan semakin banyak jumlah keteng pis yang diperlukan, sehingga keberadaan pis bolong menjadi semakin berkurang, yang berakibat pada kesulitan para perajin dalam mencari dan menyediakan material. Para seniman dan perajin dalam penggunaan pis bolong sebagai media karya seni, awalnya ada yang menggunakan pis bolong asli (Cina) dan ada pula perajin yang menggunakan pis bolong tiruan, sesuai dengan permintaan konsumen.
Kerajinan Pis Bolong di Kabupaten Klungkung Selengkapnya

 Kecamatan Manggis yang memiliki luas wilayah 69,83 km2 dengan jumlah penduduk 47.202 jiwa berada dibagian Selatan Kabupaten Karangasem dengan jarak tempuh 9 KM dari kota Karangasem. Kecamatan yang sarat dengan mitos, adat dan tradisi megeret pandan ternyata memiliki berbagai potensi profesi yang cukup beragam. Lebih membanggakan lagi, berbagai jenis seni , budaya, adat dan kerajinan sampai saat ini masih tetap berlanjut. Tenganan yang identik dengan kain klasik pegringsingan dan megeret pandan juga memiliki potensi dibidang pembuatan prasi. Secara visual bentuk dan teknik tampilan prasi yang berkembang di Desa Tenganan ada perbedaan dengan yang di Sidemen. Bentuk penampilan tokoh yang ada dalam lembaran sebuah daun rontal dihiasi dengan beberapa tokoh atau setiap adegan/babak digambar beberapa tokoh. Untuk sebuah ceritera seperti memerlukan beberapa lembar daun rontal. Tampilan wujud visual dibuat dengan merangkai lembaran-lembaran daun rontal yang menggunakan seutas benang. Untuk merangkai lembaran-lembaran daun rontal tersebut dengan cara melobangi kedua sisi dan bagian tengah rontal. Dari beberapa sumber tertulis maupun nara sumber mengatakan, Tenganan adalah desa tua yang tergolong Bali Age atau pegunungan.
Kecamatan Manggis yang memiliki luas wilayah 69,83 km2 dengan jumlah penduduk 47.202 jiwa berada dibagian Selatan Kabupaten Karangasem dengan jarak tempuh 9 KM dari kota Karangasem. Kecamatan yang sarat dengan mitos, adat dan tradisi megeret pandan ternyata memiliki berbagai potensi profesi yang cukup beragam. Lebih membanggakan lagi, berbagai jenis seni , budaya, adat dan kerajinan sampai saat ini masih tetap berlanjut. Tenganan yang identik dengan kain klasik pegringsingan dan megeret pandan juga memiliki potensi dibidang pembuatan prasi. Secara visual bentuk dan teknik tampilan prasi yang berkembang di Desa Tenganan ada perbedaan dengan yang di Sidemen. Bentuk penampilan tokoh yang ada dalam lembaran sebuah daun rontal dihiasi dengan beberapa tokoh atau setiap adegan/babak digambar beberapa tokoh. Untuk sebuah ceritera seperti memerlukan beberapa lembar daun rontal. Tampilan wujud visual dibuat dengan merangkai lembaran-lembaran daun rontal yang menggunakan seutas benang. Untuk merangkai lembaran-lembaran daun rontal tersebut dengan cara melobangi kedua sisi dan bagian tengah rontal. Dari beberapa sumber tertulis maupun nara sumber mengatakan, Tenganan adalah desa tua yang tergolong Bali Age atau pegunungan.