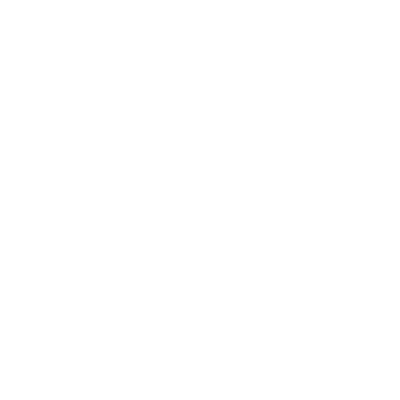by admin | Jun 21, 2010 | Artikel, Berita
Oleh I Wayan Diana
 Ringkasan Makalah Mahasiswa Berprestasi
Ringkasan Makalah Mahasiswa Berprestasi
Gender adalah nama dari sebuah tungguhan gamelan yang berbentuk bilah (metalophone). Kata gender biasanya dirangkaikan dengan kata rambat dan wayang yang mempunyai bentuk, laras, dan fungsi yang berbeda. Gender Wayang adalah nama dari salah satu tungguhan gender yang berbilah sepuluh dan berlaras selendro. Spesifikasi Gender Wayang adalah sebuah tungguhan gender yang dipakai untuk mengiringi pertunjukan wayang
Gender wayang merupakan sebuah gamelan yang masuk pada klasifikasi golongan gamelan tua, di Bali gambelan Gender Wayang diduga telah ada pada abad ke 14 . Tunggguhan gender atau yang lebih dikenal dengan gamelan Gender Wayang keberadaannya menyebar hampir diseluruh penjuru pulau Bali. Gender Wayang adalah sebuah instrument yang digunakan untuk mengiringi upacara keagamaan di Bali seperti pada upacara Dewa Yadnya untuk mengiringi pertunjukan Wayang Gedog (wayang lemah) dan pada upacara Manusa Yadnya mengiringi prosesi potong gigi (mepandes). Begitu luas manfaat dan fungsi dari keberadaan gamelan Gender Wayang tersebut bagi kehidupan ritual religius dari masyarakat Bali, namun semua itu masih terbatas dari segi konteks fungsi dari unsur musikalnya, apabila dilihat dari tinjauan etnomusikologi banyak elemen-elemen yang belum terungkap yang memberikan dampak dan pengaruh dalam perkembangan gamelan Gender Wayang khususnya. Di sini pendekatan etnomusikologi digunakan bukan hanya untuk mengulas unsur musikalnya saja, akan tetapi digunakan untuk membedah faktor-faktor lain diluar unsur musikal. Seperti bagaimana hubungannya dengan lingkungan masyarakat pendukung, letak geografis, bentuk topografi, bahasa, kebudayaaan, dan agama dari sebuah tempat hidup berkembangnya gamelan Gender Wayang.
Gamelan Gender Wayang jika dilihat dari sudut etnomusikologi, banyak aspek yang muncul bagaikan tiada bertepi, begitu luasnya pengungkapan hal-hal yang sebelumnya belum pernah terungkap namun lewat pendekatan etnomusikologi sebagai sebuah pisau bedah diharapkan mampu menghadirkan hubungan-hubungan, kaitan-kaitan baru yang terkait dengan sumber atau pokok permasalahan. Di sini gamelan Gender Wayang hadir tidak saja sebagai sebuah bagian dari kesenian, namun Bali sebagai daerah tempat lahir dan berkembangnya juga sebagai bagian dari kajian karena Bali merupakan warisan budaya (heritage culture), filasafat, dan agama dari hidup berkembangnya Gender Wayang. Dari sudut budaya, karakteristik masyarakat pendukung sangat mempengaruhi style atau gaya kedaerahan dari Gender Wayang, terbukti adanya tiga laras slendro dalam kategori saih atau tinggi rendahnya Tuning. Disamping itu juga berpengaruh pada bentuk repertoar gending, jenis tungguhan, dan sistem permainan/pola tetabuhan.

by admin | Jun 21, 2010 | Artikel, Berita
Oleh : Ni Ketut Suryatini, SSKar., M.Sn dan Ni Putu Tisna Andayani, SS (dosen PS Seni Karawitan)
 Teknik permainan gamelan Gender Wayang adalah sangat elaborate, intricate, pholiponic, melodie, dan bermacam sistem kotekan atau interloking figuration yang digunakan I Made Bandem, dkk, Wimba Wayang Kulit Ramayana (Ketut Madra), dicetakan oleh Proyek Penggalan/Tradisional dan Baru, 1981/1982, P. 5.. Gender Wayang mempunyai/memiliki kekhasan tersendiri dalam teknik permainan. Berbicara tentang desa Sukawati yaitu di Banjar Babakan Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati yang termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Gianyar. Sukawati adalah merupakan daerah agraris karena sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian bercocok tanam. Selain itu banyak juga penduduk yang hidup sebagai pedagang terutama untuk kebutuhan konsumsi pariwisata lewat pasar seni dan art shop, pemahat, pemaking, pelukis dan ada pula yang menjadi tukang printing mas (perada). Yang paling menarik adalah disana terdapat puluhan orang dalang yang rata-rata dari mereka itu menggunakan pekerjaan ”ngewayang” sebagai mata pencaharian. Kalau saja dalang-dalang pergi ngewayan sudah tentu akan banyak melibatkan pemain-pemain gender Sukawati telah menyebar ke seluruh daerah-daerah di Bali, lewat kaset-kaset yang dijual di toko-toko kaset, belajar secara langsung oleh orang-orang lokal Bali maupun orang asing dari manca negara. Oleh karena keeksisannya itulah peneliti tertarik menganalisa teknik permainannya sebagai pembanding dan teknik permainan Gender Wayang Kayumas dapat dilihat dari Nada
Teknik permainan gamelan Gender Wayang adalah sangat elaborate, intricate, pholiponic, melodie, dan bermacam sistem kotekan atau interloking figuration yang digunakan I Made Bandem, dkk, Wimba Wayang Kulit Ramayana (Ketut Madra), dicetakan oleh Proyek Penggalan/Tradisional dan Baru, 1981/1982, P. 5.. Gender Wayang mempunyai/memiliki kekhasan tersendiri dalam teknik permainan. Berbicara tentang desa Sukawati yaitu di Banjar Babakan Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati yang termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Gianyar. Sukawati adalah merupakan daerah agraris karena sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian bercocok tanam. Selain itu banyak juga penduduk yang hidup sebagai pedagang terutama untuk kebutuhan konsumsi pariwisata lewat pasar seni dan art shop, pemahat, pemaking, pelukis dan ada pula yang menjadi tukang printing mas (perada). Yang paling menarik adalah disana terdapat puluhan orang dalang yang rata-rata dari mereka itu menggunakan pekerjaan ”ngewayang” sebagai mata pencaharian. Kalau saja dalang-dalang pergi ngewayan sudah tentu akan banyak melibatkan pemain-pemain gender Sukawati telah menyebar ke seluruh daerah-daerah di Bali, lewat kaset-kaset yang dijual di toko-toko kaset, belajar secara langsung oleh orang-orang lokal Bali maupun orang asing dari manca negara. Oleh karena keeksisannya itulah peneliti tertarik menganalisa teknik permainannya sebagai pembanding dan teknik permainan Gender Wayang Kayumas dapat dilihat dari Nada
Perbedaan laras. Laras Gender Wayang disebut slendro. Secara teoritis laras slendro memiliki lima nada. Perbedaan laras gender wayang Sukawati yang dilihat dari perbedaan frekuensi, interval dan getarannya menunjukkan pada kita adanya sistem dipersifikasi dalam pembuatan gender wayang dan sistem ini menjadi lebih rumit jika dikaitkan dengan aspek komposisi dan teknik permainan.
Teknik Permainan Gender Wayang Sukawati Sebagai Suatu Perbandingan selenmgkapnya

by admin | Jun 21, 2010 | Artikel, Berita
Oleh Saptono, Dosen PS Seni Karawitan
 Salah satu sumber dapat dilihat dari babad Banyumas. Ada beberapa versi tentang babad Banyumas diantaranya: babad Pasir, Raden Baribin, Adipati Wirasaba, Tragedi hari Sabtu Pahing, Adipati Mrapat, Joko Kaiman membentuk Kabupaten Banyumas, Pembagian Daerah Kasepuhan dan Kanoman.
Salah satu sumber dapat dilihat dari babad Banyumas. Ada beberapa versi tentang babad Banyumas diantaranya: babad Pasir, Raden Baribin, Adipati Wirasaba, Tragedi hari Sabtu Pahing, Adipati Mrapat, Joko Kaiman membentuk Kabupaten Banyumas, Pembagian Daerah Kasepuhan dan Kanoman.
Babad Pasir yang menceritakan hubungan antara kerajaan Pajajaran dengan negeri Pasirluhur. Ketika Raden Banyakcatra sebagai putra raja pajajaran (Prabu Siliwangi)menyamar dan mengabdi pada patih Pasirluhur Ki Reksanata, kemudian putra raja tersebut (dengan samaran Kamandaka)menjalin hubungan asmara dengan putri bungsu Adidapi Kandadaha dari negeri Pasirluhur yang bernamaa Dewi Ciptarasa. Akhirnya adipati Pasir pun menjodohkan putrinya dengan Banyakcatra yang selanjutkan menggantikan kedudukan mertuanya menjadi adipati Pasir. Kadipaten Pasir mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, Demak. Namun dengan perubahan jaman kadipaten pasir menjadi sebuah kademangan, dan selanjutnya menjadi desa perdikan.
Raden Baribin: dalam versi babad Banyumas, diceritakan salah seorang putra Raja Majapahit ke-4 bernama Raden Baribin. Ia merupakan adik dari raja Majapahit yang terakhir (1466-1478) yang bernama Kertabumi (Prabu Brawijaya ke 5) dari ibu yang berbeda. Rutuhnya majapahit diandai dengan candrasengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi = 0041 atau 1400 tahun saka. Ketika Raden Baribin diusir oleh kakaknya (Brawijaya V), selanjutnya mereka bersama pengikutnya pergi ke arah barat hingga tiba di kerajaan Pajajaran, dan mereka mengabdi disana. Rajanya adalah Prabu Siliwangi yang mempunyai empat orang putra, dan yang paling bungsu bernama Roro Dewi Retno Pamekas. Setelah sekian lama mengabdi pada raja Pasundan, Prabu Siliwangi. Singkat cerita putra Majapahit itu dikawinkan dengan putrinya dan perkawinannya melahirkan seorang putra bernama Raden Ketuhu. Trah (keturunan) Majapahit dan trah Pajajaran inilah yang kelak membuka babad Banyumas dan menjadi leluhur (dinasti) para bupati di wilayah Banyumas.
Salah satu politik kerajaan untuk memperkuat kekuasaannya adalah memperisteri keluarga para adipati di daerah-daerah kekuasaannya. Hegemoni kekuasaan kerajaan-kerajaan besar tersebut dapat dipilah menjadi dua macam, yaitu kekuasaan secara teritorial seperti dalam kekuasaan yang secara turun-temurun yang tersirat dalam cerita babad, dan secara kultural.
Demikian juga degan versi babad Banyumas yang lain, menceritakan Raden Baribin yang bermukim di daerah Pajajaran dan mempunyai empat orang anak. Keempat anak tersebut yaitu Raden Ketuhu, Banyaksasra, Raden Banyakkusuma yang kelak tinggal di Kaleng (kebumen), dan keempat R. Rr Ngaisah (Nyi Mranggi) tinggal di Banyumas.
Diceritakan R.Ketuhu mengabdi pada Ki Gede Buwara di Wirasaba (Purbalingga). Adipati Wirasaba atau yang bernama Adipati Paguwan (Wirautama I sampai kerajaan Islam Pajang) mengangkat R.Katuhu sebagai anak (jaman Majapahit). Setelah Adipati Paguwan mangkat R.Katuhu menggantikan kedudukan ayah angkatnya dengan gelar Adipati Wirautama II (jaman Demak). Selanjutnya berturut-turut yang menjadi Adipati Wirasaba yaitu Adipati Wirautama III (Adipati Urang), Adipati Surawin, Adipati Surautama atau Joko Tambangan (pada jaman Demak).
Bayumas: sebuah Tijauan Historis selengkapnya

by admin | Jun 21, 2010 | Artikel, Berita
Oleh : Drs. I Wayan Mudra, M.Sn.Dosen PS Kriya seni
 Berdasarkan hasil penggalian yang dilakukan oleh para ahli purbakala di beberapa tempat di Bali membuktikan bahwa masyarakat Bali purba sudah mengenal pembuatan barang-barang keramik dari tanah liat. Stupa-stupa kecil dan materai-materai dari tanah liat ditemukan di Pejeng (Gianyar). Benda-benda tersebut diyakini berhubungan dengan kepercayaan Agama Budha. Sedangkan periuk-periuk yang ditemukan diyakini berhubungan dengan kepercayaan bekal kubur untuk tempat makanan dan minuman (Oka, I.B., l975 : 10). Nilai-nilai kepercayaan tersebut masih dapat kita jumpai sampai sekarang. Hal ini terlihat dari penggunaan benda-benda gerabah sebagai sarana pelengkapan upacara yang dilakukan masyarakat Hindu di Bali dapat dijumpai sampai sekarang. Misalnya gerabah sebagai tempat air suci, tempat api suci, dan lain-lain.
Berdasarkan hasil penggalian yang dilakukan oleh para ahli purbakala di beberapa tempat di Bali membuktikan bahwa masyarakat Bali purba sudah mengenal pembuatan barang-barang keramik dari tanah liat. Stupa-stupa kecil dan materai-materai dari tanah liat ditemukan di Pejeng (Gianyar). Benda-benda tersebut diyakini berhubungan dengan kepercayaan Agama Budha. Sedangkan periuk-periuk yang ditemukan diyakini berhubungan dengan kepercayaan bekal kubur untuk tempat makanan dan minuman (Oka, I.B., l975 : 10). Nilai-nilai kepercayaan tersebut masih dapat kita jumpai sampai sekarang. Hal ini terlihat dari penggunaan benda-benda gerabah sebagai sarana pelengkapan upacara yang dilakukan masyarakat Hindu di Bali dapat dijumpai sampai sekarang. Misalnya gerabah sebagai tempat air suci, tempat api suci, dan lain-lain.
Pembuatan gerabah di Bali pada awalnya tersebar di beberapa pedesaan, seperti Banjar Basangtamiang (Desa Kapal) dan Banjar Benoh (Desa Ubung) di Kabupaten Badung, Desa Pejaten di Kabupaten Tabanan, Desa Banyuning di Kabupaten Buleleng, Desa Jasi di Kabupaten Karangasem dan di Desa Pering Kabupaten Gianyar. Dari beberapa sentra kriya tersebut yang masih menampakkan aktifitasnya sampai sekarang adalah pembuatan gerabah di Banjar Basangtamiang, Binoh, Pejaten dan Banyuning.
Masing-masing sentra kriyawan tersebut memiliki kekhasan yang berbeda-beda sesuai sumber daya dan budaya masing-masing kriyawan. Pada awalnya pekerjaan mengerjakan gerabah ini hanya sebagai kegiatan sampingan diluar pekerjaan pokok sebagai petani. Demikian juga hasil yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari baik untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kepentingan yang berhubungan dengan kepercayaan/agama masyarakat setempat. Bahan baku yang digunakan adalah tanah liat dan batu padas halus sebagai bahan campurannya dengan perbadingan 2 : 1.
Perkembangan pariwisata di Bali yang cukup pesat terlihat berpengaruh terhadap kemajuan beberapa sentra pembuatan gerabah di wilayah ini. Aktifitas pembuat kriya makin meningkat, karena kebutuhan pariwisata akan barang-barang gerabah meningkat. Beberapa kriyawan mengkhususkan diri bekerja sebagai pembuat gerabah, bukan lagi merupakan pekerjaan sampingan tetapi sudah merupakan pekerjaan pokok keluarga. Benda-benda gerabah hasil kriyawan tersebut telah meimiliki nilai ekonomi yang dapat menghidupi keluarga. Pekerjaan membuat gerabah di Bali kebanyakan ditekuni oleh keluarga yang diwarisi secara turun temurun. Nampaknya kriya gerabah kurang menarik untuk ditekuni oleh masyarakat umum. Dengan demikian walaupun peluang pasarnya cukup baik, pembuatannya di masyarakat tidak sebaik kriya lainnya. Sehingga kalau dibandingkan apa yang terlihat di pasar secara kuantitas gerabah Bali masih jauh ketinggalan dari gerabah Lombok dan Yogyakarta. Disamping itu beberapa sentra gerabah di Bali yang tidak sanggup bersaing sudah tidak berproduksi lagi.
Gerabah Bali Selengkapnya

by admin | Jun 20, 2010 | Artikel, Berita
 Oleh: I Nyoman Suardina, S.Sn.,Msn.
Oleh: I Nyoman Suardina, S.Sn.,Msn.
Dalam mengulas karya pribadi, yang dapat dilakukan tidak lebih dari menyampaikan deskripsi, atau mendeskripsikan karya yang dibuat. Ada dua hal yang dapat dilakukan dalam mengulas karya yang dibuat, pertama yang berkaitan dengan fisik karya, M. Dwi Marianto menjelaskan …tiga hal utama dalam dimensi fisik karya seni yang bersangkutan, yaitu: subjek matter, medium, dan form. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan isi (contens), berupa makna, pesan atau hal-hal batiniah yang ingin disampaikan melalui karya tersebut, yang merupakan penggambaran perasaan yang dialami saat rangsang awal muncul.
Deskripsi Karya:
Judul Karya Introspeksi. Medium: kayu. Shape: kayu gempinis, kayu mahoni, kayu sonokeling, lem, dan bahan-bahan finishing. Subject Matter (materi subjek): Seekor igure serangga dalam kepompong, Display: sebagai karya mandiri di atas pustek. Dimensi/Ukuran: 20 X 25 X 80 Cm.
Struktur:
Karya yang dibuat bermatra tiga dimensional, dibentuk dalam abstraksi kepompong. Setting karya merupakan karya mandiri. Serangga (dalam kepompong) sebagai obyek sentral diwujudkan deformatif, bagian depan dipahat dengan teknik auto relief, badan kepompong dihiasi tekstur yang terinspirasi dari tekstur-tekstur kepompong serangga, serta bulatan-bulatan kecil berwarna hitam dengan teknik inlay, bertekstur kasar. Finishing, kombinasi warna-warna gelap dan natural.
Analisis Simbolik:
Introspeksi adalah suatu perilaku lumrah dalam kehidupan manusia, akan tetapi perilaku ini tidak selalu mudah untuk dilakukan. Bagai manapun introspeksi adalah sebuah pilihan sebagai salah satu jalan bagi pendewasaan diri manusia.
Ulasan Karya Serikat Serangga Dalam Penciptaan Seni Kriya I Selengkapnya

by admin | Jun 18, 2010 | Artikel, Berita
Oleh: Drs. I Made Bendi Yudha, M.Sn
1. Proses Penciptaan
 Dalam proses penciptaan karya seni lukis ini, diperlukan suatu metode untuk menguraikan secara rinci tahapan-tahapan yang di lakukan dalam proses penciptaan, sebagai upaya dalam mewujudkan karya seni. Melalui pendekatan-pendekatan dengan disiplin ilmu lain, dimaksudkan agar selama dalam proses penciptaan dapat dijabarkan secara ilmiah dan argumentatif. Dalam kaitan ini Sachari (2000: 223), menguraikan bahwa selama ini penelitian yang bersifat proses penciptaan dengan bahasa rupa dapat dikelompokkan dalam dua katagori, yaitu kajian estetik dan proses desain. Dalam kajian estetik jurus-jurus yang sering dipakai oleh seniman dan perancang dalam penggalian ide dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan: a). heurostik: spontanitas dan kreatif; b). semantik: metafor atau kepatutan; c). sinektik: analogi atau fantasi; d). semiotik: pengkodean atau penandaan; e). simbolik: pemaknaan atau penyimbolan; f). holistik: bersifat universal dan global; g). tematik: pendekatan tema tertentu; h). hermeneutik: tafsiran atau interpretasi.
Dalam proses penciptaan karya seni lukis ini, diperlukan suatu metode untuk menguraikan secara rinci tahapan-tahapan yang di lakukan dalam proses penciptaan, sebagai upaya dalam mewujudkan karya seni. Melalui pendekatan-pendekatan dengan disiplin ilmu lain, dimaksudkan agar selama dalam proses penciptaan dapat dijabarkan secara ilmiah dan argumentatif. Dalam kaitan ini Sachari (2000: 223), menguraikan bahwa selama ini penelitian yang bersifat proses penciptaan dengan bahasa rupa dapat dikelompokkan dalam dua katagori, yaitu kajian estetik dan proses desain. Dalam kajian estetik jurus-jurus yang sering dipakai oleh seniman dan perancang dalam penggalian ide dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan: a). heurostik: spontanitas dan kreatif; b). semantik: metafor atau kepatutan; c). sinektik: analogi atau fantasi; d). semiotik: pengkodean atau penandaan; e). simbolik: pemaknaan atau penyimbolan; f). holistik: bersifat universal dan global; g). tematik: pendekatan tema tertentu; h). hermeneutik: tafsiran atau interpretasi.
Sehubungan dengan penciptaan ini, dalam proses penciptaan karya seni lukis ini menggunakan metode pendekatan semiotik, karena data-data yang akan dicermati dalam penciptaan ini berupa tanda-tanda. Sedangkan metode pendekatan hermeneutik dan simbolik digunakan karena data-data yang akan dicermati berupa interpretasi, dan berupa simbol-simbol. Sedangkan metode penciptaan yang digunakan dalam penciptaan ini adalah menggunakan teori Hawkins, karena metode tersebut dapat dipakai sebagai rambu-rambu yang menuntun dan mengarahkan pola pikir dan pola tindak yang lebih sistimatis. Hal ini akan lebih mempermudah langkah-langkah aplikasinya secara teknik, demikian juga dalam mengimplementasikan ide-ide dan tahapan penciptaan, sehingga persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penciptaan ini dapat dideskripsikan dengan jelas serta dielaborasi secara optimal.
Hawkins dalam bukunya Creating Through Dance yang diterjemahkan oleh RM. Soedarsono (2001: 207), menyebutkan; penciptaan seni lukis dan seni tari yang baik, selalu melewati tiga tahap: pertama exploration (eksplorasi); kedua improvisation (improvisasi); dan yang ketiga forming (pembentukan atau komposisi). Dalam Hubungan ini Hadi (2003: 24,29,40) menterjemahkan, metode tersebut meliputi: eksplorasi, improvisasi, dan forming (pembentukan).Eksplorasi yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai langkah awal dari suatu penciptaan karya seni. Tahap ini termasuk berpikir, berimajinasi, merasakan dan merspon objek yang dijadikan sumber penciptaan; Improvisasi tahap ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi imajinasi, seleksi dan mencipta dari pada tahap eksplorasi.
Karena dalam tahap improvisasi terdapat kebebasan yang baik, sehingga jumlah keterlibatan diri dapat ditingkatkan. Dalam tahap improvisasi memungkinkan untuk melakukan berbagai macam percobaan-percobaan (eksperimentasi) dengan berbagai seleksi material dan penemuan bentuk-bentuk artistik, untuk mencapai integritas dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Forming (pembentukan), tahap ini adalah suatu proses perwujudan (eksekusi) dari berbagai percobaan yang telah dilakukan.
Metode Penciptaan Simbolisasi Bentuk Dalam Ruang Imaji Rupa selengkapnya

 Ringkasan Makalah Mahasiswa Berprestasi
Ringkasan Makalah Mahasiswa Berprestasi