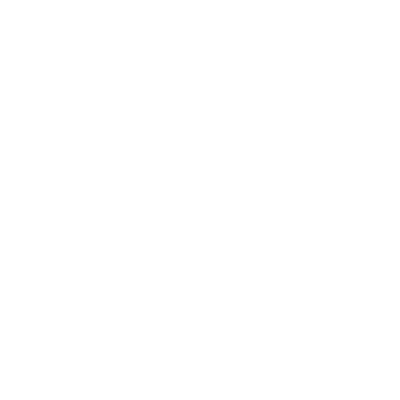by admin | Aug 24, 2010 | Artikel, Berita
 Oleh Drs. I Gede Mugi Raharja, MSn
Oleh Drs. I Gede Mugi Raharja, MSn
Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian tentang desain interior rumah tingal era Bali Madya di lapangan, maka sebagian besar konsep ruang rumah tinggal tradisional era Bali Madya berdasarkan pola-pola ruang sanga mandala, swastika, serta mengadaptasi konsep pempatan agung atau catuspatha. Aplikasi filosofi Trihitakarana pada konsep ruang rumah tinggal tradisional Bali Madya, sangat jelas memperlihatkan pembagian area: Parahyangan untuk tempat suci (sanggah/ merajan); Pawongan untuk bangunan dan bale-bale; dan Palemahan untuk kebun/ teba. Bebagai aktivitas keluarga dilakukan di dalam satu area atau ruang yang dibatasi tembok pembatas atau penyengker. Berbagai jenis bale-bale berada di dalam tembok pembatas/ penyengker, seperti bangunan Bale Dauh, Paon (dapur) dan Jineng (lumbung). Area khusus untuk tempat suci (sanggah/ merajan) keluarga, terletak di area timur laut.
1. Orientasi Ruang
Orientasi ruang rumah tinggal tradisional era Bali Madya nampak mengacu pada konsep Andabhuwana (bumi), berarti konsep ruang yang berorientasi pada potensi alam setempat (local oriented). Orientasi ruang ini mengacu pada arah: Gunung-laut (arah: kaja – kelod); Terbit-terbenamnya matahari (arah: kangin – kauh). Berdasarkan konsep ini kemudian ditetapkan area/ zona yang paling suci sampai area/ zona yang paling provan, sehingga unit-unit bangunan ditempatkan sesuai dengan fungsinya. Ruang paling suci adalah di timur laut (kaja kangin) untuk tempat suci, area utara (kaja) untuk tempat tidur (Bale Daja/ Bale Meten), area timur (kangin) untuk balai upacara (Bale Dangin/ Bale Gede), area barat untuk bangunan anak remaja/ tamu (Bale Dauh/ Loji), sedangkan area selatan untuk lumbung dan dapur. Selanjutnya orientasi ruang pada desain interiornya juga menyesuaikan, sehingga hulu ruang balai upacara mengarah ke timur (kangin) dan hulu ruang tidur mengarah ke utara (kaja).
Konsep Ruang yang Mendasari Desain Interior Rumah Tinggal Tradisional Bali Madya/Bali Arya I Selengkapnya

by admin | Aug 23, 2010 | Artikel, Berita
 Oleh: I Gede Yudartha, Dosen PS Seni Karawitan
Oleh: I Gede Yudartha, Dosen PS Seni Karawitan
– Pangisep
Dalam struktur inti sebuah komposisi lelambatan, pangisep merupakan bagian ke tiga dari struktur komposisi tabuh lelambatan. Dilihat dari ukurannya, bagian pangisep mempunyai ukuran yang sama dengan pangawak. Jumlah baris dalam satu baitnya, jumlah ketukan, pukulan panyacah, pukulan jublag, jegogan dan kempur-kemplinya sama dengan uger-uger pangawak. Hanya yang membedakanya adalah diantaranya: motif pukulan kakendangan yang disebut dengan pupuh kakendangan pangisep, melodi, tempo yang dimainkan, dan dinamika. Begitupula di dalam bentuk lelambatan yang sudah dikreasikan akan tampak perbedaan ornamentasi dan variasi pukulan antara pangawak dan pangisep.
Adapun bentuk pangisep dari tabuh dua yang digarap dalam FGK, karena sudah berupa bentuk lelambatan kreasi maka terdapat beberapa motif pangembangan terhadap melodi dasar, pukulan kakendangan, serta berbagai aspek musical lainnya sehingga terkesan dinamis. Sama halnya dengan bentuk pengawaknya pada bagian pengisep ini pula gending yang disajikan terdiri dari dua bagian yang dijadikan satu sehingga menjadikannya sebuah pola mebasang-metundun. Sebagaimana umumnya, pada bagian akhir dari kalimat lagu pangisep terdapat bagian penyalit mempunyai fungsi sebagai jembatan yang menghubungkannya menuju bagian selanjutnya yaitu bagian pangecet.
– Pangecet
Pangecet adalah salah satu bagian dari struktrur sebuah komposisi karawitan Bali. Dalam struktur tabuh lelambatan pagongan pangecet adalah merupakan bagian ke empat yang mempunyai kerangka tersendiri berbeda dengan kerangka gending pangawak atau pangisep.
Struktur Tabuh Lelambatan, Bagian II, selengkapnya

by admin | Aug 23, 2010 | Artikel, Berita
 Oleh: Olih Solihat Karso Dosen PS Desain Interior
Oleh: Olih Solihat Karso Dosen PS Desain Interior
- Hakikat
Hakikat; adalah kebenaran, kenyataan (Poerwadarminta,1984) hakekat menyaring dan memusatkan aspek-aspek yang lebih rumit menjadi keterangan yang gamblang dan ringkas, hakikat mengandung pengertian-pengertian kedalam aspek yang penting dan instrinsik dari benda yang dianalisa
Sebagai contoh, misalnya karya-karya John Portman dari Atlanta yang termashur yaitu hotel-hotel dengan interior yang ”inovativ dramatis” seabagai konsepnya.Portman memadukan citra perhatian dan fungsi, memahami apa yang menarik dan menggairahkan masyarakat dan ini divisualisasikan dalam karya-karyanya terutama dalam elevator lobby yang dihiasi dengan bola-bola lampu dan ditembusi dengan jendela-jendela untuk memberikan pandangan yang dramatis.
Contoh lainnya karya Eero saarinen dengan konsep hakikatnya adalah gerakan dan wista bandar udara internasional Kennedy untuk mempersatukan seluruh proyeknya kedalam satu kesatuan yang utuh (wholiam).
Lambang adalah suatu sub perangkat kategori hakekat. Lambang mengandung arti bahwa hakekat dapat digolongkan dalam bentuk-bentuk spesifik dan cita-cita yang dapat dimengerti masyarakat. Lambang adal hubungannya dengan harapan, sedangkan kenyataan adalah banyak type bangunan dapat menjadi wadah atau tempat untuk menjadi suatu kegiatan dan citra yang melambangkan kegiatan itu.
Konsep Desain Interior II selengkapnya

by admin | Aug 22, 2010 | Artikel, Berita

Oleh: I Wayan Diana Putra (Mahasiswa PS Seni Karawitan)
Tungguhan merupakan istilah untuk menunjukan satuan dari alat gamelan yang terdiri dari pelawah dan bagian-bagiannya berikut bilah atau pencon. Gender wayang merupakan sebuah tungguhan berbilah dengan terampa yang terbuat dari kayu, sebagai alas dari resonator berbentuk silinder dari bahan bambu atau yang lebih dikenal dengan sebutan bumbung sebagai tempat menggantung bilah. Bentuk tungguhan dari segi bilah gamelan Gender Wayang dalam buku “Ensiklopedi Karawitan Bali” karya Pande Made Sukerta disebutkan berbentuk bulig yaitu bilah yang terbuat dari perunggu atau bilah kalor adalah bilah yang permukaannya menggunakan garis linggir (kalor) dan dalam buku ini juga disebutkan bilah ini biasa digunakan pada jenis-jenis tungguhan gangsa seperti halnya gamelan Gender Wayang. Bilah bulig adalah bentuk bilah yang digunakan di gamelan Gender Wayang secara umum di Bali.
Kemudian terampa ataupun pelawah dari gamelan Gender Wayang di Bali memiliki model dan bentuk yang sama, yaitu 2 (dua) buah adeg-adeg yang terbuat dari kayu berfungsi sebagai penyangga gantungan bilah dan tempat resonator atau bumbung. Meskipun secara umum model dan bentuknya sama, faktanya dari setiap daerah memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing sesuai dengan budaya seni dan kreativitas seniman di daerah setempat. Hal ini terletak pada ornamentasi yang berarti hiasan atau pepayasan. Di sini sesuai dengan pendapat dari Mantle Hood yang menyebutkan bahwa dalam kontes etnomusikologi musik itu dipelajari melalui peraturan-peraturan tertentu yang dihubungkan dengan bentuk kesenian lainnya; seperti tari, drama, arsitektur, dan ungkapan kebudayaan lain termasuk bahasa, agama, dan filsafat. Unsur arsitektur yang merupakan induk dari ornamentasi dan pepayasan juga hadir sebagai bagian dari alat musik, yang berkaitan dengan bidang tertentu. Khususnya dalam gamelan Gender Wayang terlatak pada bidang terampa atau tungguhan. Setiap daerah di Bali memiliki sebuah persepsi yang tidak sama, walaupun berakar dari satu konsep style atau gaya di Bali, hal ini juga berkaitan dengan kearifan lokal atau disebut local genius dari masyarakat Bali yang majemuk.
Daerah Bali Utara yaitu Buleleng dan sekitarnya Gender Wayang memiliki ciri khas terampa dengan penuh kesederhanaannya yaitu adeg-adeg di buat hanya sesuai bentuk wadag (kasar) saja dan dengan bambu resonator yang dibiarkan alami yang difinishing (diselesaikan) dengan sentuhan perpaduan warna merah dan biru dari cat. Perpaduan warna merah dan biru inilah yang menjadikan sebuah ciri khas tersendiri dari daerah Buleleng dengan julukannya Bumi Panji Sakti dengan warna merah sebagai warna kebesaran. Dari warna inilah orang langsung mengetahui bahwa Gender Wayang itu milik dan ciri khas daerah Buleleng.
Di daerah Badung dan Denpasar, dari segi bentuk dan model hampir persis dengan yang ada di daerah Bali Utara khususnya Buleleng, pelawah di daerah Badung dan Denpasar memiliki sebuah keunikan tersendiri yaitu tungguhan pelawahnya bisa dilipat apabila sudah selesai dimainkan, hal ini menurut seniman gender dari Banjar Kayu Mas, I Wayan Suweca, Sskar. pada kelas Filsafat Seni Karawitan dikatakan hal ini berkaitan dengan mitologi Ciwa Tattwa dan mengandung konsep Purusa dan Predana. Purusa dan Predana yaitu sebuah filsafat yang menguraikan dua hal yang berbeda apabila bersatu akan menghasilkan sebuah energi yang besar yang biasa disebut dengan lanang wadon atau laki perempuan (Wawancara dengan I Wayan Suweca, SS.Kar, di kampus ISI Denpasar, tanggal 9 Desember 2009). Walaupun bentuk dan model sama persis, pelawahnya di kedua daerah ini sudah dibubuhi dengan sedikti ornamentasi atau pepayasan pada adeg-adeg berupa beberapa jenis motif ukiran sebagai pemanis dan diberi aksen warna emas dari warna prada.
Bentuk Tungguhan dan Ornamentasinya selengkapnya

by admin | Aug 22, 2010 | Artikel, Berita
 Oleh: Saptono, Dosen PS Seni Karawitan
Oleh: Saptono, Dosen PS Seni Karawitan
Dalam semiotika ada dua aliran utama yaitu mazab Peirceian yang berangkat dari logika, dan mazab Saussurian bertumpu pada ilmu bahasa. Semiotika Saussur sering disebut “semiotika signifikasi” yang berbasis pada elemen-elemen sebuah tanda di dalam sebuah sistem yang kompleks. Semiotika signifikasi yang bertumpu pada ilmu bahasa, Saussur membuat sepasang kebahasaan dengan istilah langue (bahasa) dan parole (ucapan, ujaran, tulisan). Langue merupakan struktur bahasa yang secara kesatuan aturan linguistik harus dipatuhi, dan parole (ucapan, ujaran, tulisan).
Pertunjukan jemblung sebagai kesenian bertutur adalah syarat dengan penggunaan bahasa, baik bahasa suara, bahasa gerak, dan bahasa visual. Bahasa, seperti yang dijelaskan Edi Sedyawati (1998; makalah untuk lokakarya Internasional Metodologi Kajian Tradisi Lisan, tgl 8-11 Juni 1998 di Bogor) sebagai berikut: pertama bahasa adalah sistem ungkap melalui suara yang bermakna, dengan satuan-satuan utamanya berupa kata dan kalimat, yang masing-masing memiliki kaidah-kaidah pembentukannya. Kedua, bahasa yang berarti bermakna kiasan, istilah “bahasa” juga dugunakan untuk menamakan cara-cara ungkap apa pun yang mempunyai susunan dan aturan (dalam Pudentia. Ed. 1998:1).
Dengan demikan bahasa dalam pertunjukan jemblung yang unsur utamanya adalah suara vokal, maka unsur bahasa baik dalam arti sebenarnya maupun dalam arti kiasan memiliki kekhasan keterkaitannya dengan kebudayaan Banyumas. Di dalam kebudayaan Banyumas terkandung unsur-unsur kebudayaan Jawa lama terutama tercermin pada bahasa dan sistem kepercayaan. Bagi masyarakat Banyumas, bahasa Banyumasan merupakan bahasa ibu yang hadir sebagai sarana komunikasi sehari-hari. Bahasa Banyumasan diyakini sebagai peninggalan bahasa Jawa lama (Jawa Kuno, dan Jawa Tengahan) atau bahasa Jawa baku yang bagi masyarakat Banyumas sering menganggap dengan istilah “bandhek, sedangkan masyarakat luas menganggap bahasanya orang Banyumas dengan istilah “ngapak-ngapak” (pengucapan konsonan diakhir kata dibaca dengan jelas dan apa adanya).
Jemblung: Sebuah Pendekatan Semiotika Selegkapnya

by admin | Aug 21, 2010 | Artikel, Berita
 Oleh: I Gede Yudartha, Dosen PS Seni Karawitan
Oleh: I Gede Yudartha, Dosen PS Seni Karawitan
– Pangawit
Pangawit berasal dari kata dasar yaitu ngawit/kawit yang mempunyai pengertian mulai (Anandakusuma, 1978:84). Pengawit di dalam sebuah struktur komposisi lagu lelambatan pagongan menjadi bagian yang paling awal dimana pada bagian ini terdapat sebuah kalimat lagu/melodi yang menandakan mulainya sebuah komposisi. Melodi yang disajikan berupa rangkaian nada-nada yang dimainkan dengan mempergunakan instrumen terompong yang diakhiri dengan gong. Panjang pendek melodi yang dimainkan tidak terlalu dipentingkan namun, pada bagian akhirnya sebelum jatuhnya pukulan gong ada suatu motif irama pukulan instrumen kendang yang menjadi ciri khas bagian pengawit.
Dalam bentuk penyajian kreasi baru, pada bagian pengawit ini terdapat bagian yang dinamakan gineman. Ada dua bentuk gineman yaitu gineman gangsa dan gineman terompong. Gineman gangsa yaitu motif permainan gangsa serta didukung oleh beberapa instrumen dalam gamelan gong kebyar yang dimainkan secara bersama-sama dengan berbagai variasi teknik gegebug sehingga menghasilkan jalinan-jalinan melodi yang dinamis. Biasanya di dalam gineman gangse terdapat pengrangrang terompong yang merupakan variasi teknik gegebug terompong yang dimainkan secara solo/tunggal. Dalam penyajian tabuh lelambatan klasik pegongan, untuk mengawali sebuah komposisi selalu diisi dengan gineman terompong. Dimainkannya pengrangrang ini memiliki arti yang sangat penting yang biasanya dipergunakan sebagai kode persiapan kepada para penabuh akan dimainkannya sebuah komposisi. Adakalanya motif pengrangrang ini dilakukan untuk mengecek atau memeriksa posisi dan kondisi nada-nada terompong jikalau ada pencon yang bersinggungan atau posisi nada yang terbalik. Namun demikian, walaupun memiliki arti yang cukup penting, gineman dan pengrangrang bukanlah merupakan bagian inti dari struktur sebuah komposisi tabuh lelambatan pegongan. Motif ini hanya sebagai variasi tambahan karena terkadang ada juga yang tidak memainkan gineman pada saat mengawali dimainkannya komposisi tabúh lelambatan.
Struktur Tabuh Lelambatan, bagian I Selengkapnya

 Oleh Drs. I Gede Mugi Raharja, MSn
Oleh Drs. I Gede Mugi Raharja, MSn