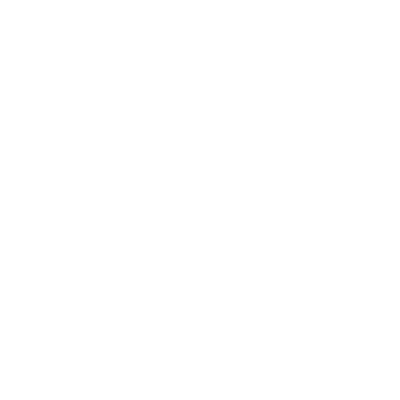by admin | Nov 18, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman I Gede Bayu Suyasa, mahasiswa PS Seni Karawitan
Kiriman I Gede Bayu Suyasa, mahasiswa PS Seni Karawitan
Berawal dari Perang pada tahun ±1860 antara Jero Wayahan Lanang Celuk di Jero Kerobokan dengan Desa Kelibul yang dulunya adalah wilayah kekuasaan Raja Mengwi, sebelum terjadi perang sakral yang dianggap memiliki kekuatan magis yang ada di Desa Kelibul tersebut seperti :
– Gong + Bande
– Tapel Barong (dipura Maspait Kelibul)
– Kul-kul (Kentungan)
– Belong
– Arca
Tujuan daripada dicarinya benda-benda tersebut agar desa Tibubeneng tidak memiliki kesaktian, untuk menghadapi Jero kerobokan. Perang terjadi karena Jero Wayahan Lang Celuk di Kerobokan ingin memperluas daerah kekuasannya itu.
Sarana-sarana yang merupakan kesaktian daripada tibubeneng tersebut diambil hanya untuk taktik atau cara orang dulu dalam berperang. Setelah sekian lama perang bergejolak selama puluhan tahun dan pada akhirnya pada Tahun 1926 perang usai.
Bersamaan pada waktu itu seiring berkembangnya Gamelan Gong Kebyar, timbullah keinginan dari keturunan beliau untuk melengkapi yang mulanya hanya ada 1 Gong dan 1 bande yang dianggap sakti itu menjadi satu bangunan Gong Kebyar lengkap, namun Gong DAN Bande yang dianggap sakral tersebut tetap disimpan, hanya dibuatkan duplikatnya saja.
Keturunan Beliau bersaudara empat orang, masing-masing mendiami, Jero Gede, Jero Kelod, Jero Kajanan, dan Jero Anyar-Anyar dan yang mewarisi Gong tersebut adalah Jero Br. Anyar yaitu “A.A Ratu Pemecutan” dengan putranya yang bernama A.A Putu Regeg.
Karena A. Ratu Pemecutan tidak suka dengan sanaknya yang suka berjudi maka A. Ratu Mecut minggat dan kembali ke Jero Kelodan sampai akhir keturunan beliau maka dikembalikanlah lagi Gong Kebyar tersebut ke Jero Kelodan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang sudah bermacam-macam sekaa yang menabuh Gong tersebut namun yang dapat diketahui sekarang adalah ‘Sekaa Eka Satya Budaya”.
Konon katanya jika sekaa gong yang pada saat menabuh gamelan terkena racun dan muntah darah disana di mintakan air (tirta) dari Gong sakti tersebut setelah diminum langsung sembuh. Dan jika ada orang yang sampai dewasa tidak bisa bicara dimintakan juga air tirta dari gong tersebut.
Konon juga katanya jika gong tersebut dibunyikan akan terjadi hujan yang sangat lebat (dulu katanya pernah dibuktikan). Nama dari Gong Due tersebut karena kata “Due” berarti kepemilikan raja. Dulunya Gong kebyar yang ada di Jero Kerobokan hanya satu-satunya yang ada di Kerobokan.
Dulunya Gong tersebut hanya difungsikan pada saat ada upacara (odalan) di Jero dan di Pura adapun tabuh-tabuhannya merupakan tabuh-tabuh lelambatan, adapun pelatihannya yang dapat diketahui yaitu :
Nyoman Redit Br. Campuan
Wayan Rideg Br. Gede
Gong Due tersebut juga katanya pernah dipinjam oleh Pak Berata ke Belawan dan dipinjam juga oleh tamatan Asti dulu untuk ujian Sarjananya.
Sejarah Gong Due Di Jero Kelodan Kerobokan selengkapnya

by admin | Nov 16, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman I Gede Suwidnya, Mahasiswa PS Seni Karawitan
Kiriman I Gede Suwidnya, Mahasiswa PS Seni Karawitan
Megibung adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau sebagian orang untuk duduk bersama saling berbagi satu sama lain, terutama dalam hal makanan. Tidak hanya perut kenyang yang didapat dari kegiatan ini namun sembari makan kita dapat bertukar pikiran bahkan bersendagurau satu sama lain.
Megibung bersasal dari kata dasar gibung yang mendapat awalan me-. Gibung berarti kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang yaitu saling berbagi antara orang yang satu dengan yang lainnya, sedangkan awalan me- berarti melakukan suatu kegiatan.
Tradisi Megibung merupakan kegiatan yang dimiliki oleh masyarakat Karangasem yang daerahnya terletak di ujung timur Pulau Dewata. Tanpa disadari Megibung menjadi suatu maskot atau ciri khas Kabupaten Karangasem yang ibu kotanya Amlapura ini. Tradisi Megibung sudah ada sejak jaman dahulu kala yang keberadaannya hingga saat ini masih kerap kali kita dapat jumpai. Bahkan sudah menjadi sebuah tradisi bagi Masyarakat Karangasem itu sendiri didalam melakukan suatu kegiatan baik dalam upacara Keagamaan, Adat maupun kegiatan sehari-hari masyarakat apabila sedang bercengkrama maupun berkumpul dengan sanak saudara.
Saat ini kegiatan megibung kerap kali dapat dijumpai pada saat prosesi berlangsungnya Upacara Adat dan Keagamaan di suatu tempat di Karangasem. Seperti misalnya dalam Upacara Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya, Rsi Yadnya dan Manusa Yadnya. Pada kegiatan ini biasanya yang punya acara memberikan undangan kepada kerabat serta sanak saudaranya guna menyaksikan prosesi kegiatan upacara keagamaan tersebut. Sehingga prosesi upacara dapat berlangsung seperti yang diharapkan.
Proses penyembelihan babi pun dilakukan sebagai salah satu menu di dalam mempersiapkan hidangan yang disebut Gibungan ini. Daging babi diolah sedemikian rupa dan di kasi bumbu tertentu sehingga daging yang mentah menjadi menu pelengkap yang menggugah selera seperti sate, lawar, soup (komoh), Gegubah/lempyong, pepesan serta yang lainnya. Menu yang dihidangkan dalam Megibung tidaklah harus daging babi, namun dading ayam, kambing serta daging sapipun tidaklah masalah.
Megibung berlangsung apabila tamu undangan sudah lama bersanda gurau dengan kerabat serta sanak saudara serta setelah selesai membantu tugas-tugas yang dapat dilakukan guna kelangsungan acara tersebut, sebelum para undangan pulang terlebih dahulu di ajaklah untuk makan (megibung) sebagai tanda terimakasi atas kedatangan dan bantun dalam acara tersebut. Dalam Megibung biasanya terdiri dari lima hingga tujuh orang, yang dilakukan dengan duduk bersama membentuk lingkaran. Adapun ciri khas dari megibung ini adalah :
Tradisi Megibung dari Karangasem, selengkapnya

by admin | Nov 15, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman Kadek Suartaya, dosen PS Seni Karawitan
Kiriman Kadek Suartaya, dosen PS Seni Karawitan
Seniman bertubuh tambun, Slamet Gundono, yang dikenal sebagai dalang Wayang Suket, tampil menggugah dan menggelitik dalam sarasehan seni pertunjukan kontemporer, Kamis (5/11) siang di ISI Denpasar. Di tengah perbincangan yang sarat gairah itu, Gundono didaulat untuk menunjukkan aksi pentasnya. Sembari memetik sebuah gitar kecil, celoteh dan alunan vokalnya yang improvisatoris membuat penonton terpana.
Aksi dadakan alumnus STSI Surakarta tersebut direnspon oleh koreografer Miroto dan komposer Agus Santosa. Sementara Miroto bergerak ekspresif di sisi-sisi tubuh Gundono yang duduk di tengah, Agus berjinjit-jinjit di bagian belakang sembari mengeksplorasi bunyi sebuah gong. Kolaborasi dalang, penari, pemusik yang sudah cukup dikenal secara nasional itu seakan menunjukkan bahwa seni komporer adalah ruang berkesenian yang keberadaannya tak bisa dipisahkan dari kebudayaan kontemporer masyarakat kita.
Kendati bergulir hanya sekitar tujuh menit, ketiga seniman itu tampak berhasil menggedor apresiasi dan hasrat-hasrat sukmawi para peserta sarasehan terhadap nilai estetik dan kandungan pesan dari ekspresi seni kontemporer tersebut. Gundono, Miroto, dan Agus Santosa yang dalam sarasehan itu diundang sebagai nara sumber, tak hanya berungkap secara verbal menuturkan eksistensi seni kontemporer di luar dan di dalam negeri namun juga menawarkan gagasan-gagasan sarat inspirasi dengan presentasi estetis eksploratif yang berdaya gugah.
Selain sebagai pembicara seminar, ketiga seniman Indonesia yang telah merambah forum seni internasional itu juga diusung sebagai juri Lomba Cipta Seni Kontemporer (LCSK) yang digelar oleh Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar, Rabu (4/11) malam. Hasil pengamatan mereka itulah, diantaranya, diperbincangkan dalam sarasehan yang dihadiri oleh para peserta lomba dan peminat seni pertunjukan. Gundono, Miroto, dan Agus Santosa tampak bersemangat mengisahkan dan membagi pengalamannya dalam kancah seni kontemporer.
Slamet Gundono menuturkan pergulatannya dengan seni kontemporer lebih banyak ditimbanya langsung di tengah masyarakat komunal pedesaan. “Seorang seniman harus mau bermandi lumpur untuk mengasah dan merangsang kepekaannya menemukan gagasan dan penuangan karya seninya,“ ujar Gundono. Menurutnya, di tengah masyarakat tradisional Indonesia, seorang seniman seni kontemporer akan banyak bisa menyerap kearifan lokal untuk dipresentasikan menjadi ungkapan artistik. “Pementasan wayang atau teater saya banyak mendapat inspirasi dan disangga oleh pergulatan saya di tengah lingkungan kultur alamiah pedesaan,“ ungkapnya polos.
Seni Kontemporer Dikebiri Seni Tradisi Bali? Selengkapnya

by admin | Nov 13, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman: Nyoman Lia Susanthi, Dosen PS Seni Pedalangan ISI Denpasar
Kiriman: Nyoman Lia Susanthi, Dosen PS Seni Pedalangan ISI Denpasar
Sesuai dengan yang disampaikan Mosco (1996), Terdapat tiga entry point untuk masuk kedalam ekonomi politik pada kajian komunikasi: komodifikasi (commodification); spasialisasi (spatialization); dan strukturasi (structuration). Komodifikasi yang merupakan titik awal ekonomi politik komunikasi, berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling tepat dikatakan sebagai transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Strukturasi berkaitan dengan hubungan antara gagasan agensi, proses sosial dan praktek sosial dalam analisa struktur.
Pada penulisan artikel ini lebih memfokuskan pada entry point dari spasialisasi. Pembahasan tentang spasialisasi konomi politik, tidak bisa mengabaikan kedigdayaan rezim kapitalisme. Hal itu dikarenakan spasialisasi ekonomi politik hadir setelah perkembangan kapitalisme yang mendominasi peradaban dunia global. Marx berpendapat bahwa perkembangan hubungan kapitalis memiliki efek mengatasi semua hambatan spasial: menghapuskan ruang dan waktu. Kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Hal ini mengacu pada daya tumbuh modal untuk menggunakan dan memperbaiki sarana transportasi dan komunikasi, mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan barang, orang, dan, sehingga mengurangi pentingnya jarak spasial sebagai kendala perluasan modal. Herbert Marcuse dalam One Dimensional Man (1991) berkata: “… Kapitalisme, yang didorong oleh teknologi, telah mengembang untuk mengisi semua ruang sosial kita; telah menjadi suatu semesta politis selain psikologis. Ini dibuktikan dengan kapitalisme tumbuh modal yang digunakan untuk memperbaiki sarana trasportasi dan komunikasi, sehingga pemanfaatan teknologi ini mampu memindahkan barang, orang dan pesan dalam waktu relative lebih cepat (singkat). Istilah ini diperkenalkan oleh ahli teori sosial Henri Lefebvre (1979).
Spasialisasi adalah sistem konsentrasi memusat, yang melahirkan hegemoni. Hegemoni sebagai perubahan di era globalisasi yang terjadi karena adanya pemusatan konsentrasi media dan teknologi. Seiring dengan pesatnya Teknologi Informasi (TI) di Indonesia, tiba-tiba saja masyarakat memiliki ruang tanpa batas (Barry, 2006: 74). Kelompok Media Bali Post (KMB) saat ini adalah perusahaan media terbesar di Bali. KMB memiliki anak cabang perusahaan yang bergerak dibidang media cetak dan elektronik. Jenis medianya beragam dan mengakar dibawah bendera Kelompok Media Bali Post. Ranah jangkauannya tak hanya di Bali tapi juga memasuki NTB hingga pulau Jawa. Dalam perluasannya KMB melakukan perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi bersifat horizontal maupun vertical dengan konsep Ajeg Bali. Wacana “Ajeg Bali” pertama kali dirancang oleh kaum intelektual dalam Kelompok Media Balipost (KMB). “Ajeg Bali” diartikan sebagai kemampuan manusia Bali untuk memiliki cultural confidence, yaitu keyakinan untuk memegang keteguhan jati diri yang bersifat kreatif meliputi segala aspek, dan tidak hanya terpaku pada hal-hal fisikal semata serta selektif terhadap pengaruh-pengaruh luar. Wacana ajeg Bali didengungkan untuk melindungi identitas, jati diri, ruang, serta proses budaya Bali.
Spasialisasi Kelompok Media Bali Post (KMB), Berkonsep Ajeg Bali, selengkapnya

by admin | Nov 11, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman I Wayan Mudra, Dosen PS Kriya Seni
Kiriman I Wayan Mudra, Dosen PS Kriya Seni
Gerabah adalah bagian dari keramik yang dilihat berdasarkan tingkat kualitas bahannya. Namun masyarakat ada mengartikan terpisah antara gerabah dan keramik. Ada pendapat gerabah bukan termasuk keramik, karena benda-benda keramik adalah benda-benda pecah belah permukaannya halus dan mengkilap seperti porselin dalam wujud vas bunga, guci, tegel lantai dan lain-lain. Sedangkan gerabah adalah barang-barang dari tanah liat dalam wujud seperti periuk, belanga, tempat air, dll. Untuk memperjelas hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa sumber berikut ini.
Menurut The Concise Colombia Encyclopedia, Copyright ã 1995, kata ‘keramik’ berasal dari Bahasa Yunani (Greek) ‘keramikos’ menunjuk pada pengertian gerabah; ‘keramos’ menunjuk pada pengertian tanah liat. ‘Keramikos’ terbuat dari mineral non metal, yaitu tanah lihat yang dibentuk, kemudian secara permanen menjadi keras setelah melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Usia keramik tertua dikenal dari zaman Paleolitikum 27.000 tahun lalu. Sedangkan menurut Malcolm G. McLaren dalam Encyclopedia Americana 1996 disebutkan keramik adalah suatu istilah yang sejak semula diterapkan pada karya yang terbuat dari tanah liat alami dan telah melalui perlakukan pemanasan pada suhu tinggi.
Beberapa teori lain tentang ditemukannya keramik pertama kali, salah satunya terkenal dengan ‘teori keranjang’. Teori ini menyebutkan pada zaman prasejarah, keranjang anyaman digunakan orang untuk menyimpan bahan makanan. Agar tak bocor keranjang tersebut dilapisi dengan tanah liat di bagian dalamnya. Setelah tak terpakai keranjang dibuang keperapian. Kemudian keranjang itu musnah tetapi tanah liatnya yang berbentuk wadah itu ternyata menjadi keras. Teori ini dihubungkan dengan ditemukannya keramik prasejarah, bentuk dan motif hiasnya di bagian luar berupa relief cap tangan keranjang (Nelson, 1984 : 20).
Dari teori keranjang dan teori lainnya di atas dapat dimengerti bahwa benda-benda keras dari tanah liat dari awal ditemukan sudah dinamakan benda keramik, walaupun sifatnya masih sangat sederhana seperti halnya gerabah dewasa ini. Pengertian ini menunjukkan bahwa gerabah adalah salah satu bagian dari benda-benda keramik.
Pengertian gerabah Selengkapnya

by admin | Nov 9, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman: I Gde Made Indra Sadguna, mahasiswa pascasarjana ISI Surakarta
Kiriman: I Gde Made Indra Sadguna, mahasiswa pascasarjana ISI Surakarta
Sebagai seorang lulusan institusi seni seperti Institut Seni Indonesia Denpasar, penulis telah banyak mendapatkan pengetahuan mengenai kesenian Bali khususnya yang terkait dengan seni karawitan Bali. Pada institusi tersebut telah dikenalkan berbagai jenis barungan gamelan, persoalan teknis gamelan, serta pembelajaran mengenai istilah-istilah yang melekat pada gamelan Bali. Salah satu istilah yang sering kita dengar dipergunakan baik oleh para mahasiswa, alumni, serta dosen yang membidangi karawitan adalah ‘oktaf’. Di sini saya akan mencoba memberikan suatu argumentasi mengenai merubah paradgima ‘oktaf’ dalam gamelan Bali.
Dalam suatu pembicaraan sehari-hari di lingkungan kampus, acap kali terdengar suatu dialog seperti:
“A: seperti apakah bentuk pelarasan gamelan Gong Kebyar?
B: Gong Kebyar merupakan salah satu gamelan yang memiliki laras pelog lima nada dalam satu oktafnya.”
Apakah ada yang salah dalam percakapan tersebut? Tidak. Hanya saja ‘Keliru”. Kasus-kasus seperti di atas merupakan satu dari sekian banyak contoh yang terjadi di dalam dunia karawitan Bali dan istilah ‘oktaf’ telah menyebar hingga ke desa-desa. Lalu yang menjadi pertanyaan pertama adalah: kenapa istilah ‘oktaf’ tersebut menjadi keliru? Untuk menjelaskan hal tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita memahami betul apa yang dimaksud dengan ‘oktaf’ itu sendiri.
Dalam dunia musik Barat, oktaf memiliki arti octavo atau menunjuk pada nada ke delapan. Ada suatu pemahaman mendasar mengenai oktaf yang telah menjadi suatu konvensi dalam dunia musik barat di seluruh dunia, yakni istilah ‘oktaf’ itu sendiri telah memiliki ukuran yang tepat dan pasti dalam dunia musik Barat (absolute pitch). Tiap-tiap nada memiliki ukuran interval yang pasti dalam jenis instrumen apapun di dalam orkestrasi musik Barat.
Lalu kenapa istilah ‘oktaf’ tidak tepat dipergunakan dalam sistem pelarasan gamelan Bali, padahal ada kemiripan cara kerja dalam sebuah tuning system? Pertama, perlu dipahami bahwa dalam karawitan Bali tidak akan pernah mengenal absolute pitch. Tidak ada satu barungan gamelan di Bali yang benar-benar sama pelarasannya. Coba saja ukur pelarasan suatu gamelan Gong Kebyar A dengan Gong Kebyar B, tidak akan mungkin semuanya sama. Itu bukan dikatakan falsch seperti di dalam musik Barat, namun pemahaman mengenai estetika dari bunyi gamelan Bali dengan musik Barat itu berbeda. Jika sebelumnya sudah dikatakan bahwa musik Barat sudah mengenal suatu konvensi tersendiri dalam menentukan tuning system, namun bagi pelaras Bali perbedaan antar suatu barungan gamelan itulah yang dikatakan indah. Sebuah “harmony in diversity”. Meskipun dalam dunia pelarasan dikenal istilah petuding – sebuah contoh laras yang biasanya dibuat pada beberapa potongan bambu kering – namun jarang sekali ada yang benar-benar tepat dengan petuding tersebut. Ada pemesan gamelan yang minta dipercepat lagi sedikit ataupun diperlambat gelombang ombaknya. Sesungguhnya apa yang diinginkan oleh si pemesan gamelan? Identitas. Suatu sistem pelarasan tertentu akan menghasilkan ciri yang tertentu pula pada suatu barungan gamelan. Simak saja beberapa contoh gamelan Gong Kebyar, seperti saih Gladag, saih Peliatan, saih STSI, semuanya memiliki pelarasan yang berbeda. Umumnya suatu daerah akan bangga dengan memiliki sebuah sistem laras yang bisa dikenal di Bali.
Meng-angkep-kan Oktaf Dalam Gamelan Bali, selengkapnya

 Kiriman I Gede Bayu Suyasa, mahasiswa PS Seni Karawitan
Kiriman I Gede Bayu Suyasa, mahasiswa PS Seni Karawitan