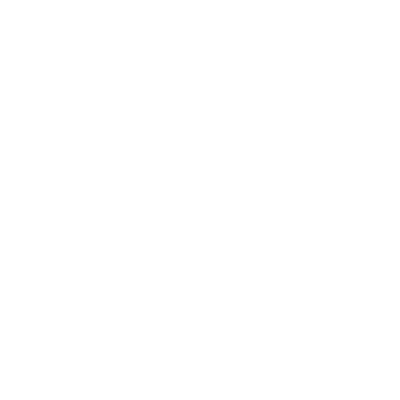by admin | Dec 2, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman Kadek Suartaya, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman Kadek Suartaya, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Di tanah air kita, bambu sebagai media musikal setidaknya telah dicatat keberadaanya pada abad ke-12. Sastra kakawin Bharatayuda karya Empu Sedah dan Empu Panuluh (1130 – 1160) dalam salah satu baitnya menulis: pering bungbang muni kanginan manguluwang yeaken tudungan nyangiring yang terjemahan bebasnya adalah bambu berlubang tertiup angin suaranya merdu meraung-raung bagaikan suara suling. Musik bambu yang dimaksud dalam kakawin berbahasa Jawa Kuno itu adalah sunari yang hingga kini masih ditemukan di Bali, mengalun sendu di tengah persawahan atau berdesah magis dalam ritual keagamaan besar di pura.
Gambang sebagai salah satu gamelan bambu tua Bali juga telah dilukiskan dalam Candi Penataran di Jawa Timur (abad ke-14 Masehi). Prasasti yang dibuat pada zaman pemerintahan Anak Wungsu di Bali (1045 Masehi) menyinggung pula tentang anuling (peniup seruling), yang kemungkinan besar serulingnya terbuat dari bambu. Dua lontar tua tentang gamelan Bali, Aji Gurnita dan Prakempa memposisikan gamelan Gambang dan Petangyan (gamelan Joged Pingitan) sebagai barungan (set gamelan) bambu yang menjadi representasi budaya dan presentasi estetik masyarakat Bali zaman kerajaan tempo dulu.
Selain memiliki martabat sebagai media ekspresi musikal, bambu di tengah masyarakat Bali, sejak dulu hingga sekarang, menempati posisi sakral-simbolik disamping tentu juga praktis multi fungsi. Dalam konteks sakral religius, ketika hari raya Galungan, sebatang bambu yang dihias janur ditancapkan di depan rumah setiap penduduk sebagai ungkapan syukur kemenangan dharma (kebajikan) atas adharma (kezaliman). Tiying gading (bambu kuning) secara khusus dipakai properti benda-benda suci keagamaan, dari upacara persembahan kepada Tuhan hingga upacara pembakaran mayat.
Kendati diupacarai begitu takzim, di tengah dinamika kehidupan yang dahsyat dalam era kesejagatan ini, kini seni tradisi pada umumnya mengalami guncangan hebat. Termasuk, beberapa bentuk gamelan bambu seperti Gambang dan Tingklik (gamelan Joged Pingitan) yang semakin langka. Bahkan Terompong Beruk, gamelan yang dulu menjadi bagian dari budaya agraris tradisional itu kini hampir punah. Namun demikian, di sisi lain, hak hidup tumbuhan bambu dan kesanggupannya sebagai wadah berkesenian masih tampak menunjukkan geliatnya.
Bambu, Pohon Musikal Peneduh Sukmawi

by admin | Dec 1, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman Kadek Suartaya, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman Kadek Suartaya, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Puluhan orang gadis Rusia tampak begitu antusias belajar tari Bali. Akhir Agustus lalu, para penari ballet itu mengikuti pelatihan tari Bali yang diarahkan oleh dosen dan mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar. Bertempat di Tartarstan State Choreography Theater, beberapa sikap pokok tari Bali seperti agem dan gerakan mata seledet, tampak sangat mengesan para peserta workshop itu. Sepenggal tari Pendet itu, rupanya mereka selami lekuk-lekuk keunikan dan keindahannya. Sensasi dari karakter estetik bahasa tubuh tari Bali tersebut agaknya mereka nikmati dengan suka cita. Tari Pendet tak hanya populer di Malaysia namun juga disukai gadis-gadis Rusia.
Adalah sekelompok seniman dari Pulau Dewata, pada pertengahan Agustus hingga awal September lalu melawat ke salah satu negeri pecahan Uni Soviet itu. Workshop tari Bali adalah salah satu program memperkenalkan kesenian Indonesia di belahan Eropa Timur itu. Kota Kazan, ibu kota Tartarstan—sekitar 18 jam perjalanan darat arah selatan Moscow–adalah tempat yang sempat disinggahi oleh tim kesenian ISI Denpasar tersebut. Selain memperkenalkan tari Pendet, dalam workshop yang bergulir sekitar satu jam itu, para peballet pria Kazan juga diberikan gerak-gerak tajam dan lugas tari Baris.
Kesenian Bali memang telah tampil di berbagai belahan dunia. Akan tetapi, Rusia mungkin salah satu negeri yang belum begitu banyak disambangi oleh para seniman Pulau Dewata. Tahun ini, untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia, seperti sudah disinggung tadi, sekelompok penari dan penabuh gamelan Bali melanglang Rusia pada 24 Agustus-3 September lalu, “Melalui kesenian, kita berharap dapat membuka jalan untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Rusia,“ ujar Duta Besar Republik Indonesia, Hamid Awaludin, saat menyambut kedatangan 22 orang seniman Bali di KBRI Moscow.
Kesenian sebagai pembuka jalan memang banyak dipergunakan sebagai alat diplomasi budaya. Soft diplomacy yakni diplomasi dengan cara damai kini banyak dilancarkan dalam pergaulan antar bangsa dan diplomasi antar negara. Untuk kepentingan itulah, Pemerintah Indonesia, sejak Juni lalu mengutus para seniman Indonesia, salah satunya, ke Rusia. Para seniman Bali yang terdiri dari para mahasiswa dan dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar ditampilkan sebagai puncak penampilan kesenian Indonesia. Para insan seni dari Pulau Dewata bukan hanya menyajikan tari dan gamelan Bali saja namun sajian seni pentas yang merepresentasikan keindahan kesenian Nusantara.
Penampilan tari Nusantara sebagai ekspresi estetik dari keberagam budaya Indonesia itu ditutup dengan pementasan Kecak atau Cak. Seluruh penari dan penabuh bergabung menyajikan Cak Ramayana berdurasi 25-30 menit. Keunikan suara dan jalinan vokal dari 22 orang seniman Bali ini mengundang decak penonton. Seusai pementasan di kota tua Tula–sekitar 4 jam perjalanan darat dari Moscow–misalnya, penonton seakan histeris dan secara kompak memekikkan ocen ichorosho (bagus sekali) berkali-kali sembari mencoba mengocehkan cak cak cak dengan amat girang. Rangkain bunga dibawa penonton ke atas panggung sebagai ungkapan suka cita mereka. “Syukur, mereka kagum dengan penampilan kita,“ ujar Ida Bagus Nyoman Mas, SSKar dengan wajah berseri-seri sumeringah yang bertugas mengkomandoi Cak.
Bukan Hanya Malaysia, Rusia Juga Suka Pendet selengkapnya

by admin | Nov 30, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman Drs. I Wayan Mudra, M.Sn.
Kiriman Drs. I Wayan Mudra, M.Sn.
Permasalahan dari penelitian ini adalah beberapa sentra kerajinan gerabah di Bali dari waktu kewaktu semakin berkurang. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu dicari penyebabnya untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Kami sebagai peneliti dan sekaligus memiliki disiplin ilmu yang terkait dengan bidang ini merasa khawatir suatu saat kerajinan gerabah hanya tinggal kenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriftif kualitatif, bertujuan menjelaskan eksistensi gerabah tradisional sebagai warisan budaya di Bali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi melalui pemotretan. Sumber data penelitian adalah perajin gerabah dan produk gerbah Bali. Penentuan sumber data perajin sebagai informan kunci dan produk dari masing-masing sentra dilakukan dengan metode sampel dengan mempertimbangkan tingkat kompetensinya.
Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa pembuatan kerajinan gerabah tradisional Bali masih tetap eksis dan beberapa sentra tetap eksis namun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sentra-sentra kerajinan gerabah yang masih eksis saat ini di Bali antara lain :
1. Kerajinan gerabah di Banjar Basangtamiang.Desa Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.
Kerajinan gerabah di Banjar Basangtamiang masih tetap eksis dengan produk yang dibuat beragam antara lain untuk kebutuhan upakara Agama Hindu, kebutuhan rumah tangga, maupun untuk benda-benda hias. Produk-produk tersebut dipasarkan untuk kebutuhan masyarakat umum dan kebutuhan hotel. Teknik pembentukan yang diterapkan perajin adalah teknik putar “ngenyun” dengan alat yang disebut “pengenyunan/lilidan” dan teknik cetak menggunakan bahan kayu. Pembakaran gerabah dilakukan dengan tungku bak pada ruang tertutup. Di banjar ini sebagian besar penduduknya hidup sebagai perajin gerabah. Eksisnya kerajinan gerabah di tempat ini terkait dengan mitos yang dipercaya masyarakat setempat.
2. Kerajinan gerabah di Desa Pejaten Kabupaten Tabanan.
Kerajinan gerabah ini justru berkurang membuat produk-produk untuk kepentingan upacara keagamaan. Perajin saat ini lebih fokus membuat produk-produk untuk kebutuhan hotel dan konsumen luar negeri. Perajin berproduksi dengan menggunakan teknik cetak dengan bahan gift. Hasilnya produk dapat dibuat sama dan ukurannya dapat dibuat lebih besar dibandingkan menggunakan teknik putar. Perajin menggunakan tungku keramik api berbalik untuk proses pembakaran. Di desa ini hanya ada satu keluarga yang menekuni kerajinan gerabah sejak lama, memliki sifat lebih terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Wujud karya lebih banyak berwujud patung, salah satu patung inovasi yang menjadi ikon perajin ini disebut dengan “Patung Kuturan”. Patung ini menjadi ciri khas produk patung gerabah di Desa Pejaten.
3. Kerajinan gerabah Banjar Binoh Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Barat.
Kerajinan gerabah di Banjar Binoh ditekuni oleh para wanita yang rata-rata sudah berusia lanjut. Perajin ini bergabung dalam satu kelompok usaha gerabah disebut Kriya Amerta. Mereka bekerja dan menjual hasil produknya dalam kelompok tersebut. Perajin Binoh lebih banyak mengerjakan benda-benda benbentuk gentong berbagai ukuran dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Perajin memasarkan produknya untuk kebutuhan untuk masyarakat umum dan kebutuhan hotel.
4. Kerajinan gerabah Desa Banyuning Kabupaten Buleleng.
Kerajinan gerabah di desa ini lebih berkembang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perajin yang menekuni kegiatan pembuatan gerabah ini semakin bertambah. Pada awal perkembangannya kerajinan gerabah di desa ini ditekuni oleh satu keluarga. Produk-produk yang dibuat adalah untuk kepentingan upacara keagamaan, perlengkapan rumah tangga dan benda-benda hias. Padagang memasarkan produk-produk gerabah di wilayah Buleleng, Badung dan Denpasar. Produk gerabah Buleleng tidak memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan produk perajin lain di Bali. Perajin menggunakan mesin untuk membantu mengolah bahan baku, sehingga proses produksi bahan lebih cepat. Teknik pembentukan dilakukan dengan teknik putar. Perajin menggunakan tungku dengan bahan plat baja dan besi dalam pembakaran gerabah dengan bahan bakar jerami dan kayu bakar.
5. Kerajinan gerabah Desa Tojan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung.
Saat ini kerajinan gerabah di Desa Tojan masih eksis, namun kedepan dikhawatirkan tidak generasi yang meneruskan, sehingga kemungkinan akan hilang. Perajin yang masih menekuni kerajinan di desa ini hanya satu keluarga yang terdiri dari tiga orang perempuan tua. Perajin menekuni usaha kerajinan ini merupakan warisan para orang tua mereka. Perajin menghasilkan produk-produk ukuran kecil untuk kepentingan upacara keagamaan seperti pulu, caratan, senden, dan lain-lain. Menurut perajin tidak banyak hasl yang didapat dari usahanya ini. Pada bulan-bulan terakhir ini, perajin membuat alat peleburan perak pesanan perajin perak. Teknik pembentukan barang dilakukan dengan teknik putar. Pembakaran menggunakan tungku ladang pada halaman terbuka dengan bahan bakar jerami, kayu dan bahan sejenis lainnya. Pedagang memasarkan produknya di pasar Klungkung.
Umumnya perajin gerabah Bali tidak menerapkan finishing warna pada produknya. Perajin menggunakan lapisan pere pada permukaan gerabah sebelum dibakar, untuk menghasilkan warna merah bata yang lebih cerah. Pere bias berupa tanah dan batuan batuan yang dihaluskan. Bahan ini juga dimanfaatkan dalam pewarnaan lukisan tradisi sepert wayang Kamasan.
Tetap eksis dan berkembangnya kerajinan gerabah di Bali, dapat disebabkan oleh tiga faktor antara lain faktor mitos yang berkembang pada perajin tersebut, faktor umat Hindu di Bali masih tatap menggunakan benda-benda gerabah sebagai perlengkapan upakara agama dan berkembangnya kepariwisataan di Bali.
Kata Kunci : eksistensi, gerabah tradisional Bali.
Studi Eksistensi Gerabah Tradisional Sebagai Warisan Budaya Di Bali, selengkapnya

by admin | Nov 28, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman I Gde Made Indra Sadguna
Kiriman I Gde Made Indra Sadguna
Pendahuluan
Kulkul atau kentongan (Jawa) merupakan instrumen musik yang bisa dibuat dari kayu ataupun bambu. Secara spesifik, kayu yang dapat dipergunakan sebagai bahan kulkul adalah: kayu ketewel (nangka), kayu teges (jati), kayu camplung, dan kayu intaran gading (batang pohon pandan yang sudah tua). Untuk mendapatkan kulkul yang baik, maka dipilihlah kayu atau bahan yang baik pula, karena dengan bahan yang baik dapat memberikan kualitas suara yang baik pula. Kayu terbaik untuk dipergunakan sebagai bahan kulkul adalah kayu nangka (artocarpus heterophyllus). Hal ini disebabkan karena serat kayu nangka lebih padat dibandingkan dengan kayu yang lainnya, sehingga dapat menghasilkan suara yang lebih padat dan bagus.
Kulkul berbentuk bulat memanjang, di mana pada bagian tengah tubuhnya terdapat rongga suara yang berfungsi sebagai resonator. Alat musik ini dikelompokkan ke dalam golongan idiophone sebab sumber suaranya berasal dari getaran tubuhnya sendiri. Ukuranya bervariatif, ada yang panjangnya hanya ½ meter dengan lebar lingkaran 10 cm, tapi ada juga yang lebih dari 1 meter dengan lebar lingkaran 100 cm. Biasanya kulkul yang berukuran besar ditempatkan (digantung) di pos-pos siskamling, banjar-banjar atau pura-pura.
Sesungguhnya budaya kentongan terdapat di seluruh daerah di Nusantara sebagai sarana komunikasi. Sebut saja di Pulau Jawa misalnya, instrumen kentongan biasa difungsikan untuk sarana siskamling atau dijadikan sarana membangunkan orang puasa ketika bulan Ramadhan. Namun hal ini kiranya tidak terjadi di Bali. Keberadaan kulkul di Pulau Dewata secara umum diposisikan sesuai kegunaannya di dalam kehidupan masyarakat.
Lalu pertanyaannya, berapakah jenis kulkul yang terdapat di Bali? Mengapa keberadaan instrumen kulkul begitu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Bali ? Apakah karena faktor sejarah, politik, sosial, agama atau faktor lain, sehingga kalau di daerah lain kulkul dipandang sebagai alat musik biasa, tapi di Bali kulkul sangat bermakna? Penjelasan mengenai permasalahan tersebut akan dibahas penulis sebagai berikut.
Kulkul Sakral
Di Bali terdapat tiga jenis kulkul. Pertama, ada kulkul sakral yang keberadaannya selalu ditempatkan di pura-pura dan disakralkan oleh masyarakat. Sebagai instrumen perkusi, keberadaan kulkul sakral tersebut tidak bisa dilepaskan dari odalan, karena selalu difungsikan sebagai sarana upacara. Dalam tata upacara di Bali disebutkan bahwa yang harus ada dalam suatu odalan adalah Panca Gita. Panca berarti lima sedangkan gita berarti suara atau nyanyian. Pembagian Panca Gita tersebut adalah suara kulkul, suara genta dari orang suci atau pendeta, suara kidung atau nyanyian berisi pujian kepada Tuhan, suara sunari dan suara gamelan. Jadi berdasarkan uraian tersebut, kehadiran kulkul sifatnya wajib dan harus ada pada saat upacara berlangsung.
Kulkul Sebagai Simbol Budaya Masyarakat Bali, selengkapnya

by admin | Nov 26, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman I Gede Suwidnya, mahasiswa PS Seni Karawitan
Kiriman I Gede Suwidnya, mahasiswa PS Seni Karawitan
Timbulnya barungan gambelan Slonding di Pura Puseh Desa Seraya Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yaitu sebelum tahun 1995 sangat dikeramatkan oleh Prajuru Desa Seraya, Krama ngarep atau Penua dan termasuk Krama Desa Seraya.
Karena Gamelan Selonding ini ditaruh di Pura Pasimpenan yang disebut Pura Slonding (disimpan memakai wadah kropakan/kotak kayu). Tiga bilah Gangsa yang kecil hanya dikeluarkan/dipundut (ditempatkan pada sebuah tapakan) pada saat Usaba Balai Sanghyang. Sedangkan tapakan-tapakan Idha Betara yang lainnya di pundut pada saat Usaba Bubuh, Purnama Kedasa, Usaba Kaja dan tiap Purnama Kapat.
Sedangkan bilah-bilah ini bisa juga berfungsi sebagai Gamelan atau alat tabuhan untuk mengiringi upacara-upacara Di Pura Desa Seraya. Awal Upacara di Pura Puseh Desa Seraya yaitu pada tahun 1996 setelah I Made Putu Suarsha Menjabat sebagai Kelihan Desa Adat yang diangkat pada tahun 1995.
Beliau menjelaskan bahwa, berwal dari rasa penasaran beliau yang ingin mengetahui isi dari Pelinggih Pasimpenan. Setelah beliau memeriksa ternyata di dalam kropakan tersebut ada bilah-bilah gangsa yang terbuat dari besi, yang terpanjang sampai mencapai 120 cm. Dan juga ditemukan satu pasang Relief dengan rantai dan jejuluknya disertai dengan beberapa cagak serta beberapa penyeleng gangsa yang terbuat dari perunggu yang berbentuk Naga.
Berawal dari penemuan tersebut I Made Putu Suarsha langsung berkordinasi dengan Bapak Wayan Tusan dari Desa Bebandem untuk mohon bantuan memfasilitasi dalam upaya membangun kembali (merakit agar kembali berfungsi). Pad akhirnya diperiksalah oleh beliau dan ternyata jumblah bilahnya masih dikatakan utuh oleh beliau, hanya saja pelawahnya harus di perbaharui/diganti dengan kayu nangka/ketewel yang berukuran sangat besar. Yang oleh beliau dikatakan sebagai Gamelan Selonding pada waktu itu.
Mengetahui demikian adanya fakta yang didapat ahirnya I Made Putu Suarsha selaku Kelihan Desa Adat Seraya langsung membuat banten atau sesaji dan ngaturang piuning/memohon Kepada Idha Sanghyang Widhi Wasa Tuhan yang berstana di Pura Puseh Desa Seraya agar gamelan tersebut diijinkan untuk diperbaiki dan diijinkan untuk ditabuh sebagai mana layaknya gamelan selonding yang ada di daerah lain.
Selain hal tersebut I Made Putu Suarsha melaporkan hal tersebut ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang pada akhirnya menanggapi dan langsung melakukan survei ke Pura Puseh Desa Seraya. Yang kemudian memberikan dana bantuan untuk merenopasi Gamelan Selonding tersebut. Yang ahirnya sampai saat ini Gamelan Selonding tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Namun Gamelan Selonding ini hanya bisa ditabuh dan dibunyikan di Areal Pura Puseh Desa Seraya dan pada saat hari raya-hari raya tertentu.
Gamelan Slonding Di Pura Puseh Desa Seraya Karangasem, selengkapnya

by admin | Nov 20, 2010 | Artikel, Berita
 Kiriman I Made Agus Dwipa Kartianta, mahasiswa PS Seni Karawitan
Kiriman I Made Agus Dwipa Kartianta, mahasiswa PS Seni Karawitan
Gamelan angklung adalah gamelan tua di Bali, dan salah satu perangkat gamelan yang pada masa lalu mengalami popularitas dapat dilihat dari data perkembangannya yang tersebar di seluruh kabupaten di Bali. Dalam perkembangannya gamelan ini mengalami perubahan-perubahan dalam fungsi,tata cara penyajian, yang mengikuti konsep desa kala patra sebagai sebuah media ritual yang fleksibel. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara fungsional angklung pun telah mengalami perubahan dimana secara ritual tetap berlangsung tetapi secara estetis gamelan ini menjadi sebuah iringan tari,iringan wayang, serta diolah dalam komposisi music modern.
Gamelan angklung adalah gamelan berlaras selendro, tergolong barungan madya yang dibentuk oleh instrument berbilah dan pencon dari krawang, kadang-kadang ditambah angklung bamboo kocok (yang berukuran kecil). Dibentuk oleh alat-alat gamelan yang relative kecil dan ringan (sehingga mudah untuk dimainkan sambil berprosesi). Jenis gamelan angklung ada tiga yaitu : angklung Kembang Kiran, angklung Klentangan dan Angklung Don Nem. Perbedaan ketiga jenis angklung ini terletak pada jumlah penggunaan nada yang maupun bilah dalam tungguhan jenis gangsa maupun jegogannya
Berdasarkan konteks penggunaan gamelan ini hanya mempergunakan 4 nada sedangkan untuk daerah Bali Utara mempergunakan 5 nada. Berdasarkan konteks penggunaan gamelan ini, serta materi tabuh yang dibawakan angklung dapat dibedakan menjadi :
- Angklung klasik yang dimainkan untuk mengiringi upacara (tanpa tari-tarian);
- Angklung kebyar yang dimainkan untuk mengiringi pagelaran tari maupun drama
Gamelan Angklung Di Desa Tanjung Benoa, selengkapnya

 Kiriman Kadek Suartaya, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman Kadek Suartaya, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar