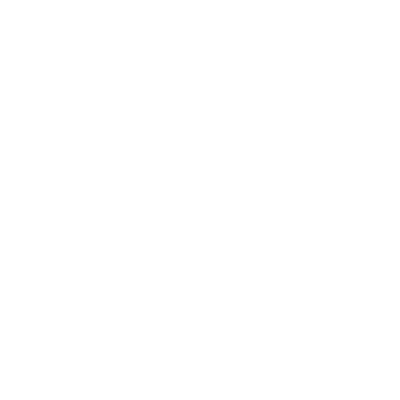by admin | Apr 1, 2011 | Artikel, Berita
 Oleh: Pande Artadi, Dosen PS Desain Interior ISI Denpasar
Oleh: Pande Artadi, Dosen PS Desain Interior ISI Denpasar
Kolonisasi yang terjadi di Indonesia oleh Belanda kurang lebih tiga setengah abad, meninggalkan jejak-jejak sejarah yang amat penting bagi bangsa Indonesia. Salah satu terwujud dalam bentuk karya-karya arsitektur sebagai bangunan penunjang pemerintahan kolonial. Masa penjajahan di Bali khususnya di Buleleng mulai dari tahun 1849 dan berakhir 1945, ini berarti lama penjajahan mendekati satu abad, namun waktu satu abad adalah rentang masa yang relatif singkat bila di bandingkan dengan masa penjajahan daerah lain di Indonesia yang berlangsung tiga setengah abad. Oleh karena itu peninggalan arsitektur kolonial di daerah Buleleng tidak sebanyak daerah lain seperti: di Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya dan beberapa kota di Pulau Sumatra. Arsitektur kolonial di kabupaten Buleleng tersebar di beberapa kawasan bersejarah di kota Singaraja, seperti: bangunan sarana perkantoran dan perumahan di Jalan Vetran, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Ngurah Rai, serta beberapa bangunan kantor dan pabrik di sekitar waterfront /pelabuhan Pabean.
Berdasarakan periodisasi perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia yang diungkapkan oleh Hellen Jessup, tahun 1849 (awal Belanda menundukan Bali) merupakan masa periode kedua perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia (tahun 1800-an sampai tahun 1902). Dalam periode ini kekuasaan VOC di Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Belanda. Periode ini juga menjelaskan tentang kemampuan bangsa Belanda dalam setiap karya arsitekturnya untuk beradaptasi dengan keadaan iklim tropis di Indonesia. Ungkapan ini juga ditegaskan oleh Sumintardja dalam ‘Kompendium Sejarah Arsitektur’ yang mengatakan bahwa pada periode ini banyak arsitektur kolonial Belanda mencoba untuk mengadopsi pola ruang rumah tinggal tradisional di daerah pesisir pantai utara Sumatra dan Jawa. Hadirnya bentuk arsitektur rumah tinggal seperti ini merupakan bagian dari sikap orang Belanda untuk menyesuaikan arsitekturnya dengan kebutuhan dan kondisi iklim tropis basah di Indonesia.
Salah satu karya arsitektur kolonial yang mampu beradaptasi dengan iklim tropis di Indonesia adalah arsitektur Ladhuis. Jeni Arsitektur ini tersebar di sepanjang Jalan Gajah Mada di Singaraja, Buleleng Bali. Beberapa bangunan yang ada di jalan Gajah Mada adalah rumah dinas yang dibangun pada tahun 1914-an untuk para pegawai Belanda yang ditugaskan di Bali, namun tidak diketahui siapa yang menjadi arsiteknya. Ini disebabkan karena bangunan yang didirikan adalah bangunan sederhana jenis rumah tinggal sebagai program pemerintah kolonial, sehingga tidak harus dirancang oleh seorang arsitek. Proses perancangannya hanya dilakukan oleh pegawai dari Departemen Pekerjaan Umum Pemerintah Belanda BOW (Bugerlijke Openbare Werken) melalui gambar atau model yang telah disediakan.
Konsep Interior Tropis Pada Arsitektur Landhuis Di Kota Singaraja Selengkapnya

by admin | Mar 30, 2011 | Artikel, Berita
 Kajian Tekstual Gending Leluangan Kekebyaran Dalam Upacara Piodalan Di Pura Kayangan Tiga Desa Adat Tembawu.
Kajian Tekstual Gending Leluangan Kekebyaran Dalam Upacara Piodalan Di Pura Kayangan Tiga Desa Adat Tembawu.
Kiriman I Ketut Ardana, S.Sn., Dosen Jurusan Seni Karawitan ISI Yogyakarta.
Gending-gending leluangan merupakan sebuah motif lagu atau gending yang biasa dimainkan dengan menggunakan gamelan luang atau gong luang. Ciri khas dari lagu ini adalah menggunakan 1 buah kendang yaitu kendang cedugan, sebuah kendang yang menggunakan panggul (Jawa : tabuh) kendang sebagai alat pukul. Mayoritas pola garap gending-gending leluangan sangat sederhana baik secara olahan melodi maupun tafsir garap ornamentasinya. Reportoar-reportoar gong luang termasuk gending-gending klasik yang notabenanya digunakan untuk kepentingan upacara ritual keagamaan.
Kekebyaran berasal dari kata kebyar yang mengandung banyak pengertian. Kebyar atau byar dapat berarti sinar yang muncul secara tiba-tiba, cepat, keras, dan lain sejenisnya. Kebyar dapat pula berarti bunyi yang timbul akibat dari pukulan instrumen gamelan secara keseluruhan, sedangkan Colin McPhee menyebutnya sebagai suara yang memecah secara tiba-tiba bagaikan pecah atau mekarnya sekuntum bunga. Oleh karena itu sudah sepantasnya gamelan yang mengandung karakter kebyar ini disebut gamelan kebyar, gong kebyar, atau gamelan gong kebyar. Dengan demikian kekebyaran memiliki arti sebuah lagu yang menggunakan gong kebyar sebagai media ungkap. Sajian gending yang menggunakan gong kebyar memiliki karakterisasi keras, lincah agresif, dan sejenisnya. Popularitas dan fleksibilitas gamelan gong kebyar menyebabkan refortoar dari barungan gamelan gong luang juga bisa disajikan melalui gong kebyar. Tentu saja karakter gending yang disajikan akan berbeda dengan gending yang disajikan melalui gong luang. Gending-gending leluangan yang menggunakan gong kebyar sebagai media ungkap memiliki nuansa gembira. Namun demikian, nuansa-nuansa ritual yang terkandung dalam gending-gending leluangan tidak hilang.
Ada suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Tembawu yaitu melaksanakan upacara piodalan di Pura Kahyangan Tiga. Upacara tersebut jatuh setiap 6 bulan sekali dalam hitungan Wuku Bali. Ditengah-tengah melakukan upacara piodalan, masyarakat Desa Adat Tembawu menggunakan media gamelan sebagai iringan upacara. Transformasi gending leluangan ke dalam gong kebyar menjadi ciri khas gending. Upacara piodalan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali merupakan persembahan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ide Sang Hyang Widi Wasa) dalam bentuk upacara dewa yadnya.
Setiap prosesi upacara piodalan di Pura Kahyangan Tiga Desa Adat Tembawu selalu diiringi gamelan baik itu gamelan balaganjur maupun gamelan gong kebyar. Pada gamelan gong kebyar, gending-gending terbagi dalam berapa jenis gending antara lain : gending-gending lelambatan klasik pegongan Bali untuk mengiringi rentetan upacara ritual ngatur piodalan dan persembahyangan, sedangankan gending leluangan kekebyaran untuk mengiringi prosesi ritual pangilan-ngilen. Dari uraian di atas bagaimanakah pola tekstual gending leluangan kekebyaran ?
Desa Adat Tembawu adalah salah satu organisasi masyarakat desa yang yang menangani secara admistratif tentang pelaksanaan upacara keagamaan di wilayah Tembawu. Tanggung jawab keagamaan yang paling besar adalah melaksanakan upacara piodalan di Pura Kahyangan Tiga dan melaksanakan upacara prosesi melasti dalam rangka hari raya Nyepi yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
Pura Kahyangan Tiga merupakan tempat suci untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa bagi umat Hindu. Yang termasuk pura Kahyangan Tiga di Desa Adat Tembawu antara lain: Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem, dan Pura Kahyangan. Pada Sabtu Kliwon wuku Kuningan masyarakat Desa Adat Tembawu melaksanakan upacara piodalan di Pura Desa. Pada Selasa Kliwon wuku Medangsia dilaksanakan upacara piodalan di Pura Kahyangan. Pada Rabu Umanis wuku Medangsia masyarakat melaksanakan upacara piodalan di Pura Puseh. Pada Tilem (Bulan mati) pertama setelah hari raya galungan maka masyarakat melaksanakan upacara piodalan di Pura Dalem.
Upacara piodalan bisanya berlangsung selama 2 hari. Hari pertama berlangsung upacara piodalan (hari H). Pada hari kedua berlangsung upacara penyimpenan. Pada hari pertama yang merupakan upacara pokok terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap melasti, tahap ngaturang piodalan dan tahap pangilen-ngilen. Upacara ini berbentuk pangilen-ngilen. Upacara pangilen-ngilen terdiri dari beberapa jenis ritual, yaitu: nyanjan, memendak, meatur-atur, pangider bhuwana, mererauhan,wayang-wayang, meyab-yaban, nanda, biasa, ngurek, mendak keluwur, kincang-kincung. Setiap prosesi ritual pangilen-ngilen selalu diiringi gending-gending leluangan kekebyaran. Di bawah ini akan diuraikan jenis upacara dan reportoar pengiringnya.
Kajian Tekstual Gending Leluangan Kekebyaran Selengkapnya

by admin | Mar 29, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman I Ketut Partha, SSKar., M. Si., dosen PS Seni Karawitan
Kiriman I Ketut Partha, SSKar., M. Si., dosen PS Seni Karawitan
1. Pendahuluan
Gamelan Semara Pagulingan adalah perangkat gamelan yang berlaras pelog sapta nada (pelog tujuh nada) terdiri dari lima nada pokok dan dua nada pemero. Gamelan ini merupakan pemekaran dari gamelan Pagambuhan yang barungannya sangat sederhana menjadi barungan yang lebih besar dan tepat guna. Pemekaran ini diilhami pula oleh adanya gamelan Gong Luang (Rembang, 1985 : 3).
Menurut Wayan Rai S. dalam Mudra (1997 : 145), istilah Semara Pagulingan terdiri dari kata “Semara” dan “Pagulingan”. Semara, atau sering pula disebut semar ; adalah dewa keindahan; sedangkan pagulingan adalah istilah yang sering diaso-siasikan dengan bed chamber. Karena itu Semara Pagulingan diartikan sebagai love music for the bed chamber (Hood), atau gamelan rekreasi raja-raja zaman dahulu (Bandem). Menurut I Nyoman Rembang, Semara Pagulingan bukanlah sebuah istilah yang semata-mata diasosiasikan dengan musik yang bernuansa sex, melainkan suatu istilah yang diberikan kepada gamelan yang mampu memberikan rasa keindahan yang luar biasa, dalam bahasa Bali disebut ngelangenin.
Pada mulanya masyarakat Bali mengenal Semara Pagulingan hanya berlaras pelog saih pitu, akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya muncul gamelan Semara Pagulingan yang berlaras pelog saih lima. Kedua jenis Semara Pagulingan tersebut secara fisik lebih kecil dari barungan Gong Kebyar jika dilihat dari ukuran instrumen gangsa dan trompong yang melengkapi. Sebagai penentu identitas, instrumen trompong memegang peranan penting dalam gamelan Semara Pagulingan.
Semara Pagulingan Banjar Teges Kanginan adalah gamelan Semara Pagulingan berlaras pelog saih lima memiliki identitas yang khas dengan keunikannya, yang masih mampu bertahan sesuai tradisi dan kondisi kehidupan masyarakat pendukungnnya. Tradisi menggunakan Semara Pagulingan dalam upacara-upacara adat dan keagamaan di Banjar Teges Kanginan telah berlangsung cukup lama yang hingga sekarang masih tetap dilaksanakan oleh generasi penerusnya.
Sampai dewasa ini Banjar Teges Kanginan masih memelihara dan memanfaatkan gamelan Semar Pagulingan secara fungsional, masih kokoh dan mampu melestarikan salah satu media kesenian Bali yang telah diwarisi secara turun-temurun. Lestarinya repertoire tersebut tidak terlepas dari adanya tabuh-tabuh yang disajikan secara khusus, baik untuk kepentingan melengkapi ritual keagamaan maupun untuk menunjang aktivitas masyarakatnya.
Tulisan ini akan mengkaji konsep musikal dan nilai-nilai yang menjadi identitas gamelan Semara Pagulingan yang berkembang di Banjar Teges Kanginan, Peliatan, Gianyar. Dengan menjadikan gamelan Semara Pagulingan sebagai topik tulisan ini, penulis bermaksud untuk menyajikan bagaimana perkembangan gamelan Semara Pagulingan dalam konteks aktivitas sosial masyarakat Teges Kanginan, baik yang berkaitan dengan aspek kehidupan beragama maupun dengan aspek kehidupan berkesenian dalam menghadapi perubahan dilingkungan budayanya.
Konsep Musikal Gamelan Semara Pagulingan Banjar Teges Kanginan selengkapnya

by admin | Mar 28, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman AAA Kusuma Arini, SST., MSi. Dosen PS Seni Tari ISI Denpasar.
Kiriman AAA Kusuma Arini, SST., MSi. Dosen PS Seni Tari ISI Denpasar.
Kesenian merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas ritual masyarakat Hindu Bali. Dalam setiap kegiatan upacara, ada saja kesenian yang dipentaskan, terutama seni tari dan tabuh, lebih-lebih bagi mereka yang mampu secara material karena ritual masyarakat Hindu Bali tidak akan selesai tanpa ikut sertanya tari dan tabuh.
Tari-tarian yang diperkirakan oleh para ahli sebagai kelompok kesenian yang paling tua, meliputi sejumlah tarian sacral, yang di Bali lazim disebut tari Wali hingga kini masih terpelihara dengan baik oleh masyarakat pendukungnya, di samping tari-tarian Bebali dan Balih-balihan. Dalam beberapa dekade belakangan ini, terdapat sejumlah kesenian Wali yang sudah punah dan ada pula yang sudah mengalami perubahan fungsi, misalnya dari sajian upacara keagamaan kini dipentaskan untuk komoditi pariwisata.
Baris berbaris rupanya sudah dikenal masyarakat Bali sejak dahulu. Buktinya, ada tari Baris yang dalam pementasannya memakai cara berbaris, berderet dan berjajar. Pada dasarnya tarian ini dibagi atas dua macam. Pertama tari Baris Wali yang hanya dipentaskan dalam kaitan pelaksanaan suatu upacara Dewa Yadnya yang lazim disebut Babarisan, didukung oleh krama desa tertentu. Jenis yang kedua adalah tari Baris Balih-balihan yang berfungsi sebagai tontonan / hiburan, seperti tari Baris tunggal dan tari Baris kreasi berpasangan yakni Baris Bandana Manggala Yuda.
Salah satu bentuk Baris Wali tersebut adalah Baris Katekok Jago yang akrab disebut Baris Poleng karena kostum yang dipakai dominan hitam putih dan membawa tombak yang juga dicat hitam putih. Tarian ini merupakan tari tradisional yang langka karena hanya dijumpai di desa Tegal Darmasaba (Badung) dan Tangguntiti (Kota Denpasar). Sebelumnya pernah ada di Tembau dan Begawan (Kota Denpasar). Baris Katekok Jago mempunyai fungsi ganda, selain sebagai sarana upacara Dewa Yadnya, juga sering dipentaskan untuk upacara Pitra Yadnya. Tarian tersebut bisa diupah oleh perorangan atau kelompok terutama untuk upacara yang tergolong utama, baik untuk Dewa Yadnya maupun Pitra Yadnya.
Literatur tertua yang mengungkap tentang Baris adalah lontar Usana Bali yang menyatakan: setelah Mayadanawa dapat dikalahkan maka diputuskan mendirikan empat buah kahyangan di Kedisan, Tihingan, Manukraya dan Kaduhuran. Begitu kahyangan berdiri megah, upacara dan keramaianpun diadakan dimana para Widyadari menari Rejang, Widyadara menari Baris dan Gandarwa menjadi penabuh. Legenda Mayadanawa tersebut terjadi pada saat Bali diperintah raja Sri Candrabhaya Singha Warmadewa sebagai raja keempat dari dinasti Warmadewa yang memerintah dari tahun 962 hingga 975. Dengan demikian dapat disimak bahwa pada abad X sudah ada tari Baris, namun bentuknya apakah sama dengan Baris upacara yang ada sekarang, memerlukan perenungan lebih mendalam.
Sumber lain yang lebih muda yakni Kidung Sunda yang ditulis tahun 1550 dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, karena merupakan kesusastraan Majapahit yang kemudian banyak mempengaruhi kebudayaan Hindu Bali. Disebutkan, tujuh macam Babarisan yang dipentaskan raja Hayam Wuruk, sehubungan dengan upacara pemakaman raja Sunda yang tewas terbunuh dalam perang Bubat.. Salah satu Babarisan itu disebut tari Limping yang bentuknya mendekati Baris Tombak yang ada di Bali.
Jenis tarian ini merupakan perwatakan yang sangat unik, menekankan keseimbangan dan kestabilan langkah-langkah pada waktu berbaris maupun saat memainkan senjatanya sehingga disebut tari kepahlawanan. Semula merupakan tarian pengawal istana untuk bersiaga melindungi kerajaan dari kekacauan dan kemudian menjadi suatu sajian suci untuk berbagai kegiatan upacara agama. Dalam penyajiannya membentuk formasi berbaris ke belakang dan ke samping yang dibawakan secara masal, sampai 40 orang penari laki-laki. Kini jenis tari Babarisan diperkirakan masih bertahan sekitar 20 macam, yang masing-masing memiliki perwatakan yang cukup unik. Demikian pula namanya sesuai dengan jenis senjata atau alat upacara yang dibawa ( Baris tombak, panah, tamiang, pendet dsb), warna pakaian (Baris kuning, poleng), penokohan (Baris Cina, Demang), serta wujud yang ditiru (Baris lutung, goak, kupu-kupu).
Tari Baris Katekok Jago Pengawal Arwah Ke Sorga selengkapnya

by admin | Mar 27, 2011 | Artikel, Berita
 Oleh: Hendra Santosa, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Oleh: Hendra Santosa, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Instrumen Gong Beri disebutkan pada 22 naskah kuno dari berbagai abad. Pada umumnya instrumen Gong Beri tidak berdiri sendiri melainkan di ikuti oleh berbagai instrumen. Gong Beri sebagai instrumen, tidak ditempatkan pada setiap peperangan, tetapi pada peperangan tertentu dengan nama-nama tertentu pula yang ada pada lingkungannya, bahkan ada pada saat duka cita.
Untuk mendukung kesimpulan tersebut, kita lihat dalam beberapa naskah kuno seperti kekawin Bharatayudha, kekawin Arjuna Wiwaha, dan kidung Rangga Lawe. Dalam Kekawin Baratayudha, kata beri, hanya tercantum dalam pupuh X no 3, disebutkan:
Samangkana sang aryya bhisma pinakagra senapati.
Katon mabhiseka sampun asekar sira bhusana
Penuh paseluring prawira masurak masanggharuhan.
lawan paddahi bheri cangka ti nulup hurung ring langit.
(Pada saat itu Bhisma dijadikan panglima tertinggi. Orang dapat menyaksikan. Ketika ia ditasbihkan: setelah ia memakai bunga-bungaan, ia lalu berhias. Orang-orang pahlawan yang banyak jumlahnya dan berbondong-bondong itu bersorak-sorak. Kelompok demi kelompok, berganti-gantian, padahi, bheri yang dipukul, dan sangka yang ditiup itu riuh rendah suaranya memenuhi langit).
Gamelan Gong Beri hanya terdapat dalam satu pupuh, padahal dalam kekawin Bharatayudha yang menyangkut peperangan sangat banyak. Kenapa hanya pada saat penobatan Bhisma yang menjadi senapati Korawa saja yang menggunakan Gong Beri? Tentu ada alasan-alasannya. Pertama, penulis menganggap bahwa Rsi Bhisma merupakan orang yang paling dihormati oleh kedua belah pihak yaitu Korawa dan Pandawa. Kedua, beliau adalah guru bagi kedua pihak.
Dalam C.C Berg, Bibliotheca Javanica, Ranggalawe.Middel Javaninsche Roman, kata beri ada pada bagian pupuh VII no. 86 dan pupuh ke XI (pupuh Durma) no. 104. Jaap Kunts mengungkapkan hanya pada satu yaitu pupuh ke XI no. 104. Dalam pupuh ke VII no 58 disebutkan:
Gong Beri Dalam Berbagai Naskah Kuno selengkapnya

by admin | Mar 25, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman I Ketut Ardana, Dosen Jurusan Karawitan ISI Yogyakarta.
Kiriman I Ketut Ardana, Dosen Jurusan Karawitan ISI Yogyakarta.
Alam ritual dengan gending leluangan adalah bagian yang tak terpisahkan. Para seniman meyakini, bermain gending leluangan dalam upacara ritual adalah sebagai wujud bakti manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widi Wasa). Keberadaan gending merupakan faktor keindahan, hal ini sangat mempengaruhi para umat dalam menyatukan diri kepada Nya. Dari keindahan juga akan menghadirkan suatu ketenangan dalam melakukan yadnya. Hadirnya gending leluangan merupakan salah satu pengimplementasian keindahan dalam upacara. Gending leluangan itu indah. Keindahan gending muncul dari bunyi-bunyian yang tertata berbentuk sebuah aroma bunyi-bunyian yang melankolis. Memiliki melodi, ritme, dinamika, dan harmoni yang dapat menyentuh hati bagi si pendengarnya.
Sejak jaman dulu sudah berkembang pemahaman bahwa gamelan Bali selalu digunakan dalam mengiringi upacara keagamaan. Bahkan ada pendapat mengatakan, eksistensi gamelan Bali saat ini sangat besar disebabkan oleh budaya Bali yang selalu melibatkan kesenian. Dari fenomena ini keberadaan gending leluangan dalam upacara salah satunya digunakan untuk mengiringi ritual pangilen-ngilen. Besar keyakinan para umat bahwa gending juga sangat mempengaruhi tercapainya alam ritual bagi masyarakat.
Pada setiap proses persembahan pangilen-ngilen yang dilakukan oleh Pemangku pura diawali dengan memberikan koordinasi pada para Sekehe Gong untuk memulai gending iringan. Seandainya gending tidak dimainkan oleh para pengrawit, maka para Pemangku juga tidak memulai upacara. Mulainya gending dapat merespon para Pemangku untuk memulai berdoa, mengheningkan pikiran agar mencapai alam kerawuhuan (trans). Dalam konteks ini, gending sebagai iringan dimainkan dengan irama cepat dan memiliki dinamika yang keras. Gending mengalun berulang kali sambil mengiringi para Pemangku untuk mempersembahkan sesajen yang merupakan bagian dari proses ritual.
Leluangan Sebagai Sarana Membangun Suasana Ritual
Ada sebuah asumsi, Kemantapan dalam melakukan proses persembahan upacara Ritual sangat dipengaruhi oleh keberadaan musikal dalam upacara. Tentu saja asumsi ini ada benarnya jika berangkat dari pernyataan Hazrat Inayat Khan yang mengatakan bahwa “… penyembuhan melalui musik dalam kenyataannya merupakan awal dari perkembangan seni musik, yang tujuannya adalah mencapai sesuatu yang dalam bahasa Wedanta disebut samadhi” (Khan, 2002:130). Pencapain alam samadhi adalah salah satu harapan yang ingin dicapai masyarakat dalam upacara ritual. Pencapaian ini sangat dibantu oleh keberadaan gending leluangan sehingga bisa membantu para pemedek (umat) dalam menyatukan diri kepada Nya. Dalam upacara ritual masyarakat memberikan suatu persembahan yadnya sembari memohon kepada Nya untuk diberikan kehidupan yang damai, tenang, dan sejahtera.
Leluangan Dan Upacara Piodalan Di Desa Kesiman Selengkapnya

 Oleh: Pande Artadi, Dosen PS Desain Interior ISI Denpasar
Oleh: Pande Artadi, Dosen PS Desain Interior ISI Denpasar