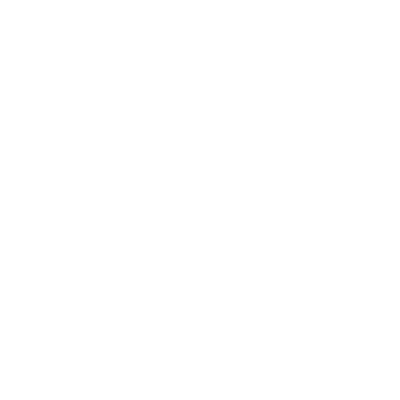by admin | May 3, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman I Wayan Sucipta, Mahasiswa PS. Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman I Wayan Sucipta, Mahasiswa PS. Seni Karawitan ISI Denpasar
Sejarah adalah rentetan peristiwa pada jaman lampau yang memang benar-benar terjadi. Keberadaannya dapat dibuktikan berupa peningalan-peninggalan arca maupun prasasti. Sejarah pada umumnya sangat berkaitan dengan manusia, lingkungan, dan kebudayaan. Untuk menunjukan bukti tentang terjadinya suatu peristiwa pada jaman dahulu, orang-orang pada waktu itu menuliskan sebuah prasasti maupun tanda-tanda peninggalan sejarah berupa arca-arca. Misalnya sejarah perkembangan desa, yang secara tidak langsung diikuti oleh seni dan kebudayaan masyarakat tersebut. Di dalam mengungkap sebuah sejarah perlu adanya langkah-langkah khusus yang dapat membantu menemukan bukti-bukti sejarah yang akan dicari.
Untuk menggali data-data yang dapat menunjang dan memberikan imformasi sejarah Gambuh Kedisan yang sebenaranya, peneliti menggunkan metode heuristik. Peneliti berusaha menemukan serta mengumpulkan jejak-jejak peristiwa sejarah yang sebenar-benarnya, yang mencerminkan berbagai aspek aktivitas manusia di waktu yang lampau. Dengan menelusuri berbagai sumber sejarah, seperti benda dan peralatan, sumber sejarah tertulis (dokumen dan prasasti), dan sumber lisan yaitu wawancara. Dalam mengungkap sejarah Gambuh Desa Kedisan selain peneliti mendapat data-data tertulis dari dokumen, peneliti lebih banyak menggunakan metode wawancara. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui kevaliditas data tertulis yang didapat, dan secara khusus tidak ada prasasti dan bukti atau sejarah tertulis tentang kesenian Gambuh ini. Hanya sedikit disinggung pada sejarah terbentuknya Desa Kedisan.
Menurut Jro Mangku Manggih (56 tahun) jauh sebelum kedatangan warga Aan ke Desa Kedisan kesenian Gambuh tersebut sudah ada di desanya. Ketika warga Aan mengetahui di Desa Kedisan terdapat Kesenian Gambuh, warga tersebut memutuskan untuk ikut ngamuh (bergabung dengan Kesenian Gambuh) dan menetap di Desa Kedisan.
Menurut lontar Arya Wang Bang Sidemen, Ki Pasek Katrangan dan pengiring lainnya meninggalkan Aan pada windhu wisaya warih prabu, yang artinya Isaka 1450 atau tahun 1528 masehi, dengan tujuan mengiringi kepergian I Gusti Kacang Dawa. Warga Aan pada saat itu membawa Gelungan Panji yang merupakan tanda kesaktian dari Ki Pasek Katrangan. Gelungan Panji tersebut sampai sekarang ini masih terdapat di Desa Kedisan. Keberadaannya disakralkan dan ditempatkan (disungsung) di Pura Pemaksan (kawitan) warga Aan. Pura kawitan adalah pura yang penyungsungnya ditentukan oleh ikatan wit atau leluhur berdasarkan garis vertikal geneologis. Secara tidak langsung dari prasasti ini menyebutkan Kesenian Gambuh di Desa Kedisan sudah ada sejak jaman kerajan terdahulu. Bukti tertulisnya secara tidak langsung diketemukan pada lontar Candrasangkala yang mengisahkan tentang terbentuknya Desa Kedisan. Pada tahun Isaka Apuy Awtaraning Jaladhi Canra
(Apuy = 3, Awtara = 6, Jaladhi = 4, Candra = 1) artinya 1464 saka atau 1541 masehi.
I Gusti Ngurah Widiantara, mengatakan secara historis Gambuh Kedisan tidak ada kaitannya dengan Kesenian Gambuh dan puri yang ada di daerah lainnya, terkecuali dengan Puri Kedisan. Puri Kedisan merupakan tempat tinggal penglingsir (tokoh puri) yang datang ke Desa Kedisan membawa Gelungan panji dengan Ki Pasek Katrangan. Akan tetapi di Puri Kedisan tidak terdapat Bale Pegambuhan, seperti di Puri Gianyar.
Gambuh Kedisan tidak dibentuk dalam wilayah puri, melainkan secara autodidak tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakat Kedisan yang memang menyukai Kesenian Gambuh. Gambuh ini selalu diminta ngayah (pentas) di Puri Gianyar, Puri Ubud, dan masyarakat lainnya ketika ada kegiatan upacara keagamaan di lingkungan puri dan masyarakat. Maka dari seringnya pentas di Puri Gianyar, Puri Ubud dan puri lainnya Gambuh Kedisan menjadi terkenal, dan dikenal dengan istilah Gambuh Kedisan.
Gambuh Kedisan merupakan Gambuh yang memiliki ciri khas tersendiri dari Gambuh lainnya. Ciri khas yang paling menonjol adalah penari, dimana semua penari Gambuh diperankan oleh seorang laki-laki. Sehingga Gambuh Kedisan juga disebut dengan istilah Gambuh lanang. Tarian Gambuh Kedisan memiliki gerak tari yang sedikit kaku (sogol), karena ditarikan oleh laki-laki. Sehingga dari sebuah gerak tari yang kaku (sogol) pada Gambuh Kedisan menimbulkan sebuah ke khasan dalam tarian tersebut.
Pada tahun 1965 Gambuh Kedisan sempat mengalami fakum dari pertunjukan, karena makin sedikitnya penari Gambuh dan sedikitnya generasi yang mau menekuninya. Untuk membangkitkannya kembali, timbul inisiatif untuk mendatangkan pelatih Gambuh dari Desa Batuan, yaitu I Nyoman Kakul dan putranya I Nyoman Mukel. Pada tahun 1965 sempat dua periode mendatangkan pelatih dari Desa Batuan yang pertama Dewa Aji, dan yang kedua barulah I Nyoman Kakul. Karena kuatnya style Gambuh Kedisan yang dikuasai, dan dipergunakan dari jaman dulu, mengakaibatkan sulitnya menerima style tarian dari Batuan, yang diajarkan oleh I Nyoman Kakul dan I Nyoman Mukel.Tidak lama kemudian akhirnya kembali dengan style Kedisan yang sering dipergunakan dari jaman dulu.
Sejarah Gambuh di Desa Kedisan, selengkapnya
by admin | May 3, 2011 | Berita, pengumuman
Diberitahukan kepada Mahasiswa FSRD ISI Denpasar yang telah mendaftar Tugas Akhir (TA) Semester Genap 2010/2011 bahwa Pendaftaran Ujian TA dan Penyerahan Karya Pameran dilaksanakan pada tanggal 16 – 20 Mei 2011.
Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan. Terima kasih.
Denpasar, 3 Mei 2011
A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,
Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn
NIP. 196107061990031005
by admin | May 3, 2011 | Berita, pengumuman
Jadwal Tugas Akhir FSRD Semester Genap 2011 dapat didownload di sini
Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,
Drs. Olih Solihat Karso, M.Sn
NIP. 196107061990031005

by admin | May 3, 2011 | Berita
 Tiap kali memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) seperti hari ini, dalam konteks reflektif, kita selalu dihadapkan pada salah satu pertanyaan mendasar,sudahkah ”produk” pendidikan mampu menjawab berbagai persoalan yang sifatnya kekinian dan mengantisipasi masa depan?
Tiap kali memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) seperti hari ini, dalam konteks reflektif, kita selalu dihadapkan pada salah satu pertanyaan mendasar,sudahkah ”produk” pendidikan mampu menjawab berbagai persoalan yang sifatnya kekinian dan mengantisipasi masa depan?
Berangkat dari pertanyaan mendasar itulah, tulisan ini mencoba memberikan jawaban. Konteksnya tentu masih dalam memperingati Hardiknas, yang dalam temanya terkandung makna, menyiapkan generasi dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia, generasi 2045. Tema Hari Pendidikan Nasional 2011 ini adalah Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa dengan subtema Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti. Tema dan subtema ini erat kaitannya dengan sebuah proses panjang menyiapkan generasimendatang, karenamemang pendidikan karakter, prestasi, dan budi pekerti,diakui sebagai upaya proses panjang yang tidak bisa dilakukan seperti ”membalik telapak tangan”.
Semua telah memahami, dalam dunia pendidikan, manusia sebagai pemeran utamanya, baik sebagai subjek sekaligus objek. Keilmuan sebagai medianya,memanusiakan manusia sebagai salah satu tujuannya, dan kemampuan untuk menjawab berbagai persoalan yang sifatnya kekinian maupun antisipasi masa depan (kenantian) sebagai keniscayaannya. Itulah sebabnya mengapa dunia pendidikan itu kompleks, menantang, namun sangat mulia.Kompleksitas dan tantangan terus berkembang, seiring dengan perjalanan zaman. Karena itu, kita semua harus secara bersama-sama terus-menerus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menanganinya, demi kemuliaan diri, bangsa, negara, dan umat manusia.
Selain itu, kita juga memahami dan menyadari tentang tantangan global dan internal yang sedang dihadapi, yang mengharuskan kita semua untuk lebih memperkuat jati diri,identitas,dan karakter sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi sumber daya alam yang sangat kaya, sumber daya manusia berupa bonus demografi (2010-2040) yang luar biasa besar, dan perjalanan panjang sebagai bangsa yang tangguh dan penuh optimisme.Demikian juga kesempatan yang sangat terbuka untuk menjadi bangsa dan negara yang besar, maju, demokratis, dan sejahtera. Jadi sekarang ini, ada potensi dan ada kesempatan. Untuk itu, momentum yang sangat mahal ini harus kita manfaatkan dengan baik dengan menyiapkan generasi menuju 2045, yaitu pada saat 100 tahun Indonesia merdeka.
Yang Harus Disiapkan
Dari sekian banyak yang harus disiapkan, penyiapan sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas adalah syarat mutlaknya,serta pendidikan karakter sebagai salah satu kuncinya. Ada tiga kelompok pendidikan karakter, yaitu: (i) pendidikan karakter yang menumbuhkan kesadaran sebagai makhluk dan hamba Tuhan Yang Maha Esa (ii),pendidikan karakter yang terkait dengan keilmuan, dan (iii) pendidikan karakter yang menumbuhkan rasa cinta dan bangga menjadi orang Indonesia.
Kesadaran sebagai makhluk dan hamba Tuhan Yang Maha Esa akan menumbuhkan nilai transendensi dan nilai keagamaan yang kuat, yang pada gilirannya tumbuh sifat kasih sayang dan toleransaling menghargai dan menghormati (karena merasa sesama makhluk) dan menjauhkan diri dari perilaku destruktif dan anarkistis. Kesadaran sebagai makhluk-hamba juga akan menumbuhkan sifat jujur, karena merasa ‘malu’ kepada Tuhan. Alangkah indahnya,sesama makhluk dan hamba termasuk lingkungan alam semesta tumbuh rasa kasih sayang secara tulus dan jujur.Tidakkah kita ini memiliki misi utama untuk memberikan ‘kerahmatan’ bagi alam semesta.
Metodologi dan materi pembelajaran yang merangsang tumbuhnya kepenasaranan intelektual haruslah lebih ditonjolkan untuk membangun pola pikir, tradisi dan budaya keilmuan,menumbuhkan kreativitas dan sekaligus daya inovasi.Di sini peran guru lebih dominan dibanding kecukupan sarana dan prasarana. Budaya keilmuan merupakan modal penting dan menjadi semakin rasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan. Dengan kreativitas dan daya inovasi, semakin cerdas dalam mengelola sumber daya yang kita miliki, semakin tinggi nilai tambah yang bisa diberikan. Pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan lebih signifikan. Inilahpendidikankarakter yang terkait dengan keilmuan.
Kelompok karakter ketiga yang harus dibangun adalah menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kecintaan karena sadar bahwa bangsa dan negara dengan empat pilarnya yaitu: Pancasila,UUD 1945,Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita, hasil dari perjuangan yang luar biasa. Penumbuhan kebanggaan itu dilakukan melalui kegemaran kita untuk berprestasi. Prestasi positif kita kontribusikan dan dedikasikan demi kemajuan bangsa dan negara. Inilah yang bisa menumbuhkan kebanggaan sejati. Tanpa prestasi dikhawatirkan kita bisa terjebak dalam kebanggaan semu, kebanggaan tanpa makna.
Itulah alasan mengapa tema Hardiknas 2011 ini adalah Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa dengan subtema Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti. Membangun ketiga kelompok karakter tersebut tidak cukup hanya pembelajaran di kelas, tapi juga harus secara simultan melalui membangun kultur sekolah (school culture), keluarga, dan masyarakat. Ini harus diajarkan mulai dari pendidikan anak usia dini,perguruan tinggi, sampai belajar sepanjang hayat (life long learning).
Pendidikan PAUD
Banyak agenda yang harus disiapkan dalam menyiapkan generasi 2045, antara lain pendidikan anak usia dini (PAUD). Pada usia inilah masa emas dari generasi kita.Mereka inilah 30- an tahun ke depan yang akan menjadi pemegang kunci kemajuan bangsa. Karena itu, tidak ada pilihan lain kalau kita ingin menyiapkan generasi 2045, harus kita mulai dari sekarang yaitu dengan memberikan perhatian khusus pada PAUD, dengan tetap memberikan perhatian pada jenjang pendidikan yang lain. Kementerian Pendidikan Nasional,mulai 2011 menjadikan PAUD sebagai gerakan nasional.
Alhamdulillah, kesadaran dan antusiasme masyarakat terhadap PAUD sangat tinggi. Kita yakin, angka partisipasi kasar PAUD, yaitu 57% pada 2010 dapat ditingkatkan secara signifikan menjadi 70%.Pada PAUD inilah paling tidak kita mulai tanamkan tiga kelompok pendidikan karakter tersebut, yaitu karakter sebagai hamba Tuhan, karakter keilmuan,dan karakter cinta terhadap bangsa dan negara. Harus diakui, pada dasarnya pendidikan merupakan sebuah proses panjang, berkelanjutan, dan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, konsistensi kebijakan dan kebersamaan diperlukan. Inilah ‘hadiah’’ yang kita siapkan dan persembahkan dalam menyambut generasi 2045, generasi 100 tahun Indonesia merdeka. Insya Allah.
MOHAMMAD NUH
Menteri Pendidikan Nasional
Sumber: seputar-indonesia.com

by admin | May 2, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman Saptono, SSen., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar.
Kiriman Saptono, SSen., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar.
Langkah awal yang harus dikerjakan penglaras sebelum membuat embat, terlebih dahulu diawali dengan “nggrambyang” nada-nada instrument gamelan seperti gong, kempul, kenong, balungan, sanpai gender. Jika dirasa sudah cukup kemudian yang diperlukan pertama adalah melepas bilah-bilah gender barung untuk membuat “babonan” nada dasar gamelan. Bilah-bilah gender dilepas dari tali pelunturnya kemudian disusun kembali di atas peluntur sesuai dengan urutan nadanya. Untuk memudahkan pengerjaan membuat babonan gamelan, di dalam pencarian nada-nadanya dibutuhkan malam/lilin untuk ditempel pada bagian lambung bilah gender, maka menaruh bilahnya dibalik menjadi lambungnya di atas, seperti yang terlihat pada gambar tersebut.
Suraya menjelaskan bahwa membuat babonan embat harus memiliki kepekaan rasa terhadap jangkah atau interval gamelan Jawa. Yang menarik adalah masing-masing penglaras gamelan akan memiliki kepekaan rasa yang berbeda dan tidak ada yang sama setiap membuat embat (penjelasan saat materi magang tanggal 22 September 2010 di Musium Ronggowarsito Semarang). Hal ini didukung penjelasan Supanggah dalam bukunya Bothekan karawitan 1(2002) menurutnya sampai sekarang ini belum dan mudah-mudahan tidak aka ada standarisasi larasan gamelan di dunia ini, walau diskusi tentang itu telah banyak dilakukan. Kecuali dalam hal ini penglaras gamelan ada pesanan dari si pemilik gamelan agar gamelan miliknya dilaras sesuai dengan gemelan tertentu. Misalnya lngln sama dengan gamelan RRI Sirakarta, maka si penglaras harus meminjam untuk ngukur (dengan cara merekam nada/membuat tetuding dengan bilah atau suling) embat yang dimiliki gamelan di RRI Surakarta.
Disaat yang sama juga didekatkan saron barung laras slendro. Karena penglaras gamelan setiap menggarap atau mengerjakan nglaras gamelan akan dibantu oleh beberapa orang asisten (dalam bahasa pande gamelan lebih lumrah dengan istilah rewang/bahu). Seperti juga para pemilik pande gamelan atau penglaras gamelan jika menerima order mereka akan mengajak rewang. Begitu juga dengan Suraya ketika menggarap proyeknya, ia akan mengajak orang yang bisa diandalkan dalam membantu pekerjaan pelarasan. Dan biasanya ia akan mengajak tiga sampai empat orang termasuk sopir, dan biasanya orang-orang yang diajak ini tidak segan-segan kepada Suraya akan memanggilnya “juragan” (bos). Sungguh pun umur dari Suraya bisa dibilang masih tergolong muda (44 th) di bandingkan dengan para pembuat gamelan (pande gamelan) di Solo, yang lain rata-rata umur-umur mereka di atas 55 tahun, bahkan di atas 60-an.
Sementara pekerjaan Suraya juga dibantu oleh orang-orang yang masih tergolong muda, akan tetapi mereka memiliki pengalaman dibidang melaras gamelan ( pelarasan dan perawatan gamelan). Dan menurut Suraya pengalaman kerja dibantu oleh mereka, dirinya (Suraya) merasa enak dan nyaman, karena mereka masing-masing bisa diandalkan pekerjaannya. Adapun orang-orang yang ikut kerja melaras gamelan dengan Suraya yaitu Sutarno (31 tahun) dari Bekonang Sukoharjo, Noma (28 tahun) dari Bekonang Sukoharjo, Gareng (41 tahun) dari Solo, dan Bejo (40 tahun) dari Solo. Jika mengerjakan pelarasan di luar Surakarta, maka Suraya akan mengajak mas Eko (45 tahun) dari Solo sebagai orang yang dipercaya untuk ngurusi transportasi. Sementara Sutarno dengan bekal pengalamannya dapat diandalkan mengerjakan pelarasan ricikan-ricikan pencon. Untuk Noma dan Gareng pekerjaan pelarasannya diserahi nggarap ricikan-ricikan bilah. Bejo adalah memiliki tenaga yang luar biasa (roso) dan lebih nyaman ia sebagai laden (melayani kebutuhan) dari mereka. Sebagai pengusaha gamelan, Suraya juga mempekerjakan Bejo di tempat usahanya sebagai tukang cet/plistur rancakan-rancakan gamelan, maka jika ada pemelisturan atau pengecetan rancak gamelan akan ditangani oleh Bejo.
Dengan demikian, ketika Suraya sedang mengerjakan membuat babonan mereka (bahu tersebut) sudah paham tentang apa-apa yang harus disiapkan (termasuk peralatan) dan apa-apa yang akan dikerjakan. Jika bahu tersebut tidak mau tahu akan pekerjaannya maka akan dianggap malas oleh juragannya dan besok-besok kalau ada proyek lagi akan dikurangi bayarannya atau bahkan akan tidak diajak bekerja lagi dengannya dalam kesempatan yang lain.
Melaras Gamelan Jawa, Bagian I, selengkapnya

 Kiriman I Wayan Sucipta, Mahasiswa PS. Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman I Wayan Sucipta, Mahasiswa PS. Seni Karawitan ISI Denpasar