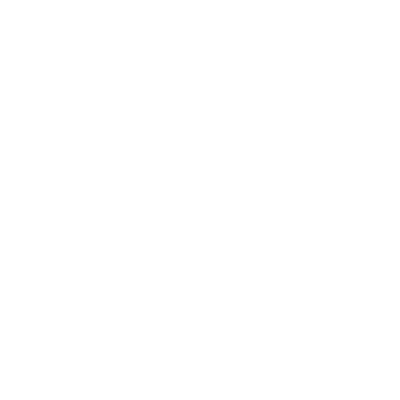by admin | Jun 2, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman Ida Bagus Surya Peradantha, S.Sn
Kiriman Ida Bagus Surya Peradantha, S.Sn
Melihat potensinya, Bali memiliki kekayaan yang luar biasa di bidang kesenian khususnya di bidang seni tari. Bila ditinjau dari karakternya, tari Bali dapat dibedakan menjadi tari putra dan tari putri. Sedangkan bila dilihat dari sisi koreografi, tari Bali dapat dipilah menjadi tari tunggal, duet, trio dan kelompok. Dibedakan dari sejarahnya, tari Bali dapat dibagi menjadi tari klasik atau tradisional serta tari kreasi baru.
Khusus mengenai tari klasik, tari-tarian yang termasuk kategori ini telah berkembang sejak jaman kerajaan. Adapun jenis tarian yang dapat dimasukkan dalam kelompok ini antara lain yaitu Gambuh, Topeng, Arja dan Legong. Semua tarian tersebut merupakan masterpiece yang telah membawa nama Bali ke dunia internasional dikarenakan nilai artistiknya yang tinggi dan membutuhkan teknik tari Bali yang baik untuk membawakannya.
Di Bali, terdapat banyak pusat-pusat pengembangan tari klasik yang masih bertahan hingga kini. Di desa Pedungan dan desa Batuan misalnya, semenjak dulu telah berkembang kesenian Gambuh. Di desa Peliatan dan Saba, berkembang tari Legong Keraton dengan pengembangan gaya masing-masing. Serta banyak lagi desa-desa lainnya yang merupakan tempat-tempat pengembangan tari-tari klasik yang masih tetap kuat mempertahankan tradisinya.
Seni tari klasik ini tumbuh dan berkembang pertama kali di lingkungan istana yang diperuntukkan demi kepentingan istana, baik itu untuk hiburan sang raja, demi kepentingan upacara maupun yang lainnya. Lalu sebenarnya siapakah yang menciptakan tari-tarian tersebut ? Kita tidak pernah tahu siapa yang menciptakan tari Gambuh, Arja, Pendet maupun Legong. Belakangan ini, khususnya setelah marak terjadi klaim beberapa jenis kesenian kita oleh Malaysia, pemerintah Indonesia seolah kebakaran jenggot dengan menyerukan kepada setiap insan seni di tanah air untuk sesegera mungkin mematenkan karyanya. Dari sini kembali muncul persoalan ; bagaimanakah jadinya kesenian tradisional seperti di Bali yang sebagian besar anonym atau tidak diketahui siapa penciptanya kemudian “dipayungi” oleh produk hukum yang dinamakan Undang-Undang Hak Cipta? Akan menguntungkan atau malah akan memenjarakan kesenian itu sendiri?
Seperti yang telah disampaikan di atas, seorang pencipta tari pada jaman kerajaan akan merasa senang dan bangga bilamana hasil karyanya disukai dan dipentaskan di lingkungan istana. Para pencipta tersebut menganggap popularitas dan keuntungan komersial bukanlah menjadi tujuan utama. Sebab, prinsip utama berkesenian orang Bali dahulu ( mungkin pula berlaku hingga sekarang ) adalah untuk kepentingan ngayah ( persembahan ) baik itu kepada sang pencipta maupun kepada sang penguasa. Ini sangat otentik sekali dengan sikap atau pola pikir adat ketimuran yang mengedepankan unsur kolektivitas. Maka dari itu, seni klasik yang juga termasuk salah satu kearifan lokal di Bali kebanyakan anonymous dan juga menjadi public domain. Namun justru dengan keadaan itulah, Bali menjadi terkenal tidak hanya di dalam negeri tetapi telah merambah ke seluruh mancanegara.
Setelah berakhirnya jaman kerajaan dan beralih ke bentuk pemerintahan republik, konsentarasi pengembangan seni klasik kini tidak lagi berada di istana, melainkan berpencar ke desa-desa dan selanjutnya berkembang disana. Misalkan, Gambuh yang pada awalnya merupakan tarian istana, kemudian dikembangkan di desa Pedungan dan Batuan sehingga kini disebut Gambuh Pedungan dan Gambuh Batuan. Demikian pula halnya dengan Tari Legong. Oleh karena sering dipentaskan di istana, maka Tari Legong akhirnya disebut Tari Legong Keraton. Setelah tidak lagi berkembang di istana, dimana sekarang berkembang di desa Peliatan dan Saba, maka tari Legong Keraton disebut Legong Keraton Peliatan atau Legong Keraton Saba. Pemberian legitimasi seperti itu jelas merupakan suatu usaha untuk mempertahankan dan melestarikan kesenian tersebut agar tidak lekang oleh jaman dan menghindarinya dari segala kemungkinan buruk tentang hak cipta. Di tempat-tempat itulah, para penari yang dulunya merupakan penari istana membina penari-penari setempat untuk dijadikan penerus berlangsungnya tari-tari klasik ini.
Setelah melakukan proses sedemikian rupa dan berlangsung dalam waktu lama, maka perkembangan tari-tari klasik ini menjadilah seperti sekarang. Di Pedungan misalnya, seni Gambuh dipertahankan dan dipelihara keberlangsungannya dengan cara menjadikan pementasan tari Gambuh menjadi sesuatu yang wajib dipentaskan dalam upacara keagamaan di pura setempat.
Dengan melihat perkembangan seni klasik di Bali seperti yang telah disinggung di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat Bali memiliki local genius yang sangat kaya. Itu pun baru di bidang seni pertunjukan. Namun, perlindungan yang diberikan pada kekayaan yang tak ternilai harganya tersebut masih terlalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang buruk, termasuk pembajakan dan pengakuan secara illegal dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengesahan terhadap suatu produk local genius-nya masih sebatas pengakuan bersama oleh masyarakat yang kurang memiliki kekuatan hukum secara tertulis. Apalagi dalam kondisi sekarang ini Bali telah menghadapi era globalisasi dengan pendekatan pembangunan ekonomi pada sektor industri pariwisata.
Di jaman global seperti sekarang dimana segala aktivitas manusia berjalan begitu dinamis, memberi kesempatan yang sangat luas bagi setiap wisatawan baik lokal maupun asing untuk menikmati berbagai keindahan alam dan kekayaan Bali secara langsung. Hal ini memang pada awalnnya merupakan sebuah keuntungan bagi masyarakat Bali yang pada umumnya mendapat kesempatan secara langsung untuk terlibat dalam berbagai kegiatan termasuk melakukan promosi terhadap segala kekayaan alam dan seni pulau Bali. Namun di sisi lain, kita juga dituntut untuk selalu waspada terhadap segala keuntungan yang ditawarkan di atas. Jika keuntungan tersebut gagal kita kelola dengan baik, maka keuntungan tersebut juga akan memberikan kerugian.
Dilema Penerapan Haki Dalam Kehidupan Berkesenian Di Bali, selengkapanya

by admin | Jun 1, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Wardizal Ssen., Msi., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman: Wardizal Ssen., Msi., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Jenis instrumen musik keluarga chardophone yang berkembang di Minangkabau adalah Rabab (rebab). Pertunjukannya sendiri disebut barabab yang berarti bercerita atau berkaba dengan iringan lagu dan bunyi rebab yang digesek oleh pencerita (Syamsudin, 1993:6). Pertunjukan rebab biasanya dilakukan disebuah ruangan tempat orang banyak dapat duduk berkumpul menyaksikan pertunjukan. Sering juga dilakukan di ruang tamu rumah orang yang mengadakan pesta keramaian. Ada tiga bentuk/jenis rebab yang berkembang di Minangkabau, yaitu:
Rebab Darek
Jenis instrumen musik berdawai (pakai snar) yang tumbuh dan berkembang terutama di daerah daratan Minangkabau (luhak nan tigo). Pemberian nama darek pada intrumen ini untuk membedakan dengan jenis musik berdawai lainnya yang juga berkembang di Minangkabau. Jika ditinjau dari sudut fisik serta bahannya, intrumen rebab darek terdiri atas tiga bagian. Pertama bagian badan yang berfungsi sebagai ronga resonansi yang terbuat dari kayu nangka yang dibentuk sedemikian rupa dan dilapisi dengan kulit kambing atau kulit sapi. Kedua, bagian leher yang terbuat dari bambu atau talang. Biasanya dipilih talang yang sudah tua agar tidak mudah pecah. Ketiga, bagian kepala berupa kayu yang diukir. Di samping kiri dan kanan kepala rebab dipasang alat pemitar tali rebab yang berjumlah 2 (dua) buah. Sebagai penimbul bunyi, dipasang dua buah tali yang terbuat dari benang. Penggesek rebab terbuat dari kayu dan bubat (ekor kuda) atau nilon.
Fungsi dari instrumen rebab darek ini adalah sebagai alat untuk mengiringi dendang, khususnya dendang-dendang yang berkembang di daerah darek Minangkabau. Pertunjukan rebab darek herat kaitanya dengan upacara adat seperti: pengangkatan penghulu, mantenan, dan acara-acara yang bersifat sosial kemasyarakatan.
Rebab Pariaman
Jenis insrumen musik berdawai yang tumbuh dan berkembang khususnya di daerah Pesisir Barat Minangkabau, tepatnya di daera Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Instrumen rabab Pariaman hampir sama bentuknya dengan rabab darek, hanya bahan pembuatannya yang berbeda. Badan rabab Pariaman terbuat dari tempurung kelapa; tangkai rabab terbuat dari bambu; mempunyai 3 (tiga) buah senar terbuat dari benang, serta penggesek rebab terbuat dari rotan dan sebagai talinya dipakai bulu ekor kuda (bubat).
Fungsi rebab Pariaman adalah sebagai alat untuk mengiringi dendang, terutama jenis dendang kaba yang berkembang di daerah Pariaman sekitarnya. Pertunjukan rebab Pariaman dilaksanakan dalam berbagai bentuk upacara dan keramaian anak nagari, seperti upacara pengangkatan penghulu, helat kawin, malam dana, sunatan dan lain sebagainya.
Rebab Pesisir
Bentuk lain dari intrumen berdawai yang berkembang di Minangkabau, khususnya di daerah Pesisir Selatan (Painan). Pada awalnya bentuk rabab pasisia ini sama dengan jenis rabab yang berkembang di Pariaman. Keterbukaan masyarakat Pesisir menerima pembaharuan tampak pada perubahan bentuk instrumen rebab. Dalam keadaannya sekarang bentuk instrumen rebab adalah seperti biola. Badan biola terbuat dari kayu nangka; mempunyai 4 (empat) buah snar (tali) (2 helai terbuat dari benang dan 2 helai dipakai dawai atau snar biola). Ada juga yang memakai 1 helai dari benang dan 3 snar biola.
Seperti halnya rebab darek dan rebab pariaman, fungsi rebab pesisir adalah sebagai alat untuk mengiringi dendang, khususnya jenis dendang kaba yang berkembang di daerah Pesisir Selatan. Dalam pertunjukan rebab pesisir, biasanya diiringi dengan sebuah instrumen musik yang dinamakan indang; fungsinya adalah untuk mengiringi dendang yang sifatnya gembira dan untuk menghilangkan rasa jenuh dalam mendengarkan kaba. Pertunjukan rebab pesisir herat kaitanya dengan upacara adat seperti: pengangkatan penghulu, mantenan, dan acara-acara yang bersifat sosial kemasyarakatan.
Instrumen Musik Minangkabau Kelompok Chardophone, Selengkapnya

by admin | May 31, 2011 | Berita
 DENPASAR- Tarian kolosal Siwa Nata Raja dan Adi Merdangga garapan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar akan mengawali atraksi budaya pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-33 pada 10 Juni mendatang.
DENPASAR- Tarian kolosal Siwa Nata Raja dan Adi Merdangga garapan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar akan mengawali atraksi budaya pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-33 pada 10 Juni mendatang.
Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Ketut Suastika di Denpasar, Senin (30/5), kedua tarian yang digarap secara apik dan profesional itu melibatkan ratusan mahasiswa dan dosen lembaga pendidikan tinggi tersebut.
Ia mengatakan, penampilan tim ISI Denpasar dalam atraksi budaya dimulau dari depan bangsal Jaya Sabha Gubernuran Denpasar hingga Taman Budaya Denpasar, tempat berlangsungnya aktivitas seni tahunan di Bali itu. Disusul dengan duta seni dari delapan kabupaten dan satu kota di provinsi itu.
Setiap kabupaten/kota menampilkan keunikan dan ciri khas daerah masing-masing yang dirangkai sedemikian rupa oleh penampilan kabupaten/kota lainnya. Dengan demikian, menjadi satu kesatuan atraksi yang unik dan menarik.
Aktivitas seni itu melibatkan ratusan seniman Bali utara, menyusul Kabupaten Karangasem yang menampilkan ketangkasan pasukan perang tradisional serta berbagai jenis pasukan dan model latihan perang.
Semuanya itu dikemas dalam bentuk seni, diiringi alunan instrumen musik tradisional Bali (gamelan), diikuti duta seni Kabupaten Jembrana, Bali barat yang menyuguhkan Segara Kertih atau petik laut menampilkan seni kerakyatan khas daerah setempat.
Kota Denpasar dalam atraksi budaya itu menampilkan harmoni multi kultur, Kabupaten Tabanan Nangkluk Merana, yakni kegiatan ritual dalam membasmi hama tanaman yang mengganggu pertanian.
SumberL mediaindonesia.com

by admin | May 31, 2011 | Berita
 Jakarta —- Pendidikan tinggi dipercaya berperan besar dalam menentukan tinggi rendahnya daya saing sebuah bangsa. Daya saing yang tinggi juga hanya bisa diraih jika ada kerangka kerja yang sesuai, dan karakternya melekat pada individu dan masyarakat bangsa tersebut. Jika tidak, bisa dipastikan daya saingnya akan rendah.
Jakarta —- Pendidikan tinggi dipercaya berperan besar dalam menentukan tinggi rendahnya daya saing sebuah bangsa. Daya saing yang tinggi juga hanya bisa diraih jika ada kerangka kerja yang sesuai, dan karakternya melekat pada individu dan masyarakat bangsa tersebut. Jika tidak, bisa dipastikan daya saingnya akan rendah.
Di sisi lain, pendidikan tinggi menghadapi banyak tantangan dan harus terus beradaptasi dengan dinamika globalisasi. Apalagi, bagi Indonesia sebagai satu negara berkembang, dengan populasi mencapai 240 juta orang, dan tersebar di tiga daerah waktu, 443 bahasa dan dialek, tapi 70 persen wilayahnya adalah perairan, mengembangkan pendidikan adalah tugas yang berat dan sangat menantang.
“Pada level pendidikan tinggi, selain membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis yang berguna dalam persaingan global, juga harus memberi kontribusi pada pembentukan demokrasi, peradaban, dan masyarakat yang inklusif,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas Djoko Santoso, saat mewakili Wakil Mendiknas Fasli Jalal membuka forum yang diselenggarakan oleh International Institution for Educational Planning UNESCO, SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development., dan Kemdiknas, di Hotel Century, Jakarta, Senin (23/05). Forum ini diselenggarakan untuk merancang sistem yang mengatur kebijakan dan aturan-aturan bagi pemerintah dalam mengatur pendidikan tinggi.
Salah satu pembicara dalam forum tersebut yakni Centre Director SEAMEO RIHED Sauwakon Ratanawijitrasin mengatakan, tahun lalu IIEP dan SEAMEO telah meluncurkan program penelitian mengenai manajemen pendidikan tinggi. Penelitian tersebut dipakai sebagai bahan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam sistem.
Penelitian tersebut melibatkan lima negara, yaitu, Jepang, Kamboja, Vietnam, Indonesia, dan China. Para peneliti dari lima negara tersebut juga akan berpartisipasi dalam forum ini untuk menceritakan pengalaman-pengalaman mereka selama melakukan penelitian.
Selain itu, Head of Governance IIEP N.V. Varghese juga mengatakan, ada empat isu yang menjadi fokus IIEP. Empat focus tersebut adalah persamaan, akses, kualitas, dan biaya pendidikan. Keempat isu tersebut juga akan dibahas dalam forum ini.
Turut hadir juga dalam forum, Programme Specialist at IIEP Michaela Martin. Michaela menyampaikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh IIEP bukanlah penelitian yang dikhususkan bagi IIEP, tapi untuk seluruh dunia khususnya pada pendidikan tinggi.
Forum ini akan berlangsung dua hari, 23-24 Mei 2011. Diharapkan hasil dari pembicaraan ini akan menjadi media bagi kemajuan pendidikan tinggi dan sebagai promosi program pendidikan tinggi kepada masyarakat.
Sumber: kemdiknas.go.id

by admin | May 30, 2011 | Berita
 Jakarta – Pemerintah akan mengkaji ulang regulasi untuk sekolah berlabel internasional. Dengan adanya UU Sisdiknas yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, maka label sekolah internasional yang awalnya berasal dari sekolah kedutaan, menjadi kabur.
Jakarta – Pemerintah akan mengkaji ulang regulasi untuk sekolah berlabel internasional. Dengan adanya UU Sisdiknas yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, maka label sekolah internasional yang awalnya berasal dari sekolah kedutaan, menjadi kabur.
“Sekarang ini kami melihat ada yang berasal dari kedutaan, kemudian berkembang menjadi sekolah internasional. Lalu, karena UU Sisdiknas, ada juga sekolah-sekolah Indonesia yang menuju pada standar internasional. Untuk itu, dua arus regulasinya harus dibuat,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal seusai berkunjung ke Jakarta International School, Selasa (24/05).
Awalnya, sekolah internasional hanya melayani anak-anak berkewarganegaraan asing. Kemudian dengan berjalannya waktu, orang Indonesia meminta agar anak-anak pribumi dimungkinkan untuk belajar juga di sana, dengan pertimbangan mutu yang lebih baik. Sebaliknya, sekolah internasional tersebut juga memerlukan siswa yang berasal dari Indonesia. Supaya dengan adanya anak-anak pribumi, maka anak-anak asing yang belajar di sekolah internasional tersebut juga dapat memahami teman-teman Indonesianya, budaya Indonesia, karena mereka tinggal di Indonesia.
Sedangkan sekolah-sekolah nasional yang menuju standar internasional, bagian terbesarnya adalah anak-anak Indonesia. Namun demikian, Wamendiknas mengatakan, nanti secara bertahap akan ada satu dua orang yang berasal dari warga negara asing.
“Karena itu peraturannya mereferensi bagian terbesar di antara mereka (RSBI) adalah orang Indonesia. Jadi ini yang sedang kita atur, bagaimana seharusnya kedua kategori yg dilabel internasional tapi asal usulnya berbeda, peraturannya akan berbeda,” ujar Wamendiknas Fasli Jalal.
Kurikulum yang berlaku di sekolah internasional pun adalah kurikulum internasional. Dalam kondisi tersebut, Wamendiknas mengatakan, untuk anak-anak Indonesia yang bersekolah di sana harus diberikan hak-haknya. “Kalau mereka menerima anak-anak Indonesia, hak-hak anak Indonesia untuk menerima pelajaran agama, bahasa Indonesia, sejarah, kewarganegaraan, tetap diajarkan. Tapi caranya terserah mereka,” kata Wamendiknas.
Saat ini, sekolah internasional tidak menerapkan ujian nasional sebagai pertimbangan terhadap kelulusan siswanya. Wamendiknas menjelaskan, tidak ada masalah bagi sekolah internasional karena tidak melaksanakan ujian nasional, selama siswa dari sekolah tersebut tidak akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikut di Indonesia.
“Kalau UN, kalau dia mau melanjutkan di Indonesia, setiap jenjang dia wajib ikut un. Tapi kalau tidak melanjutkan di Indonesia terserah mereka,” ujarnya.
Wamendiknas melanjutkan, termasuk untuk guru, regulasinya sudah diatur, berapa persentasenya yang wajar, berapa persentase tenaga administrasi sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan kalau gurunya mengharapkan akreditasi dari pemerintah, pemerintah akan memberi sertifikasi.
Sumber: kemdiknas.go.id

 Kiriman Ida Bagus Surya Peradantha, S.Sn
Kiriman Ida Bagus Surya Peradantha, S.Sn