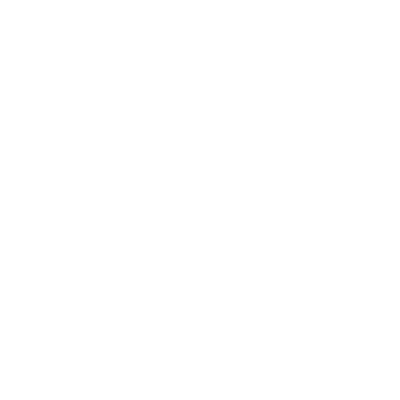Janda Jantan Ni Calonarang, Mengerang Garang Menantang Penguasa
 Kiriman: Kadek Suartaya, S.Skar., Msi., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman: Kadek Suartaya, S.Skar., Msi., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Teater Calonarang merupakan seni pertunjukan Bali yang hingga kini dipandang angker masyarakatnya. Salah satu peran terpenting dalam drama tari yang tak sembarang waktu dipentaskan ini adalah Matah Gede. Tokoh ini adalah sebutan untuk si janda sihir dari Dirah, Calonarang, sebagai manusia biasa sebelum berubah menjadi ratu leak dalam wujud yang dahsyat menyeramkan. Uniknya, pada teater tradisional Bali, penokohan Matah Gede hanya terlihat dalam seni pentas Calonarang. Tokoh ini memiliki karakter yang khas dan sekaligus menjadi identitas seni pertunjukan Calonarang, salah satu seni pentas Bali yang diduga sudah dikenal tahun 1825, era kejayaan kerajaan Klungkung.
Dalam drama tari Calonarang, Matah Gede hadir dengan jati diri perwatakan, tata busana, dan tata rias wajahnya. Pemberang adalah watak menonjol dari tokoh yang tak pernah lepas dari tongkatnya ini. Jika sedang naik pitam, sorot matanya yang menusuk tajam dilukiskan pantang dilawan jika tak ingin hangus terbakar. Memakai kain rembang dan kerudung putih serta tata polesan muka beraksen gurat-gurat keriput, penampilan tokoh ini menjadi lain dari yang lain, membangun struktur dramatik dan menghadirkan kekentalan tema utama teater ini yaitu sebagai drama of magic. Keangkeran Matah Gede juga dibangun oleh dominasi tata ucapannya dalam bahasa Kawi, bahasa Jawa Kuno.
Teater Calonarang dengan tokoh Matah Gede-nya sebagai ratu tenung banyak menarik minat para peneliti dan penulis. The drama of magic adalah sebutan yang diberikan oleh Beryl de Zoete & Walter Spies dalam bukunya Dance and Drama in Bali (1973). Hooykaas dan Meulenhoff dalam bukunya Tjalon Arang Volksverhalen en Legenden uit Bali (1979) menekankan telaahnya pada sastra Calonarang sebagai sumber lakon seni pertunjukan Calonarang. I Made Bandem dan Frederik Eugene deBoer dalam Kaja and Kelod Balinese Dance in Transition (1981) mengkaji juga drama tari Calonarang sebagai magic dance of the street and graveyard. Begitu juga Miguel Cavarrubias dalam Island of Bali (1979) juga tak lupa membahas seni pentas Calonarang.
Seni pentas Calonarang yang hingga kini tak pernah kehilangan gereget itu berangkat dari sumber sastra—seperti halnya kesenian tradisonal Bali pada umumnya–yang diperkirakan muncul pada zaman pemerintahan raja Airlangga di Jawa Timur. Kiranya De Calon-arang (1926), adalah teks sastra Calonarang terpenting yang ditranskripsikan dalam bahasa Jawa Tengahan oleh Poerbacaraka dan telah diterjemahkan oleh Dr. Soewito Santoso dengan judul Calon arang Si Janda dari Girah (1975). Selain dari sumber sastra yang berbentuk prosa itu, Gaguritan Calonarang dalam tarikan puisi pun menjadi acuan signifikan yang mengilhami dan menggiring para seniman seni pertunjukan Calonarang.
Hampir dalam semua sumber, baik yang tertulis maupun lisan, Calonarang digambarkan sebagai seorang wanita penganut teluh yang jahat. Dikisahkan ia tersinggung berat hanya karana anak gadis satu-satuanya, Ratnamangali, yang sudah dewasa belum ada yang melamar. Karena itu, para laki-laki perjaka dilabrak-labrak dan dimusuhinya. Dalam lakon yang berjudul Katundung Ratnamangali, Calonarang meradang karana pelecehan dan penghinaan menantunya, Raja Airlangga. Ia marah bukan kepalang ketika putrinya diusir secara paksa oleh penguasa Daha itu dengan tuduhan menebar petaka santet. Padahal Calonarang sendiri sama sekali tak mengajarkan ilmu sesat tersebut pada anak semata wayangnya ini. Karena merasa harga dirinya diinjak-injak, dengan jantan ia menantang penguasa Airlangga. Dalam episode Perkawinan Mpu Bahula, Calonarang marah sangat begitu garang karena buku ilmu teluhnya dicuri oleh putra Mpu Bharadah, Bahula. Adegan api marah Calonarang ini sering mencuatkan ketegangan dalam pementasan teater Calonarang.
Lazimnya, tokoh Matah Gede atau Calonarang dimainkan oleh penari pria yang sudah berumur. Soal umur mungkin untuk memudahkan memasuki karakter tokoh janda Dirah itu yang diinterpretasikan sebagai seorang nenek-nenek yang telah memiliki anak gadis perawan tua. Sedangkan mengenai kebiasaan pemeranan tokoh sihir ini dibawakan oleh aktor pria sudah demikian adanya sejak dulu. Ada dugaan, tranvesti– memerankan karakter berlawanan jenis kelamin–karena Calonarang adalah tokoh wanita yang berkarakter keras yang mungkin lebih pas dibawakan penari pria. Di beberapa kantong seni pertunjukan Calonarang di Bali, selain harus pria juga ada syarat tambahan yaitu pemainnya seorang balian atau setidaknya orang yang paham dunia supranatural.
Para penari terdahulu yang dikenang oleh masyarakat Bali sangat piawai memerankan tokoh Mata Gede diantaranya adalah I Rinda (Blahbatuh) dan I Kengguh (Singapadu), keduanya dari Kabupten Gianyar, serta I Monog dari Kedaton, Denpasar. Rinda yang banyak menekuni bidang sastra Bali memukau dengan kedalaman dan kepasihan bahasa Kawi-nya. Kengguh mempesona penonton dengan keindahan tata tarinya, dan Monog menggugah lewat gemuruh suaranya yang menggetarkan. Bahasa Kawi, keterampilan estetik tari, dan warna vokal kiranya harus dimiliki oleh para seniman yang akan membawakan Si Calonarang ini.
Janda Jantan Ni Calonarang, Mengerang Garang Menantang Penguasa, selengkapnya

Tumpek Uduh Hormati Tumbuhan di Bali
 Denpasar – Umat Hindu Dharma di Bali merayakan hari Tumpek Wariga atau yang lebih dikenal dengan Tumpek Uduh, persembahan suci yang khusus ditujukan untuk menghormati semua jenis tumbuh-tumbuhan.
Denpasar – Umat Hindu Dharma di Bali merayakan hari Tumpek Wariga atau yang lebih dikenal dengan Tumpek Uduh, persembahan suci yang khusus ditujukan untuk menghormati semua jenis tumbuh-tumbuhan.
Kegiatan ritual menggunakan kelengkapan sarana banten, rangkaian janur kombinasi bunga dan buah-buahan, dengan kekhususan “bubur sumsum”, yakni bubur dari tepung ketan yang diberi warna hijau alami dari daun kayu sugih, ditaburi dengan parutan kelapa dan diberi gula merah.
Masyarakat menggelar kegiatan ritual itu Sabtu (11/6) yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari di ladang, sawah dan pekarangan rumah tangga masing-masing.
Ketua Program Studi Pemandu wisata Institut Hindu Dharma Indonesia (IHDN) Denpasar Doktor Drs I Ketut Sumadi M.Par menjelaskan, Tumpek Uduh dirayakan umat Hindu setiap hari Sabtu uku Wariga yang jatuh setiap 210 hari sekali.
Kegiatan ritual itu dapat dijadikan sebagai mementum yang strategis dalam revitalisasi membangkitkan sektor pertanian mengimbangi kemajuan bidang pariwisata di Pulau Dewata, sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.
Hal itu sangat penting mengingat alam dan potensi Bali dimanfaatkan sebagai pendukung kehidupan masyarakat Pulau Dewata secara turun temurun.Sumber daya alam, manusia dan budaya Bali merupakan satu-kesatuan yang saling terkait dan ketergantungan satu sama lainnya.
Upaya pelestarian, harmonisasi manusia dan alam akan terjamin, jika seluruh komponen berada dalam hubungan yang selaras sesuai konsep Tri Hita Karana. Sebaliknya jika aktivitas pembangunan tidak terkendali menyebabkan kerusakan alam, sehingga berpengaruh terhadap daya dukung yang pada akhirnya mempengaruhi eksistensi manusia dan budayanya, tutur peraih doktor Kajian Budaya Universitas Udayana itu.Alam Bali selama ini telah mampu memberikan kesejukan, rileksasi, ketentraman dan kenyamanan, sehingga mendapat berbagai macam julukan, didasarkan atas kesan wisatawan yang berliburan ke Pulau Dewata.
Seperti di subak Mole dan Subak Sengawang di wilayah Desa Adat Ole. Desa Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, aktivitas petani berjalan secara alami. Hamparan sawah hijau ditata secara apik oleh petani. Saluran irigasi dengan air yang mengalir jernih, di kiri-kanannya membentang areal persawahan dengan berbagai aktivitas petani.
Kegiatan petani antara lain membajak sawah menggunakan tenaga petani, namun sejak tahun 1980 mulai berkurang, bahkan sekarang lebih banyak menggunakan tenaga traktor untuk mengolah lahan pertanian.
Perkumpulan (sekaa) cangkul di sawah maupun sekaa panen padi kini hampir tidak ada lagi, padahal itu sebenarnya merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke Bali, disamping panorama alam dan seni budaya.Ketut Sumadi menilai, konsekuensi dari semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bali menuntut adanya hotel, restoran dan prasarana pendukung pariwisata lainnya.
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan dalam penggunaan lahan dan sumber daya air untuk kepentingan pariwisata maupun bidang pertanian.Luas lahan pertanian menyusut setiap tahunnya berkisar 700-800 hektare. Pantai yang tadinya secara bebas bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian kini dikapling menjadi “private beach” oleh berbagai hotel.
Banyak manfaat
Aktivitas pertanian di Bali menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia, MS tetap mempunyai fungsi strategis, selain memenuhi kebutuhan pangan, menyediakan bahan baku industri dan obat-obatan, juga aktivitas pelestarian terhadap sda dan budaya.
Petani memelihara tumbuhan-tumbuhan, merawatnya sampai tumbuhan bisa memberikan manfaat berupa bahan pangan, sandang dan papan. Bahan yang paling pokok dihasilkan berupa padi, umbi-umbian dan jenis tanaman pangan lainnya.
Orang Bali sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap semua jenis tumbuh-tumbuhan menggelar kegiatan ritual yang bertepatan dengan “Tumpek Wariga atau Tumpuk Uduh” yang jatuh pada hari Sabtu, 11 Juni 2011. Kegiatan ritual yang jatuh setiap 210 hari sekali itu, khusus dipersembahkan untuk tumbuh-tumbuhan, yang selama ini telah mampu memberikan manfaat dan memudahkan bagi kehidupan umat manusia maupun aneka jenis satwa lainnya.
Tumpek Uduh, bukan hari untuk menyembah tumbuh-tumbuhan, namun hari untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar melalui tumbuh-tumbuhan umat manusia bisa diberikan kemakmuran dan keselamatan terhindar dari berbagai bencana.
Tumbuh-tumbuhan dengan sistem perakaran yang ada, memegang partikel tanah dan menutupi permukaan tanah, sehingga saat musim hujan permukaan tanah terhindar erosi.
“Bisa dibayangkan bagaimana parahnya erosi dan longsor, jika seluruh permukaan tanah tidak ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan. Dalam satu musim hujan saja, bagian tanah atas yang subur akan tergerus oleh aliran air,” ujar Prof Windia. Namun dengan adanya perakaran tumbuhan yang masuk jauh ke dalam tanah memungkinkan sebagian air di saat musim hujan masuk dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah itu akan dilepaskan secara bertahap disaat musim kemarau, sehingga ketersediaan air berkesinambungan sepanjang tahun.
Keberadaan tumbuh-tumbuhan dalam satu kawasan tertentu sangat membantu mencegah erosi dan banjir pada musim hujan dan mencegah kekeringan pada musim kemarau.
Dengan demikian keberadaan tumbuh-tumbuhan di alam, tidak hanya memberi hidup dan manfaat bagi umat manusia, namun juga memberikan kehidupan terhadap berbagai jenis makluk hidup lainnya.
Berbagai jenis burung, serangga, kupu-kupu dan hewan lainnya sangat tergantung pada keberadaan tumbuh-tumbuhan.Tumbuh-tumbuhan sangat bermakna bagi kehidupan di alam, selain memberikan kehidupan dan manfaat kepada umat manusia, juga kepada berbagai jenis makluk hidup lainnya di alam ini, ujar Prof Windia.
I Ketut Sutika.
Sumber: antaranews.com

Perkembangan Kerajinan Keramik Tradisional Di Desa Binoh
 Kiriman: Ni Putu Yuda Jayanthi, Mahasiswa PS. Kriya Seni/Keramik, ISI Denpasar
Kiriman: Ni Putu Yuda Jayanthi, Mahasiswa PS. Kriya Seni/Keramik, ISI Denpasar
Seni kerajinan keramik tradisional merupakan kerajinan yang sudah ada dari jaman pra-sejarah, dengan bukti adanya peninggalan-peninggalan benda-benda keramik yang ditemukan di Bali baik dalam keadaan utuh maupun pecahan-pecahan periuk. Tumbuhnya kerajinan keramik tradisional Bali didasari oleh suatu landasan kepercayaan bahwa kehidupan sebagai pengerajin keramik tradisional merupakan anugrah dari para Dewa yang selalu mereka hormati. Sistem kepercayaan seperti itu sangat membantu sekali kehidupan seni keramik tradisional yang berkembang dimasyarakat pengerajin Bali.
Disamping itu dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan selalu memerlukan peralatan dari tanah liat seperti kendi, paso, dan lainnya. Dalam pembuatan keramik tradisional untuk alat-alat rumah tangga, dari masing-masing daerah mempunyai ciri khas atau kekhususan. Adanya kekhususan ini didasari atas pendapat bahwa pembuatan barang-barang tersebut semata-mata karena warisan dan ada pula yang bertitik tolak dari faktor ekonomi karena melayani pesanan. (Mulyawati, 1992: 37). Dalam hubungan kerja adat (masak-memasak), alat perlengkapan keramik tradisional seperti periuk, cobek, paso, dan lainnya, terdapat kecendrungan untuk tetap mempertahankan pemakaian alat ini yang dirasa sulit untuk diganti dengan barang-barang yang dibuat dengan bahan lain yang lebih modern karena ini menyangkut rasa masakan yang dihasilkan. Ini membuktikan jika keramik tradisional Bali masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bali yang idealis dengan makanan khas Bali.
Keberadaan keramik tradisional yang dihasilkan oleh masyarakat pengerajin merupakan dorongan yang kuat untuk mencipta suatu kerajinan yang bernilai dan berguna bagi masyarakat. Dilihat dari hasil-hasil kerajinan keramik yang sudah ada, keramik tradisional merupakan kerajinan yang masih berkualitas rendah karena dipengaruhi oleh bahan baku yang dipakai dan peralatannya serta faktor-faktor lain yang kurang mendukung, sehingga perkembangan keramik tradisional agak lambat dan berjalan secara kecil-kecilan. Begitu halnya dengan jumlah para pengerajin keramik tradisional semakin lama semakin berkurang karena generasi penerus mereka jarang yang mau berkecimpung dalam membuat kerajinan keramik tradisional, mereka kebanyakan mencari pekerjaan lain yang dirasa membawa keuntungan yang lebih besar.
Hal ini juga terlihat pada kerajinan keramik tradisional di desa Benoh, namun dengan berkembangnya pariwisata Bali saat ini, seakan-akan membawa angin segar bagi masyarakat pengerajin keramik tradisional desa Benoh. Hal itu dapat terlihat dari hasil kerajinan yang dihasilkannya yang tidak lagi berkutat pada bentuk-bentuk tradisional yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan keagamaan semata, namun sudah berkembang jauh dengan terciptanya desain-desain dan bentuk-bentuk baru yang sesuai dengan selera pasar domestik dan internasional. Dilihat dari keanekaragaman bentuk yang dihasilkan memang sangat menarik wisatawan yang dating ke Bali. Kemajuan dalam bidang kreasi seni sejalan pula dengan kemajuan kebudayaan yang selalu mengikuti perkembangan jaman. Keadaan ini menimbulkan kreasi untuk mengubah fungsi dari beberapa jenis barang kerajinan rumah tangga menjadi alat hias, seperti pemakaian gentong yang lazim dipakai sebagai tempat air atau beras kini fungsinya diubah menjadi pot bunga dengan pengembangan suatu dekorasi atau hiasan. Akibat dari pemanfaatan hasil keramik tradisional yang bersifat multifungsi, menyebabkan produksi barang–barang kerajinan keramik tradisional di desa Benoh dapat memenuhi alat hias masyarakat pedesaan dan masyarakat kota.
Dalam pembuatan keramik gerabah di desa Benoh lebih banyak dilakoni oleh pengerajin kaum wanita dan yang paling aktif kebanyakan wanita yang sudah usia lanjut. Keadaan ini didukung karena, untuk melakukan pekerjaan lainnya yang lebih berat sudah tidak memungkinkan lagi dan di usia mereka yang seperti itu, mereka hanya memiliki skill sebagai pembuat gerabah saja. Ada berbagai karakter orang yang mau melakoni pekerjaan membuat keramik gerabah di desa Benoh. Ada yang melakoni pekerjaan tersebut hanya sebagai pengisi waktu luang disaat mereka tidak punya pekerjaan lain ada juga yang memang bener-bener fokus melakoni pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sehari-hari mereka. Di samping itu ada juga yang melakoni pekerjaan ini sebagai usaha bisnis yang sangat menjanjikan mengingat perkembangan pariwisata dewasa ini yang mulai menggeliat.
Untuk kebutuhan bahan baku gerabah, para pengerajin keramik tradisional di desa Benoh mendatangkan dari desa Dharma Saba. Hal itu dikarenakan semakin sempitnya lahan yang tersedia sehingga semakin sedikitnya bahan yang bisa dimanfaatkan. Proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat yang masih sederhana, namun dengan berkembangnya teknologi saat ini pengerajin disana sudah ada yang menggabungkannya dengan alat-alat yang modern. Namun alat-alat modern yang digunakan hanya sebatas dalam pengolahan bahannya saja, untuk proses pengerjaan benda gerabah masih menggunakan teknik dan alat-alat yang sangat sederhana yaitu menggunakan alat yang didapat langsung dari alam lingkungan sekitarnya. Pengerajin keramik tradisional Benoh memiliki beberapa teknik yang masih sangat sederhana yang dikenal dengan istilah cacalan. Ini dilakukan dengan cara tanah yang akan dibentuk dipilin dahulu lalu ditumpuk dan dipijit dengan tangan, ditekan-tekan hingga sesuai dengan keinginan. Selain cacalan, juga dikenal dengan teknik tatap batu, dengan pertolongan alat tatap yaitu kayu yang dibuat agak cembung serta batu yang digunakan untuk memukul-mukul dari kedua sisi. Dikenal juga teknik pengenyunan, pembentukan ini menggunakan alat putar yang disebut pengenyunan. Tanah yang sudah siap dipakai atau diulet dibentuk diatas pengenyunan yang dikendalikan dengan tangan dan yang terakhir adalah tehnik cetak, seperti dalam pembuatan bata dan genteng. Teknik ini dipakai jika membuat keramik tradisional dalam jumlah yang banyak atau diproduksi secara masal.
Perkembangan Kerajinan Keramik Tradisional Di Desa Binoh, selengkapnya

Mantapkan Kerja Sama Mancanegara
 Denpasar – Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar memantapkan jalinan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi seni dan berbagai pihak di mancanegara, sebagai upaya menjadikan lembaga pendidikan tinggi seni itu “go internasional“.
Denpasar – Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar memantapkan jalinan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi seni dan berbagai pihak di mancanegara, sebagai upaya menjadikan lembaga pendidikan tinggi seni itu “go internasional“.
“Melalui pengembangan seni budaya Nusantara dan jalinan kerja sama antarnegara diharapkan mampu meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional,” kata Rektor ISI Denpasar Prof Dr I Wayan Rai. S, di Denpasar Senin.
Ketika menyambut kedatangan 19 mahasiswa University of Western Australia (UWA) yang didampingi Prof Paul Trinidad untuk mengikuti proses belajar mengajar di ISI Denpasar selama tiga minggu, ia mengatakan, pihaknya sudah berhasil menandatangani naskah kerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan tinggi seni di mancanegara, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri dan lembaga internasional lainnya.
Penandatangan naskah kerja sama terakhir dilakukan dengan University of Western Australia (UWA) pada akhir Februari 2011 yang sepakat untuk saling mengisi guna menyempurnakan proses belajar mengajar bagi masing-masing lembaga pendidikan tinggi itu.
“Semua itu diharapkan menjadi kunci sukses dalam mengembangkan seni budaya Nusantara, sekaligus menjadikan ISI Denpasar mendunia,” harap Prof Rai.
Kerja sama yang dirintis ISI Denpasar selama ini selain dengan UWA juga dengan Tokyo University of the Arts (TUA) Jepang, tiga lembaga pendidikan tinggi di Thailand, Malaysia dan sejumlah lembaga pendidikan tinggi di kawasan ASEAN lainnya.
Dari kerja sama perguruan tinggi antarnegara itu, termasuk diantaranya menyangkut program pertukaran mahasiswa, di mana ISI Denpasar menerima mahasiswa dari mancanegara dan sebaliknya mahasiswa ISI Denpasar belajar ke sejumlah perguruan tinggi di luar negeri selama dua hingga empat semester.
Dengan demikian menurut Prof Rai, mahasiswa ISI Denpasar yang ikut ambil bagian dalam program pertukaran mahasiswa dengan sejumlah perguruan tinggi seni di mancanegara akan memperoleh dua ijasah, setelah menyelesaikan pendidikan di lembaga pendidikan tinggi seni tersebut.
Satu izasah dari ISI Denpasar dan satunya lagi dari perguruan tinggi yang menjadi mitra kerja sama, tempat mahasiswa tersebut mengikuti kuliah pertukaran mahasiswa di luar negeri.
Prof Rai menjelaskan, alumnus ISI Denpasar yang memiliki ijazah ganda diharapkan mampu memenangkan persaingan dalam merebut peluang kerja di dalam dan luar negeri.
“Kalau bekerja di Indonesia, izasah ISI Denpasar yang digunakan, dan kalau bekerja di luar negeri ijasah dari lembaga pendidikan tinggi seni tempatnya kuliah dapat dipergunakan,” ujar Prof Rai.