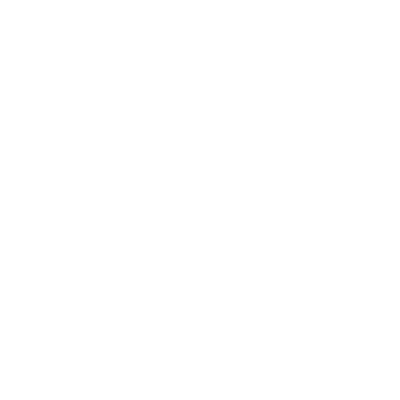by admin | Jul 7, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman I Wayan Sucipta, Mahasiswa PS. Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman I Wayan Sucipta, Mahasiswa PS. Seni Karawitan ISI Denpasar
Gambuh Kedisan adalah sebuah seni pertunjukan klasik yang masih dipelihara dan dilestarikan keberadaanya. Kesenian ini sempat mengalami kejayaanya pada tahun 1950-an. Ketika itu sempat melakukan berbagai pertunjukan di puri-puri dan masyarakat yang meminta ngayah ketika ada upacara Agama, seperti puri Agung Gianyar, Puri Ubud dan Puri Kedisan. Pada jaman dahulu ketika Raja Gianyar mengetahui di Desa Kedisan terdapat Kesenian Gambuh, Ketika itu juga Raja Gianyar meminta sekaa Gambuh tersebut untuk ngayah ngambuh di Puri Gianyar.
Pertunjukan Gambuh sering dilakukan di Puri Gianyar ketika ada upacara-upacara di lingkungan puri, seperti upacara Dewa Yadnya, Manusa Yadnya maupun Pitra Yadnya. Kesenian Gambuh Kedisan ketika itu termasuk Gambuh yang sangat digemari oleh lingkungan Puri Gianyar. Gambuh ini ketika pentas di Puri Gianyar mendapatkan tempat pementasan khusus yang disebut dengan Bale Pegambuhan. Bangunan tersebut berada di sebelah selatan ancak saji puri. Dalam kamus Bali-Indonesia ancak saji memiliki pengertian batas dari pekarangan puri. Begitu juga halnya ketika ngayah di Puri Ubud, tempat pementasannya disediakan dengan khusus seperti di Puri Gianyar. Menurut I Gusti Ngurah Mangku Puja dan anaknya I Gusti Ngurah Widiantara, bahwa Gambuh Kedisan selalu diminta pentas (ngayah) di Puri Agung Gianyar di setiap kegiatan upacara. Akan tetapi beliau tidak dapat memastikan kapan awalnya kesenian tersebut pentas di Puri Gianyar. Menurutnya hal tersebut sudah diwarisi secara turun temurun oleh Sekaa Gambuh Kedisan.
Seiring dengan berjalannya jaman dan waktu, Gambuh Kedisan banyak mengalami permasalahan, terutama dari anggota yang sudah berumur tua. Gambuh ini sempat mengalami fakum dari pertunjukannya akibat dari sulitnya mencari seorang penari Gambuh. Pada akhirnya angota tersebut mempunyai inisiatif untuk mengembangkan kembali kesenian Gambuh tersebut dengan jalan mendatangkan pelatih Tari Gambuh dari Batuan. Sempat beberapa periode mendatangkan pelatih tari Gambuh dari Batuan. Pelatih yang terakhir dari Batuan sempat melatih tari putri pada tahun 1982. Kesenian Gambuh kembali bisa dikembangkan meskipun tidak sejaya tahun 1950-an dan sebelumnya.
Pertunjukan dan tarian Gambuh Kedisan sempat mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk pentas di Eropa pada tahun 1999, dengan tujuan negara Prancis dan Swiss. Pada saat itu kesenian ini kembali di tata struktur pertunjukannya guna memperindah gerakan tarian dan komposisi pertunjukan. Ketika itu sempat mendatangkan tokoh tari Bali dari Singapadu yang bernama I Made Bandem, dengan tujuan melatih tari Gambuh dan menyesuaikan pertunjukan Gambuh dengan durasi yang ditentukan. Banyak pakem tarian yang di rubah baik dipotong dan ditambah, agar mencukupi durasi waktu yang ditentukan. Pemotongan struktur pada tariannya juga mengalami perubahan terhadap iringannya. Semenjak itu sampai sekarang, kesenian ini menggunakan struktur (paileh) pertunjukan yang dipergunakan ketika kesenian tersebut pentas di Eropa.
Perubahan
Perubahan adalah suatu hal yang selalu terjadi pada setiap kebudayaan. Perubahan memiliki suatu pengertian tidak mengalami bentuk yang tetap dengan kata lain dari bentuk Y berganti menjadi X. Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan turun temurun. Kebudayan juga tidak memiliki bentuk dan kepastian yang tetap, dimana selau mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan jaman. Untuk menganalisis perubahan yang terjadi pada kesenian Gambuh Kedisan, peneliti meminjam teorinya Alvin Boskof, yang berpendapat bahwa perubahan sosial budaya dalam masyarakat disebaban oleh dua faktor, yaitu: faktor dari dalam (internal) adalah sebagian faktor yang datangnya dari dalam atau pelaku budaya tersebut, dan faktor dari luar (eksternal) adalah faktor yang datangnya dari luar pelaku budaya tersebut.
Begitu juga dengan kesenian klasik yang keberadaanya dari jaman dahulu banyak mengalami perubahan hingga bisa bertahan sampai sekarang. Contohnya kesenian Gambuh Kedisan. Gambuh Kaga Wana Giri atau yang lebih di kenal dengan istilah Gambuh Kedisan merupakan kesenian Gambuh yang sempat jaya pada tahun 1950-an. Sekarang keberadaanya telah banyak mengalami perubahan dari segi kualitatif seperti struktur pertunjukan, dan anggota, akibat dari faktor dari dalam sekaa maupun dari luar sekaa.
Struktur pertunjukan Gambuh Kedisan mengalami perubahan ketika beberapa penari Gambuh meninggalkan Kedisan untuk bertransmigrasi ke Sumatra dan Lampung. Ketika itu penari-penari yang telah bertransmigrasi digantikan oleh beberapa orang sebagai peran pengganti, dan itupun tidak semua tarian yang hilang dapat digantikan dengan penari lain, hanya tokoh yang memang dianggap penting dalam pertunjukan. Sulitnya mencari pengganti penari Gambuh ketika itu mengakibatkan sedikitnya tarian yang bisa dilestarikan lagi. Semenjak itu dalam pertunjukan Gambuh sedikit berubah hanya mementaskan peran-peran yang pokok dalam adegan cerita yang dibawakan. Perubahan berikutnya ketika akan melakukan pertunjukan ke Prancis dan Swiss. Ketika itu masing-masing tarian dirubah struktur tariannya agar memenuhi durasi waktu yang ditentukan. Berubahnya struktur tarian Gambuh ketika itu secara tidak langsung mengalami perubahan terhadap iringannya. Semenjak itu ketika melakukan pertunjukan menggunakan struktur yang dipakai ketika pentas di Prancis dan Swiss.
Faktor transmigrasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah sekaa Gambuh Kedisan, di samping faktor usia dan peran pengganti. Sulitnya mencari pengganti untuk tarian dan iringan Gambuh, mengakibatkan semakin berkurangnya anggota sekaa Gambuh Kedisan. Kini keberadaan anggotanya rata-rata orang tua yang sudah berumur 50-an, yang beberapa anggota sudah tidak memungkinkan untuk menari Gambuh. Kini Gambuh Kedisan memiliki anggota yang sangat pas dengan peran tari dan penabuh yang ada. Terkadang sampai meminjam beberapa penari dari luar Desa Kedisan untuk menari ketika ada salah satu penari yang berhalangan.
Perkembangan Kesenian Gambuh di Desa Kedisan selengkapnya

by admin | Jul 5, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman Dr. Ni Made Ruastiti, SST. MSi., Dosen PS Seni Tari ISI Denpasar.
Kiriman Dr. Ni Made Ruastiti, SST. MSi., Dosen PS Seni Tari ISI Denpasar.
Abstrak
Puri Saren Agung merupakan sebuah obyek wisata budaya yang terletak di desa Ubud, Gianyar, Bali. Sebagai sebuah produk wisata yang dikembangkan berdasarkan konsep pariwisata budaya (cultural tourism), Puri Saren Agung memiliki nilai historis, filosofis dan estetika yang tinggi. Hal itu dapat diamati dari tata ruang puri yang didasarkan atas sejumlah konsepsi berlandaskan filosofis agama Hindu.
Berkembangnya pariwisata di Bali tampaknya telah membuat munculnya gejala komodifikasi di berbagai sektor kehidupan masyarakatnya. Komodifikasi adalah suatu konsep yang luas, yang tidak hanya menyangkut masalah produksi komoditas dalam pengertian perekonomian yang sempit saja, namun juga menyangkut tentang bagaimana barang-barang tersebut didistribusikan dan dikonsumsi. Dengan adanya sistem ekonomi yang didasarkan atas spirit untuk mendapatkan keuntungan telah mendorong pihak Puri Saren Agung kreatif mengembangkan purinya sebagai sebuah obyek wisata budaya agar dapat menghasilkan uang untuk kelangsungan puri, sebagai aset budaya Bali.
Walaupun dikembangkan sebagai sebuah obyek wisata, namun bentuk, struktur bangunan puri ini tampak masih tetap seperti sediakala/tidak berubah, yakni mempergunakan konsep sanga mandala (pembagian area puri menjadi sembilan petak), memiliki nilai utama sebagai tempat yang bernilai sakral, madya sebagai ruang tempat tinggal dan nista sebagai tempat pelayanan umum. Dari hasil pengamatan, perubahan hanya tampak dalam penggunaan area puri yang memiliki nilai profan (nista) yakni diperuntukkan sebagai tempat rest house, restaurant, art shop dan sebagai tempat pementasan kesenian untuk wisatawan. Sementara area puri lainnya masih tetap fungsional sebagai pusat kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Hal itu dapat dilihat dari rutinitas kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat di puri ini.
Dengan dikembangkannya puri ini secara tepat dan terpadu, maka komodifikasi obyek wisata Puri Saren Agung Ubud ini dapat bermakna simbiosis-mutualistis bagi puri, pariwisata, masyarakat dan kebudayaan Bali.
Key word : Komodifikasi, Puri Saren Agung Ubud, Pariwisata Bali.
1. Latar Belakang
Pulau Bali merupakan daerah tujuan wisata (tourism destination) yang sangat terkenal akan keunikan budayanya. Keunikan budaya Bali tercermin pada kehidupan masyarakatnya yang religius. Hal itu dapat dilihat dari gaya hidup masyarakatnya yang selalu mengaitkan kehidupannya dengan upacara ritual keagamaan baik di pura maupun di lingkungan rumah tempat tinggalnya. Selain gaya hidup masyarakatnya unik, arsitektur bangunan suci pura dan purinya pun tidak kalah menarik. Oleh sebab itu banyak wisatawan tertarik datang mengunjungi obyek wisata pura maupun puri.
Banyaknya wisatawan tertarik datang ke Bali karena keunikan budayanya ini disikapi Pemerintah Daerah setempat dengan mengembangkan industri pariwisatanya berdasarkan kebijakan pariwisata budaya. Kebijakan ini dituangkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 1974, yang direvisi menjadi Perda Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya, yang intinya menyebutkan bahwa setiap industrialisasi pariwisata daerah ini dilandasi kebudayaan Bali.
Pembangunan pariwisata yang konformis harus mengangkat local knowledge masyarakat karena hal ini merupakan adaptasi ekologis masyarakat tersebut. Jika konsep ini diterapkan kiranya pariwisata Bali akan dapat bermakna simbiosis mutualistis bagi masyarakat, pariwisata dan kebudayaan Bali. Setiap masyarakat tentunya memiliki pengetahuan, budaya berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dimana mereka berada. Jika ini dikembangkan menjadi sebuah produk wisata maka industri ini akan memiliki produk wisata beragam dan unik, ramah lingkungan serta diterima masyarakat secara sosial-budaya-religius.
Dengan konsep industri pariwisata budaya, Pemerintah Daerah ini mengharap industrialisasi pariwisata budaya terjadi di berbagai sektor pariwisata, baik biro perjalanan wisata (BPW), hotel dan restoran, transportasi, seni pertunjukan, cendramata, dan lain sebagainya. Hal inilah kiranya yang mendorong terjadinya komodifikasi obyek wisata di Puri Saren Agung Ubud. Proses industrialisasi sebagaimana dilakukan Puri Saren Agung ini disebut sebagai komodifikasi. Komodifikasi (commodification) adalah suatu konsep yang luas, yang tidak hanya menyangkut tentang masalah produksi komoditas dalam pengertian perekonomian yang sempit tentang barang-barang yang diperjual-belikan saja, namun menyangkut lebih daripada itu, yakni tentang bagaimana barang-barang itu didistribusikan dan dikonsumsi.
Fairclough (1995 : 207) menyatakan bahwa : Commodification is the process whereby social domains and intitutions, concern is not producing commodities in the narrower economic sense of goods for sale, come nevertheles to be organized and conceptualized in terms of commodity production, distribution and consumtions. Keat dan Abercrombie (1990) menyatakan bahwa komodifikasi bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan telah terjadi sejak dahulu sehingga seakan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Max Weber (dalam Turner, 1992 : 115-138) menyebut munculnya gejala komodifikasi ini karena adanya spirit ekonomi uang untuk memperoleh keuntungan.
Sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat Bali yang selama ini begitu kreatif melakukan inovasi menyikapi pariwisata di daerahnya masing-masing. Hal itu dapat dilihat dari menjamurnya produk wisata baru dengan segala keunikan ditawarkannya kepada konsumen. Salah satu produk wisata yang relatif baru dikembangkan adalah “wisata puri”. Wisata puri pada hakekatnya di daerah/negara lain telah berkembang sejak lama, dan populer disebut sebagai “wisata istana”. Negara-negara yang telah mengembangkan model wisata istana/wisata puri, antara lain : Grand Palace di Bangkok, Istana Malacanang di Manila, dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia, wisata puri telah dikembangkan oleh istana Yogyakarta, istana Surakarta, istana Mangkunegaran, dan Puri Saren Agung Ubud.
Puri di Bali, merupakan tempat tinggal bagi kalangan/golongan kasta kesatria yang memegang pemerintahan. Bangunan puri umumnya terletak di bagian kaja kangin di sudut perempatan agung, di pusat desa (Gelebet, 1986). Menurut Alvin Toffler yang dikutip oleh Soedarsono (1999) mengatakan bahwa istana adalah tempat menyimpan berbagai kekayaan atau warisan budaya yang sering dipergunakan sebagai daya tarik wisata oleh daerah tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh Puri Saren Agung Ubud yang mengembangkan purinya sebagai sebuah obyek wisata karena mereka memahami bahwa wisatawan sangat tertarik datang ke istana kerajaan/puri untuk melihat kebudayaan daerah yang dikunjunginya.
Komodifikasi Obyek Wisata Puri Saren Agung Ubud, bagian I, selengkapnya

by admin | Jul 3, 2011 | Berita
 Program ISACFA (International Studio for Arts & Culture FSRD-ALVA), sebuah program yang merupakan implementasi dari MoU antara ISI Denpasar dan University of Western Australia (UWA) dengan 22 mahasiswa UWA dibawah komando Prof. Paul Trinidad belajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ISI Denpasar sejak 13 Juni yang lalu, Jumat malam (1/7) yang lalu dilepas secara resmi oleh Rektor ISI Denpasar lewat pameran bertajuk “Exhibition of ISAFCA Program, Darmasiswa &ISI Denpasar Students”. Pameran ini diawali dengan penandatanganan kanvas oleh seluruh undangan dan mahasiswa UWA.
Program ISACFA (International Studio for Arts & Culture FSRD-ALVA), sebuah program yang merupakan implementasi dari MoU antara ISI Denpasar dan University of Western Australia (UWA) dengan 22 mahasiswa UWA dibawah komando Prof. Paul Trinidad belajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ISI Denpasar sejak 13 Juni yang lalu, Jumat malam (1/7) yang lalu dilepas secara resmi oleh Rektor ISI Denpasar lewat pameran bertajuk “Exhibition of ISAFCA Program, Darmasiswa &ISI Denpasar Students”. Pameran ini diawali dengan penandatanganan kanvas oleh seluruh undangan dan mahasiswa UWA.
Pameran ini terlaksana setelah mahasiswa UWA mempelajari Kamasan Painting sejak 26 Juni lalu di Klungkung selama tiga hari. Selain mengikuti perkuliahan, diantaranya Bahasa Indonesia, Seni Budaya Bali, Komunitas dalam Ritual dan Upacara, Komunitas Masyarakat dalam Subak dan Banjar, Pengenalan Arsitektur Tradisional Bali, Ashta Bumi dan Ashta Kosala-Kosali, Ornamen, fotografy, lighting, dll mereka juga mengunjungi Pura Tirta Empul untuk lebih mengenal lebih jauh tentang kebudayaan Bali. “Selain mengamati kegiatan religious di pura tersebut, mahasiswa Negeri Kangguru itu juga ikut melukat bersama mahasiswa dan dosen ISI Denpasar,”papar Dekan FSRD, Dra.Ni Made Rinu,M.Si.
Alexander Philip Wolman, salah seorang mahasiwa UWA yang memberi sambutan pada acara malam itu,mengungkapkan rasa bahagia dan terimakasih atas semua yang telah diperoleh saat perkuliahan di ISI Denpasar. “We have a very wonderful time here, so many invaluable knowledge and ISI Denpasar has given us more than what we expected, ”ujar Alex yang disambut applaus seluruh hadirin.
Rektor ISI didampingi para Pembantu Rektor, Dekan FSP, Dekan FSRD serta jajarannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar ISI Denpasar yang telah bekerja keras dalam melaksanakan setiap kegiatan untuk mahasiswa UWA,sehingga setiap kegiatan dapat berjalan lancar. “Kegiatan ini adalah implementasi dari MoU antara ISI Denpasar dan UWA. Kedepan akan ada banyak kegiatan lagi tidak hanya di FSRD, tapi juga di FSP, yang tentunya merupakan tantangan untuk kita meningkatkan diri untuk mampu bersaing di tingkat internasional,” papar Prof. Rai ditemui pada acara makan malam bersama seluruh mahasiswa UWA malam itu.
Humas ISI Denpasar melaporkan.

by admin | Jul 3, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Kadek Suartaya, SSKar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman: Kadek Suartaya, SSKar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Ni Calonarang girang bukan kepalang karena anak kesayangannya, Ratna Mangali, dipersunting oleh raja Kediri, Airlangga. Tetapi kemudian gelora suka cita janda desa Dirah itu berbalik menjadi duka kecewa yang mengobarkan api amarahnya. Calonarang tersinggung berat dan sakit hati atas diusirnya Ratnamangali dari Kediri dengan tuduhan sebagai penganut ilmu hitam leak. Calonarang berang dan mengerang garang. Bersama murid-muridnya, Si Walu Nateng Dirah ini meneror negeri Kediri dengan mengerahkan leak ganas haus darah. Raja Airlangga menitahkan kepada patih andalannya, Maling Maguna, menghentikan prahara yang ditebar Calonarang dan mengembalikan ketenteraman rakyat Kediri.
Kisah janda dari desa Dirah atau Girah itu lazimnya disimak masyarakat Bali pada tengah malam dalam sebuah seni pertunjukan yang disebut Calonarang. Tetapi pada Sabtu (16/4) lalu, Ni Calonarang dan murid-muridnya justru ngereh dan mengumbar ilmu hitamnya pada siang bolong. Tengoklah pementasan garapan seni yang bertajuk “Prahara Ing Kediri“ di panggung terbuka Balai Budaya Gianyar. Karya seni pentas besutan para seniman Sanggar Genta Manik, Desa Seronggo, Kecamatan Gianyar, itu menyihir ribuan penonton yang memadati Pawai Budaya serangkaian hari jadi ke-240 Kota Gianyar.
Didukung oleh lebih dari 200 orang pelaku seni, “Prahara Ing Kediri“ hadir kolosal, diiringi dengan sepasukan penabuh gamelan Balaganjur yang ditata apik. Para penabuh yang bergerak dinamis, merangkai variasi figurasi di atas panggung. Peran-peran yang ada dalam teater Calonarang dihadirkan merajut kisah. Tokoh Ni Calonarang tampak berperan cukup dominan terutama saat mengerahkan murid-muridnya memporakporandakan kerajaan Kediri. Klimaks drama tari ini, pertarungan hidup mati antara Ni Calonarang dengan Maling Maguna, dihadirkan mencekam. Perubahan Ni Calonarang menjadi Rangda divisualisasikan dengan ogoh-ogoh Rangda yang diusung puluhan orang. Maling Maguna meloncat ganas ke atas dan menancapkan kerisnya berkali-kali pada sekujur tubuh Rangda. Penonton tegang.
Sihir adalah tema yang selalu ditonjolkan dalam cerita Calonarang. Kendati berasal dari Jawa, tapi di Bali sendiri, hingga kini, cerita ini masih begitu menggetarkan masyarakat. Cerita dengan tokoh utama bernama Ni Calonarang itu merasuk lewat drama tari Calonarang, sebuah genre seni pertunjukan Bali yang diduga muncul pada tahun 1825, zaman kejayaaan dinasti kerajaan Klungkung. Dalam seni pentas yang oleh peneliti asing disebut the drama of magic ini, simbol sarang Ni Calonarang di tempatkan di sisi kalangan yang disebut tingga, sejenis rumah panggung yang dibuat agak tinggi. Di depan tingga itu ditancapkan gedang renteng, tempat Calonarang dalam wujud Rangda mengangkang dan menjerit-jerit memamerkan kesaktiannya
Calonarang adalah cerita semi sejarah dengan seting kejadian pada abad XI, zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur. Dalam wujudnya sebagai seni pertunjukan Bali, disamping tetap mengacu kepada sastra sumbernya, terjadi pula mengembangan dan penyimpangan. Misalnya muncul tokoh penting yang disebut Rangda yang merupakan siluman Calonarang dalam wujud yang menakutkan. Padahal yang dimaksud rangda dalam sastra sumber adalah janda.
Dalam drama tari Calonarang, Matah Gede adalah figur atau karakter untuk si janda sihir dari Dirah, Calonarang, sebagai manusia biasa sebelum berubah menjadi ratu leak dalam wujud yang dahsyat menyeramkan. Tokoh ini memiliki karakter yang khas dan sekaligus menjadi identitas seni pertunjukan Calonarang. Matah Gede hadir dengan jati diri perwatakan, tata busana, dan tata rias wajahnya. Pemberang adalah watak menonjol dari tokoh yang tak pernah lepas dari tongkatnya ini. Jika sedang naik pitam, sorot matanya yang menusuk tajam dilukiskan pantang dilawan jika tak ingin hangus terbakar. Keangkeran Matah Gede juga dibangun oleh dominasi tata ucapannya dengan suara yang berat dalam bahasa Jawa Kuno.
Antonin Artaud, seorang dramawan terkemuka Prancis, sempat sangat terpesona dengan drama tari Calonarang. Ceritanya pada tahun 1931, Artaud dan para pekerja seni pertunjukan di Eropa sempat digemparkan pementasan Calonarang oleh para seniman Bali yang dipimpin oleh Cokorda Gede Raka Sukawati di arena Paris Colonial Exhibition. Sementara itu, kajian ilmiah menyangkut teater ini juga cukup banyak. Diantaranya, Beryl de Zoete & Walter Spies dalam bukunya Dance and Drama in Bali (1931), Urs Ramseyer dalam The Art and Culture of Bali (1977), dan I Made Bandem & Fredrik deBoer dengan Kaja and Kelod Balinese Dance in Transition (1981).
Belakangan, televisi yang bersiaran di Bali juga rajin menayangkan teater Calonarang—cukup diminati pemirsa. Calonarang agaknya masih menyihir masyarakat Bali masa kini. Termasuk, garapan seni pentas “Prahana Ing Kediri” tersebut, disimak antusias ribuan penonton yang memadati lapangan Astina Gianyar. Karya seni pentas binaan seniman Drs. I Made Mertanadi, M.Si yang merupakan duta Kecamatan Gianyar ini tampak membuat haru Camat Gianyar, A.A. Gde Agung, S.Sos, M.Si dan Perbekel Desa Seronggo, A.A. Gde Bagus Udayana. Lewat bingkai cerita Calonarang, ungkap Mertanadi, para seniman Gianyar, dalam beragam pengejawantahan ekspresi kreatif seni, bertekad tetap “menyihir” dunia.
Ketika Calonarang “Ngereh” Di Siang Bolong selengkapnya

by admin | Jul 1, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Ida Bagus Gede Surya Peradantha, S.Sn., Alumni ISI Denpasar
Kiriman: Ida Bagus Gede Surya Peradantha, S.Sn., Alumni ISI Denpasar
Sejarah Sangar
Sanggar tari Printing Mas merupakan sanggar yang tidak hanya membidangi wilayah tari, namun juga tabuh dan kostum. Sanggar tari ini di Bali cukup dikenal oleh karena kualitas dan kredibilitasnya. Terletak di Jl. Meduri no.11, Denpasar Timur, sanggar tari ini selalu saja ramai dikunjungi oleh anak-anak atau remaja yang belajar tari dan tabuh serta konsumen yang ingin menyewa atau membeli pakaian tari. Wajar saja, karena disamping eksis di bidang tari, sanggar ini memiliki spesialisasi di bidang pembuatan dan sewa pakaian.
I Wayan Oklan dan adiknya I Made Oklin, adalah dua orang bersaudara yang merupakan pencetus ide untuk mendirikan Sanggar Printing Mas. Sanggar ini pada mulanya hanyalah kumpulan seniman yang merasa terpanggil untuk mengabdi di jagat seni tradisi Bali, tanpa memandang imbalan. Hal inilah yang dituturkan oleh sang ketua sanggar Eka Surya Wirawan. Sesuai penuturannya, sanggar ini dahulunya tidak memiliki modal pendukung seperti instrument gong kebyar. Instrumen tersebut akhirnya didapat dengan cara meminjam dari pihak Bank Sri Partha yang terletak di dekat sanggar ini berada. Kompensasinya, bila di Bank Sri Partha terdapat upacara keagamaan yang memerlukan pementasan kesenian, maka kelompok seni yang dipimpin Oklan dan Oklin diundang untuk ngayah. Kontan saja Oklan dan Oklin antusias menyambut tawaran tersebut.
Dengan dibantu Oleh I Nyoman Suarsa, maka kegiatan di sanggar ini pun bertambah ramai seiring dengan mulai datangnya pesanan pementasan baik yang bersifat ngayah maupun yang bersifat komersial. Seiring dengan berjalannya waktu, sanggar ini tumbuh dan berkembang hingga akhirnya memiliki perangkat gamelan Gong Kebyar yang utuh, serta memiliki beberapa pakaian tari yang dipergunakan untuk pentas keliling.
Berdasarkan kejelian dari Oklan dan Oklin, maka dilebarkanlah bentang sayap bisnis sanggar ini ke bidang kostum tari. Peruntukan dari bidang ini tidak lagi hanya sebagai pelengkap pementasan, namun juga sebagai salah satu sumber pemasukan dari segi finansial, lantaran kostum tari juga dapat disewakan. Pemasukan sanggar pun bertambah dengan adanya bidang usaha penunjang ini.
Pada awal dekade 1990-an, Sanggar Printing Mas membentuk sebuah grup dramatari Arja Muani, dimana seluruh pelakon dalam grup ini adalah laki-laki (muani dalam bahasa Bali berarti laki-laki). Grup inilah yang membawa pengaruh besar dalam melambungkan nama Sanggar Printing Mas hingga dikenal oleh sebagian masyarakat di Bali. Proses pembentukan grup ini pun tidak beda jauh dari proses berdirinya sanggar, yaitu diawali dengan niat ngayah dan berdasarkan perasaan suka berkumpul antar senimannya. Ide untuk membentuk grup ini secara permanen dicetuskan oleh I Wayan Juana, S.Sn. yang kala itu baru saja menamatkan studinya di STSI Denpasar (kini ISI Denpasar). Olehnya, digandenglah nama-nama seniman muda yang memiliki prospek cerah seperti Gde Anom Ranuara, I Gusti Lanang Oka Ardika, SST (dosen ISI Denpasar), Dek Cilik, dan Codet. Grup Arja Muani itu bertahan hingga kini dan selalu saja ada permintaan untuk pentas dari masyarakat maupun instansi pemerintah.
Kini Sanggar Printing Mas telah memiliki sekitar 90 orang murid baik anak-anak hingga remaja yang khusus belajar di bidang seni tari. Sedangkan untuk penabuh, sudah memiliki sekitar 50 orang personil. Di bidang pembuatan dan persewaan pakaian, sanggar ini telah memiliki 7 pegawai kantor dan 15 orang pekerja borongan yang khusus menggarap pesanan pakaian tari maupun tabuh.
Event yang sudah pernah diikuti sanggar ini antara lain yaitu pernah diundang ke Jepang dan Australia oleh Kedutaan besar RI di Negara masing-masing dalam bentuk grup kesenian. Sedangkan dari perorangan, personil sanggar kebanyakan memiliki koneksi yang sangat baik dengan pihan Dinas Kebudayaan propinsi Bali sehingga tidak jarang mereka ditunjuk untuk menjadi anggota rombongan melawat ke luar negeri.
Dalam skala lokal, Sanggar Printing Mas aktif mengikuti kegiatan lomba tari antar sanggar di tingkat kabupaten/kota, serta di tingkat propinsi. Gelar juara pun tidak jarang berdatangan ke lemari piala sanggar ini. Sedangkan untuk event yang bersifat pesanan, Sanggar Printing Mas juga pernah menerima tawaran syuting iklan dari salah satu produsen otomotif terbesar di tanah air dalam rangka promosi produk baru mereka. Demikian juga dari pihak Dinas Kesehatan Propinsi Bali, pernah member tawaran kepada Sanggar Printing Mas untuk mengkampanyekan pemberantasan penyakit TBC. Masih banyak lagi event yang diikuti sanggar ini termasuk acara rutin dalam Pesta Kesenian Bali (PKB) yang digelar tiap tahunnya di Bali, serta kerjasama dengan salah satu universitas di Tokyo, Jepang untuk membina mahasiswanya belajar kesenian Bali.
Pola Manajemen Sanggar
Untuk menjalankan roda kegiatan di Sanggar Printing Mas, kedua perintisnya yaitu I Wayan Oklan dan I Made Oklin pada awalnya hanya menggunakan pola manajemen kekeluargaan, dimana seluruh pengelola sanggar berasal dari anggota keluarganya. Tidak hanya sampai di sana, pola keuangan pun digarap seadanya berdasarkan rasa kekeluargaan tanpa perhitungan teknis dan ekonomis lainnya. Menurut saya, hal ini masih dirasa wajar, mengingat kala baru berdiri sanggar ini belum memiliki lingkup kegiatan seluas sekarang. Dengan memiliki beberapa bidang usaha seperti sanggar tari, tabuh dan pembuatan/persewaan pakaian tari, seharusnya menjadi kemudahan dan keuntungan tersendiri bagi sanggar ini. Namun kenyataannya, pola manajemen yang kurang perhitungan menyebabkan beberapa kali sanggar ini hampir kolaps dan mengalami masa kritis.
Terhitung sejak 1995, ditunjuklah Eka Surya Wirawan sebagai ketua sanggar. Lulusan Ekonomi manajemen di salah satu perguruan tinggi negeri di bali ini pun membentuk manajemen professional untuk membawa perubahan dalam sanggar ini.
Sanggar Printing Mas : Sejarah dan Pola Manajemennya, selengkapnya

 Kiriman I Wayan Sucipta, Mahasiswa PS. Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman I Wayan Sucipta, Mahasiswa PS. Seni Karawitan ISI Denpasar