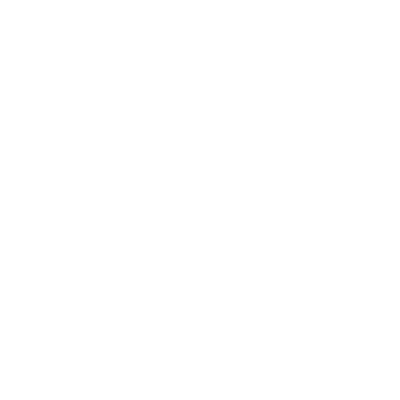by admin | Jul 10, 2011 | Berita
 Denpasar – Drs I Wayan Mudana MPar, pengamat seni lukis asal Bali, menilai perkembangan kreatif seni lukis sangat tergantung dari jiwa, dedikasi dan vitalisme seniman bersangkutan dalam menekuni proses karya seni.
Denpasar – Drs I Wayan Mudana MPar, pengamat seni lukis asal Bali, menilai perkembangan kreatif seni lukis sangat tergantung dari jiwa, dedikasi dan vitalisme seniman bersangkutan dalam menekuni proses karya seni.
“Dalam menciptakan karya seni lukis itu sangat tergantung dari batas kemampuan vitalisme untuk mengungkapkan sesuatu ke dalam media kanvas,” kata Wayan Mudana yang juga dosen Seni Murni Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, selain itu karya seni juga dipengaruhi segi-segi psikologis lain yang sangat konpleks, karena sebuah lukisan megandung kompleksitas kehidupan jiwa seniman secara total.
Kebutuhan kreatif tersebut berkembang dalam proses penciptaan seuah karya seni, yang akan diakhiri dengan apa yang disebut kepuasan kreatif.
Kepuasan kreatif merupakan tanda rampungnya sebuah karya di atas kanvas bagi seorang pelukis. “Kepuasan kreatif diibaratkan sebagai muara di lautan, dari sebuah sungai yan berliku-liku panjang meliuk-liuk di sepanjang dataran dan bukit yang berasal dari sebuah mata air di puncak bukit yang disebut kebutuhan kreatif,” tutur Wayan Mudana.
Demikian pula sebuah lukisan bermula dari kebutuhan kreatif dan berakhir dalam keputusan kreatif, yakni proses penciptaan yang disebut sebagai karakterisasi .
Namun demikian dalam penjiwaan sebuah lukisan, seorang akan tumbuh berkembang sesuai dengan kematangan jiwa seniman bersangkutan atau selaras dengan kompleks jiwanya.
Menurut Mudana, corak penjiwaan dalam proses penciptaan akan menempatkan setiap karya seni pada bentuknya yang bertentangan. yaitu vibrasi garbo dan vibrasi vitae.
Vibrasi garbo merupakan karya-karya yang dilahirkan secara inspiratif dan diciptakan dengan kecermatan teknis yang sempurna, sehingga keindahan visual mejadi tujuan utama bisa menggetarkan pesona secara mendadak.
Untuk itu seluruh elemen, warna, garis, ruang dan bentuk mendapat pengamatan secara sungguh-sungguh, hingga struktur yang membentuknya,
Demikian pula anatomi, dan proprsi diolah sampai tidak ada celanya, sehingga proses kreatif itu akan menjadi lebih lama. Akurasi demikian akan menyebabkan hilangnya spontanitas.
Hal itu penting karena spontanitas dinilai sebagai gejala emosi yang masih mentah serta belum mengalami pengendapan. Dengan demikian puncak dramatiknya akan diperoleh dalam dasar statisme yang mengendap pada statisme vitalnya, ujar Wayan Mudana.
Sumber: antaranews.com

by admin | Jul 10, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Kadek Suartaya, SSKar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman: Kadek Suartaya, SSKar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Dari Pulau Dewata, sebuah garapan seni pentas megah kini menantang penonton mancanegara untuk mengaguminya. Seni pentas yang bertajuk “Bali Agung–The Legend of Balinese Goddesses” itu, dibingkai dengan sahibul hikayat Bali Kuno yang dikemas secara spektakuler di atas panggung besar ultra modern dengan tata lampu dan suara nan canggih. Disajikan secara kolosal, selain oleh lebih dari 150 orang pelaku seni, juga oleh puluhan aneka satwa, dari bebek hingga gajah. Berdurasi satu jam, penonton seakan diajak bersafari melongok sepotong kejayaan peradaban masa lampau Bali, dalam sebuah presentasi artistik masa kini, untuk diapresiasi masyarakat dunia dari beragam budaya dan bangsa.
Disuguhkan rata-rata tiga kali seminggu, “Bali Agung“ yang digarap oleh para profesional seni pertunjukan Bali dan Barat, telah menggelinding selama sembilan bulan. Bali Theatre, sebuah panggung besar berukuran 60×40 meter yang berlokasi di Bali Safari dan Marine Park Gianyar, menjadi arena pengejewantahan kemasan seni pertunjukan yang dirajut dari beragam elemen kesenian Bali menjadi karya kreatif sarat pesona, sejak menit pertama hingga detik puncak. Minggu (1/4) siang yang lalu misalnya, ratusan penonton mancanegara yang menyimak pementasannya, tampak berdecak-decak diayun oleh keapikan visualisasi artistiknya dan kesejukan gurat-gurat pesan persahabatan dan kasih sayangnya.
“Bali Agung“ merupakan karya bersama seniman teater dan koreografer Bali I Made Sidia dengan sutradara kreatif kaliber internasional Peter Wilson. Selain Peter dan Sidia, totalitas garapan seni pentas ini didukung musik sugestif besutan Chong Lim, komposer upacara pembukaan Olimpiade Sydney 2006. Tak kalah pentingnya menjadikan garapan seni ini begitu terasa menggugah adalah juga desain kostum yang ditangani oleh Richard Jeziorny, seorang penata busana kelas dunia, yang memerlukan riset khusus untuk mendandani seluruh pemain sesuai dengan keadaan dan kultur masyarakat Bali ratusan tahun yang lalu.
Sebuah cerita romantis-tragis yang konon terjadi pada abad ke-12, dijadikan pijakan kreatif-inovatif pentas seni kolosal “Bali Agung“. Tersebutlah Sri Jaya Pangus (Dalem Balingkang), seorang raja zaman Bali Kuno yang mendirikan keratonnya di kaki Gunung Batur. Suatu hari datang saudagar dari negeri Tiongkok yang disertai putrinya Kang Ching Wie. Kecantikan Wie menggedor asmara Jaya Pangus. Kendati mendapat tentangan dari para penasihat istana, Jaya Pangus nekat memperistri Kang Ching Wie. Hanya, perkawinan Bali-Cina itu tak dikarunai keturunan. Jaya Pangus meninggalkan istrinya berkelana dan bertemu dan jatuh cinta dengan Dewi Danu. Dari pertemuan asmara dengan Dewi Danu lahir seorang anak laki-laki bernama Mayadanawa. Pada akhir cerita, Jaya Pangus dan Kang Ching Wie yang kembali bersatu, dikutuk oleh Dewi Danu menjadi patung.
Perkawinan antar bangsa yang dikaitkan dengan keberadaan Barong Landung itu, digarap dengan memadukan seni teater, tari, dan musik. Keseluruhan adegan diuntai dengan narasi (bahasa Inggris) Jro Dalang yang berkisah kepada seorang bocah. Diawali dengan penggambaran kehidupan rakyat Bali yang aman dan makmur. Segerombolan bebek yang berenang dituntun pengembalanya di bibir depan panggung, menggarisbawahi harmoni kehidupan yang nyaman dan damai. Jaya Pangus (muncul naik gajah) dilukiskan sebagai seorang raja yang arif bijaksana. Adegan berikutnya adalah kehadiran saudagar Tiongkok dengan kapal besar penuh muatan barang untuk dibarter dengan hasil bumi tanah Bali. Sang Saudagar menawarkan kain sutra, keramik, dan juga uang kepeng. Dari atas kapal juga diturunkan binatang macan, ular, burung elang dan jerapah.
Adegan perkawinan Raja Jaya Pangus dengan Kang Ching Wie dimeriahkan dengan penampilan secara bergantian dan atau bersamaan kesenian Bali dan Tiongkok. Barong Ket dan Barong Sai, ditampilkan bersamaan saling berjingkrak riang merayakan kebahagiaan perkawinan dua budaya. Dari kegembiraan, penonton kemudian disajikan adegan nestapa Jaya Pangus berkelana. Tata lampu yang dominan ungu dan biru mengantar tampilan mahluk-mahluk aneh dan monster-monster yang menyeringai seram, mengernyitkan fantasi alam gaib. Dalam buaian alam gaib inilah Jaya Pangus bercinta dengan Dewi Danu dan melahirkan Mayadanawa. Lepas dari alam gaib, Jaya Pangus dan Kang Ching Wie, dikutuk Dewi Danu, menjadi patung laki dan perempuan. Sepasang patung tinggi besar, muncul tiba-tiba di tengah arena pentas diantar dengan kepulan asap. Di latar belakang juga hadir gunung menjulang diapit candi bentar. Mayadanawa menjadi penerus dinasti raja Bali. Selesai. Penonton bertepuk. Terpukau.
Sungguh memesona. “Bali Agung“ yang sarat dengan trik dan spectacle kiranya memang dirancang sebagai sebuah tontonan megah dan menggugah namun ringan dan menghibur. Tepatnya, “Bali Agung“ berangkat dari konsep seni pertunjukan wisata yaitu sarat variasi, padat, dan disajikan secara menarik. Berbeda dengan seni pentas turistik seperti Barong dan Kecak misalnya, sebagai art by metamorphosis yang kental dengan nuansa magis, simbolis dan sakral–merupakan peniruan aslinya, “Bali Agung“ tampaknya adalah sebuah konstruksi selera estetik profan global dalam bingkai berukir ornamentik lokal Bali. Dalam konteks ini, idealisme dan gagasan progresif para senimannya diberi ruang luas, tetapi hasrat-hasrat dan orientasi ekonomi (pariwisata) juga dikalkulasi dengan cermat. Namun tak dipungkiri, “Bali Agung“ adalah “gebrakan agung“ dunia seni kita dan mudah-mudahan jua memuliakan martabat para senimannya.
Kisah Cinta Bali Kuno Dalam Pentas Wisata Bali, selengkapnya

by admin | Jul 9, 2011 | Artikel, Berita
 Penulis: Fransiskus Simon. Penerbit: Jalasutra. Yogyakarta, 2008. 5 Bab, 134 Halaman.
Penulis: Fransiskus Simon. Penerbit: Jalasutra. Yogyakarta, 2008. 5 Bab, 134 Halaman.
Kiriman: Dr. Ni Made Ruastiti, SST. MSi., Dosen PS. Seni Tari ISI Denpasar.
Manusia dan Kebudayaannya merupakan wacana yang selalu menarik untuk didiskusikan. Hal ini tidak terlepas dari korelasi keduanya yang begitu erat dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Bagi manusia, kebudayaan merupakan mode of being dan mode of doing atas realitas kehidupan yang membuat manusia dalam budaya kolektif tertentu memiliki makna panutan baku untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan.
Manusia adalah makhluk kritis dan kreatif. Dengan potensi kognitifnya manusia mampu mengubah segala sesuatu yang ada di sekitarnya menjadi lebih berarti dan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Manusia sesungguhnya telah memiliki masalah dengan kebudayaannya sejak lahir ke dunia ini. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan manusia untuk memahami kebudayaannya baik secara empiris, genealogis, metaforis dengan melakukan kajian-kajian bidang kebudayaan dan telah menghasilkan pengertian-pengertian baru, yang bukan saja saling menyempurnakan namun adapula mendekonstruksi pengertian sebelumnya sehingga wacana kebudayaan seolah tidak kunjung tuntas. Manusia dan kebudayaannya memang merupakan salah satu permasalahan hidup yang kompleks, baik secara empiris maupun teoritis. Dari berbagai persoalan, wacana kebudayaan yang muncul tentunya menuntut strategi baru, konsekuensi atas proyek-proyek imaji manusia yang cenderung liar tidak terbendung. Persoalan inipun telah melahirkan hal-hal baru sebagai identitas budaya di zamannya masing-masing.
Menarik untuk disimak karena Fransiskus Simon melalui bukunya yang berjudul “Kebudayaan dan Waktu Senggang”, mewacanakan perihal hubungan kebudayaan dengan waktu senggang. Arah pemikiran Fransiskus Simon dalam bukunya ini mencoba menarik kebudayaan dari pergumulan konseptualitasnya, kemudian mengajak para pembaca untuk memetakan, memahami dan memberi makna atas kebudayaan itu kembali. Dengan kata lain, arah dari penjabaran yang disampaikan dalam bukunya itu tidak bermaksud menumpas kebudayaan dalam konteks konseptualitas, melainkan untuk memperkaya perbendaharaan ide dan usul yang lebih representatif.
Fransiskus Simon di awal bukunya secara struktural mengawali perbincangannya dengan membahas persoalan tentang pengertian kebudayaan sampai pada substansi pembahasan mengenai pemahaman baru kebudayaan. Dalam kaitan ini, beragam pemahaman kebudayaan yang diungkapkan dilihat dari ide-ide para pemikir di Indonesia maupun luar Indonesia yang dijabarkan sedemikian rupa dari berbagai konteks di zaman yang berbeda. Dari sejumlah pemahaman yang majemuk tersebut, Fransiskus Simon mengajak para pembaca menengok pemahaman kebudayaan yang telah ada.
Pada zaman pra-modern, manusia memiliki pengalaman eksistensial pada makna kehidupan spiritualitas. Kekuatan alam semesta yang indah sekaligus menakutkan telah mengkonstruksikan budaya pemujaan manusia. Diri dihayati sebagai bagian dari kesemestaan, demikian pula sebaliknya. Sehingga refleksi dialog batin antara semesta dan dirinya termanifestasi dalam ritual. Sementara, makna hidup berbudaya pada manusia modern terletak pada pemikiran, analisis dan spekulatif. Keberadaan imaji audiovisual elektronik di zaman ini melahirkan keterpesonaan terhadap kecerdasan dan kekuasaan elektronik. Oleh karenanya, segala energi terserap oleh pesona eksisteorisitas hasrat dan imaji (kerja, belanja, mengonsumsi, dan traveling) sehingga ruang reflektivitas kurang menjangkau substansi budaya, melainkan bergeser menjadi dialog rasional tentang kemungkinan-kemungkinan pemahaman diskursif dan kesimpulannya. Walaupun identitas kebudayaan masing-masing zaman berbeda-beda, baik ketika zaman pra-modern maupun zaman modern, namun penekanan reflektivitas manusia berbudaya tetap tergantung pada ruang potensial yang disebut sebagai “waktu senggang”.
Beragam masalah kebudayaan baik secara intern maupun ekstern dibahas pada Bab 2. Secara intern meliputi persoalan identitas, kebingungan dalam proses sejarah dan tradisi, ketidak-sadaran akan karakter fiktif, kesadaran diri dan kesenjangan antara visi ideal normatif tentang diri dengan realitas yang sulit, penyikapan paranoia ketika mendarat pada wilayah-wilayah pengalaman “perubahan”, ketegangan-ketegangan internal yang terjadi ketika menampilkan “diri” di hadapan “interlokutor-diri” pada perangkat pemahaman. Sedangkan secara ekstern, wacana kebudayaan mencangkup masalah : politik representasi multifaset, kemungkinan-kemungkinan dalam melakukan transaksi-transaksi kultural, identitas yang berkelanjutan, kebudayaan pada proses yang nomadik masa lampau, sebagai unsur-unsur pembentuk kesadaran, akar ketidak-sadaran nilai-nilai dan perilaku kolektif, kebudayaan sebagai sistem simbol yang telah menyingkapkan makna kehidupan dalam ruang dan waktu, serta kebudayaan sebagai rasionalitas khas yang telah membuat hidup manusia menjadi lebih dapat dipahami.
Berdasarkan problematik, Fransiskus Simon membahas dan memahami kebudayaan dengan meminjam kerangka pikir Van Peursen sebagaimana dipaparkan pada bab 3. Sebelum menjelaskan waktu senggang, sebagai strategi kebudayaan Fransiskus Simon memperkenalkan pemahaman teknis terminologi strategi. Pokok-pokok gagasan Peursen ini oleh dipaparkannya kemudian ditransmisikan untuk memperoleh pemahaman baru tentang kebudayaan.
Pada Bab 4, Fransiskus Simon mewacanakan waktu senggang sebagai unsur dasar dari kebudayaan. Pembahasan ini diawali dengan memperkenalkan Josef Pieper, kemudian melanjutkan dengan penjelasan reposisi waktu senggang sebagai unsur dasar dalam perspektif Josef Peiper. Setelah itu, Fransiskus Simon sang Penulis melanjutkan dengan menjabarkan dan menguraikan pengertian dasar “interlokutor waktu senggang”. Di tengah ruang waktu senggang menurutnya terdapat dimensi perayaan dan pembebasan dalam rangkaian “permainan” dan kreativitas imajinasi. Hal ini diperkuat oleh gagasan Gadamer tentang permainan sebagai mode of being. Berbeda halnya dengan waktu senggang yang berdimensi pembebasan, bagi Fransiskus Simon hal ini dianggap telah memberi ruang pada gagasan “pekerjaan intelektual”, yakni kontemplasi dan relevansinya bagi kebudayaan. Pada akhir Bab ini, Fransiskus Simon membahas peranan waktu senggang bagi kebudayaan. Fransiskus Simon yang terinspirasi pemikiran Pieper membicarakan fungsi waktu senggang sejalan dengan paradigma tindakan, yakni artes liberales, kritik kebudayaan, proses belajar, dan pemberadaban. Dengan pemahaman ini, Fransiskus Simon mengajak pembaca memandang kebudayaan sebagai proses rehumanisasi.
Menarik untuk disimak karena peranan waktu senggang pada kebudayaan dianggap sangat penting. Pemikiran yang dipaparkan Simon pada Bab 3, Bab 4, dan Bab 5 merupakan acuan inspiratif, pokok pemikiran utama dari buku ini. Fransiskus Simon sebagai penulis buku ini menegaskan berbagai hal-hal khas pada kebudayaan dan persoalan terkait dengan waktu senggang.
Waktu senggang di sini merujuk pada ranah yang mengandung beragam tantangan bagi pemilik intelektual, sehingga waktu senggang juga dipahami sebagai medan radikalisasi dan penajaman semua hal yang terpahami maupun sebaliknya. Dengan berwaktu senggang dan membiarkan diri tenggelam dalam samudra imajinatif sangat berpotensi menumbuhkan gagasan-gagasan baru yang menakjubkan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian besar para koreografer dalam proses melahirkan suatu karya seni baru ketika ujian tahap akhir (TA).
Resensi Buku: Kebudayaan Dan Waktu Senggang selengkapnya

by admin | Jul 8, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Kadek Suartaya, SSKar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman: Kadek Suartaya, SSKar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Sendratari merupakan nama seni pertunjukan yang sangat familiar di tengah masyarakat Bali. Adalah di arena Pesta Kesenian Bali (PKB) pamor seni drama tari ini melejit. Sejak awal PKB, 1978, sendratari menjadi pagelaran bergengsi, membuka dan menutup pesta seni, hingga kini. Demikian pula pada PKB ke-33 tahun 2011 ini, pementasan sendratari kembali akan dapat disimak penonton. Tengoklah persiapannya di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar. Sejak sebulan terakhir ini, lembaga yang dulu bernama ASTI dan STSI tersebut, telah melakukan latihan-latihan sendratari untuk ditampilkan pada pembukaan PKB tanggal 11 Juni nanti. Para seniman–mahasiswa dan dosen–lembaga seni ini akan menyuguhkan sendratari kolosal bertajuk “Bhisma Dewabharata“.
Penonton tak hanya dapat mengapresiasi sendratari garapan ISI. Selain akan ditutup dengan sendratari besutan SMK Negeri 3 Sukawati (dulu Kokar-SMKI), duta kabupten/kota se-Bali juga telah mempersiapkan garapan sendratarinya. Sendratari masing-masing daerah tingkat II itu ditampilkan sebagai suguhan pamungkas Parade Gong Kebyar. Sendratari pendek dan padat yang disebut fragmen tari itu biasanya digarap dengan gereget sarat rivalitas karena dihadirkan dalam bentuk pentas bersanding alias mabarung. Karenanya, penggarapan dan pementasan sendratari kabupaten/kota itu menjanjikan kreativitas seni yang sangat diminati penonton pesta seni.
Di arena PKB, sendratari adalah primadona penonton. Bahkan PKB itu sendiri identik dengan sendratari. Sebab, dulu ketika PKB yang dirintis gubernur Bali Ida Bagus Mantra digelinding di tengah masyarakat, gaungnya belum segemuruh sekarang. Pagelaran sendratarilah yang menggiring penonton ke tempat penyelenggaraan PKB, Taman Budaya Bali. Mengambil tempat pentas di panggung terbuka Ardha Candra, sendratari yang disajikan oleh para seniman Kokar dan ASTI tersebut berhasil memesona penonton. Dalam bentuk pementasan sendratari kolosal yang dibawakan ratusan pelaku seni pertunjukan, PKB semakin menor pamornya. Tokoh Bima dan Sakuni dalam sendratari Mahabarata menjadi idola penonton yang datang dari penjuru Bali.
Sendratari menguak di tengah khasanah kesenian Bali pada tahun 1960-an. Konsep artistiknya sudah muncul sebelumnya di Jawa. Tetapi sendratari Bali memilih langkah perjalanannya sendiri. Jika di Jawa Tengah sendratari diciptakan untuk kepentingan wisatawan mancanegara, sendratari Bali berkembang sebagai seni pentas tontonan masyarakat lokal. Sebelum melambung di arena PKB, genre sendratari yang disosialisasikan Kokar dan ASTI, menjadi seni tontonan favorit masyarakat di pelosok desa yang dihadirkan serangkaian dengan ritual keagamaan. Pada tahun 1970-an, masyarakat Bali sering menggelar sendratari, selain juga wayang kulit, Drama Gong dan Arja.
Konsep artistik sendratari Jawa adalah drama tari tanpa dialog langsung. Konsep ini pada awalnya juga diterapkan di Bali, dimana narasi cerita hanya dikisahkan secara abstrak lewat alunan tukang tandak seperti halnya yang sudah ditradisikan dalam tari klasik legong. Tetapi konsep dramatik non verbal ini kemudian bergeser. Di panggung Ardha Candra PKB, peranan dalang sebagai pengkisah menjadi cukup dominan. Penonjolan peran dalang ini sebagai konsekuensi dari panggung yang luas, tata garap kolosal, dan lebarnya jarak pandang dan dengar penonton. Di panggung terbesar di Bali itu, ramuan estetika koreogarafi seni pentas ini disiasati, dari yang bersifat detail individual ke global massal. Dengan jumlah penonton yang relatif banyak, visualisasi artistik yang dipaparkan di atas panggung, dikomunikasikan secara verbal oleh dalang.
Sebagai sebuah genre seni pentas masa kini, sendratari rupanya terbuka dengan segala pembaharuan artistik, selain berkembang secara kompromistis dengan dinamika atmosfer masyarakat. Secara kodrati, seni sebagai ekspresi budaya memang akan mereprersentasikan nilai-nilai kehidupan manusia pelaku kebudayaan. Sendratari telah menjadi bagian dinamika masyarakat Bali modern, dari masyarakat di pelosok desa hingga dikagumi masyarakat penonton PKB, forum penikmat seni seluruh Bali. Kini, telah lebih dari 30 tahun, sendratari dinikmati penonton di arena PKB. Dari tahun ke tahun, para seniman pertunjukan sendratari tak pernah berhenti berproses dan bereksplorasi menggali berbagai kemungkinan artistik, membinarkan sendratari.
Binar sendratari agaknya akan masih berkemilau. Pada awal paruh tahun 2000-an, memang dirasakan antusiasisme penonton PKB menyaksikan sendratari agak menurun. Tetapi karena semangat para kreator dan seniman pelakunya tetap konsisten, penggarapan dan pementasan sendratari kolosal PKB belum pernah sepi penonton. Disaksikan ribuan penonton, ketika pembukaan atau penutupan PKB, Pemda Bali dengan bangga menyuguhkan sendratari kepada para pejabat tinggi negara. Dalam konteks ini, sendratari berkontribusi mengawal reputasi dan prestise budaya Bali di tataran nasional. Sendratari Bali sebagai sebuah ekspresi seni budaya bangsa hadir luwes dan elegan. Seni sebagai media komunikasi spesifik dipadukan dengan seni sebagai media komunikasi verbal. Keindahan dan keapikan aspek astistiknya disangga oleh tata narasi, selain dalam rajutan bahasa Bali namun juga dalam bahasa Indonesia. Seni, sendratari menyatukan kita.
Sendratari Bali Menyatukan Bangsa Indonesia, selengkapnya

by admin | Jul 7, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Kadek Suartaya, SSKar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman: Kadek Suartaya, SSKar., M.Si., Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Gemerincing suara gamelan terdengar renyah dari sebuah rumah di Banjar Kukuh, Desa Marga, Tabanan. Bunyi gamelan tari Bali pada pertengahan Desember lalu itu keluar dari rekaman kaset mengiringi sebuah latihan tari Bali. Tampak seorang pelatih tari, Luh Kade Pebria Satyani (18 tahun) mengajar beberapa orang gadis belia membawakan tari Condong (bagian dari Legong Keraton) dan tari Tenun. Luh Satyani tampak sibuk mengarahkan sembari melontarkan istilah dalam tari Bali seperti seledet, agem, ngegol dan sebagainya. Anak asuhnya penuh semangat mengolah tubuh dan berolah rasa mengikuti arahan sang pelatih.
Minggu sore itu, sanggar tari Ratna Mekar yang berlokasi di Desa Marga Tabanan memang sedang melakukan latihan terakhir menjelang mengikuti Lomba Tari Anak-anak Se-Bali 2010 di Denpasar, 24-26 Desember. Dari enam materi yang dipertandingkan, sanggar tari pimpinan Ni Komang Ratni, S.Pd itu hanya mengikuti tari Condong dan Tenun saja. “Ini adalah untuk pertama kalinya kami ikut lomba tari yang paling bergengsi di Bali itu,” ujar Satyani. Menurut Satya, juara bukan menjadi tujuan melainkan memberikan pengalaman dan menumbuhkembangkan kecintaan pada diri murid-muridnya terhadap kesenian luhur bangsa. Sebab, tambahnya, kesenian berkontribusi penting terhadap pembentukan karakter generasi penerus.
Geliat anak-anak Bali bermesraan dengan jagat seni, khususnya seni pertunjukan, belakangan, cukup membanggakan. Suasana yang menggairahkan itu dapat dengan mudah disimak di tengah-tengah masyarakat, baik yang hadir dalam konteks ritual keagamaan maupun yang teramati lewat peristiwa seni di arena profan. Pesta Kesenian Bali (PKB) yang sudah menggelindang lebih dari seperempat abad, ikut berkontribusi menggiring generasi muda Bali mencintai keseniannya. Festival Gong Kebyar Anak-anak se-Bali, misalnya, adalah forum dan momentum bergengsi anak-anak Bali unjuk kiprah dan keterampilan dalam bidang seni tabuh dan tari, yang, mendapat perhatian antusias masyarakat luas.
Bersanding dan bersaing secara elegan memang semestinya tersemai dalam dunia seni, termasuk di kalangan anak-anak. Tradisi mabarung dalam seni pertunjukan Bali, adalah histeria berkesenian secara bersanding yang menstimulasi pendakian keterampilan dan penampilan seni. Proses latihan-latihan menyongsong pentas bersifat kompetitif itu, misalnya, menampakkan kemajuan skil yang siginifikan. Pentas dalam konteks lomba memunculkan penampilan yang sarat gairah. Begitu pula proses berkesenian untuk merebut prestasi sekaligus prestise seperti yang terjadi dalam Lomba Tari Anak-anak Se-Bali 2010, sudah pasti menstimulasi gelora jengah nan berkobar-kobar yang berimplikasi pada rasa bangga dengan dunia seni tari.
Semangat bersaing dan bersanding telah menunjukkan fenomena menggembirakan terhadap pewarisan nilai-nilai estetik bangsa. Di kalangan anak-anak Bali, seperti yang mencuat dalam Festival Gong Kebyar, menabuh atau menari dengan dorongan lomba menggedor motivasi mereka untuk berprestasi seni yang biasnya bukan hanya sebatas hasrat berprestasi dalam jagat seni semata namun bisa jadi pula dalam kehidupan yang lebih luas. Lewat kancah seni, anak-anak Bali yang sejak dini berasyik masyuk dengan nilai-nilai keindahan seni tumbuh menjadi generasi kontributif bagi masa depan yang lebih cerah dalam kehidupan berbangsa.
Seni adalah nilai keindahan yang hidup dan berkembang seturut dengan peradaban kebudayaan manusia. Dipercaya, binar lahiriah keindahan seni menyemburkan kedamaian nurani dan aura terdalam dari jagat seni memiliki dimensi spiritual yang berkontribusi kuat pada moralitas subjek kemanusiaan. Idealnya, seni malahan dianggap mampu memanusiakan manusia. Untuk mengawal moralitas setiap individu–dengan keyakinan seni sebagai penyejuk moral—jagat kesenian sangat fungsional dijadikan sebagai media pendidikan moralitas bangsa. Kebhinekaan Indonesia yang memiliki puspa warna ekspresi seni, dengan demikian, sangat memungkinkan menjadi bangsa yang menjunjung moral dengan penuh takzim.
Akan tetapi, di tengah gelombang kesejagatan ini, peranan seni sebagai media pendidikan moral telah mulai tergerus. Di tengah masyarakat Bali yang sangat kental dengan kehidupan seninya, tak terkecuali, juga terdegradasi oleh kehidupan modern kekinian. Dulu, kesenian merupakan wahana komunikasi spesifik yang karismatik dalam memberikan pengetahuan dan tuntunan moral pada masyarakatnya. Pementasan Wayang Kulit misalnya, di masa lalu, tak hanya menyajikan tontonan namun juga tuntunan hidup positif pada komunitasnya. Demikian pula Topeng saat ritual keagamaan, Arja di bale banjar sebagai seni balih-balihan sarat dengan muatan moral yang diteladani masyarakat. Akan tetapi kini tidak lagi. Wayang, Topeng, Arja, dan seni tradisional lainnya ditekuk oleh televisi dan hiburan modern lain yang melenakan.
Beruntung di pulau Bali, seni masih kokoh bersemi integral dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Dalam peristiwa keagamaan misalnya, seni selalu hadir menyediakan ruang olah rasa bagi setiap orang. Sebagai bagian dari penempaan olah rasa, budaya ngayah dalam ritual keagamaan masih dilestarikan. “Para penari anak asuh sanggar kami juga sering ngayah dalam upacara adat dan agama yang berlangsung di lingkungannya,“ ungkap Luh Kade Pebria Satyani saat menghias salah satu muridnya menjelang tampil dalam Lomba Tari Anak-anak Se-Bali 2010 di Denpasar itu.
Dari Kukuh Memperkokoh Tari Bali selengkapnya

 Denpasar – Drs I Wayan Mudana MPar, pengamat seni lukis asal Bali, menilai perkembangan kreatif seni lukis sangat tergantung dari jiwa, dedikasi dan vitalisme seniman bersangkutan dalam menekuni proses karya seni.
Denpasar – Drs I Wayan Mudana MPar, pengamat seni lukis asal Bali, menilai perkembangan kreatif seni lukis sangat tergantung dari jiwa, dedikasi dan vitalisme seniman bersangkutan dalam menekuni proses karya seni.