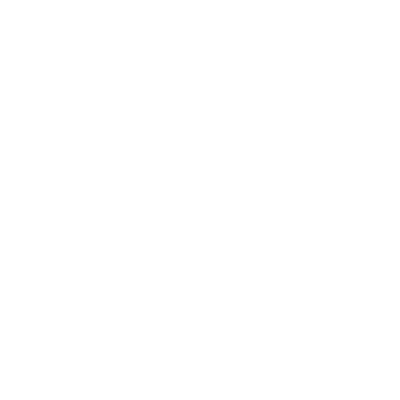by admin | Jul 15, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: I Made Dwi Andika Putra, Mahasiswa PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman: I Made Dwi Andika Putra, Mahasiswa PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Oleh : Drs.K.M. Suhardana
Penerbit : “ PARAMITA”
Cetakan Pertama : Tahun 2006
Kata “Arya” menurut P.J. Zoetmulder dan S.O. Robson dalam “Kamus Jawa Kuno Indonesia” diartikan sebagai “terhormat, terpandang, mulia atau ningrat,” sedangkan kata “Nararya” diartikan sebagai “yang mulia diantara orang-orang keturunan ningrat. Sementara itu kata Nararya sering kali dicantumkan di depan nama diri. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Nararya di depan nama seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah keturunan raja, keturunan ningrat atau orang yang terhormat, mulia atau terpandang. Pemakaian gelar Arya sebenarnya sudah berjalan sejak jaman Bali Kuno ketika Raja Ugrasena Berkuasa (tahun 882 M), demikian juga pada waktu Raja Kesari Warmadewa memerintah (tahun 913 M). Jayakaton yang pada tahun 907 menjadi Patih Raja menurunkan Arya Rigih, kemudian Arya Rigih melahirkan Arya Rigis yang selanjutnya menurunkan Arya Kedi. Berikutnya Arya Kedi menurunkan Arya Karangbuncing. Kemudian pada jaman Airlangga (tahun 1019 M) pun gelar Arya juga sudah dipergunakan. Sri Airlangga sendiri dari isterinya seorang putri gunung menamakan putranya Arya Buru atau Arya Pangalasan atau Arya Timbul.
Dalam sejarahnya memang penggunaan gelar Arya itu menjadi semakin meluas setelah jatuhnya Kerajaan Kadiri ke tangan pasukan Majapahit. Sejak jatuhnya Kerajaan Kadiri, keturunan Sri Jayakatwang dan orang-orang Kerajaan Kadiri tidak lagi memperoleh kepercayaan. Semua pejabat yang semula dipegang orang-orang Kadiri diganti dengan orang-orang Majapahit. Raja Kadiri Sri Sastrajaya (tahun 1258-1271M) yang kedudukannya diganti oleh Jayakatwang turut menerima kekalahan itu dan mendapatkan gelar baru sebagai Arya Kadiri dan lazim disebut Ksatriyeng Kadiri atau Ariyeng Kadiri. Semua keturunan dan sanak saudaranya juga memperoleh gelar atau julukan yang sama. Gelar Arya atau Ksatria itu tidak saja diberlakukan bagi keturunan Raja Kadiri, tetapi juga bagi keturunan bekas Kerajaan Kahuripan. Karena itu disamping Arya Kadiri ada pula Arya Kahuripan. Ada Kesatiyeng Kadiri ada Kesatriyeng Kahuripan. Tidak itu saja, mantan Raja-raja dan keturunannya dari kerajaan-kerajaan kecil bekas daerah kekuasaan Kerajaan Kadiri maupun Kahuripan pun memperoleh gelar atau julukan yang sama. Gelar Arya diberikan juga kepada mereka yang kawin nyeburin (nyentana) dengan keturunan Kesatriyeng Kahuripan yang sudah menyandang gelar Arya. Misalnya Ida Bang Banyak Wide (wangsa Brahmana) yang kawin nyentana dengan Ni Gusti Ayu Pinatih putra Arya Beleteng (wangsa Arya) beralih kewangsaannya dari Brahmana menjadi Arya. Itulah sebabnya mengapa Ida Bang Banyak Wide menurunkan wangsa Arya Wang Bang Pinatih atau I Gusti Pinatih.
Di Bali, kata Arya yang berarti juga ksatria ini diterjemahkan menjadi Gusti. Bahkan keturunan para Arya sendiri semisal Pangeran, Kiyai dan lain-lain diberi julukan yang sama yaitu Gusti. Tidak jelas kapan julukan Gusti termaksud diberlakukan, namun dapat diduga ada keterkaitannya dengan gelar para Raja Bali yang oleh pemerintah colonial Belanda diatur berdasarkan Staatblad No. 226 tanggal 1juli 1929. ketika itu Raja-raja Bali diberi gelar Cokorda, anak Agung atau I Dewa Agung. Dari sinilah rupanya gelar atau sebutan Gusti itu menunjukkan jati dirinya sebagai pengganti kata Arya, Kiyai atau Pangeran.
Resensi Buku Babad Arya, Kisah Perjalanan Para Arya, Selengkapnya
by admin | Jul 14, 2011 | Uncategorized
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed blandit massa vel mauris sollicitudin dignissim. Phasellus ultrices tellus eget ipsum ornare molestie scelerisque eros dignissim. Phasellus fringilla hendrerit lectus nec vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In faucibus, risus eu volutpat pellentesque, massa felis feugiat velit, nec mattis felis elit a eros. Cras convallis sodales orci, et pretium sapien egestas quis. Donec tellus leo, scelerisque in facilisis a, laoreet vel quam. Suspendisse arcu nisl, tincidunt a vulputate ac, feugiat vitae leo. Integer hendrerit orci id metus venenatis in luctus tellus convallis. Mauris posuere, nisi vel vehicula pellentesque, libero lacus egestas ante, a bibendum mauris mi ut diam. Duis arcu odio, tincidunt eu dictum interdum, sagittis quis dui.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam dictum egestas rutrum. Aenean a metus sit amet massa egestas vulputate sit amet a nisi. Sed nec enim erat. Sed laoreet imperdiet dui fermentum placerat. Donec purus mi, pellentesque et congue at, suscipit ac justo. Pellentesque et augue quis libero aliquam lacinia. Pellentesque a elit vitae nisl vulputate bibendum aliquet quis velit. Integer aliquet cursus erat, in pellentesque sapien tristique vitae. In tempus tincidunt leo id adipiscing. Sed eu sapien egestas arcu condimentum dapibus. Donec sit amet quam ut metus iaculis adipiscing eget quis eros.
Sed id dui dolor, eu consectetur dui. Etiam commodo convallis laoreet. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus vel sem at sapien interdum pretium. Sed porttitor, odio in blandit ornare, arcu risus pulvinar ante, a gravida augue justo sagittis ante. Sed mattis consectetur metus quis rutrum. Phasellus ultrices nisi a orci dignissim nec rutrum turpis semper. Donec tempor libero ut nisl lacinia vel dignissim lacus tristique. Etiam accumsan velit in quam laoreet sollicitudin. Mauris euismod lacus ut magna placerat ac molestie augue consequat.
by admin | Jul 14, 2011 | Uncategorized
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed blandit massa vel mauris sollicitudin dignissim. Phasellus ultrices tellus eget ipsum ornare molestie scelerisque eros dignissim. Phasellus fringilla hendrerit lectus nec vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In faucibus, risus eu volutpat pellentesque, massa felis feugiat velit, nec mattis felis elit a eros. Cras convallis sodales orci, et pretium sapien egestas quis. Donec tellus leo, scelerisque in facilisis a, laoreet vel quam. Suspendisse arcu nisl, tincidunt a vulputate ac, feugiat vitae leo. Integer hendrerit orci id metus venenatis in luctus tellus convallis. Mauris posuere, nisi vel vehicula pellentesque, libero lacus egestas ante, a bibendum mauris mi ut diam. Duis arcu odio, tincidunt eu dictum interdum, sagittis quis dui.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam dictum egestas rutrum. Aenean a metus sit amet massa egestas vulputate sit amet a nisi. Sed nec enim erat. Sed laoreet imperdiet dui fermentum placerat. Donec purus mi, pellentesque et congue at, suscipit ac justo. Pellentesque et augue quis libero aliquam lacinia. Pellentesque a elit vitae nisl vulputate bibendum aliquet quis velit. Integer aliquet cursus erat, in pellentesque sapien tristique vitae. In tempus tincidunt leo id adipiscing. Sed eu sapien egestas arcu condimentum dapibus. Donec sit amet quam ut metus iaculis adipiscing eget quis eros.
Sed id dui dolor, eu consectetur dui. Etiam commodo convallis laoreet. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus vel sem at sapien interdum pretium. Sed porttitor, odio in blandit ornare, arcu risus pulvinar ante, a gravida augue justo sagittis ante. Sed mattis consectetur metus quis rutrum. Phasellus ultrices nisi a orci dignissim nec rutrum turpis semper. Donec tempor libero ut nisl lacinia vel dignissim lacus tristique. Etiam accumsan velit in quam laoreet sollicitudin. Mauris euismod lacus ut magna placerat ac molestie augue consequat.

by admin | Jul 14, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Drs. I Wayan Mudra, MSn., Dosen PS Kriya Seni ISI Denpasar
Kiriman: Drs. I Wayan Mudra, MSn., Dosen PS Kriya Seni ISI Denpasar
Tedung sebagai salah satu jenis perangkat upacara ritual keagamaan khususnya di Bali, memiliki beberapa bentuk, ukuran, warna, fungsi dan istilah yang beragam. Bentuk atau form dalam dunia seni rupa harus dilihat secara keseluruhan atau sebagai satu kesatuan yang utuh. Kesatuan bentuk tersebut dapat terbentuk lewat teknik pengerjaan, material yang digunakan, proporsi ukuran maupun komposisi yang tersusun. Sesuai data lapangan dan dokumen yang ada, bentuk, tinggi dan lebar ukuran tedung yang ada maupun dibuat para perajin/undagi dibeberapa pura tempat/daerah yang masih bervariasi, baik tedung agung maupun tedung robrob. Untuk dipahami, pengertian atau penyebutan istilah tedung agung dan robrob dibedakan atas lenter/ider-ider yang dikenakan pada sisi penggir tukub/atap tedung dengan posisi berjuntai. Kalau Tedung robrob, pada sisi pinggirnya diisi atau dihiasi dengan anyaman atau sulaman dari benang. Sulaman atau rajutan yang menghiasi pinggiran tedung robrob menggunakan benang wol yang berwarna, seperti hitam, putih, kuning merah maupun hijau. Sedangkan tedung agung, pada hiasan tepi pinggir dijuntai dengan kain warna atau prada yang lazim disebut dengan ider-ider. Kain yang berjuntai tersebut terdiri dari dua lapis/warna dengan ukuran kain atas/depan lebih pendek dari pada yang dibagian bawah/tengahnya.
Secara visual, posisi lingkaran pinggiran yang dibentuk oleh ruas iga-iga dari lima bentuk tedung ini, mempunyai lengkungan bentuk yang berbeda. Jenis tedung robrob yang ada di pura Besakih, memiliki bentuk melingkar yang datar, di pura pasekan payangan yang merupakan buatan perajin dari bangli mempunyai lingkaran bentuk yang “ngampid lawah” (sayap kelelawar) tidak terlalu melengkung atau datar, dan yang terdapat di Kusuma Yasa (perajin), mempunyai lingkaran bentuk ngojong atau menyerupai kerucut. Dalam arsitektur Bali disebut atap jongjong. Bebeda dengan lingkaran bentuk tedung yang berangka tahun 1910 dan 1947 foto koleksi Tropenmuseum Royal Tropical Institute mempunyai bentuk datar atau nayah. Dilihat dari proporsi antara lebar lingkaran dan tingginya tiang tedung, khususnya gambar/foto tedung yang berangka tahun 1910 dan 1947 nampak mempunyai ukuran lebih tinggi kalau dibandingkan dengan ukuran tinggi tiang tedung yang ada sekarang.
Disadari pula, untuk mendapatkan validitas data terkait dengan jenis, bentuk ukuran tedung, kober, dan umbul-umbul yang tepat dan ideal, terlebih untuk yang kategori sakral, tidaklah pekerjaan mudah yang harus diupayakan untuk ditemukan. Data berupa dokumentasi foto-foto yang ada relevansinya dengan obyek penelitian belum atau tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang ketinggian, kelebaran, dan bentuk yang bisa diukur. Namun demikian, komporasi sampel dengan populasi berbeda menjadi sulusi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Tindakan identivikasi secaran langsung dengan melakukan pengukuran dan menghitung ketinggian dan lebar jenis-jenis tedung (tedung agung dan robrob) karya para perajin yang telah ditetapkan. Langkah ini dapat memberi gambaran terhadap ukuran, dan bentuk tedung yang digunakan sebagai sarana ritual keagamaan ataupun sebagai dekorasi.
Penelitian tahap awal atau tahun pertama dari dua tahun yang kami rencanakan ini belum dilakukan penelusuran dan mengungkap data secara tuntas. Kendala utama yang ada ketika untuk mendapatkan tentang ukuran tinggi dan lebarnya tedung, umbul-umbul, kober maupun jenis Pengawin/uparengga yang tersimpan maupun yang digunakan di beberapa pura. Secara ritual, tedung, umbul-umbul, dan kober yang ada di pura telah disakralkan dan secara etika pula peneliti merasa enggan untuk melakukan pengukuran, walaupun hal tersebut sangat mungkin dilakukan atau diijinkan sesuai dengan tatacara yang berlaku. Untuk mendapatkan validasi data dalam kondisi seperti ini, peneliti mengambil nisiatif memohon informasi dari prejuru atau pemuka adat tentang asal-usul dimana tedung, umbul-umbul, kober maupun jenis Pengawin/uparengga lainnya dibuat/didapatkan. Informasi ini adalah petunjuk yang sangat efektif untuk menemukan tempat pembuat/perajin tedung, umbul-umbul, kober dengan jenis, bentuk, maupun ukuran yang sama dengan yang ada di pura. Lewat penelusuran ke sumber obyek yang relevan, validasi data dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan.
Tedung Sebagai Sarana Upacara Agama Hindu Di Bali, selengkapnya
by admin | Jul 14, 2011 | Artikel, Berita
Kiriman: Ida Bagus Gede Surya Peradantha, SSn., Alumni ISI Denpasar
Tari Legong dalam khasanah budaya Bali termasuk ke dalam jenis tari klasik karena awal mula perkembangannya bermula dari istana kerajaan di Bali. Tarian ini dahulu hanya dapat dinikmati oleh keluarga bangsawan di lingkungan tempat tinggal mereka yaitu di dalam istana sebagai sebuah tari hiburan. Para penari yang telah didaulat menarikan tarian ini di hadapan seorang raja tentu akan merasakan suatu kesenangan yang luar biasa, karena tidak sembarang orang boleh masuk ke dalam istana.
Mengenai tentang awal mula diciptakannya tari Legong di Bali adalah melalui proses yang sangat panjang. Menurut Babad Dalem Sukawati, tari Legong tercipta berdasarkan mimpi I Dewa Agung Made Karna, Raja Sukawati yang bertahta tahun 1775-1825 M. Ketika beliau melakukan tapa di Pura Jogan Agung desa Ketewel ( wilayah Sukawati ), beliau bermimpi melihat bidadari sedang menari di surga. Mereka menari dengan menggunakan hiasan kepala yang terbuat dari emas.
Ketika beliau sadar dari semedinya, segeralah beliau menitahkan Bendesa Ketewel untuk membuat beberapa topeng yang wajahnya tampak dalam mimpi beliau ketika melakukan semedi di Pura Jogan Agung dan memerintahkan pula agar membuatkan tarian yang mirip dengan mimpinya. Akhirnya Bendesa Ketewel pun mampu menyelesaikan sembilan buah topeng sakral sesuai permintaan I Dewa Agung Made Karna. Pertunjukan tari Sang Hyang Legong pun dapat dipentaskan di Pura Jogan Agung oleh dua orang penari perempuan.
Tak lama setelah tari Sang Hyang Legong tercipta, sebuah grup pertunjukan tari Nandir dari Blahbatuh yang dipimpin I Gusti Ngurah Jelantik melakukan sebuah pementasan yang disaksikan Raja I Dewa Agung Manggis, Raja Gianyar kala itu. Beliau sangat tertarik dengan tarian yang memiliki gaya yang mirip dengan tari Sang Hyang Legong ini, seraya menitahkan dua orang seniman dari Sukawati untuk menata kembali dengan mempergunakan dua orang penari wanita sebagai penarinya. Sejak itulah tercipta tari Legong klasik yang kita saksikan sekarang ini.
Bila ditinjau dari akar katanya, Legong berasal dari kata “ leg “ yang berarti luwes atau elastis dan kata “gong” yang berarti gamelan. Kedua akar kata tersebut bila digabungkan akan berarti gerakan yang sangat diikat ( terutama aksentuasinya ) oleh gamelan yang mengiringinya (Dibia, 1999:37).
Sebagai sebuah tari klasik, tari Legong sangat mengedepankan unsur artistik yang tinggi, gerakan yang sangat dinamis, simetris dan teratur. Penarinya pun adalah orang-orang yang berasal dari luar istana yang merupakan penari pilihan oleh raja ketika itu. Maka, tidaklah mengherankan jika para penari merasakan kebanggaan yang luar biasa jika menarikan tari Legong di istana. Begitu pula sang pencipta tari. Akan menjadi suatu kehormatan besar apabila dipercaya untuk menciptakan suatu tarian oleh seorang pengusa jaman itu. Walaupun nama mereka tidak pernah disebutkan mencipta suatu tarian kepada khalayak ramai, mereka tidak mempersoalkan itu asalkan didaulat mencipta berdasarkan hati yang tulus dan penuh rasa persembahan kepada sang raja. Ini dapat dilihat dari hampir seluruh tari-tari klasik maupun tari tradisi lain yang berkembang di luar istana seperti tari Legong, Baris, Jauk dan Topeng.
Kini di jaman yang tidak lagi menganut paham feodalisme, keseian Legong telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari segi kuantitas maupun kualitas. Disebutkan bahwa tari Legong Keraton ( karena berkembang di istana ) keluar dari lingkungan istana pada awal abad ke-19. Para penari wanita yang dahulunya berlatih dan menari Legong di istana kini kembali ke desa masing-masing untuk mengajarkan jenis tarian ini kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, orang Bali adalah orang yang sangat kreatif sehingga gaya tari masing-masing pun sedikit berbeda sesuai dengan kemampuan membawakannya. Oleh karena itu, timbul style-style Palegongan yang tersebar di berbagai daerah seperti di desa Saba, Peliatan, Bedulu, Binoh, Kelandis dan beberapa tempat lainnya. Dari sekian daerah perkembangan tari Legong, hanya desa Saba dan Peliatan yang masih kuat mempertahankan ciri khasnya dan mampu melahirkan jenis-jenis tari Palegongan dengan berbagai nama.
Tari-tari legong yang ada di Bali pada awalnya diiringi oleh gamelan yang disebut Gamelan Pelegongan. Perangkat gamelan ini terdiri dari dua pasang gender rambat, gangsa jongkok, sebuah gong, kemong, kempluk, klenang, sepasang kendang krumpungan, suling, rebab, jublag, jegog, gentorang. Sebagai tambahan, terdapat seorang juru tandak untuk mempertegas karakter maupun sebagai narrator cerita melalui tembang. Namun, seiring populernya gamelan gong kebyar di Bali, akhirnya tari-tari palegongan ini pun bisa diiringi oleh gamelan Gong Kebyar, karena tingkat fleksibilitasnya.

 Kiriman: I Made Dwi Andika Putra, Mahasiswa PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman: I Made Dwi Andika Putra, Mahasiswa PS Seni Karawitan ISI Denpasar