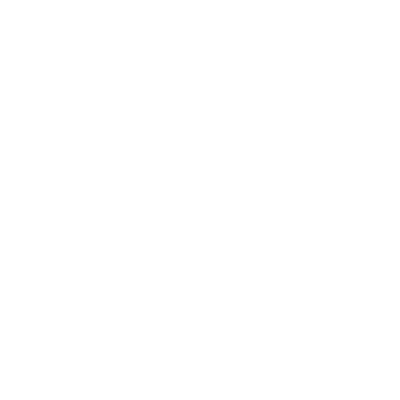by admin | Jul 20, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman Drs. I Wayan Mudra, MSn., Dosen PS. Kriya Seni ISI Denpasar
Kiriman Drs. I Wayan Mudra, MSn., Dosen PS. Kriya Seni ISI Denpasar
Rabu 19 Juli 2011 keluarga besar ISI Denpasar mengadakan tirtayatra diikuti dosen, pegawai, dan mahasiswa dari FSP dan FSRD. Acara tersebut merupakan salah satu acara rutin yang diselenggarakan lembaga ISI Denpasar dalam menyambut pelaksanaan dies setiap tahunnya. Tempat yang menjadi tujuan tirtayatra tahun ini adalah Bali Utara yaitu Pura Puseh Penegil Dharma di Desa Kubu Tambahan Kecamatan Kubu Tambahan dan Pura Ponjok Batu di Desa Julah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Kedua tempat suci tersebut merupakan Penyungsungan Jagat atau Pura Dang Khayangan. Kegiatan yang menyita waktu satu hari penuh tersebut berjalan lancar. Pada akhir pesembahyangan di Pura Ponjok Batu salah satu pemangku memberikan penjelasan kepada semua pemedek yang melakukan persembahyangan pada waktu itu tentang keberadaan pura mulai dari sejarah pura, pelinggih, pengempon pura, hari piodalan pura serta kaitannya dengan Danghyang Nirarta. Penjelasan-penjelasan yang disampaikan pemangku tersebut merupakan penjelesan yang didapat dari pendahulunya, mereka tidak menemukan sumber-sumber tertulis yang dapat menjelaskan keberadaan pura tersebut dengan pasti.
Penulis menelusuri beberapa sumber terkait dengan Pura Ponjok Batu tersebut belum ditemukan artikel atau tulisan yang dapat menjelaskan dengan data yang pasti. Analisis lebih banyak berdasarkan ceritra rakyat dan tattwa yang ada. Seperti halnya yang dimuat ILoveBlue, bahwa Pura Ponjok Batu merupakan sebuah tanjung yang terdiri dari batu dari celah-celah batu tersebut tumbuh pohon kamboja dan semak yang sangat indah. Dalam bahasa Bali “Ponjok Batu” berarti Tanjung Batu. Pura Ponjok Batu terletak lebih kurang 24 km di sebelah Timur Singaraja.
Lebih jauh didijelaskan ILoveBlue.com, asal muasal berdirinya Pura atau Kahyangan ini erat hubungannya dengan perjalanan Danghyang Nirartha yang juga dikenal dengan sebutan Danghyang Dwijendra, di dalam Dwijendra Tattwa antara lain dikisahkan sebagai berikut : Pada zaman pemerintahan Dalem Gelgel Sri Waturenggong, sekitar tahun Isaka 1411 atau tahun 1489 M datanglah ke Bali Danghyang Nirartha kemudian dikenal dengan sebutan Danghyang Dwijendra. Setelah beberapa lama tinggal di Gelgel, pada suatu hari Danghyang Nirartha ingin meninjau daerah Bali di sebelah Utara Gunung (Den Bukit) yaitu Buleleng, yang seterusnya kalau tidak ada aral melintang beliau berniat akan terus menyeberang ke Sasak (Lombok). Sesudah beliau berjalan beberapa hari lamanya kemudian Danghyang Nirartha sampai pada suatu tempat di Pantai Utara Pulau Bali yang letaknya di sebelah barat laut Gunung Agung. Tempat itu berupa sebuah Tanjung yang terdiri dari batu batu, dan dari celah-celah batu tersebut tumbuh kayu-kayuan sehingga Tanjung Batu tersebut menjadi semak-semak. Di sana Danghyang Nirartha berhenti dan duduk di atas batu pada tempat yang agak tinggi untuk menikmati pemandangan laut Jawa yang terhampar luas yang sangat mengasyikkan dan menumbuhkan inspirasi baginya. Tidak dikisahkan entah sudah berapa lama Danghyang Nirartha berada di tempat itu, pada suatu hari tidak jauh dari tempat beliau duduk arah sebelah Timur terdampar sebuah perahu. Timbul keinginan beliau untuk mengetahui apa gerangan yang menyebabkan perahu tersebut terdampar, lalu tempat perahu itu terdampar didekatinya. Setelah diperiksa ternyata perahu itu mendapat kerusakan yaitu tiang layarnya patah dan layarnya robek-robek, sedang tali temalinya terputus. Anak buah dan nahkoda perahu tersebut terlempar ke pantai dalam keadaan mabuk laut dengan kondisi fisiknya sangat lemah dan tergeletak di atas pasir seakan-akan tidak berjiwa lagi. Danghyang Nirartha menyaksikan kondisi mereka yang sangat mengerikan dan menyedihkan itu menjadi iba hati, lalu segera memberikan pertolongan. Dengan kekuatan bathinnya, anak buah dan nahkoda perahu itu oleh Danghyang Nirartha diberikan babayon (tenaga) secara gaib, sehingga anak buah dan nahkoda perahu tersebut menjadi siuman dan sadarkan diri, dan tiada lama mereka sudah dapat duduk di atas pasir. Menyadari dirinya ditolong, lalu mereka menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Danghyang Nirartha, karena mereka yakin bahwa tanpa pertolongan beliau ini mereka pasti menemui ajalnya. Kemudian Danghyang Nirartha bertanya kepada anak buah dan nahkoda perahu tersebut demikian,”Darimana saudara sekalian ini?”, dan segera dijawab oleh nahkoda perahu itu,:”Ya Paduka Pandita, kami ini bertujuh (7 orang adalah berasal dari Sasak (Lombok), dan di dalam pelayaran ini kami mendapat bahaya yaitu sekitar kurang lebih 1 bulan perahu kami terombang-ambing oleh ombak dan gelombang laut serta kami sampai kehabisan bekal.” Seterusnya nahkoda perahu itu melanjutkan ceriteranya: “Entah sudah berapa lama kami tidak makan dan minum ditambah lagi mabuk laut, sehingga kami tidak sadarkan diri. Dalam siatuasi dan kondisi yang demikian, kami sudah tidak ada harapan hidup, dan nasib kami serahkan atas kehendak Yang Maha Kuasa, yang akhirnya kami terdampar dan terlempar di pantai ini. Kami menghaturkan banyak terima kasih yang keluar dari hati nurani kami yang paling dalam atas belas kasihan dan pertolongan Paduka Pandita, yang berkenan menghidupkan kami kembali. Kami yakin tanpa belas kasihan dan pertolongan Paduka Pandita kami tidak akan mungkin hidup seperti sekarang,” demikian jawaban dan ceritera nahkoda perahu tersebut. Oleh karena ketujuh orang itu tampaknya sudah agak pulih kesehatannya, lalu Danghyang Nirartha memberitahu kepada mereka itu untuk membersihkan diri masing-masing dan minum air pada sebuah mata air yang baru saja timbul. Kemudian mereka disarankan mencari buah-buahan di dalam semak-semak untuk dimakan, dan setelah itu mereka lakukan , kemudian mereka beristirahat dan bermalam bersama Danghyang Nirartha disana. Di sana Danghyang Nirartha menyarankan, andaikata mereka akan kembali berlayar ke Sasak (lombok) sebaiknya esok harinya saja dan Danghyang Nirartha akan ikut ke Sasak (Lombok). Semua saran dan nasehat Danghyang Nirartha itu diturut dan ditaati oleh anak buah bersama nahkoda perahu tersebut, dan pada malam harinya mereka bermalam di sana. Tidak dikisahkan bagaimana gembira hatinya anak buah bersama nahkoda perahu tersebut, besoknya pagi-pagi mereka sudah bangun dalam keadaan fisik yang segar bugar sebagaimana keadaan sebelumnya. Menurut mereka hal ini terjadi tidak lain adalah berkat kekuatan bathin dan ketinggian ilmu gaibnya Danghyang Nirartha. Hari itu keadaan laut tenang karena tidak ada gelombang besar seperti hari kemarinnya, serta menurut hemat Danghyang Nirartha saat itu adalah waktu yang baik untuk berlayar ke Sasak (Lombok). Mereka lalu bersama-sama dengan mempergunakan perahu itu berlayar menuju ke Sasak (Lombok) dalam keadaan selamat dan sampai ke tempat tujuan, walaupun perahu itu tanpa layar. Sesudah tanjung Batu itu ditinggalkan oleh Danghyang Nirartha terjadilah keajaiban yang membuat orang-orang di sekitarnya terheran-heran, karena setiap malam hari di bekas tempat Danghyang Nirartha berhenti dan duduk itu batu-batunya menyala. Orang-orang itu ingin melihat dan membuktikan apa gerangan yang telah terjadi di atas batu-batu tersebut, sehingga setiap hari Tanjung Batu itu ramai dikunjungi orang. Mereka itu bukan saja ingin mengetahui mengenai keajaiban yang terjadi di sana, melainkan ingin mendapatkan keselamatan, lalu mereka melakukan persembahyangan di sana. Akhirnya di sana dibangun sebuah Pura atau kahyangan dengan bangunan sucinya berbentuk sebuah “Sanggar Agung” dan Pura atau Kahyangan itu diberi nama “Pura Ponjok Batu” sesuai dengan tempat itu yang merupakan tanjung batu. Kata “tanjung” sama dengan “ponjol” dalam bahasa Bali, sehingga kata “ponjok batu” berati “tanjung batu”, dan sekarang pura atau Kahyangan itu menjadi tempat persembahyangan umum, untuk memohon keselamatan. Tidak mustahil bahwa sampai sekarang sudah terjadi perubahan-perubahan dari aslinya pura atau kahyangan tersebut, baik mengenai arealnya maupun mengenai palinggih (banguna sucinya). Tentu saja perubahan-perubahan itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan penyungsungnya, namun yang jelas dilihat dari segi status dan fungsi dari Pura Ponjok Batu ini masih tetap sebagaimana semula. Dari uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pura Ponjok Batu ini tidak dapat dipisahkan dengan kisah perjalanannya Danghyang Nirartha.
Lain halnya dengan Babad Bali.com memuat bahwa Pura ini memiliki rekaman sejarah yang panjang dan unik. Hal tersebut ditelusuri lewat temuan arkeologi, efigrafi dan folklore (cerita rakyat) yang hidup di tengah masyarakat Julah dan sekitarnya.
Berdasarkan kajian arkeologis, saat penggalian di lokasi perbaikan pura tahun 1995 ditemukan sarkopah/sarkopagus. Kini sarkopah itu disimpan bersama sarkopah lainnya di halaman depan Pura Duhur Desa Kayuputih, Banjar. Sarkopah (peti mayat) terbuat dari batu cadas, banyak ditemukan di beberapa daerah di Bali.
Sistem penguburan menggunakan sarkopah berlangsung sejak zaman perundagian di Bali tahun 2500-3000 SM, atau sekitar 5.000 tahun lalu. Berarti di sekitar kawasan Pura Ponjok Batu pernah dihuni masyarakat yang mendukung budaya sarkopah. Sarkopah merupakan tempat disemayamkannya jasad orang yang dihormati masyarakat
Sementara menurut kajian efigrafi atau prasasti, Desa Julah sebagai pemukiman sangat ramai. Ini diketahui dari prasasti yang dikeluarkan raja-raja dari Dinasti Warmadewa, masing-masing masa pemerintahan Raja Sang Sri Aji Ugrasena (tahun 923 M), Raja Sri Aji Tabanendra Warmadewa (955 M), Raja Sri Janasadhu Warmadewa (975 M), Raja Sri Dharma Udayana Warmadewa (1011 M), Raja Putri Sang Adnyadewi, Prabu Marakatta (1022-1026 M), Raja Sri Paduka Anak Wungsu dan Raja Sri Prabu Jayapangus (1181 M).
Raja-raja yang pernah berkuasa itu hampir semuanya pernah mengeluarkan prasasti tentang keberadaan Desa Julah. Di sana disebutkan pula bahwa tugasnya menjaga sebaik-baiknya semua pura yang ada di wilayah Desa Julah. Kendati tidak disebutkan dengan jelas tentang Pura Ponjok Batu, tetapi dipastikan Pura Ponjok Batu merupakan salah satu pura yang ikut dirawat. Di pura itu juga ditemukan beberapa patung, di antaranya patung Dewa Siwa, Nandini dan Ganesa. Ini merupakan petunjuk bahwa perhatian raja Dinasti Warmadewa terhadap Pura Ponjok Batu sangat besar.
Masa kekuasaan Warmadewa berlangsung sampai 1343, ditandai dengan jatuhnya Kerajaan Bedahulu oleh Majapahit. Selanjutnya pemerintahan di Bali dipegang Dinasti Kepakisan yang berpusat di Samprangan, lalu pindah ke Gelgel. Sampai kekuasaan Dalem Waturenggong, mulai ada perhatian terhadap Pura-pura di Bali Utara/ Denbukit. Diawali dengan kedatangan Danghyang Nirartha. Saat itu Pura-pura yang ada di Bali Utara mendapat kunjungan kembali dalam bentuk dharma yatra, mulai dari Pura Pulaki dan pura lainnya, termasuk Ponjok Batu.
Sejak kedatangan Danghyang Nirartha, nilai spiritual tempat suci kembali bangkit. Pura Ponjok Batu mulai memancarkan sinar secara terus-menerus, walaupun Danghyang Nirartha telah meninggalkan tempat itu menuju ke Lombok, seperti terungkap dalam lontar Dwijendra Tattwa.
Sementara berdasarkan folklore, Pura Ponjok Batu berasal dari cerita Ida Batara di Bali yang menimbang beratnya Bali Utara dari Pura Penimbangan di Desa Panji. Ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka Ida Batara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara sehingga timbangan itu menjadi seimbang.
Pura Ponjok Batu telah beberapa kali dipugar. Pemugaran terakhir dimulai 1994 hingga dilakukannya upacara Ngenteg Linggih pada Saniscara Wayang Karo, 8 Agustus 1998. Pura ini terbuat dari batu hitam yang didesain sedemikian rupa agar keberadaannya tetap kuat. Saat ini, pelinggih yang ada di Pura Ponjok Batu meliputi:
1. Padmasana
2. Pelinggih Dang Hyang Nirartha
3. Pelinggih Ciwa
4. Pelinggih Ganesa
5. Pelinggih Batara Baruna
6. Pelinggih Seluang
7. Pelinggih Ratu Ayu Pangenter
8. Pelinggih Taksu (Dewa Gede Ngurah)
9. Pelinggih Ratu Bagus Mas Pengukiran
10. Pelinggih Ratu Bagus Mas Subandar
11. Pelinggih Taksu (Ratu Bagus Penyarikan)
12. Bale Pesandekan
13. Bale Paselang
14. Bale Ongkara
15. Bale Gegitaan
16. Bale Reringgitan
17. Bale Kulkul
18. Bale Pegat
19. Bale Paninjoan
Piodalan di Pura ini dilaksanakan dua kali setahun masing-masing saat Purnama Desta dan Sasih Kasa Purnama Kasa, Pangelong Ping Tiga (sasih gemuh). Saat odalan atau Purnama Tilem, banyak warga pedek tangkil ke pura ini untuk mohon keselamatan. Pura ini memiliki hubungan dengan Pura Bukit Sinunggal di Desa Tajun, Kubutambahan. Setiap ada upacara melasti Ida Batara di Pura Bukit Sinunggal dan Pura-pura lain di Tajun, upacara pemelastian selalu diselenggarkan di Pura Ponjok Batu karena di sana terdapat sumber air tawar yang memiliki kesucian dan dikatakan sebagai air campuhan antara air darat dan laut.
Keluarga Besar ISI Denpasar Adakan Tirtayatra, Selengkapnya

by admin | Jul 20, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman Bayu Suyasa, Mahasiswa PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman Bayu Suyasa, Mahasiswa PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Judul buku : GAMELAN DIGUL di balik sosok seorang pejuang (hubunga antara Australia dan revolusi Indonesia)
Penulis : Margaret J. Kartomi
Penerjemah : hersri setiawan
Penerbit : yayasan obor Indonesia
Edisi pertama : juni 2005
YOI : 488.23.8.2005
Desain cover : adjie Soeroso
Tebal halaman : 221 halaman
Buku ini mengisahkan tentang nasib seperangkat gamelan Jawa yang merupakan satu-satunya jenis dari perangkat ini karena dibuat di kamp tahanan, dahulu Niugini barat, atau yang sekarang dikenal sebagai irian atau papua barat. Perangkat gamelan ini juga merupakan perangkat gamelan pertama yang diketahui di bawa ke Australia, dan sekarang dirawat dengan baik di Archive of the scool of music konservatorium di monash university. Gamelan ini dibuat tahun 1927 oleh seorang pengerawit atau pemusik jawa “ahli” dari Surakarta, juga seorang tokoh aktivis poltik yang menjadi tawanan di kamp para tapol pemerintah belanda di tanah merah digul atas, di wilayah hindia belanda dahulu. Gamelan-gamelan ini sama sekali dibuat dari bahan-bahan seketemunya saja.
Berkaitan dengan kisah gamelan ini dikaitkan juga dengan dua kisah yang bersifat sebagai pelengkap, dan sementara itu juga merupakan kisah-kisah yang berpadanan. Yang pertama tentang riwayat hidup sang pengrawit, bapak pontjopangrawit; yang kedua mengisahkan tentang peranan gamelan itu sebagai lambabg persahabatan Australia-indonesia semasa dasawarsa pergolakan tahun 1940-an.
Hubungan Australia dengan Indonesia 1943 hingga sekarang. Marilah kita kembali ke digul atas sekitar tahun 1940-an. Ketika perang dunia II mulai perang di asia pun menyusul pecah, kisah gamelan digul memasuki babak baru. Kekuasaan belanda memasuki saat-saaat terakhir kekuasaannya. Sesudah kegiatan periode ekonomi di hindiaa belanda dalam tahun 1930-an dilewati secara damai, jepang menyerang pearl harbor, hongkong, dan Malaya pada tanggal 7/8 desember 1941. Menggabungkan diri dengan kekuatan sekutu, belanda menyatakan perang terhadap jepang. Invasi jepang terhadap hindia dimulai pada tanggal 10 januari 1942. Dengan cepat dihancurkannya armada gabungan belanda, inggris, amerika dan Australia pada pertempuran di laut jawa. Dengan kapitulasi belanda pada tanggal 8 maret 1942 pemerintah colonial di hindia tamat rawayatnya, dan suatu badan resmi hindia belanda mengungsi ke Australia, dengan Charles O. van der plas sebagai kepala perwakilan badan ini. Tapi pada akhir tahun 1943 pemerintah belanda di pengasingan (Inggris) menujuk menteri jajahan, yaitu Dr. H.K. Van Mook, sebagai letnan gubernur jendral dan mengepalai permerintahan sementara hidia belanda di Australia itu (O’Hare dan Reid 1995:6).
Kira-kira akhir tahun 1942 jepang hampir menaklukkan ham[ir seluruh wilayah hindia belanda, walaupun idak seluruhnya pernah berhasil menduduki nuigini belanda (papua). Dan evakuasi pun dilakukan dimulai pada 9 maret dan selesai pada 10 juni 1943. Serdadu-serdadu Australia diterbangkan ke tanah merah dengan pesawat terbang air (flying boat; gambar 24), yang mendarat di sungai digul, dan menerbangkan para tawanan bergelombang 15 sampai 20 kelompok, ke pemukiman karantina Australia di pulau Horn, dekat pulau Thursday di selat torres (Bondan 1992:183-184). Selain itu kira-kira 120 orang Indonesia, termasuk 70 tawanan, diangkut dengan kapal dari merauke ke pulau horn dengan kapal tangker milik belanda, “minyak’. Gamelan digul dikemas dengan sebaik-baiknya dan diangkut bersama dengan barang-barang milik para tahanan menuju pulau horn itu (bondan 1992:185-186).
Disana mereka dibagikan baru yang hangat (warna merah celupan , yaitu warna dari penduduk dari negeri musuh), sebagai ganti pakaian mereka yang suda compang-camping. Dengan kereta api khusus kemudian mereka diangkut ke Cowra, New south Wales. Atas anjuran belanda mereka diperlakukan seperti tawanan dari negeri yang sedang berperang denagan Australia. Seperti yang mereka lakukan di tanah merah, disini juga merekapun bermain gamelan, sehingga karena itulah mereka mempunyai kekuatan untuk bertahan terhadap cobaan-cobaan hidup yang lebih berat(ibu Dahlan, komonikasi pribadi). Sesudah mata dunia mengetahui bahwa orang-orang Indonesia ini merupakan benar-benar tapol belanda yang tak tahu menahu tentang urusan perang dunia, apalagi pembantu orang jepang seperti bagaimana yang dituduhkan oleh belanda, pemerintah Australia menyadari telah menawan mereka secara tidak sah.
Jadi, orang-orang eks-digulis itu menggunakan sebagian waktu mereka untuk memperdalam pengatauan mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka sendiri tentang kebudayaan Indonesia di Melbourne. serta mempergelarkannya di hadapan penduduk public Australia. Pertunjukan-pertunjukan ini membuka mata orang-orang Australia untuk pertama kalinya tentang indah dan rumitnya seni pertunjukan Indonesia, sehingga memperkuat perhatian terhadap kegiatan politik Pro-republik Indonesia. Darisanlah berawal hubungan baik antara Indonesia dengan Australia yang sepintas diperkuat oleh gamelan digul jawa yang dibawa ke Australia.
Buku ini sangat cocok dibaca oleh semua orang yang senang akan sejarah tentang kuatnya kebudayaan Indonesia untuk masyarakat Indonesia sendiri, Karena cerita dari buku ini sendiri sangat menarik sehingga tentunya tidak akan membosankan untuk dibaca. Berikut juga dilengkapi dengan foto-foto arsip terdahulu.
Resensi Buku Gamelan Digul, selengkapnya

by admin | Jul 19, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Drs. I Wayan Mudra, MSn., Dosen PS Kriya Seni ISI Denpasar
Kiriman: Drs. I Wayan Mudra, MSn., Dosen PS Kriya Seni ISI Denpasar
Agar dapat mengenal lebih dekat dan mendetail budaya Bali yang beragam , perlu juga mengetahui budaya yang berlaku secara umum baik dari segi tingkah laku (kelakuan) maupun benda-benda (tanda budaya) lainnya untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi suatu perbedaaan. (T.O. Ihromi, 1996: xxiii). Konsep desa,kala,patra, dan kuna dresta, maupun desa/drsta mawa cara, adalah prinsip yang sampai saat ini masih berlaku bahkan oleh komunitas maupun lembaga-lembaga terkait cenderung untuk dipertahankan. Keragaman budaya yang ada/ dimiliki oleh masing-masing komunitis desa pekraman telah memperkaya dan memberi keindahan tersendiri bagi masyarakat Bali. Bentukan budaya “baru” dari keragaman komunitas terhadap penggunaan sarana keagamaan seperti; umbul-umbul, kober, bandrangan, tumbak, mamas, payung pagut, payung robrob, Penawesange, dan Dwaja
tidak terlepas dari adanya interaksi dan internalisasi pendukungnya. Secara kultur keragaman budaya berada dalam ruang interaksi dan internalisasi nilai-nilai yang memiliki pandangan berbeda, bahwa kolektivitas atau komunitas menentukan anggotanya, pandangan lainnya adalah anggota menentukan kebersamaan. (Mudji Sutrisno, 2009:140). Sejalan dengan pendapatnya Mudji Sutrisno, tentang timbulnya budaya baru dalam kehidupan masyarakat khususnya tentang keseragaman dalam keragaman sarana upacara keagamaan tidak lepas dari keinginan dan rasa tanggung jawab untuk melestarikan tradisi yang sesuai dengan jiwa jamannya. Sudah tentu pula dalam upaya pelestarian nilai-nilai sakral religius magis tersebut dibarengi dengan kondisi perkembangan jaman yang ada.
Adanya kemajuan teknologi, dominasi budaya, serta dinamika terpadu telah membentuk komunitas yang terwujud bukan oleh lingkungan tempat lingkungan itu berada. (David Kaplan dan Albert A. Manners, 1999: 241-242). Jadi budaya itu memang tidaklah statis, dapat bertahan dan berkembang sesuai dengan jamannya. Bali yang sarat dengan prosesi ritual religius keagamaan sekaligus sebagai daerah tujuan wisata secara tidak langsung telah bersentuhan dengan budaya baru sesuai adat kebiasaan daerah/negaranya masing-masing. Atau atas kemauan masyarakat/komunitas pramuwisata yang dengan “sengaja” memanjakan para wisatawan dengan menyajikan seni budaya yang mengandung nilai sakral sebagai daya tariknya. Tidak jarang belakangan ini dijumpai sarana upacara keagamaan yang lengkap dengan atributnya berada di tempat-tempat umum.
Dalam transformasi kebudayaan Bali, I Wayan Geriya mengungkapkan, perubahan bentuk kebudayaan berimplikasikan dan mempunyai aspek yang sangat besar dan luas. Cakupan itu tidak saja berupa dimensi, cara, jaringan relasi fungsional, juga struktur yang terkait dengan pembesaran skala secara horizontal dan vertikal, tanpa meninggalkan esensi jati diri kebudayaan yang berkelanjutan. Lebih lanjut dianalogikan seperti kupu-kupu dengan proses transformasi biologisnya, dari perubahan telur menjadi ulat, kepompong hingga menjadi kupu-kupu yang dapat terbang bebas karena ada perubahan bentuk dan fungsi, namun tetap dalam esensi spesiesnya, tidak berubah ke spesies burung maupun yang lainnya. (I Wayan Geriya, 2000 : 109). Apa yang diungkapkan dalam tronspormasi budaya memang sulit dihindari, namun dalam penelitian ini adanya simbol-simbol/atribut keagamaan yang digunakan ditempat ibadah dan disakralkan digunakan ditempat lainnya/diluar pura.
Kronologis kebudayaan Bali, kalau ditinjau dari persepektif historis, dapat dirunut menjadi tiga tradisi pokok, yaitu tradisi kecil, tradisi besar, dan modern. Tradisi kecil yang dimaksud adalah kebudayaan yang berorientasikan Bali lokal dengan ciri-ciri tertatanya sistem pengairan oleh kelompok-kelompok organisasi nonformal yang disebut subak dan berternak dengan tujuan untuk keperluan upacara maupun memenuhi kebutuhan keluarga serta membuat barang-barang/peralatan rumah dan sarana keagamaan. Dalam tradisi besar telah terjadinya akulturasi antara kebudayaan Bali lokal dengan kebudayaan Hindu Jawa yang melahirkan kebudayaan Bali tradisi. Ciri-cirinya adalah adanya kekuasaan terpusat lewat konsep Dewa Raja. Raja dianggap sebagai inkarnasi Dewa dengan segala kelebihannya dibandingkan rakyat kebanyakan. (I Wayan Geriya, 2000 : 2).
Terbentuknya Budaya Bali Tradisi diikuti pula terjadinya sistem penanggalan (kalender Hindu-Jawa) arsitek dan kesenian yang bermotif Hindu dan Budha. Kebudayaan Bali tradisi ini sebuah refleksi dari budaya ekpresif, dominannya nilai religius, nilai estetis dan solidaritas, sebagai inti kebudayaan Bali. Perbedaan antara bagian inti suatu kebudayaan dengan bagian perwujudan lahirnya, dapat dilihat dari beberapa ciri seperti yang ada pada inti kebudayaan misalnya: 1). Sistem nilai, 2). Keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, 3). Adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, 4). Adat mempunyai fungsi yang terjaring dalam masyarakat, sedangkan bagian akhir dari suatu kebudayaan fisik, alat-alat, benda-benda yang berguna, ilmu pengetahuan, tata cara dengan segala tekniknya, untuk memberi kenyamanan. (Koentjaraningrat, 1990: 97). Bagian akhir dari terbentuknya kebudayaan yaitu kebudayaan fisik, oleh masyarakat Bali masih terpelihara dan dirawat dengan baik. Kiat-kiat perawatan dan pelestarian warisan tersebut dilakukan dalam bentuk upacara ritual yang disebut dengan otonan atau odalan yang datangnya enam bulan sekali / 210 hari sekali. Khusus bagi masyarakat Hindu di Bali, selain diwariskan kebudayaan berbentuk fisik, yang lebih berharga dan bermanfaat adalah adanya suatu tatanan dan tuntunan “wajib” cara-cara atau alokasi waktu perawatan/pemeliharaan secara berkelanjutan.
Budaya Bali selengkapnya

by admin | Jul 19, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: I Ketut Baskara Program Studi Desain Komunikasi Visual Jurusan Desain ISI Denpasar
Kiriman: I Ketut Baskara Program Studi Desain Komunikasi Visual Jurusan Desain ISI Denpasar
I Poster
Pada sub ini mahasiswa akan membahas tentang visualisasi desain pembuatan media promosi Poster yang digunakan sebagai salah satu media komunikasi visual sebagai sarana promosi Aromas Café di Jalan Legian Kuta-Bali.
Unsur Visual Desain
1. Bentuk Fisik
Bentuk fisik dari promosi poster ini persegi panjang dan mempunyai ukuran 42 x 30 cm. Ukuran dibuat dalam ukuran kertas A3 agar poster lebih jelas terlihat, walaupun jika dilihat dari jarak yang agak jauh.
2. Ilustrasi
Dalam desain media poster ini, ilustrasi yang dipergunakan adalah gambar brokoli sebagai background, gambar dari salah satu menu di Aromas Café, serta logo dari Aromas Café itu sendiri.
Menggunakan background brokoli agar memberi kesan hijau yang merupakan cirri khas warna sayuran. Gambar salah satu menu di Aromas Café yaitu Aromas Pizza karena merupakan salah satu menu andalan di Aromas Café. Menggunakan gambar logo Aromas Café agar masyarakat mengetahui identitas dari Aromas Café itu sendiri. Selain itu juga digunakan gambar dari tampak depan Aromas Café agar masyarakat mengetahui seperti apa rupa bangunan Aromas Café.
3. Teks
Pada media poster ini, menggunakan teks berupa slogan “healthy vegetarian cuisine“, dimana memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di Aromas Café menyediakan masakann vegetarian yang menyehatkan. Sedangkan copy text menampilkan sedikit informasi tentang Aromas Cafe. Serta teks “Enjoy The Sight of a Comfortable Romantic Garden Restaurant” dimana menunjukan bahwa lingkungan di Aromas Café sangatlah asri karena terdapat banyak tanaman.
4. Huruf / Typografi
Desain media promosi ini menggunakan dua jenis huruf atau typografi, yaitu: Vivaldi, serta Arial. Jenis typografi tersebut diatas dikomposisikan menurut ukuran dan keseimbangan guna mendapatkan kesatuan serta ritme yang tepat dimana nantinya dapat memberikan keseimbangan informasi yang dinamis.
5. Warna
– Untuk background menggunakan warna hijau kekuningan.
Penggunaan warna hijau kekuningan pada background disesuaikan dengan tema yang diangkat, yaitu tentang vegetarian yang sangat terkait dengan sayuran.
– Untuk kotak tempat tulisan memakai warna orange dari wortel dan juga agar lebih atraktif
– Logo Aromas Café menggunakan warna kuning serta biru.
Warna kuning merupakan warna yang menarik mata dibanding dengan warna lainnya serta membangkitkan nafsu makan, kemudian warna biru lebih berhubungan dengan ketenangan dan meditasi yang selalu dikaitkan dengan iman dimana yang menjadi salah satu alasan seseorang untuk menjadi seorang vegetarian adalad untuk melatih kesabaran iman. Sehingga kedua warna tersebut diharapkan mampu menunjukan bahwa Aromas Café adalah sebuah restoran vegetarian.
– Tulisan menggunakan warna putih dan coklat tua.
Warna putih pada tulisan ini digunakan karena merupakan warna netral sehingga tidak terpengaruh oleh warna lain. Begitu juga warna coklat yang merupakan salah satu warna tanah. Merupakan salah satu warna alam selain warna hijau.
6. Bahan
Desain media poster ini menggunakan bahan art paper 150 gsm. Kertas art paper 150 gsm dipilih karena memiliki kualitas yang bagus.
7.Teknik Cetak.
Untuk mewujudkan poster dalam jumlah banyak, cetak offset dipilih karena harganya relatif lebih murah dan lebih bagus daripada teknik cetak lainnya.
Kreatif Desain
Kreatif desain merupakan proses kreatif yang terdiri dari layout/gambar kasar dan gambar detail, serta mempertimbangkan indikator serta unsur-unsur desain dan bobot penilain desain sebagai acuan desain terpilih. Dalam proses kreatif desain poster ini, dibuat 3 alternatif desain.
Desain poster ini dipilih karena jika dibandingkan dengan 2 alternatif desain yang lainnya, tata letak dalam desain ini dianggap lebih menarik, lebih banyak memenuhi kriteria desain serta paling sesuai dengan konsep perancangan yang digunakan yaitu “natural”. Teks yang digunakan dalam desain ini berupa slogan promosi yang singkat, jelas dan informatif. (untuk lebih jelasnya lihat lampiran).
Poster, X-Baner, Dan Flyer Sebagai Sarana Promosi Aromas Café Di Legian Kuta Bali, selengkapnya

by admin | Jul 18, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Arik Wirawan, Mahasiswa PS Seni Karawitan ISI Denpasar
Kiriman: Arik Wirawan, Mahasiswa PS Seni Karawitan ISI Denpasar
JUDUL BUKU : Inkulturasi Gamelan Jawa Studi Kasus Di Gereja Katolik Yogyakarta
PENULIS : Sukatmi Susantina
PENGANTAR : Prof.Dr. Timbul Haryono, M.Sc.
EDITOR : Purwadi
CETAKAN : I, 2001
PENERBIT : MedPrint Offset
TEBAL : XIV.,112 Halaman
Buku Inkulturasi Gamelan Jawa Studi Kasus Di Gereja Katolik Yogyakarta, karya Sukatmi Susantina menyajikan berbagai gambaran tentang proses inkulturasi di Gereja-gereja Katolik Yogyakarta yang mengadopsi Gamelan Jawa sebagai musik Gerejani. Inkulturasi dalam arti luas berarti sejenis penyesuaian dan adaptasi kepada masyarakat, kelompok umat, adat, kebiasaan, perilaku pada suatu tempat.
Pada kasus Inkulturasi ini adalah proses umat setempat menghayati Injil Yesus Kristus dalam situasi dan kebudayaan setempat, jadi mereka tidak merasa asing dari kebudayaannya sendiri. Sumbangan seperti ini tidak akan merusak hakikat Gamelan Jawa, malahan akan menempatpatkannya pada status dan fungsi keagamaan yang lebih tinggi. Inkulturasi yang terjadi di gereja Katolik kiranya dapat kita pelajari sebagai salah satu model perjalan kehidupan berbudaya dan membudaya, jika kita tidak ingin kehilangan budaya yang pernah kita miliki. Budaya kita yang dibangun oleh leluhur kita dengan melibatkan seluruh potensi kemampuan yang ada seharusnya tidak begitu saja kita singkirkan karena kita telah merasa mendapat budaya lain hasil pergaulan yang semakin luas ini. Inkulturasi bukanlah suatu tujuan, melainkan suatu proses, atau menempatkan dan mengadopsi budaya setempat dan dapat terekspresikan dalam bermacam-macam penghayatan agama. Sebagai suatu proses, inkulturasi tidak pernah mandeg, sejalan dengan kebudayaan selalu berkembang.
Buku yang memuat V BAB ini juga mengungkapkan langkah-langkah inkulturasi di Indonesia, khususnya di Jawa, inkulturasi gending didalam ibadat sudah dirintis tahun 1925 di sekolah pendidikian guru Muntilan oleh C. Hardjosoebroto, atas dorongan Br.Clementius ia memberanikan diri mengarang beberapa gending Gereja dalam bahasa Jawa dengan tangga nada pelog yang dinyanyikan tanpa iringan. Pada tahun 1956, usaha inkulturasi gamelan pertama kali diadakan dan didemontrasikan gending Gereja dengan iringan Gamelan, karangan Atmodarsono dan C. Hardjoesoebroto. Baru setelah Konsili Vatikan II tahun 1962 orkes gamelan dipakai secara utuh dalam mengiringi gending Gereja,
Dalam buku karya Ibu Sukatmi Susantina ini disimpulkan bahwa penggunaan Gamelan Jawa dalam ibadat keagamaan dapat mengungkapkan kepercayaan dan penghargaan umat terhadap Tuhan secara tepat. Buku ini patut dianjurkan untuk dibaca dan menjadi sumber referensi utama bagi para mahasiswa, dosen, seniman kontemporer atau tradisi, kaum terpelajar, pustakawan, wartawan, dan mereka yang yang tertarik kepada masalah-masalah seni dan budaya. Penyajian buku ini cukup sederhana, mudah diikuti, namun tetap bertumpu pada realita dan para pembaca diajak untuk menemukan nilai-nilai adi luhung dari budaya setempat, dipertemukan dengan nilai-nilai religious, untuk saling memperkokoh dan menguatkan.
Resensi Buku: Inkulturasi Gamelan Jawa Studi Kasus Di Gereja Katolik Yogyakarta, selengkapnya

 Kiriman Drs. I Wayan Mudra, MSn., Dosen PS. Kriya Seni ISI Denpasar
Kiriman Drs. I Wayan Mudra, MSn., Dosen PS. Kriya Seni ISI Denpasar