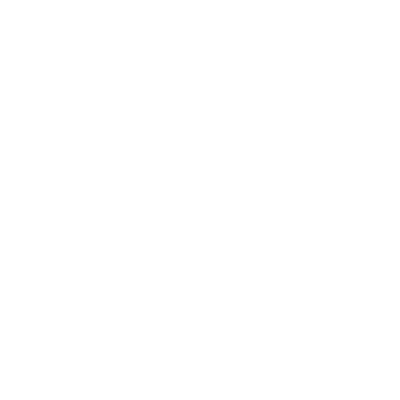by admin | Jul 23, 2011 | Berita
 Kiriman Hery Budiyana, Staf FSRD ISI Denpasar
Kiriman Hery Budiyana, Staf FSRD ISI Denpasar
Gempuran era globalisasi mengharuskan para seniman untuk menguasai potensi serta tidak mengabaikan kearifan lokal yang telah ada. Hal tersebut terungkap dalam Seminar Akademik Fakultas Seni Rupa dan Desain, yang dilaksanakan tadi pagi (22/7), bertempat di gedung Lata Mahosadi ISI Denpasar. Seminar sehari dalam rangka Dies Natalis VIII serta Wisuda Sarjana IX, bertemakan “Reinterpretasi Local Genius dalam perkembangan seni rupa dan desain mutakhir.” Rektor ISI Denpasar, Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A yang hadir sekaligus membuka acara seminar tersebut mengungkapkan bahwa dengan diadakannya seminar ini menunjukkan atmosfir akademik di ISI Denpasar berkembang, dan ini merupakan sinyal positif, karena tema yang diangkat sesuai dengan tujuan dan visi misi kampus ISI Denpasar yakni menuju kampus berunggulan lokal dan bertaraf internasional. “Berkaitan dengan tema seminar kali ini, sehubungan dengan Local Genius, kita harus menguasai potensi atau kearifan local sebelum berfikir atau bertindak secara global”, ungkap Prof Rai.
Sementara Dekan FSRD ISI Denpasar, Dra. Ni Made Rinu, M.Si menyambut baik dukungan Rektor dan menyampaikan bahwa ini adalah sebuah perkembangan yang baik dan memacu para dosen untuk selalu rajin memperbaharui penelitian maupun tulisannya agar dapat dijadikan makalah dalam seminar.
Seminar diikuti oleh dosen, pegawai, serta mahasiswa dari lingkungan ISI Denpasar, menghadirkan pemakalah yaitu I Wayan Kun Adnyana, S.Sn., M.Sn, I Ketut Sida Arsa, S.Sn, Cok Istri Ratna Cora S, S.Sn.,M.Si, I Nyoman Larry Julianto, S.Sn.,M.Ds dan I Made Bayu Pramana, S.Sn., M.Sn, dengan moderator Drs. I Ketut Buda, M.Si. Pemakalah I Wayan Kun Adnyana, S.Sn., M.Sn mengambil judul “Wacana ‘Ketradisian’ dalam Medan Seni Rupa kontemporari.” Mengangkat tema yang berhubungan dengan seni lukis, film, dan pameran. Dimana salah satu film Eat, Pray, and Love mengangkat ketradisian di tiga negara yaitu Italia, India, dan Bali dalam wahana seni kontemporer. Local genius yang berhubungan dengan seni rupa adalah adanya Desa,Kala,Patra yang sejajar dengan pengertian laku, nilai, dan karya serta berhubungan dengan konteks ruang, waktu, dan keadaan. Pemakalah I Ketut Sida Arsa, S.Sn mengambil judul “Wadah Sebagai objek Komoditas di Kota Denpasar.” Menurut I Ketut Sida Arsa, pada jaman dahulu jika ada orang meninggal dunia barulah dibuat wadah, namun saat ini kebutuhan ini telah bergeser, dimana wadah telah disiapkan terlebih dahulu kemudian menunggu konsumen untuk memesannya. Hal inilah akibat dari pencitraan produk sehingga saat ini barang yang mengontrol konsumen/pembeli. Selanjutnya Cok Istri Ratna Cora S, S.Sn.,M.Si menyampaikan presentasi dengan judul “Implementasi Think Globally & Act Locally dalam ranah desain kekinian terhadap eksistensi local genius”. Terungkap bahwa penelitian berkaitan dengan kain dan warna hingga ke daerah-daerah terpencil untuk menemukan identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat yang kemudian dibawa ke dalam desain teknologi yang berkembang saat ini. I Nyoman Larry Julianto, S.Sn.,M.Ds mengangkat judul “Reinterpretasi local genius dalam perkembangan seni rupa dan desain mutakhir.” Dalam kesempatan ini ia mengatakan bahwa lokal genius tidak harus dari luar tetapi juga bisa digali dari dalam diri manusia atau yang disebut dengan potensi diri. Potensi diri kemudian digunakan untuk mengembangkat visualisasi yang bergerak kea rah modern seperti penggunaan media Ambient advertising. Dan pemakalah terkhir I Made Bayu Pramana, S.Sn., M.Sn mengangkat judul “Levitasi local genius dalam berkarya fotografi.” Bayu menyampaikan bahwa fotografi tidak terlepas dari mengabadikan momen yang tepat, dalam kesempatan ini diangkatlah konsep mengenai pralina, dimana hal ini bisa diamati dalam sebuah bongkahan mobil yang telah usang, kemudian foto-foto detail mengenai karat ini pun diambil. Selain itu konsep pralina juga diambil dari mengamati bongkahan kayu yang mulai membusuk dan didapatlah hasil karya seni yang mutakhir.

by admin | Jul 23, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: I Gde Made Indra Sadguna, Alumni ISI Denpasar
Kiriman: I Gde Made Indra Sadguna, Alumni ISI Denpasar
Pengantar
Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menyimpan berbagai macam kekayaan kesenian. Tiap pulau dari Sabang hingga Merauke memiliki keunikannya tersendiri. Salah satu pulau di bagian timur Indonesia yang memiliki alat musik yang khas terdapat di Pulau Nusa Tenggara Timur. Jenis alat musik yang cukup dikenal di daerah tersebut adalah alat musik Sasando. Perangkat musik ini tergolong dalam perangkat dawai petik. Hal ini disebabkan karena perangkat ini mempergunakan dawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Walaupun dalam permainan musik ini menggunakan vokal, akan tetapi tetap digolongkan dalam perangkat dawai petik sebab kategori vokal nanti akan menjelaskan musik-musik yang memang khusus suara manusia saja tanpa melibatkan instrumen dan jenis-jenis instrumen yang mengiringi dan menjadi bingkai dari lagu vokal itu.
Perangkat Musik Sasando
Perangkat musik Sasando merupakan salah satu jenis alat musik yang cukup dikenal di Pulau Nusa Tenggara Timur. Setidaknya ada dua jenis Sasando, yaitu yang berasal dari daerah Rote dan Sabu. Kedua daerah tersebut merupakan daerah yang kering dan gersang. Hanya bisa ditumbuhi oleh beberapa jenis tumbuhan saja, salah satunya adalah pohon lontar. Oleh masyarakat setempat, pohon lontar banyak dimanfaatkan. Buahnya dibuat gula dan minuman, daunnya dapat dibuat sebagai atap, tempayan, ember, dan juga salah satu yang menarik adalah dibuat sebagai resonator dari Sasando itu sendiri.
Daun lontar yang telah cukup berumur akan dimasak untuk membuat resonator Sasando. Daun akan diikatkan satu sama lainnya. Rangkaian dari daun-daun tersebut akan menghasilkan bentuk menyerupai separo bejana yang tengahnya menggembung seperti periuk. Di tengah rangkaian daun tersebut akan dipasangkan sebuah bambu atau kayu yang panjangnya sekitar 40cm, dengan diameter selitar 11cm, dan dipasangkan dengan sepuluh hingga 12 dawai. Agar dapat berbunyi, setiap dawai diberikan senda yang terbuat dari kayu atau bambu dan berfungsi untuk menegangkan dan mengangkat dawai.
Secara harafiah, Sasando menurut asal katanya dalam Bahasa Rote (sasandu), berarti bergetar atau berbunyi. Mengenai awal kemunculan alat musik Sasando belum dapat diketahui secara pasti, akan tetapi ada sebuah legenda yang menceritakan mengenai kemunculan alat musik Sasando tersebut. Konon ada seorang pemuda bernama Sangguana di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Suatu hari ia menggembala di Padang Sabana. Ketika merasa lelah dan mengantuk, ia pun tertidur di bawah pohon lontar. Dalam tidurnya, ia bermimpi memainkan sebuah alat musik misterius. Ketika terbangun ia masih mengingat nada-nada yang dimainkannya. Akhirnya berdasarkan mimpi tersebut, Sangguana memutuskan untuk membuat sebuah alat musik dari daun lontar dengan senar-senar di tengahnya.
Secara umum, Sasando berfungsi sebagai sarana hiburan masyarakat. Musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Umumnya masyarakat Indonesia sangat antusias dalam menonton pagelaran musik. Jika ada perunjukan musik di daerah mereka, mereka akan berbondong- bondong mendatangi tempat pertunjukan untuk menonton.
Unsur Musikal
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada dua jenis Sasando yang berkembang yaitu di daerah Rote dan Sabu. Ada beberapa perbedaan dan persamaan yang dapat ditemui pada alat musik Sasando di kedua daerah tersebut. Adapun persamaannya adalah sama-sama mempergunakan instrumen Sasando dan dalam pementasannya diiringi oleh vokal.
Perbedaannya mencakup beberapa hal seperti Sasando Rote mempergunakan sebuah tambur kecil sedangkan pada Sasando Sabu tidak mempergunakan tambur. Tambur dimainkan dengan menggunakan alat pemukul kecil. Petikan dari Sasando Rote mempunyai pola yang sama secara terus – menerus, dengan iringan vokal dari penyanyi akan tetapi tidak terikat dengan melodi Sasando.
Pada Sasando Sabu yang tidak menggunakan tambur, petikan dawainya mempunyai variasi yang lebih kompleks dari Sasando Rote. Selain itu, petikan Sasando mengikuti vokal dari penyanyi. Sehingga antara petikan Sasando dengan vokal sangat terkait.
Musik Tradisi Pulau Nusa Tenggara Timur, selengkapnya
by admin | Jul 22, 2011 | Berita, pengumuman
Pengumuman Pengumpulan Magang : Klik disini
PENGUMUMAN
Nomor : 1645/IT5.5.1/KM/2011
Tanggal 21 Juli 2011
PENGUMPULAN LAPORAN MAGANG
PROGRAM MAHASISWA WIRAUSAHA
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2011
Diumumkan kepada mahasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar penerima Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Tahun 2011 (nama-nama terlampir) agar segera :
1. Mengumpulkan laporan Magang ke Sub Bagian Kemahasiswaan ISI Denpasar Gedung Rektorat lantai Satu, sampai
tanggal 29 Juli 2011.
2. Mengambil uang transport Magang
3. Mengambil kontrak kerja PMW yang sudah ditanda tangani.
Demikian disampaikan agar segera laksanakan.
an. Rektor
Pembantu Rektor III
ttd
Drs. I Made Subrata,M.Si
NIP.195202111980031002
Tembusan :
1. Rektor sebagai laporan.
2. Dekan FSRD untuk diketahui
3. Dekan FSP untuk diketahui

by admin | Jul 22, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: I Ketut Baskara Program Studi Desain Komunikasi Visual Jurusan Desain ISI Denpasar
Kiriman: I Ketut Baskara Program Studi Desain Komunikasi Visual Jurusan Desain ISI Denpasar
I. T-Shirt
Pada sub ini mahasiswa akan membahas tentang visualisasi desain pembuatan media promosi T-Shirt yang digunakan sebagai salah satu media komunikasi visual sebagai sarana promosi Aromas Café di Jalan Legian Kuta-Bali.
Unsur Visual Desain
1. Bentuk Fisik
Bentuk fisik dari media t-shirt ini adalah menyerupai huruf T.
2. Ilustrasi
Dalam desain media t-shirt ini, ilustrasi yang dipergunakan adalah ilustrasi sayur-sayuran dan logo Aromas Cafe yang dimaksudkan untuk memberi kesan simple. Diharapkan nantinya pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat tersampaikan.
3. Teks
Desain media spanduk ini menggunakan teks berupa slogan “healthy vegetarian cuisine“, dimana memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di Aromas Café menyediakan masakann vegetarian yang menyehatkan.
4. Huruf / Typografi
Desain media promosi ini menggunakan dua jenis huruf atau typografi, yaitu: Vivaldi, serta Arial. Jenis tipografi tersebut diatas dikomposisikan menurut ukuran dan keseimbangan guna mendapatkan kesatuan serta ritme yang tepat dimana nantinya dapat memberikan keseimbangan informasi yang dinamis.
5. Warna
Dalam desain t-shirt ini menggunakan warna kuning kehijauan. Warna ini dipilih berdasarkan salah satu konsep dari perancangan media ini karena merupakan salah satu warna yang menggambarkan alam dan sayuran.
6. Bahan
Desain media t-shirt ini menggunakan bahan kain cotton.
7. Teknik Cetak
Untuk mewujudkan media t-shirt ini menggunakan teknik cetak sablon.
Kreatif Desain
Kreatif desain merupakan proses kreatif yang terdiri dari layout/gambar kasar dan gambar detail, serta mempertimbangkan indikator serta unsur-unsur desain dan bobot penilain desain sebagai acuan desain terpilih. Dalam proses kreatif desain t-shirt ini, dibuat 3 alternatif desain.
Desain t-shirt ini dipilih karena jika dibandingkan dengan 2 alternatif desain yang lainnya, tata letak dan ilustrasi dalam desain ini dianggap lebih simple sehingga informasi yang disampaikan lebih cepat tersampaikan, lebih banyak memenuhi kriteria desain serta paling sesuai dengan konsep perancangan yang digunakan yaitu “natural”. Teks yang digunakan dalam desain ini berupa slogan promosi yang singkat, jelas dan informatif. (untuk lebih jelasnya lihat lampiran)
Tampilan Desain
Dari hasil alternatif desain, dapat ditampilkan desain terpilih sebagai berikut:
Nama Media : T-Shirt
Ukuran : S (small), M (medium), L (large), XL(Xtra Large)
Bahan : Kain Cotton Combed 20 S
Huruf : Vivaldi, Arial
Teknik : Cetak sablon
Dalam desain media promosi t-shirt ini, ilustrasi yang dipergunakan adalah sayuran dan logo Aromas Cafe yang dimaksudkan untuk memberi kesan simple. Diharapkan nantinya pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat tersampaikan.
T-Shirt dan Daftar Menu sebagai Sarana Promosi Aromas Café Di Legian Kuta Bali Selengkapnya

by admin | Jul 21, 2011 | Artikel, Berita
 Kiriman: Kadek Suartaya, SSKar., Msi, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar.
Kiriman: Kadek Suartaya, SSKar., Msi, Dosen PS Seni Karawitan ISI Denpasar.
Pertunjukan dengan mengenakan topeng merupakan seni pentas tertua di jagat ini. Hampir setiap bangsa di berbagai pelosok dunia mempunyai benda seni penutup wajah dalam berbagai wujud dan watak. Kiranya hingga kini pun topeng-topeng itu masih menjadi bagian tradisi atau ekpresi estetik masyarakat manusia. Bahkan pada masyarakat yang masih lekat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, topeng bukan hanya dipandang sebagai sekedar penutup wajah namun dianggap memiliki kekuatan magis. Sedangkan keberadaan topeng pada masyarakat modern selain tetap diusung sebagai benda seni juga dikembangkan sebagai bentuk seni pertunjukan tari atau teater.
Masyarakat bhineka Indonesia memiliki beragam seni tari dan teater yang dalam penampilannya mengenakan topeng. Masyarakat suku Dayak di Kalimantan mewarisi topeng Hudoq yang biasanya hadir sebagai seni sakral dalam ritual keagamaan mohon kesuburan atau syukuran atas panen yang melimpah. Masyarakat desa Trunyan di tepi danau Batur, Bangli, hingga kini juga mengeramatkan pantomime bertopeng yang disebut Barong Berutuk. Teater menggunakan topeng berwajah primitip yang terbuat dari batok kelapa ini merupakan ritual mohon kesuburan. Selain tari topeng untuk mohon kesuburan, topeng di tengah masyarakat Nusantara umumnya dipakai sebagai perantara berhubungan dengan arwah nenek moyang seperti masih terlihat jejak-jejaknya kini pada suku Batak (Sumatera Utara), masyarakat Tolage-Alfur (Sulawesi Tengah), dan suku-suku di pedalaman Papua.
Topeng sebagai seni pertunjukan berkembang subur di Jawa dan Bali. Di pulau Jawa, tari dengan mengenakan topeng sudah dikenal sejak jaman Majapahit. Raja Brawijaya masyur sebagai penari topeng yang piawai. Demikian pula di Bali, tari atau teater dengan mengenakan topeng sudah berkembang pada abad ke-16-17, zaman kejayaan kerajaan Bali. Catatan-catatan tua berupa prasasti atau lontar juga telah menyinggung tentang adanya tari topeng atau kelompok pemain topeng. Batu bertulis Jaha yang ditemukan di pulau Jawa pada tahun 840 Masehi menyebutkan tentang atapukan yang artinya topeng. Di Bali, prasasti Bebetin 896 Masehi juga menyebutkan adanya partapukan yang artinya perkumpulan penari topeng.
Jawa dan Bali adalah dua wilayah budaya di Indonesia yang kaya dengan ekspresi seni tari dan teater yang menggunakan topeng. Di pulau Jawa, wilayah budaya Parahyangan memiliki seni tari dan teater bertopeng yang sangat khas. Masyarakat Sunda di Cirebon dikenal sebagai pewaris seni pertunjukan topeng yang tetap eksis hingga kini. Keberadaan topeng Cirebon patut diketengahkan sebab, menurut pakar tari Jawa, Edi Sedyawati, topeng Cirebon adalah mata air pertumbuhan dari tari-tarian Sunda yang kita kenal sekarang. Di Cirebon dan sekitarnya, tari topeng masih dapat disimak dalam upacara syukuran yang berkaitan dengan budaya pertanian dan perayaaan kebahagiaan perkawinan.
Pada awalnya, topeng Cirebon adalah media untuk menghormati arwah nenek moyang. Dalam perkembangannya, topeng ritual ini mendapat mengayoman kaum bangsawan. Pada masa Cirebon menjadi pusat penyebaran agama Islam, Sultan Cirebon Sunan Gunung Jati bekerja sama dengan Sunan Kalijaga memanfaatkan tari topeng sebagai media komunikasi dalam penyebaran agama. Begitu kuat dan luasnya pengaruh tari topeng sebagai alat siar agama Islam di tanah Pasundan pada masa lalu, hingga memitoskan Sunan Kalijaga sebagai pencipta tari topeng Cirebon. Hingga kini, penghormatan pada Sunan Kalijaga sebagai pencipta tari topeng masih dianut takzim oleh seniman topeng Cirebon.
Topeng Cirebon berorientasi dari cerita Panji, kisah kepahlawan raja-raja Jawa yang banyak dijadikan tema dalam seni pertunjukan tradisi, bukan hanya di Jawa dan Bali tapi juga di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand. Di Negeri Gajah Putih, tokoh protagonis cerita Panji yaitu Inu Kertapati disebut dengan Inao. Di Bali, cerita Panji menjadi tema utama dari drama tari Gambuh, teater klasik sumber tari Bali. Opera Arja yang kini kian sayup tembangnya juga mengacu pada cerita Panji. Teater rakyat Drama Gong pada masa kejayaaan tahun 1970-1980-an juga mengharubiru penonton dengan kisah romantis dan heriok Raden Inu Kertapati dengan kekasihnya Putri Candrakirana. Dalam topeng Cirebon, cerita Panji itu dituangkan dalam bentuk penonjolan seni tari seperti yang terlihat dalam Topeng Babakan dan secara naratif dalam Topeng Dalang atau Wayang Topeng.
Topeng Babakan yang hanya menyajikan potongan-potongan dari cerita Panji, lebih merupakan penampilan simbol-simbol kehidupan manusia lewat karakter 5-8 topeng. Diawali dengan penampilan Topeng Panji menggambarkan watak manusia yang arif, bijaksana dan rendah hati. Kemudian, Topeng Samba menggambarkan watak manusia yang suka hura-hura dan penuh canda. Topeng Tumenggung menggambarkan watak ksatria yang gagah berani dan percaya diri. Topeng Kalana menggambarkan sifat manusia yang tamak dan Topeng Rumyang melambangkan sifat ketakwaaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain kelima tokoh itu ada pula tokoh Aki-aki dan Kedok Cina. Seluruh topeng-topeng itu dibawakan oleh seorang penari seperti Topeng Pajegan di Bali. Dulu masyarakat pecinta tari topeng di Jawa Barat mengenal dua maestro seni pertunjukan ini, yakni Mimi Sawitri dan Mimi Rasinah kini telah tiada.
Masyarakat Bali memiliki beberapa bentuk seni pertunjukan bertopeng. Namun yang lazim disebut topeng adalah adalah seni pentas ritual Topeng Pajegan. Pertunjukan topeng yang umumnya dibawakan secara solo oleh seorang penari ini tidak hanya hadir dalam prosesi keagamaan di halaman utama pura namun juga berfungsi dalam upacara perkawinan, potong gigi, hingga ritus ngaben. Tema-tema kisah yang dibawakan bersumber dari babad, cerita semi sejarah, dengan puncak penampilan figur topeng berkarakter angker yang disebut Sidakarya.
Seni pertunjukan Wayang Wong, Barong Kedingkling, dan Barong Berutuk misalnya, juga memakai tapel tapi tak pernah disebut sebagai topeng. Wayang Wong yang berangkat dari sumber epos Ramayana seluruh pemerannya memakai tapel atau topeng. Barong Kedingkling yang biasanya hadir dalam tradisi ngelawang mempergunakan tapel figur-figur penting Ramayana. Begitu juga Barong Berutuk yang disakralkan di Desa Trunyan, Bangli, semua perannya menggunakan topeng bernuansa primitif. Namun ketiganya tak disebut seni pertunjukan topeng. Rangda dan tari Jauk juga tidak digolongkan genre topeng.
Seni pertunjukan bertopeng tergolong sangat tua dan hampir dapat dijumpai di seluruh dunia. Di Bali, kesenian yang diduga berkaitan dengan topeng termuat dalam prasasti Bebetin yang berangka tahun 869 Masehi. Dalam prasasti itu disinggung istilah partapukan yang artinya perkumpulan topeng. Sedangkan bagaimana bentuk dan apa lakonnya tidak jelas. Pertunjukan topeng diduga merupakan kreativitas seniman Bali yang bukan pengaruh kesenian Majapahit. Pada mulanya kesenian ini muncul pada era kejayaan Gelgel, akhir abad ke-17. Konon I Gusti Pering Jelantik membawakan drama tari seorang diri dengan memakai topeng rampasan leluhurnya, Patih Jelantik, ketika Gelgel menaklukkan Blambangan. Saat konflik politik mengguncang Gelgel, topeng-topeng itu diboyong ke Desa Blahbatuh sekitar tahun 1879 yang hinggi kini dikeramatkan di Pura Penataran Topeng.
Pada tahun-tahun berikutnya, setelah pementasan di puri Gelgel tersebut, penampilan Topeng Pajegan itu kemudian menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Bali, terutama ditradisikan saat prosesi keagamaan, odalan misalnya. Perkembangannya kemudian muncul Topeng Panca, drama tari topeng yang dibawakan oleh lima orang penari yang lebih mengarah sebagai seni pentas tontonan non ritual. Perkembangan ini bukannya membuat Topeng Pajegan surut, justru seni pentas ini kian multifungsi dalam beragam tingkatan dan hirarki upacara agama dan ritus kehidupan masyarakatnya.
Pementasan Topeng Pajegan dimulai dengan penampilan tokoh yang berkarakter keras. Warna tapel-nya gelap kemerah-merahan, mata mendelik dan disertai sepasang kumis hitam tebal. Gerakannnya tangkas, gagah dengan ayunan langkah berwibawa. Sehabis tokoh ini, biasanya disambung dengan kemunculan topeng yang berkarakter tua renta. Rambut, alis, dan kumisnya memutih. Gerakannya lambat terbata-bata namun menampilkan sorot mata yang arif. Kedua figur ini disebut dengan topeng pengelembar, tari lepas, arena tempat pemain mempertontonkan kepiawaannya menari.
Aspek dramatik sebuah pementasan Topeng Pajegan baru bergulir ketika muncul tokoh penasar yang lazim memakai tapel setengah terbuka, terutama pada mulut dan matanya. Penasar bertindak selaku narator, komentator, penterjemah, dan pelawak. Tokoh inilah yang mengendalikan alur cerita. Ketika ia kemudian berganti topeng berwatak tampan dengan tata gerakan alus penuh perhitungan, tokoh rajalah yang dibawakannya yang sering disebut topeng dalem atau arsawijaya. Kehadiran topeng dengan ekspresi karismatis ini memberikan perintah sesuatu, mungkin perang dan mungkin perdamaian.
Topeng Menyingkap Karakter Manusia Dan Sejarah Masyarakat, selengkapnya

 Kiriman Hery Budiyana, Staf FSRD ISI Denpasar
Kiriman Hery Budiyana, Staf FSRD ISI Denpasar