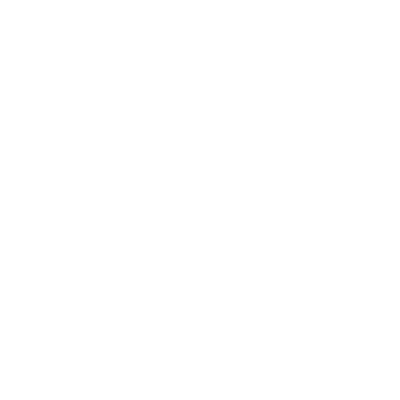by admin | Dec 17, 2015 | Artikel
Kiriman : Kadek Suartaya, SSKar., M.Si (Dosen Jurusan Karawitan ISI Denpasar)
Sebuah diskusi bertema “Menakar Nasib Seni dan Seniman Bali” berlangsung hangat di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Selasa (8/12) siang lalu. Penyelenggaraan diskusi atas kerja sama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI Gede Pasek Suardika, SH,MH dengan pihak ISI itu berlangsung hangat. Mengerucut opini dari para peserta diskusi yaitu belum maksimalnya peran negara pada jagat seni dan seniman. Keberpihakan negara atau pemerintah pada nasib seni dan seniman masih memperihatinkan, yang, sudah seharusnya memberikan pengayoman yang setimpal dengan kemuliaan dan keadaban yang telah dipersembahkan jagat seni dan seniman kepada negara.
Di masa lalu, negara dalam representasi kerajaan menunjukkan perannya sebagai pelindung seni dan seniman yang cukup penting. Pengayom seni dan seniman pada era feodalisme ini memiliki perhatian dan respek yang besar bagi eksistensi jagat kesenian. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak kelahiran dan kebesaran para seniman didukung oleh tradisi perlindungan seni. Juga harus diakui tak sedikit cipta seni dan perjalanan suatu kesenian dikondisikan oleh system maesenas alias pelindung seni dan seniman.
Sejatinya, kedermawanan kepada seniman dan seni adalah dedikasi yang luhur. Betapa tidak. Banyak seniman berbakat dapat menyalurkan segala kemampuan yang dimilikinya karena simpati positif dari sang maesenas. Tak sedikit masterpiece yang menjadi kebanggaan dunia disebabkan oleh kebiasaan memberikan motivasi semangat dan materi dari para dermawan seni. Demikian pula andil para sponsor seni dalam pemeliharaan dan pelestarian ekspresi atau wujud-wujud karya seni.
Kedermawanan dan perlindungan terhadap seni dan seniman Bali dengan jelas dapat kita tarik dari masa keemasan raja-raja. Ini dapat direntang antara abad ke 16-19 pada pemerintahan Dalem Waturenggong (1416-1550), Dalem Bekung (1550-1580), Dalem Sagening (1580-1665), Dalem Dimade (1665-1685). Diduga kuat bahwa seni pertunjukan Bali seperti Gambuh, Topeng, Wayang Wong, Parwa, Arja, Legong Kraton dan seni klasik lainnya tumbuh dan berkembang pada era itu dengan gaya sponsor para penguasa saat itu. Demikian juga yang terjadi pada bidang kesenian lainnya seperti seni rupa, sastra, arsitektur dan lain-lainnya.
Kesenian pada masa itu bukan hanya sebagai hiburan atau bagian ritual semata, namun juga berdimensi politis dan prestise. Maka tak mengherankan bila setiap kraton atau puri memiliki tempat khusus untuk memajang atau mempertunjukan kesenian kebanggaannya sepertinya adanya bale pagambuhan misalnya. Para seniman menjadi insan yang sangat penting dan dibanggakan, dipuji, disayangi, dilindungi, diberikan gaji dan gelar bahkan dijamin masa tuanya.
Drama tari Gambuh yang dianggap sebagai sumber tari Bali rasanya tak mungkin memiliki kualitas seni dan nuansa klasik seperti itu tanpa ada campur tangan dan perlindungan kaum bangsawan. Kisah-kisah yang dituturkan Gambuh adalah romantika disekitar kaum bangsawan yang berisi puji-pujian terhadap para leluhur mereka, keluarga keraton. Lalu, tata penyajian drama tari ini sangat protokoler yang mencerminkan budaya keraton. Karenanya, teater tari yang pernah jadi primadona keluarga puri ini tentu mengalami pengayoman yang begitu asih dari elite penguasa. Kompleksitas ketatnya penyajian tari, sastra dan musiknya jelas mengalami masa perlindungan yang serius dan panjang. Dan para senimannya dari generasi ke generasi tentu juga adalah orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan dan tokoh-tokoh terpandang di tengah masyarakat.
Respek dan kedermawanan terhadap seni dan seniman pada era kejayaan raja-raja dulu dapat pula kita kaji dari eksistensi lukisan gaya Kamasan. Gaya lukisan tradisional Kamasan meskipun pada mulanya adalah “lukisan kaum sudra”, namun sebagai akibat dari patronisasi para bangsawan kerajaan Klungkung terserap menjadi kesenian tradisi agung dari pusat kerajaan di Klungkung. Para maesenas pada zaman kejayaan kerajaan Klungkung selain bangsawan adalah juga para sastrawan yang mumpuni dalam hal agama dan kesenian klasik.
Hanya sayangnya, lehadiran kolonialisme yang menyebabkan berkurangnya bahkan hilangnya kekuasaan dan harta benda kaum bangsawan berpengaruh terhadap perhatian dan kedermawanan mereka terhadap seni dan seniman. Walau masih ada beberapa kaum bangsawan berusaha respek terhadap seni dan seniman namun hanya mampu sebatas apresiator atau pengagum saja. Sebagai dermawan yang memberikan jaminan hidup kepada seniman, mantan penguasa itu tak punya daya dan biaya lagi. Terjadilah kekosongan maesenasisme di Bali.
Kokosongan perlindungan seni dan seniman pasca zaman kerajaan tersebut mengalihkan perkembangan kesenian Bali ke tengah rangkulan masyarakat luas. Mantan seniman istana yang tak mutlak lagi dibawah pengayoman puri dan memiliki dedikasi tinggi terhadap kesenian menjadi pilar-pilar pengembang kesenian yang berpengaruh. Ini berarti wajah maesenas yang tadinya individual menjadi kolektif (masyarakat). Seni dan seniman Bali mendapat perlindungan dari masyarakat dalam wadah sekaa-sekaa kesenian. Baru sejak zaman kemerdekaan, negara atau pemerintah mulai unjuk perhatian, misalnya mendirikan sekolah seni. Idealisme Gubernur Bali Ida Bagus Mantra menggelindingkan Pesta Kesenian Bali (PKB) pada tahun 1979, menjadi salah satu wahana yang mencerahkan dunia seni dan arena berekspresi seniman Bali. Namun demikian, geliat seni dan kehidupan seniman masa kini tampaknya belum merasakan pengayoman kasih tulus dan kepedulian negara seperti pada masa lampau. Kenapa negara atau pemerintah kita terkesan kurang peduli dengan harkat seni dan martabat seniman sang pengawal jati diri bangsanya?
by admin | Dec 17, 2015 | Artikel
Kiriman : Kadek Suartaya, SSKar., M.Si (Dosen Jurusan Karawitan ISI Denpasar)
Sebuah sajian tari kontemporer menambat perhatian penonton pada akhir Mei lalu. Kamis (28/5) malam lalu, para penonton yang memadati pagelaran ujian akhir di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, menyimak penuh antusias karya seni tari bertajuk “Di Balik Boneka”. Dibawakan oleh sepasang penari putra dan putri, tari yang bergulir sekitar 13 menit tersebut menggiring penonton pada fantasi cinta seorang gadis dalam bingkai estetika seni tari yang menggugah, apik, dan unik. Ya, sebuah garapan tari kontemporer yang mengena, terkesan sederhana namun membuat hati terpana.
Tema cinta yang diusung garapan tari ciptaan Anak Agung Istri Inten Pradnyandari ini kisahnya sederhana, yaitu tentang fantasi seorang gadis kepada seorang laki-laki penjaga toko boneka. Namun kesederhanaan kisah ini mampu dituturkan secara naratif dalam ancangan kompleksitas koreografi yang menawan. Kedua orang penari, Inten Pradnyandari sendiri dan Anak Agung Gede Dalem Segara Putra, menunjukkan totalitasnya merangkai laku gerak tubuh, menjelajah ruang dan meniti waktu dalam sinergi dan interaksi yang padu. Imajinasi keindahan cinta sang gadis berpadu mesra dengan rona estetis kontemporer tata garap tarinya.
Ruang untuk merambah tari kontemporer dibuka lebar dalam ujian seniman akademis di ISI Denpasar. Gung Is, demikian sapaan akrab koreografer muda itu, memilih bentuk tari kontemporer, bersama sejumlah temannya. Sebuah pilihan yang kurang populer, jika dibandingkan menggarap cipta tari dengan sumber pijak kreasi dari seni tradisi. Sebab di tengah jagat berkesenian di Bali, garapan seni kontemporer, termasuk dalam dunia seni tari, hingga kini masih megap-megap keberadaannya. Penonton, masyarakat Bali pada umumnya, belum begitu banyak melirik aksi-aksi tari kontemporer. Simaklah di arena PKB, pementasan garapan seni pertunjukan kontemporer, kalau ada, tidak begitu diperhitungkan.
Diperhitungkan atau tidak, di ISI Denpasar, tari kontemporer tak pernah henti menggeliat. Dalam setiap pagelaran ujian akhirnya, baik untuk strata S1 maupun S2, tidak sedikit mahasiswanya bergairah menampilkan tari kontemporer. Pradnyandari, salah satunya, dengan ciptaannya “Di Balik Boneka” seperti ingin menyapa penonton agar bersemangat mengapresiasi tari kontemporer. Tampaknya, sapaan Gung Is tak bertepuk sebelah tangan. Garapan tarinya banyak menuai pujian penonton. Artinya, tari kontemporer besutannya layak simak, menarik plus komunikatif.
Mempergunakan iringan sejumlah alat musik modern seperti keyboard, havy, biola, frogy dan chime yang ditata oleh I Wayan Diana Putra, S.Sn, M.Sn, “Di Balik Boneka” bergulir dengan kisah kehadiran seorang gadis di sebuah toko boneka, berharap bersua dengan pemuda penjaga toko yang telah menambat hatinya. Ketika sang pria muncul, si gadis berpura-pura menjadi boneka menggenggam boneka kecil. Kepintaran si gadis menjadi boneka mengundang rasa penasaran penjaga toko yang seakan dipermaiankan oleh salah satu boneka jualannya. Kesal dengan ulah boneka yang tak diketahuinya adalah seorang gadis yang jatuh cinta padanya, pria penjaga toko marah, merebut boneka kecil dari sang gadis hingga robek berkeping-keping.
Memakai asesories kepala, baju, dan sepatu berwarna pink, sang gadis hadir di tengah panggung di atas kursi panjang. Untaian geraknya berkelebat di sekitar kursi mengekspresikan kegelisahan dan harapan untuk segera bertemu dengan pria penjaga toko. Sang pria, menggunakan bareta, celana panjang, dan sepatu, berinsut hadir melangkah dalam beberapa sepakan gerak menghampiri lemari pajangan bonekanya. Selanjutnya kedua penari dalam penokohannya masing-masing, dengan bahasa ragawi, berungkap simbolik, maknawi, stailistik merangkai adegan per adegan, menyembur lembut, elastis, gesit, lugas, akrobatis, kocak, dan menggemaskan.
Tari kontemporer “Di Balik Boneka” menunjukkan kebebasannya merangkum beragam estetika gerak. Namun tampaknya Gung Is terlihat dominan mengeksplorasi tari ballet dan dansa latin walls. Gerakan serempak dan gerakan seimbang yang diperagakan kedua penari tampak rapi dengan selingan desain gerak herisontal, vertikal, dan kontras yang begitu terukur proporsinya, menjadikan garapan tari ini tampil memukau. Bagian adegan tari humoristik, ketika pria penjaga toko menggotong dan memindahkan berkali-kali si gadis boneka, mengundang gelak dan senyum simpul penonton. Keseriusan tari kontemporer yang dipersepsikan selama ini menjadi ringan menyegarkan. Malam itu, tari “Di Balik Boneka” mampu membalik pandangan para penonton.
Penonton kita memang perlu lebih diperbanyak menyimak letupan-letupan seni dari jagat tari kontemporer. Gung Is dengan tari “Di Balik Boneka”-nya telah berhasil mencuri perhatian masyarakat penonton untuk mengapresiasi ekspresi seni dengan gaya ungkap kontemporer. Memang, bentuk-bentuk ekspresi seni kontemporer, cenderung hanya hadir dan diterima dengan kementaraannya, namun sejatinya ia (seni kontemporer) memancarkan makna kultural dan bahkan bisa menorehkan sejarah seni budaya yang fenomenal. Tari kontemporer “Di Balik Boneka” telah terpajang manis di ruangan segar rumah seni kita.
by admin | Dec 16, 2015 | Artikel
Kiriman : Kadek Suartaya, SSKar., M.Si (Dosen Jurusan Karawitan ISI Denpasar)
Kecipak semburan air mancur di halaman Istana Negara Jakarta dan tugu Monumen Nasonal (Monas) nan menjulang menjadi latar atraksi utama Pawai Seni dan Budaya Kreatif Tahun 2015 pada Senin (18/8) sore yang cerah itu. Karnaval yang rutin digelar setiap tahun serangkaian dengan HUT Kemerdekaan RI tersebut, kali ini mengusung tema “Indonesia Bersatu”. Para kontingen pawai yang didatangkan dari seluruh penjuru Nusantara itu disatukan dalam sebuah perhelatan yang digadang sebagai alat pemersatu bangsa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, para pejabat Negara serta undangan lainnya menyimak satu persatu atraksi yang dipersembahkan oleh duta 33 provinsi dan dua perusahan negara. Masing-masing kontingen tampil hanya 2,5 menit.
Kebhinekaan budaya bangsa Indonesia terekspresi dari keberagaman keseniannya. Sebagai mutumanikam yang sering dibanggakan mengawal martabat bangsa, puspa ragam kesenian Nusantara menerima apresiasi yang istimewa pada perayaan kemerdekaan ke-69 itu. Melalui sajian pawai, masyarakat penonton dapat menyimak aneka seni tari dan musik dalam pertunjukan bergerak, yang berawal dari Istana Negara menuju Jalan Merdeka Barat dan berakhir di silang Monas. Diapresiasi oleh petingggi negara hingga rakyat jelata, tentu menggetarkan kebanggaan pelaku seni peserta pawai. Tampak mereka menunjukan kebolehan dan keindahan keseniannya dengan penuh kesungguhan.
Tapi, betulkah kita sungguh-sungguh menghargai kesenian kita? Semestinya begitu. Tengoklah antusiasnya Ibu Negara Ani Yudhoyono yang sibuk mengabadikan dengan kameranya penampilan para peserta pawai. Lalu, tidakkah pawai seni di halaman Istana Negara hanya merupakan media pengindahan, sebuah estetisasi politik kekuasaan seperti halnya pada zaman raja-raja di masa lampau? Tentu, terserah saja. Namun bagi I Nyoman Jegu, seorang petani dari Tabanan, Bali—salah satu penabuh gamelan okokan (sejenis musik masyarakat agraris tradisional)–yang sengaja diboyong ke Jakarta oleh PLN, hal itu tak terpikirkan. “Tiang demen polih pentas di istana presiden (saya suka dapat kesempatan tampil di istana presiden),” ujarnya polos sembari terengah usai pentas menggoyang instrumen yang terbuat dari kayu dengan berat sekitar 15 kilogram.
Para peserta pawai yang datang jauh-jauh dari pelosok daerah kiranya tak berbeda jauh dengan Nyoman Jegu, yang bangga ke Jakarta dan yang bangga “menguasai” halaman sakral Istana Negara, kendati hanya dua setengah menit. Kendati sesaat, hampir semua kontingen menunjukkan totalitasnya. Kontingen Bali misalnya, menyergap perhatian penonton dengan garapan “Garuda Jaya” yang sarat spectacle berdaya pukau. Kontingen Jambi yang tampil di halaman istana dengan karya seni bertajuk “Kakitau” juga tak kalah mempesona dengan semburan pesan kepedulian terhadap budaya agraris tradisional yang sarat kearifan. Demikian pula Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengetengahkan garapan “Mutiara Laut Selatan”, mengetuk perhatian penonton dengan kisah kemilau mutiara sebagai potensi yang menjanjikan masyarakat setempat.
Selengkapnya dapat unduh disini
by admin | Dec 16, 2015 | Artikel
Kiriman : Kadek Suartaya, SSKar., M.Si (Dosen Jurusan Karawitan ISI Denpasar)
Pada tahun 2015 ini, Pesta Kesenian Bali (PKB) sudah memasuki penyelenggaraan ke-37. Bagi masyarakat Bali, pesta seni yang digulirkan Gubernur Bali Ida Bagus Mantra di tahun 1979, adalah sebuah pesta yang sarat dengan semangat jengah. Sedangkan bagi para seniman Bali, selama sekian lama itu pula, kiranya PKB adalah arena berkesenian yang menggelora dari nurani ngayah. Deru jengah dan ketulusan ngayah itu kiranya adalah penyangga yang sangat signifikan terhadap perjalanan pesta seni yang cukup banyak menyita perhatian masyarakat Bali ini.
Kini pesta seni akbar Bali ini sudah mulai dikenal hingga ke mancanegara. Tak ada bulan Juni-Juli yang berlalu tanpa adanya perhelatan pesta seni yang penyelenggaraannya disokong oleh Perda No. 7/1986. Secara idealistik, PKB dicetuskan dan dilaksanakan sebagai media dan sarana untuk menggali dan melestarikan seni budaya, mendorong masyarakat, mengembangkan kreativitas, hiburan sehat, pendidikan generasi muda dan promosi pariwisata budaya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.
Namun demikian, PKB tampaknya masih memerlukan perjuangan yang panjang. Memang, jika ditelusuri, kehadiran PKB berimbas konstruktif bagi iklim berkesenian di pulau kesenian ini. Secara herisontal, misalnya kesenian langka, nilai seni yang terpinggir atau pingsan dibangkitkan lagi, direaktualisasikan. Secara vertikal, misalnya muncul kreativitas bahkan inovasi seni yang memberi binar dan memperkaya khasanah kesenian Bali. Semua ini mengangkat prestise kesenian itu sendiri dan mempertebal kepercayaan diri masyarakat Bali yang sebelumnya konon dulu sempat “minder” terhadap nilai-nilai seni tradisinya sendiri.
Seniman adalah pilar dan sumber insani mutlak dalam PKB. Seniman di mana pun, apalagi di Bali, cenderung memanjakan batinnya. Berkesenian sebagai persembahan masih dianut oleh umumnya seniman Bali. Jika batinnya terpuaskan dan bila eksistensinya diterima, persoalan lahir dan finansial malah sering tak diabaikan. Demikian pula kiprah mereka di arena PKB. Mereka dengan antusias berkorban segalanya, waktu-pikiran-materi. Dedikasi mereka sungguh-sungguh mengharukan. Implementasi sikap yang tulus demikian, memang mengkristal dan berlangsung alamiah di lingkungan komunitas mereka masing-masing.
Tengok misalnya sebuah sekaa kesenian yang tampil sebagai peserta Parade Gong Kebyar–seni pentas yang banyak digemari masyarakat Bali. Gabungan seniman tari, karawitan dan pedalangan yang merupakan duta masing-masing kabupaten mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Latihan-latihan yang meletihkan hingga pentas di gelanggang PKB menyita waktu hampir empat-enam bulan. Ini pun sering tidak lancar. Terutama yang amat memusingkan adalah soal dana yang tak mencukupi. Bukan rahasia lagi, hampir semua peserta sekaa tari dan tabuh parade Gong Kebyar, harus merogoh kantongnya sendiri bahkan bila perlu harus ngutang di sana-sini terlebih dahulu.
Jengah. Itulah yang melatarbelakangi tekad mereka ke pentas PKB. Jengah dalam bingkai fanatisme sekaa, banjar, desa, dan
obsesi kebanggaan berkiprah dalam PKB. Mungkin gelora jengah pula yang bergemuruh di dada para perancang acara-acara PKB, panitia pelaksana, atau para juri berbagai lomba. Jika tak demikian bagaimana “karya agung” ini bisa bergulir? Jika tidak demikian, bagaimana mungkin institusi seperti ISI Denpasar dan SMK Negeri 3 Sukawati masih tetap setia menampilkan garapan-garapan seni kolosalnya yang menyedot biaya besar dengan sokongan dana yang tak rasional?
Selain itu, masyarakat Bali beruntung memiliki budaya ngayah. Budaya ini selalu diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam gerak laku masyarakatnya. Dalam bidang kesenian misalnya, semua orang merasa memiliki peran. Dalam konteks ritual keagamaan, tradisi ngayah tersebut begitu eksplisit terlihat. Mereka yang tak bisa menari, mendalang, menabuh atau makidung, mungkin ngayah menata atau mengerjakan dekorasi panggung. Membantu para penari mengenakan kostum tarinya pun sudah termasuk berperan. Mengangkat gamelan dan mengurus konsumsi penari dan penabuh juga termasuk ngayah.
Kesenian Bali berkaitan erat dengan agama Hindu yang dipeluk mayoritas penduduknya. Maka tak salah bila dikatakan bahwa eksistensi kesenian Bali banyak terkondisi oleh tradisi ngayah. Seorang seniman seni rupa akan merasa bahagia bila sempat menyumbangkan kebolehannya dalam membuat benda-benda keagamaan. Seorang penari Topeng Pajegan akan merasa puas batinnya bila sempat unjuk kemampuan saat prosesi upacara sedang berlangsung. Para seniman karawitan akan merasa berperan bila ikut memberi suasana hikmat lewat permainan gamelannya.
Pada zaman modern sekarang ini, budaya ngayah masih tetap kental. Di samping tetap berlangsung dalam kaitannya dengan iman keagamaan dan dalam konteks budaya feodal, ngayah berkembang pada entitas yang lebih luas yakni kepada penguasa masa kini. Kiranya inilah yang terjadi dalam perhelatan akbar PKB. Jika tak demikian, bagaimana kita bisa memahami antusiasisme para pelaku utama PKB terutama para seniman yang tetap konsisten menunjukkan kiprahnya tanpa sempat menunjukkan sikap pragmatisnya?
Kiranya perpaduan budaya jengah dan ngayah-lah yang mendorong PKB terus menggelinding yang rasanya sulit untuk dihentikan. Kecuali bila penguasa yang menghendakinya–atau kecuali para seniman Bali berontak dari gereget jengah dan kesadaran ngayah-nya. PKB sudah menjadi ajang tahunan yang ditunggu-tunggu oleh segenap lapisan masyarakat Bali.
Budaya jengah dan ngayah adalah modal positif yang perlu dipertahankan. Tapi sampai kapan PKB melenggang dengan hanya bermodal sikap budaya tersebut? Sebagai bagian dari peradaban global, masyarakat Bali pun adalah bagian dari arus transformasi budaya. Konsekuensinya adalah terjadi pergeseran-pergeseran nilai. Semua ini tentu berimplikasi terhadap prilaku dan pola berpikir masyarakatnya. Misalnya mengemuka kecendrungan sadar sesadar-sadarnya akan arti ekomomi-uang dan pasar. Tengok misalnya bisnis kesenian dalam jagat pariwisata kita.
Dari sisi pandang ini, ajang PKB kiranya pantas memberi teladan bagaimana seharusnya menghormati dan menghargai seniman. Kita tentunya tak ingin terjadi dekadensi atau lunturnya pamor positif dari budaya jengah dan ngayah yang dihayati para seniman kita yang telah terbukti memiliki kontribusi penting bagi jagat kesenian Bali.
by admin | Dec 15, 2015 | Artikel
Kiriman : Kadek Suartaya, SSKar., M.Si (Dosen Jurusan Karawitan ISI Denpasar)
Suatu malam, di Sanggar Seni Paripurna, Desa Bona, Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Masyarakat setempat, undangan, dan komunitas seni yang dipimpin oleh seniman I Made Sidia memperingati hari ulang tahun sanggarnya yang ke-25 tahun. Segenap yang hadir—anak-anak, remaja, orang-orang dewasa—tampak begitu antusias memusatkan perhatiannya pada seorang gadis yang sedang beraksi di tengah arena pentas. Tepuk tangan dan derai tawa berkali-kali mengemuka dari para penonton. Pertunjukan apa gerangan yang tersaji? Pada Minggu (26/4) malam itu, gadis tersebut, seorang penari muda, Sri Ayu Pradnya Larasari, didaulat mesatua alias mendongeng. Lho, dongeng dapat dipentaskan?
Tradisi mendongeng di abad modern serba canggih ini sejatinya telah semakin menepi. Ungkapan ada katuturan satua (alkisah sebuah cerita) yang mengawali keasyikan mesatua di tengah masyarakat Bali tak pernah terdengar lagi pada malam-malam menjelang tidur. Pembukaan anuju sawijining dina (pada suatu hari) juga semakin sayup-sayup di tengah masyarakat Jawa masa kini. Nikmatnya bersahibul hikayat dalam tradisi mendongeng kini bak menjadi dongeng yang indah bagi generasi yang pernah mencerap nilai-nilai kehidupan lewat oral tradisi itu.
Mungkin karena menyadari tradisi mendongeng itu masih pantas diaktualisasi kepada generasi muda masa kini, maka upaya-upaya untuk menggeliatkan aktivitas mesatua itu terus dicoba dibangkitkan. Salah satu langkah menggairahkan tradisi mendongeng di Bali adalah lewat fomat kompetisi mendongeng atau lomba mesatua. Adalah Badan Perpustakaan Propinsi Bali telah beberapa kali menggelar lomba mesatua itu. Betapa melalui kompetisi tersebut seluruh peserta menunjukkan kegairahan yang menyala-nyala di depan penonton yang juga tekun menyimaknya. Demikian pula dalam Porsenijar yang berlangsung setiap tahun di Bali, lomba mendongeng cukup menarik perhatian penonton. Pradnya Larasari yang pernah tampil dalam Festival Mendongeng Internasional di Korea tahun 2014, memiliki kepiawaian mendongeng dari ketekunannya mengikuti kompetisi dari kedua arena tersebut.
Apresiasi masyarakat Bali terhadap sastra lisan mesatua ternyata masih menjanjikan. Terbukti ketika beberapa kali Larasari yang kini duduk di bangku SMA, diundang pentas mesatua, masyarakat begitu menikmatinya seperti apa yang tampak di Sanggar Paripurna tersebut. Kisah Pan Balangtamak yang dituturkan dengan amat memikat oleh gadis Desa Sukawati itu disimak dengan penuh kesungguhan. Di tengah masyarakat Bali, kisah Pan Balang Tamak bukan hanya sekedar dongeng namun juga dipercaya sebagai legenda. Kisahnya, bertutur tentang seorang laki-laki yang bodoh-bodoh pintar. Ia selalu mengkritisi segala hal dalam lingkungan sosialnya. Melalui akal dan logikanya, Pan Balang Tamak, mendongkel tirani mayoritas dan pemimpin yang sewenang-wenang. Pembangkangannya tersebut harus dibayar dengan nyawa, mati diracun. Namun akhirnya masyarakat sadar tingkah polah cerdik dan konyol Pan Balang Tamak tersebut adalah perjuangannya menegakkan demokrasi.
Aksentuasi pesan demokrasi dalam kisah Pan Balang Tamak itu, oleh Larasari, disimpulkan dalam akhir cerita melalui sebuah tembang Ginanti. Dibawakan dengan olah vokal yang mantap, liriknya sebagai berikut: belog celang dewek ipun/pan balang tamak puniki/matulak ring sang wisesa/mabela ngetohang urip/ngastiti panjake bagia/salunglung mademokrasi. Sri Ayu Pradnya Larasari yang menerima Anugrah Kebudayaan Pemerintah RI Tahun 2014 dalam bidang Tari dan Bercerita, mengelaborasinya secara dramatik dalam nuansa jenaka–ketika Pan Balang Tamak diadili krama desa–situasi berdemokrasi di tengah masyarakat Bali yang memaksakan kehendak mengatasnamakan orang banyak dalam pekik briuk siu.
Tradisi mendongeng di masa lalu dituturkan terutama untuk hiburan namun baik langsung maupun tak langsung sejatinya kandungan dongeng juga sarat dengan pelajaran moral, seperti moral demokrasi dalam dongeng Pan Balang Tamak tersebut. Sebab dalam tradisi mendongeng itu, materinya tak hanya melulu tentang keajaiban dan musizat di negeri antah berantah. Kala kejayaan tradisi mendongeng di tengah masyarakat Jawa dan Bali, epos Mahabharata dan Ramayana umum dikisahkan tahap demi tahap, setiap malam, episode per episode. Zaman dulu, ketika tradisi baca tulis masih asing, kisah Pandawa dan Korawa atau perseteruan Rama dan Rahwana justru banyak diserap anak-anak Jawa dan Bali melalui tradisi mendongeng.
Pada masa lalu, kakek dan nenek atau ayah dan ibu adalah nara sumber utama sebagai pengkisah yang dongeng-dongengnya dihayati anak-anak atau cucu-cucunya. Tetapi harus dilihat bahwa mereka yang di masa kini tergolong kakek dan nenek serta mereka yang menjadi bapak atau ibu sebenarnya juga tidak akrab dengan tradisi mendongeng dan lebih jauh lagi tak ada waktu untuk mendongeng. Orang-orang tua dan dewasa masa kini lebih banyak berkutat menghadapi realita duniawi kehidupan.
Karenanya, anak-anak masa kini tak pernah lagi ditidurkan oleh dongeng atau kisah-kisah epik. Mereka adalah generasi yang dikeloni oleh layar-layar globalisasi, layar televisi, layar HP, layar internet dan seterusnya. Sebab, kepungan layar-layar itu memberikan hampir semuanya, dari madu yang positif-konstruktif hingga racun yang negatif-destrukstif. Namun idealisme untuk menawarkan penyeimbang kehidupan dengan nilai-nilai etika, estetika, dan logika melalui tradisi mesatua semestinya terus diberi ruang. Sebab satua bukan sat tuara ada (dianggap tak ada), sebaliknya sangat bermakna. Tradisi mendongeng yang begitu kontributif terhadap pembentukan watak para pencerapnya, di masa lalu, kiranya kini perlu diaktualisasikan kembali di tengah masyarakat kontemporer. Mereguk nilai kehidupan lewat oral tradisi dongeng perlu dilirik kembali.
by admin | Dec 15, 2015 | Artikel
Kiriman : Kadek Suartaya, SSKar., M.Si (Dosen Jurusan Karawitan ISI Denpasar)
Secara umum karya-karya I Wayan Beratha dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu musik alias gending-gending untuk iringan tari atau sendratari dan karya musik untuk konser. Untuk iringan tari lepas, I Wayan Beratha mulai mencipta sejak masa mudanya tahun 1958. Tari Tani, Kuputarum, Pendet, Panyembrama, adalah beberapa karyanya yang hingga kini masih eksis. I Wayan Beratha mulai menggarap musik untuk konser sejak tahun 1959 dengan judul Kebyar Swabuanapaksa. Karya ciptanya diterima penuh suka cita oleh para penabuh dan pecinta seni karawitan. Besar kemungkinan, ciptaan Sang Empu Seni karawitan Bali ini, akan lestari menjadi karya monumental, mengingat begitu getol dan asyiknya para penabuh masa kini mempelajari dan menyajikan tabuh-tabuh kreasi almarhum.
Tabuh Gambang Suling adalah salah satu karya Wayan Beratha yang dikenal luas oleh masyarakat Bali. Peristiwa seni pertunjukan tari kebyar (tari lepas) dan drama gong misalnya, sering menyajikan ciptaan Wayan Beratha ini menjelang pertunjukan inti dimulai. Penonton yang pada umumnya banyak hadir untuk menikmati tabuh pembukaan sebuah pertunjukan, begitu terkesan terhadap harmoni beragam instrumen gamelan kebyar dengan penonjolan titian melodi gangsa dan liukan manis suling dari tabuh Gambang Suling itu.
Sumber inspirasi tabuh yang diciptakan Wayan Beratha pada tahun 1963 itu datang dari tanah Jawa. Ceritanya, pada tahun itu Wayan Beratha bertandang ke Solo memimpin sebuah misi kesenian. Dalam sebuah kesempatan ia sempat menyaksikan sebuah grup gamelan Jawa memainkan gending Swara Suling. Saat itu juga nalurinya sebagai komposer beriak-riak. Tak menunggu waktu lama, “Sepulang dari Solo, saya menciptakan tabuh Gambang Suling, karena struktur tabuh-nya ada unsur gegambangan di bagian akhir dan alunan suling tersendiri di bagian tengah, “ ungkap Wayan Beratha.
Gending Swara Suling adalah seni vokal yang biasa dilantunkan anak-anak pedesaan Jawa Tengah saat berdolanan. Oleh Ki Narta Sabdo, seorang dalang terkenal dari Semarang, dipopulerkan dengan lirik lagu: gambang suling ngumandang swarane/tulat tulit kepenak uline/unine mung nrenyuh ake/barengan lan kentrung ketipung suling/sigrak kendangane. Melodi dari lirik lagu itu ditranformasikan Wayan Beratha ke dalam gamelan dengan ornamentasi nan kental genre musik kebyar Bali yang relatif tidak begitu rumit namun indah.
Sudah lazim, kreasi seni yang mengena di hati masyarakat Bali, begitu cepat tersebar. Sekaa-sekaa gamelan kebyar yang sedang menggeliat saat itu saling tak mau ketinggalan mempelajari dan menyajikan tabuh yang berduri 7-8 menit tersebut. Seorang peneliti asing, Ruby Ornstein, yang menulis disertasi berjudul Gamelan Gong Kebyar: The Development of a Balinese Musical Tradition, mencatat pada tahun 1964-1965, menyaksikan sekaa gamelan kebyar di Desa Peliatan, Gianyar, dan di Desa Kedis Kaja, Buleleng, memainkan tabuh Gambang Suling ciptaan Wayan Beratha.
Hingga kini–setelah berusia lebih dari setengah abad–tabuh Gambang Suling masih mengalun, masih sering disuguhkan dan masih diapresiasi penonton. Bahkan kumandang Gambang Suling tidak hanya terdengar di Bali namun juga bergaung di mancanegara. Grup-grup gamelan Bali di Amerika dan Jepang misalnya pernah mementaskan tabuh karya Wayan Beratha itu. Begitu juga lawatan duta-duta kesenian Bali ke berbagai belahan dunia, sering menampilkan materi tabuh pembukaan Gambang Suling. Tim kesenian ISI Denpasar dalam misi seninya di luar negeri beberapa tahun belakangan, mempesona penonton, diantaranya dengan tabuh Gambang Suling. ISI Denpasar berhasil menggugah penonton dengan tabuh Gambang Suling saat tampil di Moscow-Rusia (2010), Perth-Australia (2012), dan Beijing-Tiongkok (2013).
Keberhasilannya menciptakan berbagai jenis gending iringan tari dan karya tabuh-tabuh instrumentalia, mengukuhkan nama I Wayan Beratha sebagai komposer besar Bali yang membuat dirinya disegani oleh komunitas seni. Sebagai pencipta sendratari pertama, Sendratari Jayaprana, dan kemudian tetap berkreasi dan berinovasi dalam penggarapan sendratari kolosal PKB, I Wayan Beratha mendapat pengakuan masyarakat luas dan diapresiasi secara formal oleh pemerintah lewat penganugrahan tanda penghargaan dari tingkat kabupaten/kota hingga nasional.
Peran I Gusti Bagus Nyoman Pandji dan Ida Bagus Mantra sangat besar dalam menjadikan Wayan Beratha sebagai bapak sendratari Bali. Lahirnya Sendratari Jayaprana pada awalnya adalah atas permintaan I Gusti Bagus Nyoman Pandji, direktur pertama Kokar Bali guna memeriahkan hari ulang tahun pertama Kokar pada tanggal 1 Oktober 1961 di Denpasar “Panggung Ardha Candra Taman Budaya Denpasar yang pembangunannya dirintis Ida Bagus Mantra selaku Dirjen Kebudayaan RI dan pemakaiannya dimulai ketika era Pak Mantra jadi Gubernur Bali, yang menjadi stimulasi menggugah dan menantang saya dan kawan-kawan di Kokar Bali menggarap sendratari kolasal Pemutaran Mandara Giri produksi Kokar pada tahun 1978,” kenang I Wayan Beratha semasa hidupnya. Gagasan sendratari yang dibawakan ratusan pemain di panggung terbuka itu, sejak PKB dibuka Ida Bagus Mantra pada tahun 1979, menjadi salah satu seni pertunjukan yang banyak menyedot perhatian masyarakat penonton.
Konsep estetis yang telah digariskan I Wayan Beratha pada seni pertunjukan sendratari adalah penyajian sebuah cerita atau lakon melalui perkawinan antara seni tari dan karawitan. Antawacana atau narasi yang disampaikan oleh seorang dalang dimaksudkan untuk memberikan penekanan dramatik yang tidak terlalu dominan bagi adegan-adegan yang terjadi di atas pentas. Konsep artistik sendratari seperti ini masih secara konsisten dipertahankan I Wayan Beratha setidaknya hingga akhir tahun 1970-an.
Konsep estetis sendratari Bali yang dikembangkan I Wayan Beratha ini seturut dengan konsep artistik sendratari yang muncul di Jawa, Sendratari Ramayana Prambanan, yaitu dramatari yang dimainkan oleh para penari tanpa menggunakan dialog. Sendratari Bali yang dipelopori I Wayan Beratha taat pada konsep artistik dramatari yang diungkapkan melalui jalinan tari dan iringan gamelan. Dramatisasinya digarisbawahi oleh narasi dalang dalam alunan tembang yang mengelaborasi melodi gamelan. Unsur-unsur dialog yang dibawakan seorang dalang hanya memberi aksentuasi cerita. Bersama dalang atau tukang tandak, aspek dramatik sendratari juga diperindah dan diperkuat oleh pengkisahan dalam bentuk alunan lagu/gending oleh beberapa vokalis wanita yang disebut tukang gerong.
Pembaharuan aspek-aspek musikal iringan sendratari yang dielaborasi oleh I Wayan Beratha kini menginspirasi bahkan menjadi acuan generasi penerusnya. Pola-pola melodi, ritme, tempo, dinamika, harmoni yang dikembangkan Beratha dari kekayaan musik tradisional Bali diteruskan oleh para komposer muda. Dari aspek instrumental yang dijadikan media iringan sendratari PKB, I Wayan Beratha mencetuskan gagasan pengembangan pemakaian dua hingga tiga barung gamelan untuk memenuhi tuntutan estetis. Selain memakai gong kebyar, sendratari PKB juga sekaligus diiringi dengan gamelan gong gede dan semarapagulingan. Pemakaian tiga barung gamelan sekaligus ini memunculkan gagasan pada diri I Wayan Beratha untuk menyatukannya. Pada tahun 1983 Beratha kemudian menciptakan gamelan yang diberinya nama gamelan Genta Pinara Pitu yang dikembangkan pada tahun 1984 menjadi gamelan Semara Dahana (Semaradana) yang prinsipnya merupakan penggabungan gamelan gong kebyar dengan semara pagulingan. Gamelan baru ciptaan I Wayan Beratha ini dengan cepat berkembang di Bali, Amerika, dan Jepang karena gamelan ini bukan hanya ideal untuk mengiri sendratari namun juga sangat fleksibel sebagai media musik konser maupun untuk mengiringi tari klasik dan kreasi. “Pembaharuan adalah denyut nadi jagat seni,“ ujar Pak Beratha menegaskan prinsip berkeniannya.